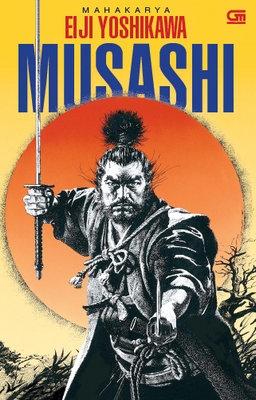
Manusia Serba bisa
MUSASHI meninggalkan
lapangan itu sambil berpikir, "Aku menang," katanya pada dirinya
sendiri, "Sudah kukalahkan Yoshioka Seijuro; sudah kutundukkan benteng
Gaya Kyoto!"
Tapi ia tahu hatinya
tidak di situ. Matanya tertunduk dan kakinya seperti tenggelam dalam dedaunan
kering. Seekor burung kecil yang terbang membubung ke langit memperlihatkan
bagian bawah tubuhnya yang mengingatkan pada seekor ikan.
Ketika ia menoleh ke
belakang, tampak olehnya pohon-pohon pinus yang ramping di atas gundukan tempat
ia menghadapi Seijuro. "Aku memukul cuma satu kali," pikirnya.
"Barangkali pukulan itu tidak membunuhnya." Ia memeriksa pedang
kayunya untuk memperoleh kepastian bahwa tidak ada sisa darah di situ.
Pagi itu, dalam
perjalanan ke tempat yang telah ditentukan, ia menduga akan menjumpai Seijuro
ditemani rombongan muridnya, yang bisa saja menempuh jalan licik. Terus terang
ia sudah siap menghadapi kemungkinan terbunuh. Agar pada akhir hayatnya ia
tidak tampak berantakan, ia sudah menggosok giginya baik-baik dengan garam dan
mencuci rambutnya.
Ternyata Seijuro jauh
berada di bawah perkiraan Musashi. Musashi bertanya-tanya, apakah Seijuro
benar-benar anak Yoshioka Kempo. Di dalam diri Seijuro yang biasa hidup di kota
dan jelas berpendidikan baik itu tidak tampak penampilan seorang guru utama
Gaya Kyoto. Ia terlalu ramping, terlalu lunak, terlalu sopan santun untuk
menjadi jagoan pedang besar.
Ketika mereka bertukar
salam, Musashi sudah berpikir tak enak. "Mestinya tak usah aku menjalani
pertarungan ini."
Penyesalannya memang
benar, kerena tujuannya adalah selalu menghadapi lawan yang lebih baik dari
dirinya. Sekali pandang cukuplah. Tidak ada gunanya berlatih setahun penuh
hanya untuk menghadapi pertarungan ini. Mata Seijuro tidak menampakkan
keyakinan diri. Api yang dibutuhkan itu tidak ada, tidak hanya pada wajahnya,
melainkan juga pada seluruh tubuhnya.
"Kenapa dia
datang kemari pagi ini," tanya Musashi sendiri, "kalau dia tak punya
keyakinan lebih di dalam dirinya?" Tapi Musashi sadar akan kesulitan
lawannya, dan ia bersimpati. Seijuro tak dapat membatalkan pertarungan itu,
sekalipun meng-hendakinya. Para murid yang diwarisinya dari ayahnya memandangnya
sebagai penasihat dan pemimpin. Tak ada pilihan lain baginya kecuali menghadapi
peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika kedua orang itu berdiri dan siap
bertempur, Musashi menoleh ke sana kemari untuk mencari alasan membatalkan
seluruh acara itu, tapi kesempatan untuk itu tidak juga datang.
Kini semuanya sudah
berlalu, dan Musashi berpikir, "Berat, berat! Mestinya tidak kulakukan
itu." Dan dalam hati ia berdoa semoga luka Seijuro lekas sembuh.
Tetapi kerja hari itu
sudah terlaksana. Tidak sewajarnya seorang prajurit matang bermuram durja
mengenai hal yang sudah lalu.
Ketika ia mempercepat
langkahnya, seorang perempuan tua muncul di atas petak rumput dengan wajah
terkejut. Semula perempuan itu sedang menggaruk-garuk tanah mencari sesuatu.
Bunyi langkah Musashi membuatnya tersengal. Perempuan itu mengenakan kimono
polos tipis. Kalau tidak karena tali lembayung yang mengikat jubahnya,
barangkali ia hampir tak bisa dibedakan dari rumput yang diinjaknya. Sekalipun
pakaiannya baju orang awam, kerudungnya kerudung biarawati. Perempuan itu
bertubuh kecil halus.
Musashi sama kagetnya
dengan perempuan itu. Tiga atau empat langkah lagi, pasti ia sudah
menginjaknya. "Apa yang Ibu cari?" tanya Musashi ramah. Ia
melontarkan pandang ke tasbih yang tersangkut pada lengan perempuan itu di
dalam lengan kimononya, dan sekeranjang tumbuhan liar kecil-kecil pada tangan
yang lain. Jemari dan tasbih itu bergetar sedikit.
Untuk menenangkannya,
Musashi berkata ringan, "Saya heran melihat tumbuhan ini sudah tumbuh.
Saya pikir musim semi baru akan mulai. Oh, saya lihat Ibu sudah punya daun
seledri yang manis-manis, juga lobak dan bunga kering, Apa Ibu memetiknya
sendiri?"
Tapi biarawati itu
menjatuhkan keranjangnya dan lari berteriak-teriak, "Koetsu! Koetsu!"
Musashi memandang
tertegun melihat sosok kecil itu menghilang ke arah tanjakan kecil di tengah
ladang yang umumnya datar. Di belakang tanjakan itu tampak asap mengepul.
Karena menurut
pendapatnya sayang kalau perempuan itu kehilangan sayuran yang sudah dengan
susah payah dikumpulkannya, maka Musashi pun memungutnya dan pergi mengikutinya
sambil menjinjing keranjang. Kira-kira semenit kemudian, muncul dua lelaki.
Mereka telah
menghamparkan permadani di sisi selatan yang kena sinar matahari, pada lereng
yang landai. Di situ terdapat juga macam-macam alat yang biasa dipergunakan
oleh pemeluk kultus teh, termasuk ketel besi di atas api dan cerek air di satu
sisi. Mereka membuat kamar teh di udara terbuka, dan menganggap lingkungan alam
itu sebagai kebunnya. Semuanya tampak sedikit bergaya dan anggun.
Seorang dari kedua
lelaki itu rupanya pelayan, sedangkan yang satunya mengingatkan orang pada
boneka porselin besar yang menggambarkan aristokrat Kyoto karena kulitnya yang putih
lembut dan garis-garis wajahnya yang serasi. Ia berperut gendut. Keyakinan diri
tercermin pada pipi dan posturnya.
"Koetsu".
Nama itu membangkitkan kenangan, karena pada waktu itu Hon'ami Koetsu sangat
terkenal dan tinggal di Kyoto. Orang mengatakan dengan nada iri bahwa upah
tahunan Koetsu, seribu gantang, diperoleh dari Yang Dipertuan Maeda Toshiie
dari Kaga yang sangat kaya. Sebagai penduduk kota biasa, ia dapat hidup mewah
dari situ saja, tapi di samping itu ia menikmati juga perkenan khusus dari
Tokugawa Ieyasu dan sering diterima di rumah kaum bangsawan tinggi. Kabarnya
para prajurit terbesar negeri ini terpaksa turun dari kuda dan berjalan kaki
bila melewati tokonya, agar tidak memberikan kesan merendahkannya.
Nama keluarga itu
dipakai karena mereka menetap di Jalan Hon'ami, dan usaha Koetsu di bidang
pembersihan, penyemiran, dan penaksiran pedang. Keluarga itu memperoleh nama
baik semenjak abad empat belas dan berkembang pesat di zaman Ashikaga. Di
kemudian hari mereka dilindungi daimyo-daimyo terkemuka seperti Imagawa
Yoshimoto, Oda Nobunaga, dan Toyotomi Hideyoshi.
Koetsu dikenal
sebagai orang yang punya banyak bakat. Ia pelukis, ternama sebagai ahli keramik
dan pembuat pernis, dan dianggap ahli seni. Ia sendiri beranggapan bahwa
kekuatannya adalah dalam kaligrafi. Di bidang ini umumnya ia disejajarkan
dengan ahli-ahli yang sudah diakui seperti Shokado Shojo, Karasumaru Mitsuhiro,
dan Konoe Nobutada, pencipta Gaya Sammyakuin, yang demikian populer hari-hari
itu.
Sekalipun terkenal,
Koetsu merasa belum sepenuhnya dihargai orang, atau demikianlah kelihatannya
dari cerita yang beredar. Menurut cerita itu, ia sering mengunjungi tempat
kediaman sahabatnya, Konoe Nobutada, yang bukan hanya seorang bangsawan,
melainkan sekaligus juga Menteri Kiri dalam pemerintahan Kaisar. Dalam salah
satu kunjungan, demikian cerita orang, pembicaraan dengan sendirinya beralih ke
kaligrafi, dan Nobutada bertanya, "Koetsu, siapa kiranya yang akan Anda
pilih sebagai tiga ahli kaligrafi terbesar negeri ini?"
Tanpa keraguan
sedikit pun Koetsu menjawab, "Yang kedua adalah Anda sendiri, dan kemudian
saya kira Shokado Shojo."
Sedikit heran,
Nobutada bertanya, "Anda mulai dengan kedua terbaik, tapi siapa yang
pertama?"
Tanpa senyum sama
sekali Koetsu memandang langsung ke mata Nobutada dan menjawab, "Tentu
saja saya."
Tenggelam dalam
lamunan itu, Musashi berhenti tak jauh dari tempat orang-orang itu.
Koeuu memegang kuas,
dan di lututnya tergeletak beberapa lembar kertas. Dengan sangat hati-hati ia
membuat sketsa air yang mengalir tak jauh dari situ. Lukisan yang sedang
digarapnya maupun beberapa karya sebelumnya yang berserakan di tanah terdiri
semata-mata atas garis-garis pucat yang menurut penilaian Musashi bisa saja dibuat
oleh setiap pemula.
Koetsu menengadah dan
berkata tenang, "Ada apa?" Kemudian ia menatap adegan itu: Musashi di
satu sisi, dan di sisi lain ibunya yang gemetar di belakang pelayan. '
Musashi merasa lebih
tenang dengan hadirnya orang itu. Ia jelas bukan macam orang yang biasa ditemui
Musashi tiap hari, tapi entah bagaimana orang itu menarik bagi Musashi. Matanya
memancarkan sinar yang dalam, yang sebentar kemudian mulai tersenyum kepada
Musashi, seakan-akan mereka kenalan lama.
"Selamat datang,
anak muda. Apa ibuku berbuat salah? Umurku sendiri empat puluh delapan, jadi
bisa kaubayangkan sudah seberapa tua beliau. Dia memang sehat sekali, tapi
kadang-kadang beliau mengeluh tentang penglihatannya. Kalau beliau melakukan
sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya, kuharap engkau mau menerima
permintaan maaf dariku." Ia meletakkan kuas dan bloknot di permadani kecil
tempat ia duduk, dan meletakkan kedua tangannya ke tanah, bersujud.
Musashi buru-buru
berlutut untuk menghalangi Koetsu. "Jadi, Anda putra beliau?"
tanyanya bingung.
"Ya."
"Sayalah yang
mesti mohon maaf. Saya sebenarnya tak mengerti kenapa ibu Anda takut, tapi
begitu beliau melihat saya, beliau menjatuhkan keranjangnya dan lari. Melihat
sayuran beliau tumpah, saya jadi merasa bersalah. Dan ini saya bawa
barang-barang yang jatuh itu. Hanya itu. Tak perlu Anda menghormat
begitu."
Sambil tertawa
senang, Koetsu menoleh kepada biarawati itu, dan katanya “Sudah Ibu dengar
sendiri, kan? Kesan Ibu salah sama sekali."
Dengan perasaaan
sangat lega, ibu itu keluar dari tempat sembunyinya di belakang pelayan.
"Maksudmu, ronin ini tak ada maksud mencelakaiku?"
"Mencelakai?
Sama sekali tidak. Lihatlah, dia bahkan mengembalikan keranjang Ibu. Apa dia
tidak baik budi?"
"Oh, maaf,"
kata biarawati itu sambil membungkuk rendah hingga dahinya menyentuh tasbih
yang ada di pergelangan tangannya. Kini ia riang dan tertawa sambil menoleh
kepada anaknya. "Aku malu mengakuinya," katanya, "tapi ketika
pertama kali kulihat anak muda ini, kupikir aku mencium bau darah. Oh,
mengerikan! Jadi tegak bulu romaku. Sekarang aku tahu, betapa tololnya aku
tadi."
Daya tinjau perempuan
tua itu mengagumkan Musashi. Ia mampu melihat ke dalam diri Musashi, dan tanpa
benar-benar memahaminva sudah menyatakannya dengan terus terang. Bagi perasaan
perempuan yang lembut ini, pasti Musashi tampak seperti hantu yang mengerikan
dan berlumuran darah.
Koetsu tentunya telah
menangkap pula dalam pandangan mata Musashi yang tajam menembus, dari rambutnya
yang tegak mengancam itu, sifatnya yang tajam bagai duri dan berbahaya, yang
menyatakan kesiapsiagaannya untuk menghantam gangguan yang bagaimanapun
kecilnya. Meskipun begitu tampaknya Koetsu cenderung mencari unsur yang baik
padanya.
"Kalau engkau
tidak terburu-buru," katanya, "tinggallah di sini dan istirahat
sebentar. Di sini sangat sepi dan tenang. Duduk di tengah lingkungan ini, aku
merasa bersih dan segar."
"Kalau saya
dapat memetik sedikit lagi sayuran, saya bisa membuat bubur yang enak nanti
untukmu," kata biarawati itu. "Dan juga teh. Atau engkau tak suka
teh?"
Bersama ibu dan anak
itu, Musashi merasa damai dengan dunia ini. Ia me-nyarungkan semangat
perangnya, seperti kucing memasukkan cakarnya. Di tengah suasana yang menyenangkan
ini, sukar ia mempercayai bahwa ia berada di tengah orang-orang asing sama
sekali. Sebelum menyadarinya, ia telah melepaskan sandal jeraminya dan
mengambil tempat duduk di atas permadani.
Sesudah mengajukan
beberapa pertanyaan, tahulah ia bahwa sang ibu yang nama biaranya Myoshu itu
dahulunya seorang istri yang baik dan setia, sebelum akhirnya menjadi
biarawati, sedangkan anaknya ternyata memang si estetikus dan seniman terkemuka
itu. Di antara para pemain pedang, tak seorang pun yang tidak mengenal nama
Hon'ami—begitu hebat reputasi keluarga itu, berkat kemampuan-nya yang sempurna
dalar menilai pedang.
Musashi merasa sukar
menghubungkan Koetsu dan ibunya denga.gambaran yang ia miliki tentang bagaimana
mestinya keadaan orang-orang seterkenal mereka itu. Baginya, mereka sekadar
orang-orang biasa yang kebetulan ia jumpai di ladang sepi. Itulah justru yang
ia kehendaki, karena kalau tidak, ia sendiri bisa jadi tegang merusak tamasya
mereka.
Sambil membawa ketel
teh, Myoshu bertanya pada anaknya, "Berapa umur pemuda ini
menurutmu?"
Sambil memandang
Musashi, jawab Koetsu, "Dua puluh lima atau enam kukira."
Musashi menggeleng.
"Tidak, umur saya baru dua puluh tiga."
"Baru dua puluh
tiga," kata Myoshu. Kemudian ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
biasa: di mana rumahnya, apakah orangtuanya masih hidup, siapa yang
mengajarinya main pedang, dan seterusnya.
Bicaranya lembut,
seolah Musashi adalah cucunya, dan ini menyebabkan jiwa kanak-kanak Musashi
muncul. Gaya bicaranya berubah menjadi gaya bicara pemuda yang tidak resmi.
Karena terbiasa dengan disiplin dan latihan keras, dan terbiasa menghabiskan
waktu dengan menempa diri menjadi pedang baja yang bagus, maka tidak sedikit
pun ia kenal sisi kehidupan yang lebih beradab. Sementara biarawati tua itu
berbicara, kehangatan menyebar di seluruh tubuhnya yang sudah tertempa cuaca.
Myoshu, Koetsu,
barang-barang di atas permadani, bahkan mangkuk teh itu, dengan halusnya
berpadu dengan suasana menjadi bagian dari alam seluruhnya. Tetapi Musashi
tidak sabar. Tubuhnya terlalu gelisah untuk duduk terus berlama-lama. Memang
cukup menyenangkan mengobrol demikian, tapi ketika Myoshu mulai menatap diam ke
ketel teh dan Koetsu membelakanginya untuk meneruskan melukis, Musashi menjadi
bosan. "Apa enaknya datang kemari ini buat mereka?" tanyanya pada
diri sendiri. "Musim semi baru saja mulai. Udara masih dingin."
Kalau mereka ingin
memetik sayuran liar, kenapa tidak menanti sampai udara lebih hangat dan lebih
banyak orang di sekitar? Waktu itu banyak bunga dan tumbuhan hijau yang segar.
Kalau mereka ingin menikmati upacara teh, kenapa pula susah-susah membawa ketel
dan mangkuk-mangkuk teh ke tempat ini? Keluarga terkenal dan makmur seperti
mereka ini pasti punya ruang teh yang anggun di rumahnya.
Apakah untuk melukis?
Ketika memandang
punggung Koetsu, tahulah ia bahwa dengan mencondongkan badan ke samping ia
dapat melihat kuas yang sedang bergerak. Tiada lain yang dilukis oleh seniman
itu kecuali garis-garis air yang mengalir, dan matanya terus tertuju pada kali
sempit yang membelok melintasi rumput kering. Koetsu berkonsentrasi hanya pada
gerakan air. Berkali-kali ia mencoba menangkap gerak air mengalir itu, namun
sentuhan yang tepat kelihatannya belum didapatnya. Tak bosan-bosannya ia terus
melukis garis-garis itu.
"Yah,"
pikir Musashi, "melukis tak semudah kelihatannya." Untuk sesaat rasa
bosannya surut, dan ia terpesona memperhatikan goresan kuas Koetsu. Koetsu
tentunya sama perasaannya dengan dirinya sewaktu menghadapi musuh dan ujung
pedang yang sudah di depan mata. Pada tahap tertentu ia akan bangkit mengatasi
dirinya dan merasa telah jadi satu dengan alam-bukan, bukan "merasa",
karena segala rasa akan lengkap pada saat pedang melukai lawan. Saat transenden
yang magis itulah segala-galanya.
"Koetsu masih
memandang air sebagai musuhnya," pikirnya. "Itu sebabnya dia tak
dapat melukisnya. Air harus menjadi bagian dan dirinya, baru dia akan
berhasil."
Karena tak ada yang
dikerjakannya, dari kebosanan ia meluncur ke dalam kelesuan, dan ini
menggelisahkannya. Ia tak boleh membiarkan dirinya kendur, biarpun cuma sesaat.
Ia mesti pergi dari tempat itu.
"Saya minta maaf
sudah mengganggu," katanya agak kasar, dan mulai mengikatkan kembali
sandalnya.
"Oh, begitu
cepat akan pergi?" tanya Myoshu.
Koetsu menoleh ke
belakang pelan-pelan, dan katanya, "Tak bisa engkau tinggal sedikit lama?
Ibu mau bikin teh sekarang, Kukira engkaulah orang yang bertarung dengan
Perguruan Yoshioka pagi ini. Minum teh sedikit sesudah berkelahi baik untuk
badan, setidak-tidaknya itulah yang dikatakan Yang Dipertuan Maeda. Ieyasu
demikian juga. Teh itu baik untuk semangat. Aku sangsi apakah ada yang lebih
baik dari teh. Menurut pendapatku, aksi dilahirkan oleh ketenangan. Tinggallah,
dan bicaralah. Akan kutemani."
Jadi, Koetsu tahu
tentang pertarungan itu! Tapi barangkali tidak begitu mengherankan. Rendaiji
tidak jauh, hanya di ladang sebelah sana. Persoalan yang lebih menarik adalah,
kenapa sampai sedemikian jauh ia tidak mengatakan sesuatu. Apakah karena
menurut anggapannya soal-soal macam itu bukan bagian dari dunianya sendiri?
Musashi sekali lagi memandang ibu dan anak itu, kemudian duduk lagi.
"Kalau Anda
mendesak, saya akan tinggal," katanya.
"Tak banyak yang
dapat kami suguhkan, tapi kami senang engkau bersama kami di sini," kata
Koetsu. Ia meletakkan tutup pada kotak tintanya, lalu meletakkan kotak itu di
atas lembar-lembar sketsa, agar tidak kabur. Di dalam tangannya kotak tinta itu
berkelip-kelip seperti kunangkunang. Rupanya berlapis emas tebal, dengan
tatahan perak dan mutiara.
Musashi membungkuk
untuk memperhatikannya. Sesudah terletak di atas permadani, kotak itu tidak
lagi berkilau cemerlang, Ia tahu, tak ada yang mencolok. Keindahannya terletak
pada lapis emas dan lukisan cat kuil-kuil Momoyama yang dikecilkan beberapa
kali. Juga terasa ada bagiannya yang sangat kuno, yaitu tahi tembaga yang
redup, yang mengingatkan orang pada kebesaran yang sudah pudar. Musashi menatap
dengan saksama. Terasa ada sesuatu yang menyenangkan pada kotak itu.
"Aku membuatnya
sendiri," kata Koetsu rendah hati. "Engkau suka?"
"Oh, jadi Tuan
membuat barang pernis juga?"
Koetsu hanya
tersenyum. Ia memandang pemuda yang kelihatannya lebih mengagumi kecerdasan
manusia daripada keindahan alam itu, dan pikirnya geli, "Bagaimanapun, dia
berasal dari desa."
Tak kenal dengan
sikap megah Koetsu, Musashi pun berkata penuh ketulusan, "Ini betul-betul
indah." ia tidak dapat melepaskan pandangannya dari kotak tinta itu.
"Sudah kukatakan
itu kubuat sendiri, tapi sajak di atasnya hasil karya Konoe Nobutada. Jadi, ini
buatan kami berdua."
"Apa itu
keluarga Konoe yang menurunkan wali kaisar?"
"Ya. Nobutada
adalah anak wali yang dahulu."
"Suami bibi saya
mengabdi pada keluarga Konoe bertahun-tahun."
"Siapa
namanya?"
"Matsuo
Kaname."
"Oh, aku kenal
baik Kaname itu. Aku selalu mengunjunginya kalau pergi ke rumah Konoe, dan dia
kadang-kadang datang mengunjungi kami.
"Betul?"
"Bu, dunia ini
kecil, ya? Bibi dia ini istri Matsuo Kaname."
"Ah, masa!"
kata Myoshu.
Myoshu meninggalkan
api dan meletakkan mangkuk-mangkuk teh di depan mereka. Tak sangsi lagi, ia
betul-betul ahli dalam hal upacara teh. Gerak-geriknya anggun, namun alamiah,
sedangkan tangannya yang lembut itu lemah gemulai. Sekalipun sudah berumur
tujuh puluh, ia kelihatan sebagai lambang keluwesan dan kecantikan wanita.
Musashi, yang merasa
betul-betul tidak leluasa, duduk bersimpuh dengan sopannya, meniru Koetsu. Kue
untuk minum teh berupa kue kismis yang dikenal dengan nama manju Yodo, tetapi
kue itu diletakkan dengan apiknya di atas selembar daun hijau yang jenisnya tak
ada di ladang sekitar. Musashi tahu ada peraturan tertentu berupa etiket untuk
menghidangkan teh, seperti halnya ada peraturan menggunakan pedang, dan selama
memperhatikan Myoshu, ia mengagumi keahliannya. Menilainya dalam istilah ilmu pedang,
"Dia sempurna sekali! Sama sekali tidak membuka peluang." Ketika ia
mengangkat mangkuk, Musashi merasakan di dalam diri perempuan itu keahlian
surgawi, seperti kelihatan pada seorang guru pedang yang siap memukul.
"Inilah Jalan," demikian pikirnya. "Inilah hakikat seni. Orang
harus memilikinya, agar dapat sempurna dalam apa saja."
Ia mengalihkan
perhatian kepada mangkuk teh di depannya. Inilah pertama kalinya ia mendapat
suguhan dengan cara ini, dan sedikit pun ia tak tahu apa yang mesti dilakukan
berikutnya. Mangkuk teh itu membuat ia kagum, karena meskipun mangkuk itu mirip
dengan yang dibuat anak kecil sewaktu bermain lumpur, namun kalau warna hijau
tua pada busa teh itu diperhatikan dengan latar belakang warna mangkuk,
tampaklah warna itu lebih tenteram dan lembut daripada langit.
Tanpa daya ia pun
memandang Koetsu yang sudah menghabiskan kuenya dan sedang memegang mangkuk
dengan penuh cinta. Ia pegang mangkuk dengan kedua tangannya, seperti sedang
membelai benda hangat di malam yang dingin, dan ia habiskan teh itu dengan
dua-tiga hirupan.
"Pak,"
Musashi berkata agak ragu-ragu, "saya ini cuma anak desa yang bodoh, dan
saya tidak tahu seluk-beluk upacara teh. Saya bahkan tidak tahu pasti,
bagaimana cara minum teh."
Myoshu segera
menegurnya baik-baik. "Oh, begini, Nak, semua itu sama saja. Tak ada yang
namanya canggih atau khusus dalam minum teh. Kalau engkau anak desa, minum saja
seperti caramu di desa."
"Apa boleh
begitu?"
"Tentu saja.
Tingkah laku itu bukan soal peraturan, tapi berasal dari hati. Sama dengan ilmu
pedang, kan?"
"Kalau Ibu
nyatakan demikian, memang ya."
"Kalau engkau
terlalu memikirkan cara yang benar untuk minum, kau takkan menikmati teh itu.
Ketika menggunakan pedang, kau tak bisa membiarkan tubuhmu terlalu tegang. Itu
akan mematahkan keselarasan antara pedang dan semangatmu. Betul begitu?"
"Betul,
Ibu." Tanpa disadari Musashi menganggukkan kepalanya dan menanti biarawati
itu melanjutkan pelajarannya.
Biarawati itu tertawa
sedikit berderai. "Coba dengarkan aku ini! Bicara tentang main pedang,
padahal aku tak tahu apa-apa tentangnya."
"Saya minum teh
saya sekarang," kata Musashi sesudah memperoleh kembali keyakinan dirinya.
Kakinya capek akibat
duduk dalam sikap resmi, karena itu ia berganti posisi bersila supaya lebih
enak. Sebentar saja sudah ia kosongkan mangkuk teh itu dan ia letakkan kembali.
Teh itu sangat pahit. Biarpun untuk sekadar basa-basi, ia tak dapat memaksa
diri mengatakan enak.
"Tambah
lagi?"
"Tidak, terima
kasih, sudah cukup."
Apa enaknya air pahit
macam ini buat orang-orang ini? Kenapa mereka bicara begitu serius tentang
"kemurnian" rasa dan segala macamnya itu? Musashi tak dapat memahami
tuan rumah, namun tak mungkin ia tidak mengaguminya. Bagaimanapun, tentunya ada
hal lain yang tak terlihat olehnya. Kalau tidak, mana mungkin masalah minum teh
ini menjadi faktor penting filsafat tentang estetika dan hidup? Dan mana
mungkin pula orang-orang besar seperti Hideyoshi dan Ieyasu akan mencurahkan
perhatian demikian besar pada minum teh ini, demikian pikir Musashi.
Ia ingat betapa Yagyu
Sekishusai menghabiskan umur tuanya untuk Jalan Teh, dan Takuan pun bicara
tentang kemuliaan. Melihat mangkuk teh dan kain tatakannya, tiba-tiba terbayang
olehnya bunga peoni putih dari kebun Sekishusai itu, dan sekali lagi ia rasakan
getaran yang dulu pernah ia alami. Kini mangkuk itu memberikan getaran yang
sama. Caranya tak bisa dijelaskan. Sesaat lamanya ia bertanya-tanya,
jangan-jangan tadi ia terengah keras.
Ia menjulurkan
tangan, memungut mangkuk dengan penuh cinta dan meletakkannya di atas lutut.
Matanya bercahaya ketika mengamati. Terasa olehnya kegembiraan yang belum
pernah ia rasakan sebelumnya. Diperhatikannya dasar mangkuk itu, demikian juga
jejak-jejak kape tukang tembikar dan sadarlah ia bahwa garis-garis itu
menunjukkan ketajaman yang sama dengan irisan yang dilakukan Sekishusai pada
batang bunga peoni. Mangkuk bersahaja ini pun hasil karya seorang genius.
Mangkuk ini mengungkapkan sentuhan semangat dan wawasan yang misterius.
Hampir-hampir ia tak
dapat bernapas. Tak tahulah ia, tapi kini ia merasakan kekuatan seniman besar
itu, kekuatan yang diam tapi Paso, karena ia memang lebih peka terhadap
kekuatan laten yang bersemayam di situ daripada kebanyakan orang lain. Ia
gosok-gosok mangkuk itu, tak ingin melepaskan kontak fisik dengannya.
"Pak
Koetsu," kata Musashi, "pengetahuan saya tentang alat-alat ini tidak
lebih baik daripada pengetahuan saya tentang teh, tapi saya kira mangkuk ini
dibuat oleh tukang tembikar yang sangat terampil."
"Kenapa
begitu?" kata-kata seniman itu sama lembutnya dengan wajahnya. Matanya
simpatik dan mulutnya bagus bentuknya. Sudut-sudut mata yang turun sedikit
memberikan kesan sungguh-sungguh, namun di sekitar ujung mata terdapat
kerut-merut.
"Saya tak bisa
menjelaskannya, tapi saya merasakannya."
"Jelasnya,
bagaimana menurut perasaanmu? Coba ceritakan."
Musashi berpikir
sejenak, kemudian katanya, "Nah, saya tak dapat mengungkapkannya dengan
jelas sekali, tapi terasa ada yang melebihi kemampuan manusia pada guratan
tajam tanah liat ini..."
"Hmmm."
Koetsu memang memiliki sikap seniman sejati. Sesaat pun ia tak pernah menilai
orang lain tahu banyak tentang karya seninya, dan karena itu merasa pasti
Musashi bukanlah perkecualian. Bibirnya mengerut. "Kenapa guratannya,
Musashi?"
"Bersih
sekali."
"Cuma itu?"
"Tidak, tidak...
lebih rumit dari itu. Ada sesuatu yang besar dan agung dari pembuatnya."
"Apa lagi?"
"Tukang tembikar
itu sendiri sama tajamnya dengan pedang Sagami. Tapi dia menyelimuti semuanya
itu dengan keindahan. Mangkuk teh ini tampak sangat sederhana, tapi terasa ada
keangkuhan, sesuatu yang agung dan congkak, seakan-akan dia menganggap orang
lain belum sepenuhnya manusia."
"Mm."
"Sebagai
manusia, orang yang membuat mangkuk ini sukar ditaksir, saya kira. Siapa pun
orangnya, saya berani bertaruh dia orang terkenal. Tak dapatkah Bapak
menyebutkan siapa dia?"
Bibir Koetsu yang
tebal itu pun tertawa keras. "Namanya Koetsu. Tapi barang ini kubuat hanya
untuk bersenang-senang hati."
Musashi yang tak tahu
bahwa dirinya sedang diuji itu terkejut dan kagum mendengar Koetsu dapat
membuat keramik sendiri. Tapi yang lebih mengesankan daripada luasnya kecakapan
artistik orang itu adalah dalamnya nilai manusia yang tersembunyi dalam mangkuk
teh yang kelihatannya sederhana mi. Agak terganggu juga Ia oleh kedalaman
sumber spiritual Koetsu. Karena terbiasa mengukur orang lain dengan kemampuan
menggunakan pedang, tiba-tiba ia menyimpulkan bahwa kemampuan dirinya terlalu
kecil. Pikiran ini membuatnya merasa hina. Ini satu orang lagi, kepada siapa ia
mesti mengakui kekalahannya. Walaupun pagi itu ia baru saja mendapat kemenangan
gemilang, sekarang ia tak lebih dar seorang pemuda pemalu.
"Jadi, engkau
suka keramik juga, ya?" tanya Koetsu. "Engkau rupanya bisa juga
menilai barang tembikar."
"Saya sangsi
apakah itu benar," jawab Musashi rendah hati. "Saya cuma menyatakan
apa yang ada dalam kepala saya. Maafkan saya, kalau ada yang tolol dalam
kata-kata saya."
"Ya, tentu saja
kita tak bisa mengharapkan kau tahu banyak tentang soal ini. Untuk membuat satu
mangkuk teh yang baik saja dibutuhkan pengalaman selama hidup. Tapi engkau
memang punya rasa keindahan, ada daya tangkap naluriah yang agak kuat. Kukira
engkau sudah mendapat sedikit kemajuan dalam mengembangkan ketajaman matamu,
karena engkau mempelajari ilmu pedang." Ada nada kagum dalam nada suara
Koetsu, tapi sebagai orang yang lebih tua ia tidak dapat memuji anak itu. Tidak
hanya perbuatan itu tidak terpuji, melainkan juga dapat membuat anak itu
sombong.
Tak lama kemudian,
pelayan kembali membawa lebih banyak sayuran liar, dan Myoshu menyiapkan bubur.
Ketika ia sudah memindahkan bubur itu ke piring-piring kecil yang rupanya juga
dibuat oleh Koetsu, seguci sake yang harum pun dipanaskan, dan pesta tamasya
pun dimulai.
Makanan dalam upacara
teh itu terlalu ringan dan lembut untuk selera Musashi. Jasmaninya menghendaki
isi dan rasa yang lebih mantap. Namun ia berusaha juga dengan sebaik-baiknya
menelan bau halus adonan berdaun itu, karena diakuinya banyak yang dapat ia
pelajari dari Koetsu dan ibunya yang luwes itu.
Waktu berlalu terus,
dan ia menoleh ke sekitar ladang dengan gelisah. Akhirnya ia menoleh kepada
tuan rumah, katanya, "Semua ini sangat menyenangkan, tapi sudah waktunya
saya pergi sekarang. Saya masih ingin tinggal di sini, tapi saya kuatir
lawan-lawan saya akan datang dan menimbulkan kesulitan. Tak ingin saya
melibatkan Bapak dalam hal seperti ini. Saya harap saya akan mendapatkan
kesempatan bertemu lagi dengan Bapak."
Myoshu bangkit
melepaskan tamunya, katanya, "Kalau kau kebetulan ada di sekitar Jalan
Hon'ami, jangan tidak mampir ke tempat kami."
"Ya, silakan
datang menengok kami. Kita nanti dapat berbincang-bincang yang enak,"
tambah Koetsu.
Sebetulnya Musashi
sudah kuatir, tapi ternyata tidak tampak tanda-tanda murid-murid Yoshioka.
Habis minta diri, ia berhenti untuk menoleh pada kedua teman barunya. Ya, dunia
mereka itu lain sekali dengan dunianya. Jalannya sendiri yang panjang dan
sempit itu takkan pernah mencapai lingkungan kesenangan hidup Koetsu yang penuh
kedamaian. Ia berjalan diam menuju tepi ladang, kepalanya tertunduk merenung.


0 komentar:
Posting Komentar