Tukang Sapu dan
Pedagang
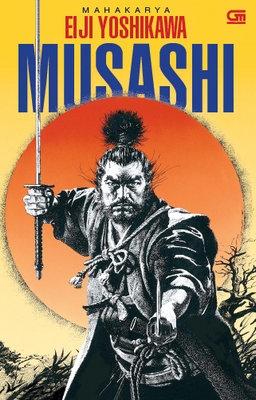
BUNGA-BUNGA sakura
jadi berwarna pucat karena sudah lewat masa puncaknya, sedangkan kembang widuri
sudah layu, mengingatkan orang pada masa berabad-abad lalu, ketikaNara masih
menjadi ibu kota. Hari itu agak terlalu panas untuk berjalan, tapi baik Gonnosuke
maupun Iori belum lelah berjalan.
Iori menarik lengan
baju Gonnosuke, dan katanya kuatir. "Orang itu masih saja mengikuti
kita!"
Gonnosuke terus
memandang lurus ke depan, katanya, "Pura-pura kita tidak melihat
dia."
"Dia sudah di
belakang kita sejak kita meninggalkan Kofukuji."
"Ya."
"Dan dia ada di
penginapan itu, waktu kita tinggal di sana, kan?"
"Tak usah kau
kuatir karena itu. Kita tak punya barang yang patut dirampas."
"Tapi kita punya
nyawa! Nyawa itu bukan barang sepele."
"Ha, ha. Tap aku
sudah mengunci nyawaku. Kau belum, ya?"
"Tapi saya dapat
menjaga diri." Dan Ion mengetatkan genggaman tangan kirinya atas sarung
pedangnya.
Gonnosuke tahu, orang
itu pendeta pengembara yang menantang Nankobo kemarin, tapi ia tak habis pikir,
kenapa pendeta itu menguntit mereka.
Iori menoleh lagi,
dan katanya, "Lho, dia tak ada!"
Gonnosuke menoleh
juga ke belakang. "Barangkali dia capek." Ia menarik napas panjang,
dan tambahnya. "Tapi aku merasa lebih lega sekarang." Mereka menginap
di rumah seorang petani malam itu, dan pagi-pagi hari berikutnya, mereka tiba
di Amano di Kawachi. Tempat itu adalah kampung kecil dengan rumah-rumah yang
rendah tepian atapnya, dan di belakang rumah-rumah itu mengalir sungai dengan
air gunung yang jernih.
Gonnosuke datang ke
situ untuk meletakkan tanda peringatan bagi ibunya di Kuil Kongoji, yang
dinamakan Gunung Koya Para Wanita. Tapi pertama-tama ia ingin mengunjungi
seorang wanita bernama Oan, yang dikenalnya sejak kecil, supaya nantinya selalu
ada orang membakar dupa di hadapan tanda peringatan itu. Kalau wanita itu tak
dapat ditemukannya, ia bermaksud pergi ke Gunung Koya, yaitu tempat pemakaman
bagi orang-orang kaya dan perkasa. la berharap tidak perlu sampai pergi ke
sana, sebab pasti ia akan merasa seperti pengemis kalau harus ke sana.
Ia bertanya pada
istri seorang penjaga toko, dan mendapat keterangan bahwa Oan adalah istri
seorang pembuat sake bernama Toroku; rumahnya adalah yang keempat di sebelah
kanan, dalam pekarangan kuil.
Ketika melewati gerbang,
Gonnosuke heran mengingat kata-kata wanita itu, karena di situ ada papan
pengumuman yang menyatakan bahwa membawa sake dan bawang perai ke pekarangan
suci itu dilarang. Bagaimana mungkin ada penyulingan sake di sana?
Teka-teki kecil
tersebut dipecahkan malam itu, oleh Toroku. Ia minta mereka menganggap tempat
itu sebagai rumah sendiri, dan dengan senang hati menyatakan bersedia berbicara
dengan kepala biara, tentang tanda peringatan bagi ibu Gonnosuke. Toroku
menyatakan bahwa Toyotomi Hideyoshi pernah mencicipi dan menyatakan kekaguman
atas sake yang dibuat untuk kuil itu. Para pendeta kemudian membangun
penyulingan untuk membuat sake bagi Hideyoshi dan lain-lain drtimyo yang
memberikan sumbangan kepada kuil itu. Produk pabrik agak jatuh sesudah meninggalnya
Hideyoshi, tapi kuil masih menyediakan produksinya bagi sejumlah pelindung
khusus.
Ketika Gonnosuke dan
Iori terbangun pagi berikutnya, Toroku sudah pergi. Ia pulang sebentar sesudah
tengah hari, dan mengatakan bahwa sudah dilakukan berbagai persiapan.
Kuil Kongoji terletak
di lembah Sungai Amano, di tengah beberapa puncak gunung berwarna batu lumut.
Gonnosuke, Ion, dan Toroku berhenti sebentar di jembatan yang menuju gerbang
utama. Bunga sakura mengapung di air di bawah jembatan. Gonnosuke membidangkan
dadanya, wajahnya memperlihatkan ketakziman. Iori membenahi kerahnya.
Ketika menghampiri
ruangan utama, mereka disambut oleh kepala biara, seorang lelaki jangkung, agak
kekar, dan mengenakan jubah pendeta biasa. Akan cocok seandainya ia memakai
topi anyaman yang sudah sobek dan sebatang tongkat panjang.
"Apa ini orang
yang ingin melakukan kebaktian untuk ibunya?" tanyanya dengan nada ramah.
"Ya, Pak,"
jawab Toroku sambil bersujud.
Gonnosuke, yang
semula menyangka akan bertemu dengan seorang pendeta berwajah garang dan
mengenakan pakaian brokat emas, menjadi bingung bagaimana akan memberi salam
kepadanya. Ia membungkuk dan memperhatikan ketika kepala biara itu turun dari
serambi, memasukkan kakinya yang besar ke dalam sandal jerami yang kotor, dan
berhenti di depannya. Dengan tasbih di tangan, kepala biara minta mereka
mengikutinya, kemudian seorang pendeta muda mengikuti mereka dari belakang.
Mereka melewati Ruang
Yakushi, kamar makan, pagoda harta bertingkat satu, dan tempat kediaman para
pendeta. Sampai di Ruang Dainichi, pendeta muda itu maju ke depan dan bicara
dengan kepala biara. Kepala biara mengangguk, dan si pendeta membuka pintu
dengan kunci yang sangat besar.
Gonnosuke dan Iori
memasuki ruang besar itu bersama-sama, dan berlutut di hadapan podium para
pendeta. Sepuluh kaki di atas podium terdapat patung raksasa Dainichi dari
emas, Budha alam semesta dari sektesekte rahasia. Beberapa waktu kemudian,
kepala biara muncul dari batik altar, dalam jubah kebesarannya, dan mengambil
tempat di atas podium. Mulailah terdengar alunan kitab sutra. Tanpa kentara, ia
seolah berubah bentuk menjadi seorang pendeta tinggi yang bermartabat.
Kekuasaannya jelas kelihatan dari posisi bahunya.
Gonnosuke
menangkupkan tangan di depan badan. Segumpal awan kecil seolah melintas di
depan matanya, dan dari gumpalan awan itu muncul bayangan Celah Shiojiri, di
mana ia dan Musashi saling menguji kekuatan. Ibunya duduk di sisi lain, tegak
seperti papan. Ia tampak kuatir, seperti ketika dulu ia menyerukan kata yang
menyelamatkan Gonnosuke dalam perkelahian itu.
"Ibu,"
pikir Gonnosuke, "Ibu tak perlu kuatir dengan masa depanku. Musashi sudah
setuju menjadi guruku. Tak lama lagi aku akan dapat mendirikan perguruanku
sendiri. Dunia boleh saja kacau, tapi aku takkan menyeleweng dari Jalan-ku. Dan
aku pun takkan melalaikan kewajibankewajibanku sebagai anak...."
Ketika Gonnosuke
lepas dari lamunan itu, alunan suara kepala biara sudah berhenti, dan ia sudah
pergi. Di sampingnya Iori duduk terpaku, matanya lekat pada wajah Dainichi yang
merupakan keajaiban dalam bidang seni patung, karya Unkei yang agung di abad
ketiga betas.
"Kenapa kau
menatap begitu, Iori?"
Tanpa mengalihkan
pandangannya, kata anak itu, "Kakak saya! Budha ini kelihatan seperti
kakak saya."
Gonnosuke tertawa
mendengarnya. "Apa yang kaubicarakan ini? Melihat dia saja kau belum
pernah. Bagaimanapun, takkan pernah ada orang yang bisa tampak sewelas asih dan
setenteram Dainichi."
Iori menggelengkan
kepala keras-keras. "Tapi saya sudah melihat dia! Dekat kediaman Yang
Dipertuan Yagyu di Edo. Dan bicara dengan dia! Waktu itu saya tidak tahu dia
kakak saya, tapi tadi, waktu kepala biara menyanyi, muka sang Budha berubah
menjadi muka kakak saya. Dan kakak saya seolah mengatakan sesuatu pada
saya."
Mereka keluar dan
duduk di beranda, enggan membuang pesona khayal yang telah mereka peroleh.
"Kebaktian tadi
itu untuk ibuku," kata Gonnosuke termenung. "Tapi hari ini hari baik
juga untuk makhluk hidup. Duduk seperti ini di sini, rasanya sukar aku percaya
bahwa perkelahian dan pertumpahan darah bisa berlangsung."
Puncak pagoda harta
yang terbuat dari logam itu berkilauan seperti pedang bertatahkan permata,
dalam cahaya matahari yang sedang tenggelam. Semua bangunan lain berdiri dalam
bayangan gelap. Lentera-lentera batu berderet di jalan gelap yang mendaki bukit
terjal menuju warung teh gaya Muromachi dan sebuah mausoleum kecil.
Seorang biarawati
tua, dengan kepala tertutup bandana sutra putih, dan seorang laki-laki gempal
berumur sekitar lima puluh tahun, sedang menyapu daun-daunan dengan sapu
jerami, dekat warung teh.
Biarawati itu
mengeluh, kemudian katanya, "Kukira sekarang sudah lebih baik." Hanya
sedikit orang datang ke bagian kuil ini, meski sekadar untuk membersihkan
dedaunan dan bangkai burung yang menumpuk selama musim dingin.
"Ibu tentunya
lelah," kata laki-laki itu. "Kenapa tidak duduk beristirahat? Biar
kuselesaikan." Ia mengenakan kimono katun sederhana dengan mantel tak
berlengan, sandal jerami, dan kaus kulit berpola bunga sakura, berikut pedang
pendek dengan gagang tanpa hiasan yang terbuat dari kulit ikan hiu.
"Aku tidak
lelah," jawab biarawati itu sambil tertawa kecil. "Tapi bagaimana
denganmu? Kau tidak biasa dengan kerja ini. Apa tanganmu tidak lecet?"
"Tidak lecet,
tapi melepuh semua."
Perempuan itu tertawa
lagi, katanya, "Nah, apa itu bukan tanda mata yang bagus buat dibawa
pulang?"
"Aku tak peduli.
Aku merasa hatiku sudah disucikan. Aku berharap persembahan kerja kita yang tak
berarti ini diterima dewa-dewa."
"Oh, sudah gelap
benar. Mari kita selesaikan besok pagi saja."
Gonnosuke dan Iori
sekarang berdiri di dekat serambi. Koetsu dan Myoshu pelan-pelan menyusuri
jalan yang menurun, sambil berpegangan tangan. Ketika sampai di dekat Ruang
Dainichi, keduanya terkejut dan berseru, "Siapa di situ?"
Kemudian kata Myoshu,
"Hari bagus, ya? Apa kalian datang buat melihat-lihat?"
Gonnosuke membungkuk,
katanya, "Tidak, saya mengirim bacaan sutra buat ibu saya."
"Oh, saya senang
sekali bertemu dengan orang muda yang tahu terima kasih kepada
orangtuanya."
Ia menepuk kepala
Iori dengan sikap keibuan.
"Koetsu, apa kue
gandum itu masih ada?"
Koetsu mengeluarkan
bungkusan kecil dari lengan kimononya dan menawarkannya pada Iori.
"Maafkan saya, menawarkan makanan sisa."
"Gonnosuke,
boleh saya menerimanya?" tanya Iori.
"Ya," kata
Gonnosuke, menyatakan terima kasih pada Koetsu atas nama Iori.
"Dari aksen
bicaramu, rupanya kau datang dari timur," kata Myoshu.
"Boleh saya
bertanya, ke mana kalian hendak pergi?"
"Rasanya ini
perjalanan tanpa akhir, di jalan tak ada ujung. Anak ini dan saya sama-sama
murid Jalan Pedang."
"Oh, jalan sulit
yang kalian pilih itu. Siapa guru kalian?"
"Namanya
Miyamoto Musashi."
"Musashi? Yang
benar!" Myoshu tertegun, seakan-akan sedang mengingat kembali kenangan
manis.
"Di mana Musashi
sekarang?" tanya Koetsu. "Lama kami tak jumpa dengannya."
Gonnosuke
menyampaikan pada mereka tentang nasib baik Musashi selama beberapa tahun
terakhir itu. Sambil mendengarkan, Koetsu mengangguk-angguk dan tersenyum,
seakan-akan mengatakan. "Itu yang saya harapkan untuknya."
Selesai bercerita,
Gonnosuke bertanya, "Boleh saya tahu siapa Bapak?"
"O ya, maaf saya
tidak mengatakannya tadi."
Koetsu memperkenalkan
dirinya dan ibunya. "Musashi tinggal dengan kami sebentar, beberapa tahun
lalu. Kami suka sekali padanya, dan sampai sekarang pun masih sering kami
bicara tentangnya." Kemudian ia bercerita pada Gonnosuke tentang dua-tiga
peristiwa yang terjadi ketika Musashi ada di Kyoto.
Gonnosuke sudah lama
tahu nama baik Koetsu sebagai penggosok pedang, dan baru-baru ini ia mendengar
tentang hubungan Musashi dengan orang itu. Tapi ia tak pernah menduga akan
melihat orang kota yang kaya itu membersihkan pekarangan kuil yang
terbengkalai.
"Apa di sini ada
kuburan orang yang dekat dengan Bapak?" tanyanya. "Atau barangkali
Bapak datang kemari untuk pesiar?"
"Tidak, tak ada
yang lebih sembrono daripada pesiar," seru Koetsu. "Setidaknya di
tempat suci seperti ini.... Apa kalian sudah mendengar dari para pendeta,
riwayat Kuil Kongoji ini."
"Belum."
"Kalau begitu,
izinkan saya sebagai ganti para pendeta, bercerita sedikit tentangnya. Tapi
harap dimengerti, saya hanya mengulang apa yang pernah saya dengar."
Koetsu berhenti dan menoleh ke sekitar pelan-pelan, kemudian katanya,
"Tepat sekali bulan malam ini," dan ia menunjuk beberapa peninggalan
penting: di atas mereka mausoleum, Mieido dan Kangetsutei, di bawah mereka
Taishido, tempat suci Shinto, pagoda harta, ruang makan, dan gerbang bertingkat
dua.
"Lihat
baik-baik," katanya, seolah-olah terpesona oleh suasana sepi itu.
"Pohon pinus itu, batu-batu itu, setiap pohon, setiap lembar rumput di
sini, adalah bagian dari keabadian yang tak kelihatan, yang merupakan tradisi
molek negeri kita."
Ia meneruskan dalam
nada sama, dan dengan khidmat bercerita bahwa di abad keempat belas, selama
berlangsungnya konflik antara istana selatan dan utara, gunung itu menjadi kubu
istana selatan. Dikatakannya, Pangeran Morinaga, yang dikenal juga sebagai
Daito no Miya, mengadakan pertemuanpertemuan rahasia untuk menggulingkan para
regent Hojo. Sementara itu, Kusunoki Masashige dan kaum loyalis yang lain
bertempur melawan tentara istana utara. Kemudian Keluarga Ashikaga memegang
kekuasaan, dan Kaisar Go-Murakami yang terusir dari Gunung Otoko terpaksa
melarikan diri dari tempat satu ke tempat lain. Akhirnya ia berlindung di kuil
itu, dan bertahun-tahun lamanya hidup sebagai pendeta gunung biasa, dengan
menanggung berbagai kekurangan. Dengan menggunakan ruang makan itu sebagai
pusat pemerintahannya, ia bekerja tanpa kenal lelah untuk memperoleh kembali
hak istimewa kekaisaran yang direbut militer.
Sebelum itu, ketika
para samurai dan orang-orang istana berkumpul di sekitar mantan Kaisar Kogon,
yaitu Komyo dan Suko, biarawan Zen'e menulis dengan pedih, "Tempat tinggal
para pendeta dan kuil-kuil gunung semuanya diruntuhkan. Kerugian tidak
terlukiskan."
Gonnosuke
mendengarkan dengan sikap hati-hati dan penuh hormat. Iori, yang terpesona oleh
kesungguhan suara Koetsu, tidak dapat melepaskan matanya dari wajah orang itu.
Koetsu menarik napas
panjang, meneruskan, "Segala sesuatu di sini adalah peninggalan zaman itu.
Mausoleum itu tempat peristirahatan terakhir Kaisar Kogon. Sejak surutnya
Keluarga Ashikaga, tak ada yang terawat secara memadai. Itu sebabnya ibu saya
dan saya memutuskan untuk membersihkannya sedikit, sebagai tanda takzim."
Karena senang dengan
ketekunan para pendengarnya, Koetsu berusaha keras mencari kata-kata yang cocok
untuk mengungkapkan perasaannya.
"Waktu sedang
menyapu, kami temukan sebuah batu berukir sajak, yang barangkali ditulis oleh
seorang prajurit pendeta zaman itu. Bunyinya:
Biar perang berjalan
terus, Sampai seratus tahun sekalipun, Musim semi kan datang kembali, Hiduplah
dengan hati bernyanyi. Hai, kalian rakyat sang Kaisar.
"Coba bayangkan,
betapa besar keberanian dan semangat yang diperlukan oleh seorang prajurit
sederhana yang sudah bertempur bertahun-tahun, dan barangkali berpuluh-puluh
tahun lamanya, dalam melindungi sang kaisar, untuk dapat bergembira dan
menyanyi! Saya yakin, dasarnya adalah karena semangat. Masashige bersemayam di
had prajurit itu. Walaupun seratus tahun pertempuran telah berlalu, tempat ini
tetap menjadi tanda peringatan bagi martabat kekaisaran. Maka, tidakkah kita mesti
menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hal ini?"
"Saya tidak tahu
bahwa ini dulu tempat berlangsungnya pertempuran suci," kata Gonnosuke.
"Saya harap Bapak memaafkan ketidaktahuan saya."
"Saya senang
mendapat kesempatan menyampaikan sebagian buah pikiran saya mengenai sejarah
negeri kita ini."
Keempat orang itu
berjalan menuruni bukit bersama-sama. Di dalam terang bulan, bayangan mereka
tampak kecil tak berarti.
Ketika mereka
melewati ruang makan, Koetsu berkata, "Kami sudah tujuh hari tinggal di
sini. Kami akan pulang besok. Kalau kalian bertemu dengan Musashi, sampaikan
padanya supaya dia menengok kami lagi."
Gonnosuke menegaskan
bahwa ia akan menyampaikan pesan itu.
Di atas sungai dangkal
yang mengalir cepat sepanjang dinding luar kuil itu, ada sebuah jembatan tanah.
Belum lagi Gonnosuke
dan Iori menginjakkan kaki di jembatan itu, sesosok tubuh besar putih
bersenjatakan tongkat muncul dari balik bayangan, dan melesat menyerang punggung
Gonnosuke. Gonnosuke menghindar dari serangan itu dengan meluncur ke samping,
tapi Iori terpental dari jembatan.
Orang itu menyeruduk
lewat Gonnosuke, ke jalan di ujung sana jembatan. Tapi seketika itu juga ia
berbalik dan mengambil jurus mantap, kedua kakinya mirip batang pohon kecil.
Gonnosuke melihat bahwa orang itu pendeta yang telah mengikuti mereka kemarin.
"Siapa
kau?" teriak Gonnosuke.
Pendeta itu tak
menjawab.
Gonnosuke
menggerakkan tongkatnya dalam posisi siap memukul, dan berteriak, "Siapa
kau? Apa alasanmu menyerang Muso Gonnosuke?"
Pendeta itu pura-pura
tak mendengar. Matanya memercikkan api, sementara jari-jari kakinya yang
menyembul dari dalam sandal jerami yang berat itu merayap maju seperti lipan.
Gonnosuke menggeram
dan mengutuk berbisik. la beringsut ke depan dengan kakinya yang pendek berat,
yang kini menggelembung karena nafsu berkelahi.
Tongkat si pendeta
patah berderak menjadi dua. Separuh melayang ke udara, separuh lagi dilontarkan
sekuat-kuatnya ke wajah Gonnosuke. Lontaran itu tidak mengena, tapi sementara
Gonnosuke memulihkan keseimbangan badannya, lawannya menarik pedang dan
menyerbu ke jembatan.
"Bajingan!"
pekik Iori.
Pendeta itu menggagap
dan memegang wajahnya. Batu-batu kecil yang dilemparkan Ion mengenai
sasarannya, satu di antaranya tepat mengenai mata. Si pendeta pun berpusing dan
lari.
"Berhenti!"
teriak Iori sambil merangkak naik ke tepi sungai, membawa sejumlah batu.
"Biarkan,"
kata Gonnosuke sambil meletakkan tangan ke lengan Iori. "Biar dia tahu
rasa!" ucap Iori puas, sambil melontarkan bebatuan itu ke bulan.
Segera sesudah mereka
kembali ke rumah Toroku dan pergi tidur, badai bertiup. Angin meraung-raung di
antara pepohonan, mengancam akan menerbangkan atap rumah, tapi itu bukan
satu-satunya hal yang membuat mereka susah tidur.
Gonnosuke terbaring
terjaga, teringat masa lalu dan masa sekarang. Terpikir olehnya, apakah dunia
ini memang lebih baik sekarang daripada berabad-abad lampau. Nobunaga, Hideyoshi,
dan Ieyasu telah memperoleh simpati rakyat, juga kekuasaan untuk memerintah,
tapi terpikir oleh Gonnosuke, tidakkah penguasa yang sebenar-benarnya itu telah
terlupakan, dan kini rakyat disuruh menyembah dewa-dewa palsu? Zaman Keluarga
Hojo dan Ashikaga adalah zaman yang menimbulkan rasa benci, yang jelas-jelas
berlawanan dengan prinsip yang menjadi dasar berdirinya negeri ini. Namun, di
zaman itu pun, para prajurit besar seperti Masashige dan anaknya, juga loyalis
dari banyak provinsi, tetap mengikuti tata krama prajurit sejati. Apa yang
telah terjadi dengan Jalan Samurai? Ya, Gonnosuke kini bertanya pada diri
sendiri. Seperti halnya Jalan Orang Kota dan Jalan Petani, agaknya Jalan
Samurai sekarang ini hanyalah demi penguasa militer.
Pikiran-pikiran itu
membuat sekujur tubuh Gonnosuke terasa panas. Puncak Pegunungan Kawachi, hutan
di sekitar Kuil Kongoji, dan badai yang melolong-semuanya jadi seperti
makhluk-makhluk hidup yang berseruseru kepadanya dalam mimpi.
Sementara itu, Iori
tak dapat mengusir pendeta tak dikenal itu dari pikirannya. Ia masih juga
memikirkan sosok putih seperti hantu itu, lama kemudian. Ketika badai makin
menghebat, ditutupkannya selimut ke atas matanya, dan barulah ia terlena dalam
tidur lelap tanpa mimpi.
Ketika mereka berangkat
lagi pagi berikutnya, awan-awan di atas pegunungan berwarna pelangi. Baru saja
mereka keluar dari kampung, seorang pedagang keliling muncul dari balik kabut
pagi, dan mengucapkan selamat pagi pada mereka dengan nada riang.
Gonnosuke menjawab
acuh tak acuh. Iori masih terbenam dalam pikiran yang membuatnya tak bisa tidur
malam sebelumnya, jadi ia pun tidak terlalu ramah.
Orang itu mencoba
membuka percakapan. "Anda menginap di rumah Toroku tadi malam, ya? Saya
sudah bertahun-tahun mengenalnya. Mereka orang-orang baik, dia dan
istrinya."
Kata-kata itu hanya
dapat memancing sungutan pelan Gonnosuke.
"Saya juga
sekali-sekali berkunjung ke Benteng Koyagyu," kata pedagang itu.
"Kimura Sukekuro banyak membantu saya."
Kata-kata itu dijawab
dengan sungutan lagi.
"Saya lihat Anda
telah mengunjungi 'Gunung Koya Para Wanita.' Saya kira sekarang Anda akan pergi
ke Gunung Koya itu sendiri. Sekaranglah waktu yang tepat. Salju mulai mencair,
dan semua jalan sudah diperbaiki. Anda dapat melintasi celah Amami dan Kiimi
dengan santai, dan menginap di Hashimoto atau Kamuro..."
Usaha orang itu untuk
mencari tahu rencana perjalanan mereka membuat Gonnosuke curiga. "Apa
kerja Anda?" tanyanya.
"Saya penjual
tali kepang," kata orang itu, sambil menunjuk bungkusan kecil di
punggungnya. "Tali ini dibuat dari katun yang dianyam datar. Belum lama
ditemukan, tapi sudah cepat disukai orang."
"Begitu,"
kata Gonnosuke.
"Toroku banyak
membantu memasarkan tali saya ini kepada para pemuja di Kuil Kongoji.
Sebetulnya saya punya rencana menginap di rumahnya tadi malam, tapi katanya
sudah ada dua tamu. Agak kecewa juga. Kalau saya tinggal di rumahnya, dia selalu
menyuguhi saya sake yang enak." Ia tertawa.
Gonnosuke jadi agak
luluh, dan mulai mengajukan pertanyaan tentang tempat-tempat di sepanjang jalan
itu, karena pedagang itu kenal benar dengan pedesaan di situ. Begitu mereka
sampai di dataran tinggi Amami, percakapan sudah menjadi cukup bersahabat.
"Hei,
Sugizo!"
Seorang lelaki datang
menderap di jalanan itu, menyusul mereka. "Kenapa kautinggalkan aku? Aku
tunggu di Kampung Amano. Kaubilang akan singgah menjemputku."
"Maaf,
Gensuke," kata Sugizo. "Aku jumpa dengan kedua teman ini dan asyik
bercakap-cakap, sampai lupa sama sekali padamu." Ia tertawa dan menggaruk
kepalanya.
Gensuke, yang
berpakaian seperti Sugizo itu, ternyata pedagang tali juga. Sementara berjalan,
kedua pedagang itu mulai membicarakan soal perdagangan.
Sampai di sebuah
jurang yang dalamnya sekitar enam meter, tiba-tiba Sugizo berhenti bicara dan
menunjuk.
"Itu
berbahaya," katanya.
Gonnosuke berhenti
dan memandang jurang yang menyerupai celah sisa gempa bumi, yang barangkali
terjadi di masa lalu. "Apa susahnya?" tanyanya.
"Balok-balok itu
tidak aman buat menyeberang. Lihat itu, sebagian batu yang mendukungnya sudah
terbawa hanyut. Lebih baik kita bereskan dulu balok-balok itu, supaya
kokoh." Kemudian tambahnya. "Kita mesti melakukannya, demi pejalan
yang lain."
Gonnosuke
memperhatikan mereka ketika mereka berjongkok di ujung karang terjal, dan mulai
memadatkan batu-batuan dan tanah di bawah balok-balok itu. Pikirnya, kedua
pedagang itu banyak mengadakan perjalanan, dan karena itu kenal betul akan
kesulitan-kesulitan perjalanan, seperti juga orang lain. Namun ia agak heran
juga.
Sungguh tidak biasa,
bahwa orang-orang seperti mereka begitu mencurahkan perhatian pada kepentingan
orang lain, hingga mau bersusah-susah membetulkan jembatan.
Iori sama sekali
tidak memikirkan soal itu. la terkesan oleh keprihatinan mereka, dan ia
membantu mengumpulkan batu untuk mereka.
"Saya kira ini
cukup," kata Gensuke. Ia melangkah ke atas jembatan. Ia putuskan jembatan
itu aman, lalu katanya pada Gonnosuke, "Saya jalan dulu." Sambil
merentangkan tangan untuk keseimbangan, ia menyeberang cepat ke sebelah sana,
kemudian mengajak yang lain-lain menyusul.
Atas desakan Sugizo,
Gonnosuke menyusul, diikuti Iori. Tapi belum lagi sampai tengah jembatan,
mereka sudah memekik kaget. Di hadapan mereka, Gensuke menghadangkan mata
lembing ke arah mereka. Gonnosuke menoleh ke belakang, dan melihat Sugizo telah
memegang lembing juga.
"Dari mana
datangnya lembing-lembing itu?" pikir Gonnosuke. Ia menyumpah dan
menggigit bibir dengan marah, sadar akan kedudukannya yang tidak menguntungkan.
"Gonnosuke,
Gonnosuke..." Dengan sembrono Iori berpegang pada pinggang Gonnosuke.
Gonnosuke sendiri memeluk anak itu dan memejamkan mata sesaat, mempercayakan
hidupnya pada kehendak Langit.
"Bajingan
kalian!"
"Tutup
mulut!" teriak pendeta yang berdiri lebih tinggi di jalan, di belakang
Gensuke, dengan mata kiri bengkak hitam.
"Tenang
saja," kata Gonnosuke pada Iori, dengan suara menenangkan. Kemudian
teriaknya, "Jadi, kaulah biang keladi semua ini! Nah, awaslah, bajingan
pencuri! Kalian berkelahi melawan orang yang keliru kali ini!"
Si pendeta menatap
dingin ke arah Gonnosuke. "Kau tidak layak dirampok. Kau tahu itu. Kalau
kau tidak lebih pintar dari itu, kenapa pula kau mencoba jadi mata-mata?"
"Kausebut aku mata-mata?"
"Anjing
Tokugawa! Buang tongkatmu. Kebelakangkan tanganmu. Dan jangan coba berbuat
sesuatu yang konyol."
"Ah!" keluh
Gonnosuke, seakan-akan kehendak untuk berkelahi sudah tak ada lagi dalam
dirinya. "Coba dengar! Kau keliru. Aku memang datang dari Edo, tapi aku
bukan mata-mata. Namaku Muso Gonnosuke. Aku ini shugyosha."
"Silakan saja
kau berbohong."
"Kenapa kaukira
aku mata-mata?"
"Belum lama ini,
teman-teman kami di timur, menyuruh kami hati-hati pada lelaki yang berjalan
dengan seorang anak lelaki. Kau dikirim kemari oleh Yang Dipertuan Hojo dari
Awa, kan?"
"Tidak."
"Buang tongkat
itu dan ayo ikut kami baik-baik."
"Aku tidak akan
ke mana-mana denganmu."
"Kalau begitu,
kau akan man di tempat ini juga."
Gensuke dan Sugizo
mulai mendesak dari depan dan belakang, dengan lembing siap beraksi.
Agar Iori lepas dari
bahaya, Gonnosuke menepuk punggungnya. Sambil memekik keras, Iori jatuh ke
dalam semak-semak yang menutupi dasar jurang.
Sementara itu,
Gonnosuke menverbu Sugizo, disertai suara menggeledek, "Y a-a-h!"
Untuk dapat mencapai
sasarannva, lembingnya membutuhkan ruang dan saat yang tepat. Sugizo
menjulurkan tangan untuk menusukkan senjatanya ke depan, tapi tidak memperoleh
saat yang tepat. Pekik parau keluar dari tenggorokannya, ketika ujung lembing
menetak udara tipis. Gonnosuke mengempaskan diri ke tubuhnya, dan ia rebah
ditimpa Gonnosuke. Ketika ia mencoba berdiri, Gonnosuke menghantamkan tinju
kanan ke wajahnya. Sugizo meringis, tapi akibatnya menggelikan, karena wajah
itu sudah berlumuran darah. Gonnosuke berdiri, menginjak kepala Sugizo sebagai
papan loncatan, untuk mencapai ujung jembatan.
Dengan tongkat
terpasang, pekiknya, "Aku tunggu di sini. Pengecut-pengecut!"
Belum selesai ia
memekik, tiga utas tali sudah melintas rumput. Yang satu diberati gagang
pedang, yang lain pedang pendek bersarung. Satu tali melilit tangan Gonnosuke,
yang lain kedua kakinya, dan yang ketiga lehernya. Sesaat kemudian, satu tali
lagi melilit tongkatnya.
Gonnosuke
menggeliat-geliat seperti serangga terjerat sarang labah-labah, tapi tidak
lama. Setengah lusin orang berlarian keluar dari hutan di belakangnya. Begitu
mereka selesai meringkusnya, Gonnosuke terbaring tak berdaya di tanah, terikat
lebih erat daripada seikat jerami. Terkecuali pendeta bermuka masam itu, semua
orang yang menangkapnya mengenakan pakaian pedagang tali.
"Tak ada
kuda?" tanya si pendeta. "Aku tak ingin menyuruhnya jalan sampai
Gunung Kudo."
"Mungkin kita
bisa menyewa kuda di Desa Amami."


0 komentar:
Posting Komentar