Bermain Api
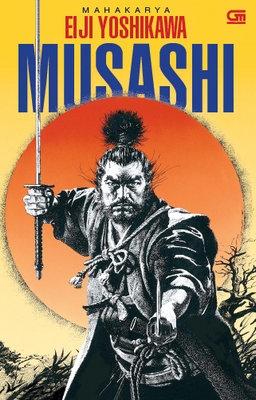
TIDAK seperti
jalan-jalan utama yang lain, tidak ada pepohonan mengapit jalan raya Koshu,
yang menghubungkan Shiojiri dan Edo lewat Provinsi Kai. Jalan yang dipergunakan
untuk keperluan militer selama abad enam belas itu tidak memiliki jaringan
jalan belakang sejenis jaringan Nakasendo, dan belum lama ditingkatkan menjadi
jalan utama. Untuk musafir yang datang dari Kyoto atau Osaka, ciri yang paling
tidak menyenangkan pada jalan raya Koshu itu adalah tidak adanya penginapan dan
tempat makan yang baik. Pesanan makanan bekal paling-paling dapat dipenuhi dengan
lempengan kue betas terbungkus daun bambu yang tidak membangkitkan selera, atau
bahkan lebih tidak merangsang lagi dari itu, kepalan nasi putih terbungkus daun
ek kering. Walaupun makanan di situ sederhana sekalibarangkali tidak banyak
bedanya dengan makanan zaman Fujiwara beberapa ratus tahun sebelum
itu-penginapan-penginapan kasar itu dikerumuni banyak tamu juga, kebanyakan
menuju Edo.
Sekelompok musafir
sedang beristirahat di atas Celah Kobotoke. Seorang dari mereka berseru,
"Lihat, ada satu rombongan lagi." Yang dimaksud adalah pemandangan
yang hampir setiap hari dinikmatinya bersama temantemannya-serombongan pelacur
yang sedang dalam perjalanan dari Kyoto ke Edo.
Gadis-gadis itu
jumlahnya sekitar tiga puluh orang, sebagian umur dua puluhan atau awal tiga
puluhan, dan setidak-tidaknya ada lima yang umurnya belasan tahun. Bersama
sekitar sepuluh orang yang mengelola atau melayani, mereka mirip keluarga
besar. Di samping mereka masih ada beberapa ekor kuda beban yang dimuati segala
macam barang, mulai dari keranjang anyaman kecil sampai peti-peti kayu sebesar
orang.
Kepala
"keluarga", yaitu seorang lelaki berumur sekitar empat puluh tahun,
sedang berbicara kepada gadis-gadisnya. "Kalau sandal jerami kalian bikin
melepuh, ganti dengan zori, tapi mesti diikat baik-baik, supaya tidak lepas ke
sana-sini. Dan jangan lagi mengeluh tak dapat berjalan terus. Lihat saja
anak-anak di jalanan itu!" Jelas dari nada bicaranya yang masam bahwa orang
itu mengalami kesulitan dalam memaksa orang-orang tanggungan yang biasanya tak
pernah bepergian itu untuk terus berjalan.
Orang itu, yang
bernama Shoji Jinnai, adalah penduduk asli Fushimi keturunan samurai, yang
karena alasan-alasan pribadi meninggalkan kehidupan militer dan menjadi pemilik
rumah pelacuran. Karena biasa cepat berpikir, banyak akal, ia berhasil
memperoleh dukungan dari Tokugawa Ieyasu yang sering tinggal di Benteng
Fushimi. Ia tidak hanya memperoleh izin memindahkan usahanya ke Edo, tetapi
juga dapat meyakinkan banyak rekan seusahanya untuk berbuat demikian juga.
Di dekat puncak
Kobotoke, Jinnai menyuruh iring-iringannya berhenti, katanya, "Sekarang
ini masih pagi, tapi kita dapat makan siang sekarang." Sambil menoleh
kepada Onao, seorang perempuan tua yang jadi semacam induk ayam, ia
memerintahkan mengeluarkan makanan.
Keranjang berisi
bekal makanan segera diturunkan dari salah satu kuda beban, dan kepalan nasi
terbungkus daun dibagikan kepada para perempuan itu, yang kemudian berpencar
mengistirahatkan diri. Debu yang membuat kuning kulit mereka juga membuat
rambut mereka yang hitam menjadi hampir putih, sekalipun mereka mengenakan
caping jalan bertepi lebar atau mengikatkan saputangan ke kepala. Karena tidak
ada teh, acara makan itu diiringi banyak jilatan lidah dan isapan gigi. Tidak
tampak di situ tipu muslihat seksual atau getaran cinta. "Tangan siapa
yang akan memeluk kembang merah padam ini malam nanti?" Benar-benar
kata-kata yang terasa tidak pada tempatnya.
"Oh, enak
sekali!" teriak salah seorang anak buah Jinnai yang masih muda, dengan
gembiranya. Nada suaranya itu kiranya bisa mendatangkan air mata ibunya.
Perhatian dua-tiga
orang lainnya mengembara dari makan siang itu, dan terpusat pada seorang
samurai muda yang lewat. "Tampan dia, ya?" bisik seorang.
"Ya,
lumayan," jawab yang lain, yang lebih duniawi pandangannya.
Yang ketiga
menyambut, "Ah, aku kenal dia itu. Dia biasa datang ke tempat kami, dengan
orang-orang dari Perguruan Yoshioka."
"Yang mana yang
kamu bicarakan itu?" tanya lainnya, yang matanya bernafsu.
"Yang muda itu,
yang tegap jalannya, membawa pedang panjang di punggungnya."
Tak sadar akan
kekaguman orang-orang itu, Sasaki Kojiro terus berusaha lewat saja di antara
barisan kuli dan kuda beban.
Satu suara tinggi
mencumbu berseru, "Pak Sasaki! Ke sini, Pak Sasaki!"
Karena banyak orang
yang bernama Sasaki, maka Kojiro sama sekali tidak menoleh.
"Bapak yang
pakai jambul!"
Alis Kojiro naik, dan
ia memutar badan.
"Jaga
lidahmu!" teriak Jinnai marah. "Kau terlalu kasar." Tapi ketika
ia menengadah dari makannya, dikenalinya Kojiro.
"Ya, ya,"
katanya sambil bangkit cepat-cepat. "Kalau tidak salah, ini teman saya
Sasaki! Ke mana Anda pergi, kalau boleh saya bertanya?"
"Oh, halo! Anda
pemilik Sumiya, kan? Saya dalam perjalanan ke Edo. Dan bagaimana dengan Anda?
Anda rupanya pindah besar-besaran, ya?"
"Betul. Kami
pindah ke ibu kota baru."
"Betul? Anda
yakin dapat kemajuan di sana?"
"Tak ada yang
bisa tumbuh di air yang tak mengalir."
"Kalau melihat
perkembangan Edo, saya bayangkan di sana banyak pekerjaan untuk pekerja
bangunan dan pandai senapan. Tapi hiburan yang elok? Masih meragukan, apa di
sana banyak permintaan."
"Anda salah
sangka. Para perempuan sudah menciptakan kota Osaka, sebelum Hideyoshi mulai
memperhatikannya."
"Barangkali
juga, tapi di tempat sebaru Edo itu, barangkali menemukan rumah yang cocok saja
pun Anda tak bisa."
"Keliru lagi.
Pemerintah sudah menyisihkan tanah rawa di tempat yang namanya Yoshiwara untuk
orang-orang dari bidang saya. Rekan-rekan saya sudah masuk, membuat
jalan-jalan, dan membangun rumah. Dari laporan yang saya peroleh, saya akan
dapat dengan mudah memperoleh tempat di pinggir jalan yang baik."
"Maksud Anda,
Keluarga Tokugawa memberikan tanahnya? Cuma-cuma?"
"Tentu. Siapa
mau bayar tanah rawa? Pemerintah bahkan menyediakan sebagian bahan
bangunannya."
"Oh, begitu.
Tidak heran, Anda semua meninggalkan daerah Kyoto."
"Dan bagaimana
dengan Anda? Atau Anda sudah punya bayangan mendapat kedudukan pada seorang
daimyo?"
"Ah, tidak. Tak
ada yang seperti itu. Saya akan menerimanya, kalau ada tawaran. Saya cuma ingin
melihat apa yang terjadi di Edo, karena tempat itu menjadi tempat semayam
shogun, dan di masa depan dari situlah asalnya macam-macam perintah. Tentu saja
sekiranya saya diminta menjadi instruktur shogun, mungkin saya terima."
Jinnai bukan orang
yang dapat menilai ilmu permainan pedang, tetapi penglihatannya atas manusia
sangatlah tajam. Menurut pikirannya, lebih baik ia tidak memberikan komentar
atas kecongkakan Kojiro yang tak terkendalikan itu. Karena itu, ia memalingkan
muka dan mulai menyuruh anak buahnya bergerak. "Sudah waktunya kita jalan
lagi."
Onao menghitung
kepala orang-orang itu, dan katanya, "Rupanya kita kehilangan satu orang.
Siapa kali ini? Kicho? Atau barangkali Sumizome. Tidak, mereka berdua ada di
sana. Aneh. Siapa rupanya?"
Karena tak suka
berteman jalan rombongan pelacur, Kojiro berjalan sendiri.
Beberapa gadis yang
pulang dari mencari gadis yang hilang itu kini kembali ke tempat Onao.
Jinnai menyatukan
diri dengan mereka. "Sini, sini, Onao, jadi yang mana yang hilang?"
"Ah, saya tahu
sekarang. Yang namanya Akemi," jawabnya menyesal, seakan-akan kesalahan
itu ia yang melakukan. "Yang Bapak ambil di jalan, di Kiso itu."
"Tentunya masih
di sekitar tempat ini."
"Kami sudah
mencari di mana-mana. Dia tentunya sudah lari."
"Ah, aku tak
punya perjanjian tertulis dengan dia, dan aku juga tidak meminjamkan 'uang
badan' kepadanya. Dia bilang dia mau, dan karena wajahnya cukup menarik untuk
dipasarkan, kuambil dia. Sekalipun kukira dia sudah menghabiskan biaya jalan
yang lumayan, tapi tak banyak, jadi tak perlu kuatir. Biarkan saja dia. Ayo
kita jalan."
Dan mulailah ia
menggiring rombongannya. Ia ingin sampai di Hachioji dalam sehari, sekalipun
itu berarti berjalan sesudah matahari terbenam. Kalau mereka dapat berjalan
sejauh itu, mereka akan sampai di Edo hari berikutnya.
Tidak lama kemudian,
Akemi muncul kembali dan menggabungkan diri dengan mereka.
"Di mana kamu
tadi?" tanya Onao marah. "Kau tak boleh berkeliaran ke mana-mana
tanpa mengatakan ke mana kau pergi. Kecuali kalau kau mau meninggalkan
kami." Perempuan tua itu lalu menjelaskan dengan cara yang menurutnya
benar, bahwa mereka semua sudah kuatir dengan Akemi.
"Ibu tak
mengerti," kata Akemi. Cacian perempuan tua itu hanya disambutnya dengan
tawa mengikik. "Ada lelaki yang saya kenal di jalan tadi, dan saya tidak
ingin dilihat olehnya. Saya lari ke rumpun bambu, tapi tak tahu di situ ada
turunan. Saya tergelincir sampai ke dasar." Ia menguatkan keterangannya
dengan mengangkat kimononya yang sobek dan sikunya yang terkelupas. Namun selagi
ia memohon maaf itu, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun tanda menyesal.
Dari kedudukannya
yang hampir di depan, Jinnai sudah mendengar tentang apa yang terjadi, dan
memanggil Akemi. Dengan garang katanya, "Namamu Akemi, kan? Akemi... ini
nama yang sukar diingat. Kalau kau betul-betul mau berhasil dalam usaha ini,
kau mesti mencari nama yang lebih baik. Coba katakan, apa kau sudah betul-betul
mengambil keputusan akan kerja di sini?"
"Apa menjadi
pelacur itu membutuhkan keputusan?"
"Ini bukan hal
yang dapat kaujalani sekitar sebulan, kemudian kau pergi. Dan kalau kau menjadi
anggotaku, kau mesti memberikan apa yang diminta para langganan, suka atau
tidak suka. Jadi, jangan sampai keliru soal ini."
"Buat saya,
semua itu sudah tak ada bedanya. Orang-orang lelaki sudah bikin hidup saya
berantakan."
"Itu sama sekali
bukan sikap yang benar. Coba pikirkan soal ini baik-baik. Kalau kau berubah
pendirian sebelum sampai Edo, itu baik. Aku takkan minta kau mengembalikan
biaya makan dan penginapan."
Hari itu juga, di
Kuil Yakuoin di Takao, seorang lelaki tua yang agaknya baru lepas dari himpitan
urusan usahanya, akan mulai menikmati bagian santai perjalanannya. Ia,
pembantunya, dan seorang anak lelaki umur sekitar lima belas tahun, datang di
sana malam sebelumnya dan meminta penginapan. Ia dan anak lelaki itu sudah
mengelilingi kompleks-kompleks kuil sejak pagi-pagi benar. Sekarang sekitar
tengah hari.
"Pergunakan ini
untuk memperbaiki atap, atau apa saja yang perlu," katanya. Ia menyerahkan
kepada salah seorang pendeta itu tiga mata uang emas besar.
Pendeta kepala, yang
mendapat berita tentang hadiah itu, demikian terkesan oleh kemurahan hati si
dermawan, hingga ia bergegas keluar untuk bertukar salam. "Barangkali Anda
akan meninggalkan nama?" katanya.
Pendeta lain
mengatakan bahwa hal itu sudah dilakukan, dan menunjukkan kepadanya tulisan
dalam daftar kuil, yang bunyinya, "Daizo dari Narai, pedagang ramuan,
tinggal di kaki Gunung Ontake, di Kiso."
Pendeta kepala
meminta maaf dengan sangat atas rendahnya mutu makanan yang dihidangkan oleh
kuil, karena Daizo dari Narai dikenal di seluruh negeri sebagai penyumbang yang
dermawan kepada tempat-tempat suci dan kuil-kuil. Pemberiannya selalu berbentuk
mata uang emas-dalam beberapa peristiwa, kata orang, bahkan mencapai jumlah
beberapa lusin. Hanya ia seorang yang mengetahui, apakah ia melakukan itu untuk
hiburan, untuk mencari nama baik, ataukah karena kesalehan.
Pendeta ingin sekali
Daizo tinggal lebih lama, dan memohon kepadanya untuk melihat-lihat kekayaan kuil,
suatu hak istimewa yang hanya diberikan kepada beberapa orang.
"Saya takkan
lama di Edo," kata Daizo. "Dan saya akan datang melihatnya lain
kali."
"Tentu, tentu,
tapi setidaknya mari saya temani ke gerbang luar," desak pendeta itu.
"Apakah Anda punya rencana menginap di Fuchu malam ini?"
"Tidak, di
Hachioji."
"Kalau begitu,
ini perjalanan yang mudah."
"Tapi siapa
penguasa Hachioji sekarang?"
"Baru-baru ini
diletakkan di bawah administrasi Okubo Nagayasu."
"Dia dulunya
hakim di Nara, kan?"
"Ya, benar.
Tambang emas di Pulau Sado juga di bawah pengawasannya. Dia kaya raya."
"Orang pandai
nampaknya."
Hari masih terang
ketika mereka sampai di kaki pegunungan itu, dan berdiri di jalan utama yang
ramai di Hachioji, di mana kabarnya terdapat tidak kurang dari dua puluh lima
penginapan.
"Nah, Jotaro, di
mana kita menginap?"
Jotaro, yang menempel
terus di sisi Daizo seperti bayangan, memberi isyarat dengan tanda-tanda
terang, bahwa ia lebih menyukai "di mana saja, asalkan tidak di
kuil."
Daizo memilih
penginapan yang paling besar dan paling mengesankan. Ia masuk dan memesan
kamar. Pemunculannya yang lain daripada yang lain, dan peti perjalanannya yang
anggun, dipernis dan didukung pelayan itu, menimbulkan kesan memikat pada
kerani kepala. Kerani kepala berkata dengan nada menjilat, "Wah, Bapak
datang dini sekali?" Penginapan-penginapan sepanjang jalan raya memang
terbiasa menerima rombongan musafir pada waktu makan malam, atau bahkan lebih
malam.
Daizo diantar ke
sebuah kamar besar di tingkat pertama, tapi tak lama sesudah matahari terbenam,
pemilik penginapan dan kerani kepala datang ke kamar Daizo.
"Saya tahu ini
sangat tidak menyenangkan," pemilik penginapan memulai dengan rendah hati,
"tapi satu rombongan besar tamu datang tiba-tiba sekali. Saya takut
suasana di sini akan ribut bukan main. Kalau Bapak tidak keberatan, saya
persilakan sebuah kamar di tingkat dua..."
"Oh, tidak
apa-apa," jawab Daizo ramah. "Saya senang melihat usaha Anda
maju."
Daizo memberikan
isyarat kepada Sukeichi, pelayannya, agar mengurus barang bawaannya, dan ia
naik ke atas. Begitu ia pergi, ruang itu pun diserbu perempuan-perempuan dari
Sumiya itu.
Penginapan jadi tidak
sekadar sibuk, tapi ingar-bingar. Karena ributnya keadaan di bawah, para
pelayan tidak datang pada waktu dipanggil. Makan malam terlambat, dan ketika
mereka selesai makan, tak seorang pun datang untuk menyingkirkan pinggan dan
mangkuk. Belum lagi suara entakan kaki yang tak henti-hentinya di kedua lantai.
Hanya rasa simpati Daizo kepada orang upahan saja yang membuat ia tidak
kehilangan kesabaran. Tanpa menghiraukan pinggan-mangkuk yang masih berantakan
di kamar, ia membaringkan diri, tidur berbantal tangan. Beberapa menit
kemudian, tiba-tiba terpikir olehnya sesuatu, dan la memanggil Sukeichi.
Sukeichi tidak
muncul, karena itu Daizo membuka mata, duduk dan berseru, "Jotaro,
sini!"
Tapi Jotaro pun sudah
lenyap.
Daizo berdiri dan
pergi ke beranda. Dilihatnya beranda penuh deretan tamu yang gembira menonton
para pelacur di lantai pertama.
Melihat Jotaro ada di
antara para penonton, direnggutkannya anak itu kembali ke kamarnya. Dengan
sorot mata menakutkan, ia bertanya, "Apa yang kautatap itu?"
Pedang kayu panjang
yang tidak dilepas Jotaro, sekalipun di dalam ruangan, menggaruk tatami ketika
ia duduk. "Semua orang melihat," katanya.
"Tapi apa yang
mereka lihat?"
"Ada banyak
perempuan di kamar belakang, di bawah."
"Cuma itu?"
"Ya."
"Apa pula yang
menyenangkan, kalau cuma itu?" Hadirnya para pelacur itu sama sekali tidak
mengganggu Daizo, tapi karena alasan tertentu, ia merasa bahwa niat besar para
lelaki yang menganga melihat mereka itu menjengkelkan.
"Saya tidak
tahu," jawab Jotaro jujur.
"Aku mau
jalan-jalan keliling kota," kata Daizo. "Sementara aku pergi, kau
tinggal di sini."
"Saya tak boleh
ikut?"
"Waktu malam
tidak."
"Kenapa tak
boleh?"
"Seperti
kukatakan sebelumnya, kalau aku pergi jalan-jalan, itu bukan sekadar buat
menyenangkan diri."
"Apa belum cukup
yang Bapak dapat dari tempat-tempat suci dan kuilkuil itu pada siang hari?
Pendeta-pendeta juga tidur waktu malam."
"Agama itu lebih
dari sekadar tempat suci dan kuil, anak muda. Sekarang panggil Sukeichi kemari.
Dia bawa kunci peti perjalananku."
"Dia pergi turun
beberapa menit lalu. Saya lihat dia mengintip ke kamar perempuan-perempuan
itu."
"Oh, dia
juga?" seru Daizo, mendecapkan lidahnya. "Pergi sana panggil dia, dan
cepat!" Sesudah Jotaro pergi, Daizo mulai mengikatkan obi-nya.
Mendengar bahwa
perempuan-perempuan itu adalah pelacur Kyoto yang terkenal kecantikannya dan
kecakapannya dalam melakukan segala sesuatu, maka tamu-tamu lelaki tak dapat
berhenti memestakan mata mereka. Sukeichi demikian asyik melihat pemandangan
itu, hingga mulutnya masih menganga ketika Jotaro menemukannya.
"Ayo, sudah
cukup kau melihat!" bentak anak itu sambil menjewer telinga si pelayan.
"Oh!" pekik
Sukeichi.
"Tuanmu
memanggil."
"Bohong."
"Tak percaya!
Dia bilang akan pergi jalan-jalan. Dia selalu jalan-jalan, kan?"
"Ha? Baik, kalau
begitu," kata Sukeichi, enggan menolehkan mukanya.
Anak itu membalikkan
badan mengikutinya, ketika tiba-tiba saja ada suara memanggilnya, "Jotaro?
Kau Jotaro, kan?"
Suara itu suara
perempuan muda. Jotaro menoleh ke sekitar, mencaricari. Harapannya untuk
menemukan gurunya dan Otsu tak pernah lenyap dari hatinya. Mungkinkah mereka?
Ia menatap tegang lewat cabang-cabang rumpun pohon.
"Siapa
itu?"
"Aku."
Wajah yang muncul
dari tengah dedaunan itu dikenalnya. "Oh, kau."
Akemi dengan kasar
menepuk punggungnya. "Anak bandel! Kan sudah lama betul kita tak jumpa!
Apa kerjamu di sini?"
"Aku bisa juga
tanya begitu."
"Oh, aku... ah,
tapi itu tak ada artinya buatmu."
"Apa kau jalan
sama perempuan-perempuan itu?"
"Betul, tapi aku
belum ambil keputusan."
"Ambil keputusan
soal apa?"
"Jadi anggota
mereka atau tidak," jawab Akemi mengeluh. Lama kemudian baru ia bertanya,
"Apa kerja Musashi sekarang ini?"
Jotaro mengerti,
itulah yang sesungguhnya ingin diketahui Akemi. Ia ingin bisa menjawab
pertanyaan itu.
"Otsu, Musashi,
dan aku... kami terpisah di jalan raya."
"Otsu? Siapa
dia?" Baru saja mengucapkan itu, teringat olehnya. "Oh ya, aku tahu.
Apa masih juga dia mengejar-ngejar Musashi?" Akemi sudah terbiasa
menganggap Musashi seorang shugyosha gagah yang mengembara seenak hatinya,
hidup di hutan dan tidur di batu-batu telanjang. Sekalipun misalnya ia berhasil
mengejar Musashi, Musashi langsung dapat mengetahui betapa cabul hidup yang
telah ditempuhnya, dan akan menghindarinya. Sudah lama ia tidak lagi memikirkan
bahwa cintanya akan berbalas.
Tetapi disebutnya
nama perempuan lain itu membangkitkan perasaan cemburu, dan mengusik kembali
bara naluri cintanya yang sedang sekarat.
"Jotaro,"
katanya, "di sekitar tempat ini begitu banyak mata yang ingin tahu. Mari
kita pergi ke tempat lain."
Mereka pergi lewat
gerbang halaman. Di jalan, mata mereka berpesta menikmati lampu-lampu Hachioji
dan kedua puluh lima penginapannya. Itulah kota tersibuk yang pernah mereka
saksikan semenjak meninggalkan Kyoto. Di sebelah barat laut, menjulang jajaran
Pegunungan Chichibu yang gelap diam, dan pegunungan yang menandai perbatasan
Provinsi Kai, tapi di sini suasana penuh aroma sake, ribut oleh detak-detik
buluh penenun, teriakan pegawai-pegawai pasar, pekik riuh para penjudi, dan rengekan
lesu penyanyi-penyanyi jalanan.
"Sering aku
mendengar Matahachi menyebut nama Otsu," kata Akemi berbohong. "Orang
macam apa dia?"
"Oh, dia baik
sekali," kata Jotaro seadanya. "Manis, lembut, baik budi, dan cantik.
Aku suka sekali padanya."
Ancaman yang terasa
mengawang di atas Akemi jadi bertambah hebat, tapi ia menyelimuti perasaannya
dengan senyuman ramah. "Apa dia memang sebaik itu?"
"Memang. Dan dia
dapat melakukan apa saja. Dia dapat menyanyi, dapat menulis dengan baik, dan
dia dapat main suling."
Sekarang Akemi tampak
gusar, katanya, "Ah, tapi aku tak melihat gunanya perempuan main
suling."
"Kalau kau tak
cocok, boleh saja, tapi semua orang memuji Otsu, termasuk Yang Dipertuan Yagyu
Sekishusai. Cuma ada satu hal kecil yang tak kusukai."
"Semua perempuan
punya kekurangan. Soalnya cuma, apa mereka mau mengakuinya dengan jujur,
seperti yang kuperbuat, atau mencoba menyembunyikan kekurangan itu di balik
sikap wanita terhormat."
"Otsu bukan
orang macam itu. Cuma ada kelemahan kecil pada dia."
"Kelemahan
apa?"
"Dia selalu
nangis. Betul-betul cengeng."
"Oh? Kenapa
begitu?"
"Dia selalu
nangis kalau memikirkan Musashi. Akibatnya murung juga ada di dekatnya, dan itu
aku tak suka." Jotaro menyatakan pendapatnya dengan sikap masa bodoh
kanak-kanak, tak sadar akan akibat yang bisa ditimbulkannya.
Hati Akemi dan
seluruh tubuhnya terbakar apt cemburu. Hal itu tampak di kedalaman matanya,
bahkan juga pada warna kulitnya. Tapi ia meneruskan pertanyaannya. "Berapa
tahun umurnya?"
"Kira-kira
sama."
"Maksudmu, sama
dengan aku?"
"Ya. Tapi dia
kelihatan lebih muda dan lebih manis."
Akemi sekarang nekat
menyerang, dengan harapan agar Jotaro menentang Otsu. "Musashi lebih
jantan dari kebanyakan lelaki. Dia tentu benci melihat perempuan yang berlaku
tak pantas terus-menerus. Otsu barangkali mengira air matanya dapat memenangkan
simpati pria, macam gadis-gadis yang bekerja untuk Sumiya."
Jotaro jengkel
sekali, dan jawabnya pedas, "Tak benar sama sekali. Pertama-tama, Musashi
suka Otsu. Memang dia tak pernah memperlihatkan perasaannya, tapi dia mencintai
Otsu."
Wajah Akemi yang
kemerahan itu berubah menjadi merah tua. Ingin ia menceburkan diri ke sungai,
untuk memadamkan nyala api yang membakar dirinya.
"Jotaro, ayo
kita ke sini." Ia tarik Jotaro ke arah lampu merah di sebuah jalan kecil.
"Tapi itu tempat
minum."
"Lalu, apa
salahnya?"
"Itu bukan
tempat untuk perempuan. Kau tak boleh pergi ke sana."
"Tiba-tiba saja
aku ingin sekali minum, dan aku tak bisa pergi sendiri. Aku malu."
"Kau malu. Tapi
aku sendiri bagaimana?"
"Di situ ada
makanan juga. Kau bisa makan apa saja yang kausukai."
Sepintas lalu, warung
itu kelihatan kosong, Akemi langsung masuk. Sambil menghadap dinding, katanya,
"Saya mau sake."
Mangkuk demi mangkuk
diteguk dengan kecepatan yang masih mungkin dicapai manusia. Kuatir melihat
banyaknya Akemi minum, Jotaro mencoba menghambatnya, tapi Akemi menepiskannya.
"Diam!"
pekiknya. "Kau ini mengganggu saja! Kasih sake lagi! Sake!"
Sambil menyelipkan
diri antara Akemi dan guci sake, Jotaro memohon, "Kau mesti berhenti
sekarang. Kau tak boleh minum terus macam ini."
"Jangan
kuatir," kata Akemi cepat. "Kau teman Otsu, kan? Aku tak suka perempuan
yang mencoba menaklukkan lelaki dengan air mata!"
"Dan aku tak
suka perempuan mabuk."
"Aku minta maaf,
tapi bagaimana mungkin orang kerdil macam kau mengerti kenapa aku minum?"
"Ayolah, bayar
saja sekarang."
"Kaupikir aku
punya uang?"
"Kau tak
punya?"
"Tidak.
Barangkali dia bisa ambil uangnya dari Sumiya. Aku toh sudah menjual diri
kepada pemiliknya." Air mata membanjiri mata Akemi. "Aku minta
maaf.... Aku betul-betul minta maaf."
"Jadi kau
menertawakan Otsu karena nangis, kan? Tapi coba lihat dirimu itu!"
"Air mataku lain
dengan air matanya. Oh, hidup ini banyak sekali kesulitannya. Lebih baik aku
mati."
Sesudah mengucapkan
kata-kata itu, Akemi berdiri dan enyah ke jalan. Tukang warung yang memang
biasa mendapat pembeli macam itu hanya tertawa, tapi seorang ronin yang selama
itu tidur tenang di sudut warung, membuka matanya yang muram dan menatap
punggung Akemi yang kian menjauh.
Jotaro mengejarnya
dan menangkap pinggangnya, tapi terlepas. Akemi lari masuk jalan gelap, dan
Jotaro mengejarnya.
"Berhenti!"
teriak Jotaro kuatir. "Kau tak boleh berpikir begitu. Ayo kembali!"
Akemi kelihatannya
tak peduli, apakah ia menubruk sesuatu dalam kegelapan atau jatuh ke paya-paya,
tapi ia sadar sepenuhnya akan permintaan Jotaro. Ketika menceburkan diri ke
laut di Sumiyoshi dulu, ia memang mau bunuh diri, tapi sekarang ia tidak lagi
sepolos dulu. Melihat Jotaro demikian kuatir akan dirinya, ia merasakan getaran
nikmat.
"Awas!"
teriak Jotaro, ketika melihat Akemi langsung menuju air parit yang kelam.
"Berhenti! Kau mau mati, ya? Gila kau."
Sekali lagi Jotaro
menangkap pinggangnya, dan Akemi pun melolong, "Apa salahnya kalau aku
mati? Kaupikir aku jahat. Begitu juga pikir Musashi. Setiap orang berpikir
begitu. Tak ada lagi pilihanku, kecuali mati sambil memeluk Musashi dalam hati.
Takkan kubiarkan dia direbut perempuan macam itu dari tanganku."
"Kau betul-betul
kacau. Bagaimana bisa kau jadi begini?"
"Tak peduli.
Sekarang tinggal kaudorong aku masuk parit. Ayolah, Jotaro, dorong aku."
Sambil menutup muka dengan kedua tangan, pecahlah tangisnya. Hal itu
menimbulkan rasa ngeri yang aneh dalam diri Jotaro, dan ia merasa ingin
menangis juga.
"Ayolah, Akemi.
Mari kita pulang."
"Oh, begitu
ingin aku melihat dia. Cobalah cari dia Jotaro. Cari Musashi untukku."
"Berdiri
diam-diam! Jangan bergerak, berbahaya!"
"Oh,
Musashi!"
"Awas!"
Pada waktu itu, ronin
dari warung sake itu muncul dari kegelapan. "Pergi kau, anak kecil!"
perintahnya. "Akan kukembalikan dia ke warung." Ia selipkan tangannya
di kedua ketiak Jotaro, dan dengan kasar ia angkat anak itu ke pinggir.
Ronin itu bertubuh
jangkung, umurnya tiga puluh empat atau tiga puluh lima tahun, matanya dalam
dan jenggotnya lebat. Sebuah tanda bekas luka menggores dari bawah telinga
kanan ke dagu. Tidak sangsi lagi, itu luka bekas pedang. Tampaknya seperti
koyakan bergerigi pada buah persik apabila dibuka.
Sambil menelan ludah
dengan susah payah untuk mengatasi rasa takutnya, Jotaro mencoba membujuk.
"Akemi, ayolah ikut aku. Semuanya akan beres." Kepala Akemi kini
terkulai di dada samurai itu.
"Lihat,"
kata orang itu, "dia sudah tertidur. Pergi kau! Akan kubawa dia pulang
nanti."
"Tidak! Biarkan
dia pergi!"
Ketika anak itu
menolak beranjak, ronin itu pelan-pelan mengulurkan satu tangannya dan
menangkap kerah Jotaro.
"Lepaskan!"
jerit Jotaro, melawan sekuat tenaga.
"Bajingan kecil!
Bagaimana kalau kau dilemparkan ke parit?"
"Siapa yang
melemparkan?" Ia menggeliatkan badan untuk melepaskan diri. Begitu
terlepas, tangannya meraba ujung pedang kayunya. Ia ayunkan pedang itu ke
lambung orang tersebut, tapi ternyata tubuhnya sendiri terjungkir balik dan
jatuh ke batu di pinggir jalan. Ia merintih sejenak, kemudian diam.
Jotaro pingsan
beberapa waktu lamanya, kemudian mulai mendengar suara-suara di sekitarnya.
"Hei,
bangun!"
"Apa yang
terjadi?"
Ketika ia membuka
mata, samar-samar tampak olehnya sejumlah orang mengelilinginya.
"Sudah
sadar?"
"Kau baik-baik
saja?"
Malu karena telah
menarik perhatian orang banyak, Jotaro memungut pedang kayunya dan pergi, tapi
seorang kerani penginapan mencengkeram tangannya. "Tunggu sebentar,"
salaknya. "Apa yang terjadi dengan perempuan temanmu itu?"
Jotaro memandang ke
sekitar, dan ia mendapat kesan bahwa orang-orang yang lain itu juga dari
penginapan, tamu-tamu dan pegawai penginapan. Sebagian orang itu membawa
tongkat. Yang lain memegang lentera kertas bulat.
"Satu orang
mengatakan kau diserang, dan seorang ronin membawa pergi perempuan itu. Apa kau
tahu ke mana mereka pergi?"
Jotaro menggeleng.
Kepalanya masih pusing.
"Tidak mungkin.
Kau mestinya tahu."
Jotaro menuding arah
pertama yang dapat ditudingnya. "Sekarang saya ingat. Ke situ!" Ia
enggan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, karena takut mendapat teguran
Daizo gara-gara terlibat soal itu. Ia juga takut mengakui di depan begitu banyak
orang bahwa ronin itu sudah melemparkannya.
Walaupun jawaban itu
samar-samar, orang banyak itu bergegas juga ke sana, dan tak lama kemudian
terdengar teriakan. "Ini dia! Ada di sini!"
Lentera-lentera
berkerumun di sekitar Akemi. Tubuhnya yang kusut masai terbaring di tempat ia
ditelantarkan, di atas setumpuk jerami dalam lumbung seorang petani. Ia baru
tersadar kembali sesudah mendengar ribut langkah kaki orang berlari, dan ia
memaksa dirinya berdiri. Bagian depan kimononya terbuka, obi-nya tergeletak di
tanah. Jerami menempel pada rambut dan pakaiannya.
"Apa yang
terjadi?"
Kata
"perkosaan" menggantung di bibir setiap orang, tapi tak ada yang
mengucapkannya. Dan tak seorang pun di antara mereka terpikir akan mengejar
bajingan itu. Apa pun yang terjadi dengan Akemi, mereka merasa ia sendiri yang
bersalah.
"Mari kita
kembali," kata seseorang sambil menggandeng tangan Akemi. Akemi cepat
menarik dirinya. Ia menempelkan wajahnya ke dinding, dan menangis sedih sekali.
"Rupanya dia
mabuk."
"Bagaimana dia
bisa sampai begitu?"
Jotaro mengawasi
adegan itu dari kejauhan. Apa yang terjadi dengan Akemi tak jelas baginya, tapi
bagaimanapun ia teringat pengalaman yang tak ada hubungannya sama sekali dengan
Akemi. Terkenang kembali olehnya rangsangan yang pernah dialaminya ketika ia
terbaring di lumbung makanan ternak di Koyagyu, bersama Kocha. Terkenang
olehnya rasa takut yang anehnya menggairahkan, rasa takut akan langkah-langkah
yang waktu itu sedang mendekat. Tapi
cuma sebentar ia menikmati kenangan itu. "Lebih baik aku kembali,"
katanya memutuskan.
Langkahnya menjadi
cepat, dan semangatnya yang baru kembali dari wilayah tak dikenal itu
menggerakkannya untuk menyanyikan lagu.
Oh, Budha logam tua
yang berdiri di ladang, Kaulihatkah gadis umur enam belas? Tak kaulihatkah
gadis itu? Kalau ditanya, jawabmu ‘Bung.' Kalau dipukul, katamu 'Bung. "


0 komentar:
Posting Komentar