Guru Menulis
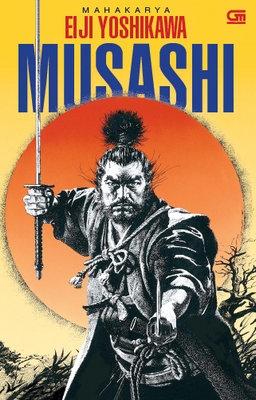
PAPAN nama di pintu
masuk jalan sempit, di daerah pedagang ikanOkazaki itu, berbunyi,
"Pencerahan Bagi Para Pemuuda. Pelajaran Membaca dan Menulis", dan
tertulis di situ nama Muka. Melihat segala sesuatunya, Muka tentunya salah
seorang dari banyak ronin yang telah jatuh miskin, namun tulus, dan mencari
penghidupan dengan menularkan pendidikan kelas prajurit kepada anak-anak orang
kebanyakan.
Kaligrafi yang
kelihatan amatiran itu membuat tersenyum orang-orang yang lewat, tapi Muka
mengatakan tidak malu karenanya. Kalau ada orang menyebutkan hal itu, ia selalu
menjawab dengan kata-kata yang sama, "Dalam hati, saya masih kanak-kanak.
Dan saya belajar bersama anak-anak."
Jalan itu berakhir
pada sebuah rumpun bambu, dan di sebelah rumpun bambu terbentang lapangan
pacuan Keluarga Honda. Kalau cuaca terang, lapangan itu selalu diliputi awan
debu, karena tentara berkuda sering berlatih dari fajar sampai senja. Garis
keturunan yang mereka banggakan adalah garis keturunan prajurit-prajurit Mikawa
yang terkenal, suatu tradisi yang telah menghasilkan Tokugawa.
Muka terbangun dari
tidur siang, lalu pergi ke sumur dan menimba air. Kimono warna kelabu gelap
yang tak berpinggir, dan topi kelabu yang dikenakannya, lebih cocok untuk orang
umur empat puluhan, padahal ia sendiri belum lagi tiga puluh tahun. Habis
mencuci muka, ia berjalan ke rumpun bambu, dan di situ ia menebang sebatang
bambu besar dengan satu tebasan pedang.
Ia basuh bambu itu di
sumur, lalu kembali masuk rumah. Kerai yang tergantung di satu sisi berfungsi menolak
debu dari lapangan pacuan, tapi karena cahaya datang dari arah tersebut,
ruangan itu jadi kelihatan lebih kecil dan lebih gelap dari yang sebenarnya.
Sebilah papan terletak mendatar di sebuah sudut. Di atasnya tergantung potret
tanpa nama dari seorang pendeta Zen. Muka menegakkan potongan bambunya di atas
papan, dan melontarkan bunga jalar ke dalam lubangnya.
"Boleh
juga," pikirnya sambil mundur, memeriksa karyanya. Ia duduk di depan meja,
mengambil kuas, dan mulai berlatih. Sebagai model, dipergunakannya pedoman
huruf-huruf resmi berbentuk persegi dari Ch'u Sui-liang, dan sapuan kaligrafi
dari pendeta Kobo Daishi. Jelas kelihatan, ia memperoleh kemajuan mantap selama
setahun tinggal di situ, karena huruf-huruf yang ditulisnya sekarang jauh lebih
unggul daripada huruf-huruf yang tertulis di papan nama.
"Boleh saya
mengganggu?" tanya wanita dari sebelah rumah, istri orang yang biasa
menjual kuas tulis.
"Silakan,"
kata Muka.
"Saya hanya
sebentar. Saya heran.... Beberapa menit yang lalu, saya mendengar bunyi keras.
Kedengarannya seperti ada barang yang patah. Apa Anda mendengarnya?"
Muka tertawa.
"Itu tadi saya memotong bambu."
"Oh. Saya begitu
kuatir. Saya pikir ada yang terjadi dengan Anda. Suami saya mengatakan samurai
yang berkeliaran di sekitar sini mau membunuh Anda."
"Sekiranya betul
begitu, tidak apa. Toh harga saya tidak sampai tiga keping uang tembaga."
"Lho, Anda tak
boleh menyepelekan. Banyak orang terbunuh akibat hal-hal yang menurut ingatan
mereka tidak mereka lakukan. Coba Anda pikirkan, alangkah sedih semua gadis itu
kalau ada sesuatu menimpa Anda."
Wanita itu
mengundurkan diri, tanpa mengajukan pertanyaan yang sering diajukannya,
"Kenapa tidak beristri? Bukan karena Anda tak suka perempuan, kan?"
Muka tidak pernah memberikan jawaban yang jelas, sekalipun secara sembrono
ucapannya sempat menyiratkan bahwa ia bisa dengan mudah mendapatkan jodoh yang baik.
Para tetangga tahu bahwa ia ronin dari Mimasaka, yang suka belajar dan pernah
tinggal di Kyoto, di Edo, dan sekitar Edo. Kata orang, ia ingin menetap di
Okazaki dan membuka perguruan yang baik. Berhubung ia masih muda, rajin, dan
jujur, tidak mengherankan bahwa sejumlah gadis berminat kawin dengannya, juga
beberapa orang yang anak-anak gadisnya memenuhi syarat.
Lingkungan kecil itu
memang memikat hati Muka. Penjual kuas dan istrinya memperlakukannya dengan
baik. Sang istri mengajarinya memasak, dan kadang-kadang mencuci dan menjahit
untuknya. Secara keseluruhan, Muka senang tinggal di lingkungan itu. Semua
orang saling mengenal, dan semua orang berusaha membuat hidup mereka menarik.
Selalu ada peristiwa yang terjadi, kalau bukan pesta tari-tarian di jalan atau
perayaan keagamaan, tentu penguburan atau ada orang sakit yang mesti diurus.
Malam itu ia melewati
rumah penjual kuas, ketika suami-istri itu sedang makan malam. Sambil mendecap,
sang istri berkata, "Ke mana dia pergi? Pagi hari dia mengajar anak-anak,
sore hari tidur atau belajar. Lalu malam hari pergi. Macam kelelawar
saja."
Di jalan-jalan
Okazaki, bunyi seruling bambu bercampur dengan dengung serangga tangkapan yang
dikurung dalam sangkar-sangkar kayu, dengan ratapan berirama dari para penyanyi
di jalan buntu, dengan teriakan para penjual semangka dan sushi. Di sini tak
ada hiruk-pikuk yang menjadi ciri di Edo. Lentera-lentera berkedap-kedip, dan
orang-orang bercengkerama di sana-sini, dengan mengenakan kimono musim panas.
Dalam udara musim panas itu, segala sesuatu kelihatan santai dan pada
tempatnya.
Ketika Muka lewat,
gadis-gadis berbisik.
"Nah, dia jalan
lagi."
"Huh, dan selalu
tidak memperhatikan siapa pun."
Sebagian gadis-gadis
itu membungkuk kepadanya, kemudian menoleh pada sesama teman-teman mereka, dan
menduga-duga ke mana arah pergi Muka.
Muka berjalan lurus,
melewati jalan-jalan samping di mana ia bisa membeli jasa para pelacur Okazaki,
yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu daya tank utama di sepanjang
jalan raya Tokaido itu. Di ujung barat kota ia berhenti dan meregangkan badan,
hingga panas badan keluar dari lengan bajunya. Di hadapannya menderas air
Sungai Yahagi dan membentang Jembatan Yahagi yang berelung 208, jembatan
terpanjang di Tokaido. Ia berjalan mendekati sosok kurus yang menantinya di
tiang pertama.
"Musashi?"
Musashi tersenyum
pada Matahachi yang mengenakan jubah pendeta. "Apa Guru sudah
kembali?" tanyanya.
"Belum."
Mereka berjalan
berdampingan, menyeberangi jembatan. Di atas bukit yang ditumbuhi pohon pinus,
di seberangnya berdiri kuil Zen tua. Karena bukit itu dikenal sebagai Hachijo,
kuil itu pun disebut Hachijoji. Mereka mendaki lereng yang gelap, di depan
pintu gerbang.
"Apa
kabar?" tanya Musashi. "Melaksanakan Zen mestinya sukar."
"Betul,"
jawab Matahachi kesal, sambil menundukkan kepalanya yang bercukur kebiruan.
"Aku sudah sering ingin melarikan diri. Kalau mesti mengalami siksaan
mental untuk menjadi manusia baik-baik, lebih baik aku menjerat leherku, habis
perkara."
"Oh, jangan
mundur karena itu. Kau baru mulai. Pendidikanmu yang sebenarnya belum terjadi,
sebelum kau dapat mengimbau Guru dan meyakinkannya untuk menerimamu sebagai
murid."
"Itu memang
tidak selamanya mustahil. Aku sudah belajar mendisiplinkan diriku sedikit. Dan
tiap kali aku kendur, aku ingat kau. Kalau kau dapat mengatasi
kesulitan-kesulitanmu, aku pun dapat."
"Memang begitu
mestinya. Apa pun yang dapat kulakukan, pasti kau juga bisa."
"Aku teringat
Takuan. Kalau bukan karena dia, aku sudah dihukum mati."
"Kalau kau tahan
menghadapi kesulitan, kau akan memperoleh kesenangan yang lebih besar daripada
derita," kata Musashi khidmat. "Siang dan malam, jam demi jam, orang
dipermainkan oleh ombak derita dan kesenangan berganti-ganti. Kalau mereka
mencoba untuk hanya menikmati kesenangan, berarti mereka tidak benar-benar
hidup. Dan kesenangan akan lenyap."
"Aku mulai
mengerti."
"Ingat saja cara
orang menguap. Kuap orang yang habis kerja, lain dengan kuap orang malas.
Banyak orang mati tanpa mengetahui nikmat yang diberikan oleh menguap."
"Ya. Aku
mendengar pembicaraan seperti itu di kuil."
"Kuharap tak
lama lagi aku bisa membawamu pada Guru. Aku sendiri ingin minta petunjuk
darinya. Aku perlu tahu lebih banyak tentang Jalan itu."
"Menurutmu,
kapan dia datang?"
"Sukar
dikatakan. Guru Zen kadang-kadang berkeliaran di seluruh negeri, seperti awan,
selama dua atau tiga tahun sekali jalan. Mumpung sudah dating di sini, kau
mesti mau menunggu dia, sampai empat-lima tahun, kalau perlu."
"Kau juga?"
"Ya. Hidup di
lorong belakang, di antara orang-orang miskin dan tulus itu, merupakan latihan
baik bagiku. Itu bagian dari pendidikanku. Waktu tidak terbuang sia-sia."
Musashi meninggalkan
Edo, melewati Atsugi. Kemudian, dengan jiwa dilanda kesangsian akan masa
depannya, ia menghilang ke tengah Pegunungan Tanzawa, dan dua bulan kemudian
muncul kembali dalam keadaan lebih gelisah dan kuyu. Selesai memecahkan satu
masalah, ia tercebur ke dalam masalah lain. Kadang-kadang ia demikian tersiksa,
hingga seolah-olah pedangnya terarah kepada dirinya.
Di antara kemungkinan
yang dipertimbangkannya adalah memilih jalan yang mudah. Sekiranya ia dapat
memaksa dirinya menempuh hidup enak dan biasa saja dengan Otsu, hidupnya akan
sederhana. Hampir setiap perdikan akan rela membayarnya dengan gaji cukup untuk
hidup, barangkali lima ratus sampai seribu gantang. Tapi kalau ia ajukan hal
itu pada dirinya dalam bentuk pertanyaan, jawabannya selamanya tidak. Hidup
yang mudah itu penuh dengan batasan. Ia tak dapat tunduk kepada batasan-batasan
itu.
Pada waktu lain, ia
merasa seolah tersesat dalam khayal pengecut, khayal hina, seperti setan lapar
dalam neraka; kemudian, untuk sesaat, pikirannya menjadi tenang, dan ia
mengumbar diri dalam kenikmatan hidup menyendiri yang penuh kebanggaan itu. Di
dalam hatinya terus berlangsung perjuangan antara terang dan gelap. Siang-malam
ia terhuyung-huyung antara kegembiraan besar dan kesenduan. Ia memikirkan
dirinya sebagai pemain pedang, dan ia merasa kecewa. Kalau dipikirkan betapa
panjang jalan yang dipelajarinya, dan betapa jauh ia dari kematangan, hatinya
pun pedih. Tapi, di lain waktu, hidup di pegunungan itu menggembirakan hatinya,
dan pikirannya melayang pada Otsu.
Turun dari gunung, ia
pergi ke Yugyoji di Fujisawa untuk beberapa hari, kemudian ke Kamakura. Di
situlah ia berjumpa dengan Matahachi. Matahachi sudah memutuskan untuk tidak
kembali menjalani hidup malas, dan ia berada di Kamakura karena banyak kuil Zen
di tempat itu, namun ia menanggung rasa hancur yang lebih parah lagi daripada
Musashi.
Musashi mencoba
meyakinkannya, "Sekarang ini belum terlalu terlambat. Kalau kau belajar
berdisiplin, kau bisa mulai dari awal lagi. Sungguh fatal kalau kau mengatakan
pada dirimu bahwa semuanya sudah lewat, dan bahwa dirimu tak berguna."
Kemudian ia merasa
perlu menambahkan, "Terus terang, aku sendiri berhadapan dengan tembok.
Ada masanya aku bertanya-tanya, apakah aku punya masa depan. Aku merasa sama
sekali kosong. Rasanya seperti terkurung dalam rumah kerang. Aku benci pada
diriku. Kukatakan pada diri sendiri, diriku ini sia-sia. Tapi dengan mendera
diri sendiri, dan memaksa diri untuk jalan terus, aku berhasil menerobos rumah
kerang itu. Lalu jalan baru terbuka di hadapanku.
"Percayalah,
kali ini sedang berlangsung perjuangan yang sesungguhnya dalam diriku. Aku
menggelepar-gelepar di dalam rumah kerang, dan tak dapat melakukan sesuatu. Aku
turun dari pegunungan karena teringat orang yang menurutku dapat
menolongku."
"Orang itu
Pendeta Gudo. "
Kata Matahachi,
"Dia yang menolongmu waktu engkau pertama kali mencari Jalan itu, kan? Apa
kau tak bisa mengenalkan aku, dan minta dia menerimaku sebagai murid?"
Semula Musashi sangsi
tentang ketulusan hati Matahachi, tapi sesudah mendengar tentang kesulitan di
Edo, ia pun yakin bahwa Matahachi betul-betul bermaksud demikian. Kedua orang
itu kemudian mencari keterangan tentang Gudo di sejumlah kuil Zen, tapi hanya
sedikit yang dapat mereka ketahui. Musashi tahu bahwa pendeta itu tidak lagi
berada di Kuil Myoshinji, Kyoto. Beberapa tahun sebelumnya, ia pergi melakukan
perjalanan selama beberapa waktu lamanya di timur dan timur laut. Ia juga tahu
bahwa pendeta itu orang yang paling tak menentu tinggalnya. Satu hari ia bisa
berada di Kyoto, memberikan kuliah tentang Zen pada Kaisar, dan hari berikutnya
mengembara di pedesaan. Gudo diketahui beberapa kali berhenti di Kuil Hachijoji
di Okazaki. Seorang pendeta mengatakan mungkin di kuil itulah tempat terbaik
untuk menantikannya.
Musashi dan Matahachi
duduk di dalam pondok kecil tempat Matahachi biasa tidur. Musashi sering
mengunjunginya di sini, dan mereka bercakapcakap sampai jauh malam. Matahachi
tidak diizinkan tidur dalam asrama yang, seperti halnya bangunan-bangunan Kuil
Hachijoji lainnya, berupa bangunan kasar, beratap lalang, sebab ia belum resmi
diterima sebagai pendeta.
"Oh,
nyamuk-nyamuk ini!" kata Matahachi sambil menyebar-menyebarkan asap dari
obat penghalau serangga, kemudian menggosok matanya yang pedih. "Mari kita
keluar." Mereka berjalan ke ruang utama dan duduk di serambi. Pekarangan
sepi, dan angin sejuk bertiup.
"Ini
mengingatkan aku pada Kuil Shippoji," kata Matahachi dengan suara hampir
tidak kedengaran.
"Ya, kukira
begitu," kata Musashi.
Mereka terdiam.
Mereka selalu berbuat demikian pada saat-saat seperti itu. Pikiran tentang
rumah selalu menimbulkan kenangan tentang Otsu dan Osugi, atau
peristiwa-peristiwa yang tak hendak mereka bicarakan, karena takut mengganggu
hubungan mereka sekarang.
Tapi, beberapa menit
kemudian, Matahachi berkata, "Bukit tempat berdirinya Shippoji itu lebih
tinggi, ya? Tapi di tempat ini tak ada pohon kriptomeria tua." Di situ ia
berhenti, memandang rant muka Musashi sejenak, kemudian katanya malu-malu. "Ada
satu permintaan yang sudah lama ingin kuajukan, tapi..."
"Permintaan apa
itu?"
"Otsu...,"
Matahachi memulai, tapi seketika itu juga ia terharu, tak bisa berbicara lagi.
Ketika merasa sudah dapat mengatasi perasaannya, ia berkata, "Rasanya aku
ingin tahu, apa yang sedang dilakukan Otsu sekarang ini, dan apa yang terjadi
dengannya. Aku sering memikirkannya hari-hari ini dan dalam hati aku minta maaf
atas segala yang pernah kulakukan. Aku malu mesti mengakuinya, tapi di Edo aku
memaksanya hidup denganku. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dia menolak kusentuh.
Kukira, sesudah aku pergi ke Sekigahara, Otsu tentunya seperti kembang yang
jatuh. Sekarang dia menjadi bunga yang berkembang di pohon lain, di tanah yang
lain juga." Wajah Matahachi memperlihatkan kesungguhan, dan suaranya
serius.
"Takezo... ah,
bukan... Musashi. Aku minta, kawinilah Otsu. Kau satu-satunya yang dapat
menyelamatkannya. Aku tak pernah dapat memaksa diri mengatakan hal ini, tapi
sekarang, sesudah aku mengambil keputusan menjadi murid Gudo, mesti kuakui
kenyataan bahwa Otsu bukan milikku. Biarpun begitu, aku menguatirkan dirinya.
Tak inginkah engkau mencari dia, dan memberinya kebahagiaan yang memang dia
inginkan?"
Kira-kira pukul tiga
pagi waktu itu, ketika Musashi mulai menuruni jalan glinting yang gelap.
Tangannya terlipat, kepalanya tertunduk. Katakata Matahachi terngiang di
telinganya. Kesedihan mendalam seakan menarik-narik kakinya. Ia dapat
membayangkan, betapa Matahachi tersiksa bermalam-malam lamanya, hanya untuk
membangkitkan keberanian berbicara seperti itu. Namun bagi Musashi, dilema yang
dihadapinya sendiri lebih berat dan menyakitkan.
Menurut pendapatnya,
Matahachi berharap dapat melarikan diri dari nyala panas masa lalu, dan mencari
keselamatan yang sejuk dalam pencerahan. Seperti bayi yang baru dilahirkan, ia
mencoba menemukan hidup bermakna dalam derita gaib kesedihan dan kebahagiaan.
Musashi tidak dapat
mengatakan, "Tak dapat itu kulakukan." Lebih tak dapat lagi ia
mengatakan, "Tak ingin aku mengawini Otsu. Dia tunanganmu. Menyesallah,
murnikan hatimu, dan rebut kembali hatinya." Akhirnya ia tidak mengatakan
apa pun, karena apa pun yang akan dikatakannya, akan merupakan kebohongan.
Dan Matahachi memohon
dengan sangat, "Hanya kalau aku yakin bahwa Otsu akan terurus, ada gunanya
bagiku menjadi murid. Kau yang mendesakku melatih dan mendisiplinkan diri.
Kalau kau memang temanku, selamatkan Otsu. Itulah satu-satunya jalan untuk
menyelamatkan diriku."
Musashi
terheran-heran melihat Matahachi menangis tersedu-sedu. Tak diduganya bahwa
perasaan Matahachi bisa sedalam itu. Bahkan ketika ia sudah berdiri untuk
berangkat, Matahachi mencengkeram lengan bajunya, minta diberi jawaban.
"Biar kupikirkan dulu," itulah satu-satunya yang dapat dikatakan
Musashi. Sekarang ia mengutuk dirinya karena bersikap pengecut, dan ia sesali
ketidakmampuannya.
Dengan sedih terpikir
oleh Musashi, bahwa orang yang tidak menanggung penyakit ini tak mungkin
mengenal nyerinya. Soalnya bukan semata-mata menyangkut sikap malas, tapi
menyangkut keinginan besar untuk melakukan sesuatu, namun tak bisa. Pikiran dan
mata Musashi kini seolah tumpul dan kosong. Sesudah menempuh jalan sejauh
mungkin ke satu arah saja, ia merasa dirinya tak berdaya untuk mundur atau
mulai menempuh jalan yang baru. Ia seperti terpenjara di suatu tempat yang tak
ada jalan keluarnya. Kekecewaan yang dialaminya menimbulkan rasa sangsi,
menyalahkan diri, dan air mata.
Sia-sia ia marah pada
diri sendiri, mengingat segala kesalahannya. Justru karena menemukan
gejala-gejala awal penyakit itulah, ia berpisah dengan Iori dan Gonnosuke,
serta memutuskan ikatan dengan teman-temannya di Edo. Tapi maksudnya untuk
menerobos rumah kerang selagi kulit kerang belum terbentuk dengan baik ternyata
gagal. Kulit kerang itu masih saja ada, membelenggu dirinya yang kosong,
seperti selongsong kulit jangkrik.
Ia berjalan tanpa
kemantapan. Keluasan Sungai Yahagi mulai tampak. dan angin yang bertiup dari
sungai terasa sejuk di wajahnya.
Tiba-tiba ia meloncat
ke samping, karena mendengar bunyi desing tajam. Tembakan itu melintas pada
jarak dua meter dari dirinya, dan bunyi bedil berkumandang di seberang sungai.
Jarak antara peluru dan bunyi itu sejauh dua tarikan napas, dan Musashi menyimpulkan
bahwa senapan itu ditembakkan dari jarak jauh. Ia melompat ke bawah jembatan
dan bergayut ke tiang, seperti kelelawar.
Beberapa menit
berlalu, kemudian tiga lelaki berlarian menuruni Bukit Hachijo, seperti buah
pohon pinus ditiup angin. Di dekat ujung jembatan, mereka berhenti dan mulai
mencari mayat. Karena yakin tembakannya mengena, si penembak membuang sumbunya.
Pakaiannya lebih gelap dibanding kedua orang yang lain, dan ia mengenakan
topeng, hanya matanya yang tampak.
Langit menjadi cerah
sedikit, dan hiasan kuningan pda gagang senapan memantulkan cahaya lembut.
Tak dapat Musashi
membayangkan, siapa gerangan orang di Okazaki yang menghendaki kematiannya.
Memang tidak kurang musuhnya. Dalam pertempuran-pertempuran yang pernah
dialaminya, ia telah mengalahkan banyak orang, yang kemungkinan masih punya
keinginan menggelegak untuk membalas dendam. Dan banyak lagi orang yang telah
dibunuhnya, hingga keluarga atau kawan-kawan mereka barangkali berharap akan
menuntut balas.
Siapa pun yang
menempuh Jalan Pedang, selamanya berada dalam bahaya dibunuh. Kalau ia lolos
dari satu bencana maut, akan menyusul kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan
perbuatan itu, ia menciptakan musuh-musuh baru atau bencana baru. Bahaya
merupakan batu gerinda yang dipakai pemain pedang untuk mengasah semangatnya.
Musuh adalah guru yang menyamar.
Belajar waspada
terhadap bahaya, biarpun sedang tidur, belajar dari musuh sepanjang waktu,
menggunakan pedang sebagai alat untuk membiarkan orang lain hidup, menguasai
alam, mencapai pencerahan, berbagi kegembiraan hidup dengan orang lain-semua
itu tak terpisahkan dari Jalan Pedang.
Sementara meringkuk
di bawah jembatan itu, situasi nyata memacu Musashi, dan kelesuannya pun
lenyap. Ia bernapas pendek-pendek sekali, tanpa bunyi, dan membiarkan para
penyerangnya mendekat. Gagal menemukan mayat, orang-orang itu memeriksa jalan
yang sunyi dan ruang di bawah ujung jembatan.
Mata Musashi terbuka
lebar. Orang-orang itu mengenakan pakaian hitam seperti bandit, tapi mereka
membawa pedang samurai, dan bersepatu rapi. Samurai di daerah itu hanyalah
mereka yang mengabdi pada Keluarga Honda di Okazaki, dan Keluarga Tokugawa
Owari di Nagoya. Ia tidak merasa mempunyai musuh di kedua perdikan itu.
Satu orang menembus
kegelapan dan mengambil kembali sumbu, kemudian menyalakan dan melambaikannya.
Musashi jadi menduga bahwa di seberang jembatan terdapat lebih banyak orang. Ia
tidak dapat bergerak, setidak-tidaknya sekarang. Kalau ia memperlihatkan diri,
kemungkinan akan mengundang lebih banyak tembakan. Sekalipun ia dapat mencapai
tepi seberang, bahaya yang menanti di sana barangkali lebih besar lagi. Tapi ia
pun tak dapat tinggal lebih lama di situ. Karena orang-orang itu tahu ia belum
menyeberang jembatan, mereka akan mengepungnya, dan barangkali akan berhasil
menemukan tempat persembunyiannya.
Mendadak ia mendapat
akal. Akal itu tidak didasarkan pada teori-teori Seni Perang yang merupakan
serabut intuisi seorang prajurit. Merancang cara menyerang merupakan proses
yang lambat, yang sering mengakibatkan kekalahan dalam situasi yang menuntut
kecepatan. Naluri seorang prajurit tidak boleh dikacaukan dengan naluri
binatang. Seperti halnya reaksi anggota tubuh bagian dalam, naluri itu datang
dari gabungan kebijaksanaan dan disiplin. Ia merupakan penalaran terakhir yang
melebihi akal, ia adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang benar dalam
sekejap mata, tanpa mesti melewati proses berpikir biasa.
"Sia-sia kalian
coba sembunyi!" pekiknya. "Kalau kalian mencariku, aku di sini!"
Angin agak kencang waktu itu; ia tak yakin suaranya terdengar atau tidak.
Pertanyaan itu
dijawab oleh tembakan lain. Musashi tentu saja sudah tidak ada di sana lagi.
Ketika peluru masih berada di udara, ia sudah melompat tiga meter ke arah ujung
jembatan.
Ia menyerbu ke tengah
mereka. Mereka pun menyebar sedikit, dan menghadapinya dari tiga jurusan, namun
sama sekali tanpa koordinasi. Ia tebas orang yang ada di tengah dengan pedang
panjang, dan serentak dengan itu ia menyayat ke samping, dengan pedang pendek,
ke arah orang di sebelah kirinya. Orang ketiga melarikan diri ke seberang
jembatan, berlari, terjatuh, dan terlontar ke luar jembatan.
Musashi mengikuti
dengan langkah biasa di satu sisi saja, sekali-sekali berhenti untuk
mendengarkan. Ketika tidak terjadi apa-apa lagi, ia pun pulang dan tidur.
Paginya dua samurai
datang ke rumahnya. Melihat jalan masuk penuh dengan sandal anak-anak, mereka
menikung ke samping.
"Anda Sensei
Muka?" tanya salah seorang. "Kami dari Keluarga Honda." Musashi
menengadah dari tulisannya, katanya "Ya, saya Muka."
"Apa nama Anda
sebenarnya Miyamoto Musashi? Kalau benar demikian, jangan Anda
menyembunyikannya."
"Saya
Musashi."
"Saya percaya
Anda kenal Watari Shima."
"Saya tidak
merasa mengenalnya."
"Dia bilang
pernah hadir dalan dua-tiga pesta haiku, di mana Anda hadir juga."
"Ya, sesudah
Anda sebutkan itu, saya ingat dia sekarang. Kami bertemu di rumah teman kami
berdua."
"Nah, dia
bertanya apakah Anda mau datang dan bermalam di rumahnya."
"Kalau dia
mencari orang yang akan diajaknya mengarang haiku, bukan saya orangnya. Memang
benar, beberapa kali saya diundang ke pesta seperti itu, tapi saya orang sederhana
yang hanya punya sedikit pengalaman dalam hal itu."
"Saya pikir dia
ingin membicarakan seni bela diri dengan Anda." Musashi membelalak gelisah
ke arah kedua samurai itu. Beberapa waktu lamanya ia menatap mereka, kemudian
katanya, "Kalau demikian, dengan senang hati saya akan datang ke rumahnya.
Kapan?"
"Apa Anda bisa
datang malam ini?"
"Baik."
"Dia akan
mengirimkan joli untuk Anda."
"Bagus. Saya
tunggu."
Setelah mereka pergi,
Musashi kembali menghadapi murid-muridnya. "Ayo," katanya.
"Kalian tak boleh membiarkan diri kalian terlengah. Ayo kerja lagi. Lihat
aku. Aku berlatih juga. Kalian mesti belajar memusatkan perhatian sepenuhnya,
sampai kalian tidak mendengar orang berbicara atau jangkrik mengerik. Kalau
kalian malas selagi muda, kalian akan jadi orang macam aku, dart mesti berlatih
sesudah kalian dewasa." Ia tertawa dan menoleh ke sekeliling, ke arah
wajah-wajah dan tangan-tangan yang berlepotan tinta itu.
Senja hari ia sudah
mengenakan hakama dan siap pergi. Ketika ia sedang meyakinkan istri penjual
kuas yang hampir menangis, bahwa ia akan selamat tak kurang suatu apa, joli pun
tiba—bukan joli anyaman sederhana seperti yang biasa kelihatan di seluruh kota
itu, melainkan joli berpernis yang dikawal dua samurai dan tiga orang abdi.
Para tetangga
terpesona melihatnya, berkerumun dan berbisik-bisik. Anak-anak memanggil
teman-temannya dan berceloteh dengan riuhnya.
"Cuma orang
besar naik joli macam itu."
"Mestinya guru
ini orang besar juga."
"Ke mana dia
pergi?"
"Dia kembali
atau tidak?"
Kedua samurai menutup
pintu joli, menyingkirkan orang banyak dari jalanan, dan berangkat.
Musashi tidak tahu
apa yang akan terjadi, tapi ia menduga ada hubungan antara undangan itu dengan
peristiwa di Jembatan Yahagi. Mungkin Shima akan menegurnya karena telah
membunuh dua orang samurai Honda. Mungkin juga Shima orang yang berdiri di
belakang usaha memata-matai dan melakukan serangan mendadak, dan sekarang siap
menghadapi Musashi secara terbuka. Musashi tidak yakin pertemuan malam itu akan
mendatangkan kebaikan, dan ia bertekad untuk menghadapi keadaan sulit.
Berspekulasi tidak akan membawanya ke mana-mana. Seni Perang menuntutnya untuk
menetapkan di mana ia berdiri, dan bertindak sesuai dengan itu.
Joli berayun-ayun
lembut, seperti perahu di laut. Mendengar angin yang mendesir di antara pohon
pinus, ia menduga mereka berada di hutan dekat dinding benteng sebelah utara.
Ia tidak kelihatan seperti orang yang sedang meneguhkan diri menghadapi
serangan tak terduga. Dengan mata setengah tertutup, ia tampak seperti sedang
tertidur.
Sesudah gerbang
benteng berkeriut membuka, langkah para pemikul menjadi lambat, sedangkan suara
para samurai lebih ditekan. Mereka melewati lentera-lentera yang
mengedip-ngedip, dan sampai di bangunan benteng. Musashi turun, dan para
pembantu mempersilakannya masuk ke sebuah paviliun terbuka dengan pelan, tapi
sopan. Karena kerai tergulung di keempat sisi ruangan, angin bertiup dalam
gelombang yang menyenangkan. Lampu-lampu memudar dan menyala liar. Malam itu
tidak mirip malam musim panas yang terik.
"Saya Watari
Shima," kata tuan rumah. Ia seorang samurai Mikawa yang khas—tegap, kuat,
waspada, tapi tidak berpura-pura, dan tidak memperlihatkan tanda-tanda
kelemahan.
"Saya Miyatomo
Musashi." Jawaban yang sama sederhananya itu diiringi bungkukan badan.
Shima membalas
bungkukan itu, katanya, "Anggaplah ini rumah sendiri," lalu langsung
menuju persoalan, tanpa basa-basi lagi. "Saya mendapat laporan, Anda
membunuh dua samurai kami tadi malam. Apa itu benar?"
"Ya,
benar," Musashi menatap mata Shima.
"Saya mesti
minta maaf," kata Shima murung. "Saya mendengar tentang peristiwa itu
hari ini, ketika kematian dilaporkan. Tentu saja dilakukan penyelidikan. Sudah
lama saya mengenal nama Anda, tapi baru sekarang saya tahu bahwa Anda tinggal
di Okazaki.
"Tentang serangan
itu, saya mendapat laporan bahwa Anda ditembak oleh sekelompok orang kami,
seorang di antaranya murid Miyake Gumbei, ahli bela diri Gaya Togun."
Karena tidak
merasakan ada dalih, Musashi menerima kata-kata Shima itu begitu saja, dan
cerita pun berkembang selangkah demi selangkah. Murid Gumbei adalah salah
seorang samurai Honda yang belajar pada Perguruan Yoshioka. Beberapa penghasut
yang ada di tengah mereka sebelumnya telah berkumpul, dan memutuskan untuk
membunuh orang yang telah mengakhiri kebesaran Perguruan Yoshioka itu.
Musashi tahu, nama
Yoshioka Kempo masih dipuja-puja di seluruh negeri. Di Jepang barat, terutama,
sukar kiranya menemukan perdikan yang tidak menyimpan samurai yang pernah
belajar di bawah pimpinannya. Musahi menyampaikan pada Shima bahwa ia dapat
memahami dendam mereka terhadapnya, tapi ia menganggap hal itu sebagai dendam
perseorangan, dan bukan sebagai alasan sah untuk melakukan balas dendam sesuai
Seni Perang.
Shima rupanya
sependapat. "Saya sudah memanggil orang-orang yang selamat, dan memarahi
mereka. Saya harap Anda memaafkan kami dan melupakan soal itu. Gumbei pun
sangat tidak senang. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin memperkenalkannya
pada Anda. Dia ingin menyampaikan permintaan maaf."
"Ah, tak perlu.
Apa yang telah terjadi itu adalah kejadian umum bagi siapa saja yang menempuh
jalan seni bela diri."
"Biar
begitu..."
"Nah, baiklah
kita buang kata-kata permintaan maaf itu. Tapi kalau dia ingin bicara tentang
Jalan, dengan senang hati saya akan menjumpainya. Nama itu saya kenal
betul."
Satu orang dikirim
untuk mengundang Gumbei, dan ketika kata-kata perkenalan sudah lewat,
pembicaraan pun beralih kepada pedang dan permainan pedang.
Kata Musashi,
"Saya ingin mendengar tentang Gaya Togun. Anda menciptakan gaya itu?"
"Tidak,"
jawab Gumbei. "Saya mempelajarinya dari guru saya, Kawasaki Kaginosuke,
dari Provinsi Echizen. Menurut kitab pegangan yang beliau berikan pada saya,
beliau mengembangkannya semasa menjadi pertapa di Gunung Hakuun di Kozuke.
Rupanya dia mengambil banyak teknik dari biarawan Tendai bernama Togumbo....
Tapi coba Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda. Saya sudah mendengar nama
Anda berkali-kali disebutkan orang. Tadinya saya mendapatkan kesan bahwa Anda
lebih tua. Dan karena Anda ada di sini, saya ingin agar Anda sudi memberikan
satu pelajaran pada saya." Nada kata-kata itu bersahabat, namun itu adalah
ajakan bertarung.
"Lain kali
saja," jawab Musashi ringan. "Saya mesti pergi sekarang. Saya pun
belum tahu jalan pulang."
"Kalau Anda
pulang nanti," kata Shima, "akan saya minta seseorang menemani
Anda."
"Waktu saya
mendengar dua orang roboh," Gumbei melanjutkan, "saya datang
menjenguk. Ternyata saya tak bisa memahami posisi tubuh dengan lukanya, karena
itu saya tanya orang yang berhasil lolos. Menurut kesannya, Anda menggunakan
dua pedang sekaligus. Apa itu benar?"
Sambil tersenyum,
Musashi mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan cara itu secara sadar. Ia
beranggapan, apa yang diperbuatnya hanyalah berkelahi dengan satu tubuh dan
satu pedang.
"Anda tak usah
merendahkan diri," kata Gumbei. "Anda ceritakanlah tentang itu.
Bagaimana Anda berlatih? Bagimana kita mesti meletakkan tekanan, agar kita
dapat menggunakan dua pedang sekaligus dengan bebas?"
Karena melihat bahwa ia
takkan dapat meninggalkan tempat itu sebelum memberikan penjelasan, Musashi
melayangkan pandang ke sekitar ruangan. Pandangan itu berhenti pada dua pucuk
bedil di dalam ceruk kamar, dan ia minta dipinjami. Shima setuju, lalu Musashi
pergi ke tengah ruangan, memegang kedua pucuk senjata itu pada larasnya,
masing-masing tangan memegang satu bedil.
Musashi mengangkat
sebelah lututnya, dan katanya, "Dua pedang sama dengan satu pedang. Satu
pedang seperti dua pedang. Kedua tangan kita ini terpisah satu dari yang lain,
tapi keduanya milik tubuh yang sama. Dalam segala hal, penalaran terakhir bukan
bersifat ganda, tapi bersifat tunggal. Demikian pula pada semua gaya dan
percabangannya. Akan saya tunjukkan pada Anda."
Kata-kata itu keluar
dengan spontan, dan ketika selesai diucapkan, ia mengangkat satu tangan,
katanya, "Maafkan." Kemudian ia mulai memutar kedua bedil itu. Kedua
bedil berpilin seperti gulungan, menimbulkan angin pusaran kecil. Orang-orang
yang hadir menjadi pucat.
Musashi berhenti, dan
menarik sikunya ke sisi. Ia berjalan ke ceruk kamar, dan mengembalikan kedua
bedil. Sambil tertawa kecil, katanya, "Barangkali itu tadi dapat membantu
Anda memahami." Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ia membungkuk
pada tuan rumah dan pergi. Karena terheran-heran, Shima lupa sama sekali
meminta seseorang untuk menemaninya.
Di luar gerbang,
Musashi menoleh untuk terakhir kali, dan merasa lega telah lepas dart
cengkeraman Watari Shima. Ia masih belum tahu maksud-maksud sebenarnya orang
itu, tapi satu hal sudah jelas. Tidak hanya identitasnya sudah diketahui orang,
tapi ia sudah terlibat dalam satu kejadian. Maka yang paling bijaksana baginya
adalah meninggalkan Okazaki malam ini juga.
Ia baru ingat akan
janjinya kepada Matahachi untuk menantikan kembalinya Gudo, ketika cahaya
Okazaki mulai terlihat, dan satu suara terdengar memanggilnya dari tempat suci
kecil di pinggir jalan.
"Musashi, ini
aku, Matahachi. Kami kuatir dengan dirimu, karena itu kami pergi ke sini
menanti."
"Kuatir?"
tanya Musashi.
"Kami tadi pergi
ke rumahmu. Perempuan tetanggamu bilang orang memata-mataimu belum lama
ini."
"Kami,
katamu?"
"Guru sudah
kembali hari ini."
Gudo duduk di beranda
tempat suci itu. Ia orang yang berwajah luar biasa, kulitnya sehitam kulit
jangkrik raksasa, dan matanya bersinar cemerlang di bawah alisnya yang tinggi.
Ia tampak seperti orang yang berumur antara empat puluh dan lima puluh tahun, namun
tak mungkin orang menebak orang seperti itu. Tubuhnya kurus kekar, dan suaranya
mendentum.
Musashi mendekat,
berlutut dan bersujud ke tanah. Gudo memandangnya tanpa berkata-kata
semenit-dua menit. "Lama sudah waktu berlalu," katanya.
Sambil mengangkat
kepala, kata Musashi tenang, "Ya, lama sekali." Gudo atau
Takuan—Musashi sudah lama yakin bahwa hanya salah satu dari mereka dapat
melepaskannya dari kebuntuan sekarang. Sesudah menanti setahun penuh, akhirnya
kini Gudo ada di hadapannya. Ia pandang wajah pendeta itu, seolah memandang
bulan di malam gelap.
Secara tiba-tiba dan
dengan penuh tenaga, serunya "Sensei."
"Ada apa?"
Gudo tak perlu lagi bertanya. Ia sudah tahu apa yang dikehendaki Musashi, dan
ia sudah menduganya, seperti seorang ibu meramalkan kebutuhan anak-anaknya.
Sambil bersujud ke
tanah lagi, Musashi berkata, "Sudah hampir sepuluh tahun sejak saya
belajar pada Bapak."
"Apa sudah
selama itu?"
"Ya. Tapi
biarpun sudah belajar selama itu, saya sangsi apakah kemajuan saya menempuh
Jalan itu dapat diukur."
"Bicaramu masih
seperti kanak-kanak, ya? Kalau begitu, tak mungkin jauh jalanmu."
"Banyak sekali
yang saya sesali."
"Betul?"
"Latihan dasar
dan disiplin diri saya begitu sedikit terlaksana."
"Kau selalu
bicara tentang hal-hal semacam itu. Selama kau masih berbuat begitu, itu
sia-sia."
"Apa yang akan
terjadi, kalau saya tinggalkan ini?"
"Kau akan
terjerat simpul lain lagi. Kau akan menjadi sampah manusia yang lebih buruk
daripada sebelumnya, ketika kau masih bodoh, tidak tahu apa-apa,"
"Kalau saya
tinggalkan Jalan ini, saya akan jatuh ke dalam jurang. Tapi, untuk mencoba
mengejarnya sampai ke puncak, saya tak sanggup menghadapi tugas itu. Saya jadi
berputar-putar dalam angin tanggung menuju ke atas. Saya tak ingin jadi pemain
pedang atau manusia."
"Ya, agaknya
begitulah kesimpulannya."
"Bapak tidak
tahu, betapa putus asa saya selama ini. Apa yang mesti saya lakukan? Bapak,
katakanlah! Bagaimana saya dapat membebaskan diri dari kemandekan dan
kekacauan?"
"Kenapa tanya
padaku? Kau hanya dapat mengandalkan dirimu."
"Izinkan saya
duduk di kaki Bapak. Saya dan Matahachi. Atau hantam saya dengan tongkat Bapak
itu, untuk membangunkan saya dari kekosongan gelap ini. Saya mohon, Sensei,
tolonglah saya." Musashi tidak mengangkat kepalanya. Ia tidak meneteskan
air mata, tapi suaranya tercekik.
Tanpa tergerak oleh
kata-kata Musashi sedikit pun, kata Gudo, "Ayo, Matahachi!" Kemudian
bersama-sama mereka pergi meninggalkan tempat suci itu.
Musashi berlari
mengejar pendeta itu, mencengkeram lengan bajunya, meminta dan memohon.
Pendeta itu
menggelengkan kepala, tidak mengatakan sesuatu. Ketika Musashi berkeras juga,
katanya, "Sama sekali tak ada!" Kemudian dengan marah, "Apa yang
mesti kukatakan? Apa lagi yang mesti kuberikan? Hanya tinggal menghantam kepala
itu." Ia mengayunkan tinjunya ke udara, tapi tidak memukul.
Musashi melepaskan
lengan baju si pendeta, dan hendak mengatakan yang lain lagi, tapi pendeta itu
berjalan cepat menjauh, tanpa berhenti lagi untuk menoleh.
Matahachi yang berada
di sampingnya berkata, "Waktu kujumpai beliau di kuil, dan kusampaikan
perasaan kita dan alasan kita ingin menjadi muridnya, beliau hampir tak
mendengarkan. Dan waktu aku selesai bicara, beliau berkata, 'Oh?' dan mengatakan
aku dapat mengikutinya dan melayaninya. Barangkali kalau kau mengikuti kami
terus, nanti kalau suasana hati beliau sedang baik, kau dapat minta apa yang
kauinginkan."
Gudo menoleh dan
memanggil Matahachi.
"Baik,
Pak!" kata Matahachi. "Lakukan anjuranku ini," nasihatnya pada
Musashi, sambil berlari mengejar si pendeta.
Karena menurut
pendapatnya membiarkan Gudo lenyap lagi dari pandangan akan fatal baginya,
Musashi memutuskan menuruti nasihat Matahachi. Di tengah aliran waktu alam
semesta, hidup manusia yang enam atau tujuh puluh tahun itu hanya merupakan
kilat. Kalau dalam jangka waktu singkat itu ia mendapat hak istimewa untuk
menjumpai seorang Gudo, sungguh bodoh melepaskan kesempatan itu.
"Ini kesempatan
yang suci," pikir Musashi. Air mata panas mengambang di sudu't-sudut
matanya. Ia harus mengikuti Gudo, sampai ujung dunia kalau perlu, dan
mengejarnya sampai ia mendengar kata yang ingin didengarnya.
Gudo pergi
meninggalkan Bukit Hachijo. Agaknya ia tidak lagi tertarik akan kuil di sana.
Hatinya sudah mulai mengalir bersama air dan awan. Sampai Tokaido, ia membelok
ke barat, ke arah Kyoto.


0 komentar:
Posting Komentar