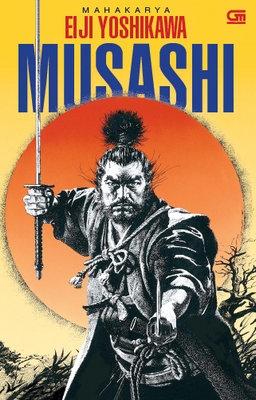
Terlalu Banyak Kojiro
DI warung minum kecil
di luar kota itu, bau kayu terbakar dan makanan yang sedang direbus memenuhi
udara. Warung itu cuma gubuk tak berlantai. Ada papan pengganti meja dan
beberapa bangku di sana-sini. Di luar, cahaya terakhir matahari terbenam
membuat seolah ada bangunan di kejauhan yang sedang terbakar. Burung-burung
gagak yang mengelilingi pagoda Toji tampak seperti abu hitam yang membubung
dari nyala kebakaran.
Tiga atau empat
pemilik warung dan seorang biarawan pengembara duduk di meja darurat tadi, sedangkan
di sebuah sudut ada beberapa pekerja berjudi dengan taruhan minuman. Gasing
yang mereka putar adalah mata uang tembaga yang lubangnya ditusuk dengan
sepotong kayu.
"Yoshioka
Seijuro betul-betul kesulitan sekarang ini!" kata salah seorang pemilik warung.
"Dan aku senang sekali melihatnya. Mari kita minum!"
"Aku ikut
minum," kata yang lain.
"Sake
lagi!" kata yang lain lagi pada pemilik warung.
Para pengunjung
warung itu minum dengan cepat dan terus-menerus. Lama-kelamaan hanya cahaya
temaram yang menerangi tirai warung. Seorang di antaranya melenguh, "Tak
kelihatan lagi, mangkuk ini sampai hidung atau mulut? Terlalu gelap di sini.
Bagaimana kalau pasang lampu?"
"Tunggu
sebentar. Akan kupasang," kata pemilik dengan letih.
Dari tungku tanah
yang terbuka segera menjulang nyala api. Makin gelap di luar, makin merah sinar
api itu.
"Bikin gila tiap
kali memikirkannya," kata orang pertama tadi. "Berapa banyak uang
diutang orang-orang itu buat ikan dan arang! Jatuhnya besar juga. Lihat saja
besarnya perguruan itu! Aku sudah bersumpah akan mendapatkan kembali uang itu
pada akhir tahun, tapi apa yang terjadi waktu aku sampai di sana? Tukang-tukang
gertak Yoshioka menghadang di pintu masuk, menggertak dan mengancam semua
orang. Berani betul mereka itu mengusir penarik rekening, pemilik-pemilik
warung yang jujur, yang bertahun-tahun memberinya kredit!"
"Tak ada gunanya
menangisi sekarang. Yang sudah terjadi sudahlah. Dan lagi, sesudah pertarungan
di Rendaiji itu, merekalah sekarang yang lebih punya alasan menangis, bukan
kita."
"Ah, aku tak
marah lagi sekarang. Mereka sudah mendapatkan ganjarannya."
"Coba bayangkan,
Seijuro ditundukkan hampir tanpa pertarungan!"
"Apa kau melihat
sendiri?"
"Tidak, tapi aku
dengar dari orang yang lihat. Musashi bikin lumpuh dia hanya dengan satu
pukulan. Dan dengan pedang kayu pula! Cacat seumur hidup dia sekarang."
"Bagaimana
jadinya perguruan itu?"
"Kelihatannya
kurang baik juga. Semua murid sekarang menuntut darah Musashi. Kalau mereka
tidak membunuh Musashi, mereka bisa kehilangan muka sama sekali. Nama Yoshioka
terpaksa runtuh. Musashi begitu kuat. Tiap orang merasa satu-satunya yang akan
dapat mengalahkan dia hanya Denshichiro. Mereka sedang mencarinya
sekarang."
"Aku tidak tahu
Seijuro punya adik."
"Memang hampir
tak ada yang tahu, tapi dia pemain pedang yang lebih baik, menurut yang
kudengar. Dialah berandal keluarga itu. Dia tak pernah memperlihat-kan muka di
perguruan itu, kecuali kalau butuh uang. Buang waktu dengan makan dan minum dan
memanfaatkan namanya sendiri. Hidup dari orang-orang yang menghormati
ayahnya."
"Bukan main
pasangan itu. Bagaimana orang terkemuka macam Yoshioka Kempo bisa memperanakkan
orang-orang macam itu?"
"Itu berarti
darah bukan segala-galanya!"
Seorang ronin
teronggok setengah sadar di dekat tungku. Sudah beberapa waktu lamanya ia di
situ, dan pemilik warung membiarkannya saja, tapi sekarang dibangunkannya.
"Pak, tolong mundur sedikit," katanya sambil menambahkan ranting-ranting
kayu api. "Api ini bisa membakar kimono Bapak."
Mata Matahachi yang
sudah merah oleh sake itu terbuka pelan-pelan. "Mm, mm, aku tahu, aku
tahu. Biarkan aku sendiri."
Warung sake ini bukan
satu-satunya tempat Matahachi mendengar tentang pertarungan di Rendaiji itu.
Peristiwa tersebut dibicarakan setiap orang, dan semakin terkenal Musashi,
semakin murung temannya yang bertingkah itu.
"Hei, kasih
lagi," panggilnya. "Tak usah dipanaskan, tuangkan saja ke
mangkukku."
"Bapak tak
apa-apa, ya? Wajah Bapak pucat sekali."
"Apa urusanmu?
Ini mukaku sendiri, kan?"
Ia menyandarkan diri
ke dinding lagi dan menyilangkan tangan di dada. "Sebentar lagi akan
kutunjukkan pada mereka," pikirnya. "Keahlian main pedang bukan
satu-satunya jalan menuju sukses. Dengan menjadi kaya, atau memiliki gelar,
atau menjadi bajingan, sama saja, asal sampai di puncak. Musashi dan aku
sama-sama berumur dua puluh tiga. Orang yang punya nama pada umur itu tak
banyak yang jauh jalannya. Umur tiga puluh tahun mereka sudah tua dan
sempoyongan—‘si anak pandai yang
menua."
Kabar pertarungan di
Rendaiji itu telah menyebar di Osaka, dan mendorong Matahachi datang ke Kyoto.
Sekalipun belum punya tujuan jelas, kemenangan Musashi itu berat menekan
jiwanya, hingga ia mesti melihat sendiri bagaimana keadaannya. "Dia sedang
menanjak sekarang," pikir Matahachi benci, "tapi pasti dia akan
jatuh." Banyak orang yang cakap di perguruan Yoshioka itu—Sepuluh Pemain
Pedang, Denshichiro, dan banyak lagi yang lain..." Hampir-hampir ia tak
dapat menanti, kapan Musashi akan menerima pembalasan. Sementara itu nasibnya
sendiri pasti sudah berubah.
"Oh, haus!"
katanya keras. Dengan menopang, menggeser, dan punggung bersandar pada dinding,
ia berhasil berdiri. Semua mata memperhatikan ketika ia membungkuk ke tong air
di sudut ruangan dan mencelupkan kepalanya, lalu menenggak beberapa tegukan
besar dengan ciduk. Ciduk dilemparkannya ke samping, digesernya tirai warung,
dan keluarlah ia tertatih-tatih.
Setelah menganga
keheranan, pemilik warung segera tersadar dan lari mengejar tubuh yang berjalan
gontai itu. "Pak, Bapak belum bayar!" panggilnya.
"Apa?" kata
Matahachi tak jelas.
"Saya pikir ada
yang Bapak lupakan."
"Aku tidak lupa
apa-apa."
"Maksud saya,
uang sake itu. Ha, ha!"
"Begitu,
ya?"
"Maaf sudah
mengganggu."
"Aku tak punya
uang."
"Tak punya
uang?"
"Ya, tak punya
sama sekali. Aku punya sampai beberapa hari yang lalu, tapi..."
"Oh, lalu kenapa
Bapak duduk minum-minum di sana...! Bapak... Bapak... „
"Diam
kamu!" Matahachi meraba-raba dalam kimononya, kemudian mengeluarkan kotak
obat samurai yang sudah mati itu dan melemparkannya kepada orang itu.
"Jangan banyak ribut! Aku samurai dengan dua pedang. Kamu lihat sendiri,
kan? Aku belum bangkrut dan tidak akan ngeluyur tanpa bayar. Barang itu lebih
mahal daripada sake yang kuminum. Boleh kembaliannya kamu simpan!"
Kotak obat tepat
mengenai muka orang itu. Ia memekik kesakitan dan menutup mukanya dengan
tangan. Para pembeli lain yang melongokkan kepala lewat celah tirai warung
berteriak marah. Seperti kebanyakan orang mabuk, mereka marah melihat pemabuk
lain ingkar membayar.
"Bajingan!"
"Penipu
busuk!"
"Mari kita hajar
dia!"
Mereka berlari
mengepung Matahachi.
"Bajingan!
Bayar! Tidak bisa kamu pergi begitu saja!"
"Brengsek! Kamu
rupanya biasa begitu terus, ya? Kalau kamu tak bisa bayar, kami gantung
kamu!"
Matahachi menjamah
pedangnya untuk menakut-nakuti mereka. "Kalian pikir kalian bisa?"
gertaknya. "Akan menarik sekali ini. Boleh coba! Apa kalian sudah tahu,
siapa aku?"
"Kami tahu macam
apa kamu itu—ronin kotor dari tumpukan sampah, yang harga dirinya lebih rendah
dari pengemis, tingkahnya lebih dari pencuri:"
"Jadi, kalian
belum tahu!" teriak Matahachi memandang tajam dan mengerutkan kening dengan
ganas. "Bicara kalian akan lain kalau kalian tahu namaku."
"Namamu? Apa
istimewanya nama itu?"
"Aku Sasaki
Kojiro, murid seangkatan Ito Ittosai, pemain pedang Gaya Chujo. Kalian pasti
sudah mendengar tentangku!"
"Jangan bikin
aku ketawa! Tak perlu itu nama-nama khayal, bayar saja."
Satu orang
mengulurkan tangan untuk mencekal Matahachi, tapi Matahachi berteriak,
"Kalau kotak obat itu tak cukup, akan kuberi kamu sedikit pedangku buat
tambahan!" Ia cepat menarik senjatanya, menebas tangan orang itu sampai
putus.
Melihat bahwa
ternyata mereka tadi terlalu menyepelekan musuh, yang lain beraksi seolah darah
mereka sendiri yang sudah tercurah. Mereka pun melarikan diri ke dalam
kegelapan.
Dengan wajah penuh
kemenangan Matahachi menantang. "Kembali kalian, kutu-kutu! Akan
kutunjukkan pada kalian cara Kojiro menggunakan pedang kalau sedang serius.
Sinilah, akan kupotong kepala kalian."
Ia memandang ke
langit dan tertawa terpingkal-pingkal, giginya yang putih berkilau di tengah
kegelapan, girang atas suksesnya. Kemudian tiba-tiba sikapnya berubah. Wajahnya
berselimut kesedihan. Ia seperti mencucurkan air mata. Dengan kaku ia entakkan
pedangnya kembali masuk ke sarungnya dan pergilah ia dengan gontai.
Kotak obat di tanah
itu berkelip-kelip di bawah sinar bintang. Kotak itu terbuat dari kayu cendana
dengan tatahan kulit kerang; kelihatannya tidak terlalu berharga, tetapi kilat
kulit kerang mutiara yang biru itu menyinarkan keindahan lembut, seperti
sekelompok kecil kunang-kunang.
Ketika keluar dari
gubuk, si biarawan pengembara melihat kotak obat itu dan memungutnya. Ia
berjalan terus, tapi kemudian kembali dan berdiri di bawah ujung atap warung.
Dalam cahaya redup yang keluar dari celah dinding ia amat-amati pola dan tali
kotak itu dengan saksama. "Hmmm,° pikirnya. "Ini pasti milik guru
itu. Dia tentu sedang membawanya ketika terbunuh di Kuil Fushimi. Ya, ini
namanya, Tenki, tertulis di dasarnya."
Biarawan itu segera
mengejar Matahachi. "Sasaki!" panggilnya. "Sasaki Kojiro!"
Matahachi mendengar
nama itu, tapi dalam keadaan bingung ia tak mampu menghubungkannya dengan
dirinya. Ia terhuyung terus dari Jalan Kujo ke Jalan Horikawa.
Biarawan itu berhasil
mengejarnya dan memegang ujung sarung pedangnya. "Tunggu, Kojiro," katanya.
"Tunggu sebentar."
"Hah?" kata
Matahachi tersentak, "Maksudmu aku?"
"Anda Sasaki
Kojiro, kan?" Sinar tajam menyala dalam mata biarawan itu. Matahachi
sedikit sadar sekarang.
"Ya, aku Kojiro.
Apa urusannya itu denganmu?"
"Saya mau
mengajukan satu pertanyaan."
"Nah, pertanyaan
apa itu?"
"Di mana Anda
mendapat kotak obat ini?"
"Kotak
obat?" tanya Matahachi kosong.
"Ya. Di mana
Anda mendapatkannya? Itu yang ingin saya ketahui. Bagaimana kotak ini bisa
menjadi milik Anda?" Biarawan itu berbicara agak resmi. Ia masih muda,
barangkali baru sekitar dua puluh enam tahun, dan tampaknya bukan biarawan
pengemis yang tak bersemangat, yang mengembara dari kuil ke kuil dan hidup dari
derma. Sebelah tangannya memegang tongkat kayu ek bulat, lebih dari enam kaki
panjangnya.
"Tapi siapa kamu
ini?" tanya Matahachi, wajahnya mulai tampak prihatin.
"Itu tak
penting. Kenapa tidak Anda nyatakan saja dari mana ini datangnya?"
"Tidak dari
mana-mana. Selamanya itu milikku."
"Anda bohong! Katakan
yang sebenarnya!"
"Sudah kukatakan
yang sebenarnya."
"Anda menolak
mengakuinya?"
"Mengakui
apa?" tanya Matahachi tak bersalah.
"Kau bukan
Kojiro!" Seketika tongkat di tangan biarawan itu membelah udara.
Naluri Matahachi
mendorongnya bergerak mundur, tapi ia masih terlampau pening untuk cepat
beraksi. Tongkat mengenai sasaran, dan melolong kesakitan ia sempoyongan ke
belakang lima belas atau dua puluh kaki jauhnya, dan jatuh telentang. Begitu
bangkit lagi, ia langsung lari.
Si biarawan
mengejarnya, dan beberapa langkah kemudian melontarkan lagi tongkat ek itu.
Matahachi mendengar tongkat itu terbang ke arahnya. Ia meren-dahkan kepala.
Peluru terbang itu melayang lewat telinganya. Karena ketakutan, ia
melipatgandakan kecepatannya.
Si biarawan meraih
senjata yang terjatuh itu, mengambilnya, dan sesudah membidik baik-baik,
melontarkannya lagi, tapi sekali lagi Matahachi merunduk.
Sesudah berlari
dengan kecepatan tinggi lebih dari satu setengah kilometer, Matahachi melewati
Jalan Rokujo dan mendekati Jalan Gojo. Akhirnya ia lepas dari kejaran dan
berhenti. Terengah-engah ia mengetuk-ngetuk dadanya. "Tongkat itu...
senjata mengerikan! Orang mesti berhati-hati sekarang ini."
Sudah tenang benar
tapi haus bukan main, ia mencari sumur. Ia temukan sumur itu di ujung sebuah
jalan sempit. Ia angkat satu timba dan ia reguk air sepuas-puasnya, kemudian ia
taruh ember di tanah dan berkecipaklah ia membasahi wajahnya dan berkeringat.
"Siapa pula
orang itu?" pikirnya, "Dan apa maunya?" Tapi begitu merasa
normal kembali, datanglah kembali rasa murung itu. Di ruang matanya tampaklah
wajah mayat tak berdagu yang kelihatan menderita sekali di Fushimi.
Hati nuraninya terasa
sakit, karena ia menggunakan uang orang mati itu. Bukan untuk pertama kalinya
ia bermaksud menebus perbuatan keliru itu. "Kalau aku punya uang,"
sumpahnya, "yang pertama akan kulakukan adalah membayar kembali utangku.
Barangkali nanti setelah aku sukses akan kudirikan batu peringatan
untuknya."
Cuma sertifikat itu
yang tinggal. Barangkali aku mesti melepaskannya. Kalau nanti orang yang tidak
tepat tahu aku yang memilikinya, bisa timbul kesulitan." Ia meraba ke
dalam kimononya dan menyentuh gulungan yang selama itu selalu diselipkan di
perut, di bawah obi, sekalipun terasa tak enak.
Bahkan kalaupun ia
memang tak dapat mengubahnya menjadi uang dalam jumlah banyak, sertifikat itu
dapat menjadi pembuka ke anak tangga ajaib yang pertama menuju sukses. Jadi,
pengalaman sial dengan Akakabe Yasoma tidak menyembuhkan-nya dari penyakit mimpi.
Sertifikat itu sudah
menjadi amat berguna. Dengan menunjukkannya ke dojo-dojo kecil tak bernama atau
kepada orang kota yang polos dan ingin belajar main pedang, ia dapat memperoleh
penghormatan dari mereka bahkan juga mendapat makan bebas dan tempat menginap,
walaupun tidak dimintanya. Begitulah cara ia hidup selama enam bulan terakhir
ini.
"Tidak ada
alasan membuangnya. Ah, apa yang terjadi dengan diriku ini? Rupanya makin lama
aku makin jadi penakut. Barangkali itulah vang menghalangiku mencapai kemajuan
di dunia ini. Dari sekarang aku takkaa berbuat seperti itu lagi! Aku akan jadi
besar dan berani, seperti Musash. Akan kutunjukkan pada mereka!"
Ia menoleh ke
sekitar, ke pondok-pondok yang mengitari sumur. Orang-orang yang tinggal di
situ membuatnya iri. Memang rumah mereka melengkung akibat beratnya lumpur dan
rumput liar di atapnya, tapi setidaknya mereka memiliki peneduh. Ia mengintip,
melihat beberapa di antara keluarga itu. Di satu rumah ia lihat sepasang
suami-istri duduk menghadapi kuali berisi makan malam mereka yang sederhana. Di
dekat mereka duduk anak lelaki dan perempuan bersama nenek mereka yang sedang
memotong-motong.
Sekalipun miskin
dalam hal keduniaan, mereka memiliki semangat kesatuan keluarga, suatu kekayaan
yang tidak dimiliki bahkan oleh orang-orang besar seperti Hideyoshi dan Ieyasu.
Matahachi merasa bahwa semakin orang menderita kemiskinan, semakin kuat rasa
saling cinta. Orang miskin juga dapat memahami kegembiraan sebagai manusia.
Dengan rasa malu ia
teringat benturan kemauan yang menyebabkan ia pergi meninggalkan ibunya sendiri
di Sumiyoshi. "Mestinya aku tak boleh berlaku demikian terhadapnya,"
pikirnya. "Apa pun kesalahannya, tak bakal ada orang lain yang cintanya
padaku seperti cintanya."
Selama seminggu
tinggal bersama, berjalan dari tempat suci ke kuil, dan dari kuil ke tempat
suci yang sangat menjengkelkan itu, Osugi berkali-kali berbicara kepadanya
tentang daya-daya ajaib Kannon di Kiyomizudera. "Tak ada bodhisatwa di
dunia ini yang dapat menciptakan keajaiban lebih besar daripada dia,"
demikian ibunya meyakinkannya. "Kurang dari tiga minggu sesudah aku pergi
berdoa ke sana, Kannon memimpin Takezo datang padaku membawanya langsung ke
kuil itu. Aku tahu engkau tak begitu peduli dengan agama, tapi lebih baik
engkau percaya kepada Kannon."
Sekarang hal itu
terpikir oleh Matahachi, dan teringat olehnya ibunya mengatakan bahwa sesudah
tahun baru ia punya rencana akan pergi ke Kiyomizu, meminta perlindungan Kannon
atas keluarga Hon'iden. Jadi, ke sanalah ia mesti pergi! Malam itu ia tak punya
tempat untuk tidur. Ia dapat menginap di beranda, ada kemungkinan bisa bertemu
dengan ibunya kembali.
Ketika menyusuri
jalan-jalan gelap menuju Jalan Gojo, ia diikuti segerombolan anjing kampung
liar yang menyalak-nyalak, yang sialnya bukan dari jenis yang dapat dibungkam
dengan melemparkan sebutir dua butir batu. Untungnya ia sudah biasa digonggong
anjing, jadi tidak ada halangan anjing-anjing itu menggeram kepadanya dan
memperlihatkan gigi mereka.
Di Matsubara, sebuah
hutan pinus dekat Jalan Gojo, ia melihat kawanan anjing kampung lain berkumpul
sekitar sebatang pohon. Anjing-anjing yang mengawalnya itu berlari
menggabungkan diri dengan mereka. Jumlahnya lebih banyak dari yang dapat
dihitungnya. Semuanya begitu gaduh. Sebagian ada yang melompat-lompat sampai
setinggi dua meter ke batang itu.
Ia menajamkan mata,
dan tampak olehnya seorang gadis meringkuk gemetar di sebuah cabang pohon itu.
Paling tidak, ia cukup yakin orang itu seorang gadis.
Ia mengacung-acungkan
tinju dan berteriak mengusir anjing-anjing itu. Ketika dilihatnya tanpa hasil,
ia lemparkan batu-batuan, tapi juga tak berhasil. Kemudian ia ingat kata orang,
cara menakuti anjing adalah dengan merangkak dan meraung keras. la pun berbuat
demikian. Tapi ini pun tak ada hasilnya. Barangkali jumlah anjing itu demikian
banyaknya, melompat ke sana kemari seperti ikan dalam jaring. Ada yang
mengibas-ngibaskan ekor, mencakar-cakar kulit pohon, dan melolong kejam.
Tiba-tiba terpikir
olehnya, seorang perempuan bisa menganggap lucu bahwa seorang pemuda dengan dua
bilah pedang merangkak menirukan binatang. Sambil memaki ia meloncat berdiri.
Sesaat kemudian seekor anjing melolong untuk terakhir kali dan mati. Ketika
yang lain-lain melihat pedang Matahachi yang berdarah itu teracung di atas
kepalanya, mereka pun menarik diri berdekatan, hingga punggung mereka yang
kurus-kurusitu berombak naik-turun seperti ombak samudra. "Mau lagi,
ya?"
Takut akan ancaman
pedang itu, anjing-anjing buyar ke segala jurusan. "Hai, yang di atas
itu!" seru Matahachi. "Turun kamu sekarang."
Dari tengah dedaunan
pinus itu ia dengar denting logam kecil yang manis. "Oh, Akemi,"
gagapnya. "Akemi, kau, ya?"
Dan terdengar Akemi
berseru ke bawah, "Siapa kamu?"
"Matahachi. Apa
kau tidak kenal suaraku?"
"Mana mungkin!
Kamu bilang Matahachi?"
"Apa kerjamu di
atas itu? Kamu bukan orang yang gampang takut dengan anjing."
"Aku di atas ini
bukan karena anjing."
"Nah, apa pun
sebabnya, turunlah."
Dari tempat
bertenggernya, Akemi meninjau ke sekitar, ke tengah kegelapan yang tenang.
"Matahachi!" katanya mendesak. "Pergi kamu dari sini. Kukira dia
datang mencariku."
"Dia? Siapa dia
itu?"
"Tak ada waktu
membicarakannya. Seorang lelaki. Dia menawarkan bantuan padaku akhir tahun
lalu, tapi ternyata dia binatang. Semula kukira dia baik, tapi kemudian
dilakukannya segala macam tindakan kejam padaku. Malam ini kulihat kesempatan
lari."
"Apa bukan Oko
yang mengejarmu?"
"Bukan, bukan
Ibu. Lelaki!"
"Gion Toji,
barangkali?"
"Jangan melucu
begitu, aku tidak takut pada Gion Toji.... Oh, oh, dia sudah di sana. Kalau
kamu tetap di situ, dia nanti menemukan aku. Dan dia akan berbuat yang
mengerikan juga padamu! Cepat sembunyi!"
"Jadi, maumu aku
lari hanya karena muncul seorang lelaki?" Matahachi tetap berdiri, gelisah
oleh sikap ragu-ragunya sendiri. Ia setengah ingin melakukan perbuatan gagah
berani. Ia seorang lelaki. Ada perempuan dalam bahaya. Ia ingin menebus malu
karena merangkak ketika hendak mengusir anjing tadi. Semakin Akemi mendesaknya
bersembunyi, semakin ingin Matahachi memperlihatkan kejantanannya, baik kepada
Akemi maupun kepada diri sendiri.
"Siapa di
situ!"
Kata-kata itu
serentak diucapkan oleh Matahachi dan Kojiro. Kojiro menatap pedang Matahachi
dan darah yang masih menetes-netes darinya. "Siapa engkau?" tanyanya
dengan sikap bermusuhan.
Matahachi diam saja.
Mendengar nada takut dalam suara Akemi tadi, ia menjadi tegang. Tapi sesudah
memperhatikan lagi ketegangan pun mereda. Orang baru itu jangkung dan tegap
tubuhnya, tapi tak lebih tua dari Matahachi sendiri. Dari potongan rambut dan
pakaiannya, Matahachi menduga orang itu bawahan yang masih buruk kelakuan dan
matanya pun tampak merendahkan. Biarawan tadi memang telah membuat ia
ketakutan, tapi ia yakin takkan kalah oleh pemuda pesolek itu.
"Apa ini orang
kejam yang sudah menyiksa Akemi?" tanyanya pada dirinya sendiri.
"Kelihatannya begitu hijau seperti labu. Cerita seluruhnya belum kudengar,
tapi kalau memang dia orang yang bikin susah itu, kukira lebih baik kuberi dia
satu-dua pelajaran."
"Siapa
engkau?" tanya Kojiro lagi. Daya ucapan itu demikian rupa, hingga seolah
dapat mengusir kegelapan sekitar mereka.
"Aku?"
jawab Matahachi menggoda. "Aku cuma manusia." Dan dengan sengaja ia
menyeringai.
Wajah Kojiro merah
oleh amarah. "Jadi, engkau tak punya nama rupanya," katanya.
"Atau barangkali kau malu dengan namamu?"
Matahachi merasa
gusar, namun tidak takut, dan jawabnya pedas, "Aku tak melihat perlunya
memberikan nama kepada orang asing yang barangkali juga takkan mengenali nama
itu."
"Jaga lidahmu
itu!" bentak Kojiro. "Tapi mari kita tunda dulu perkelahian antara kita.
Aku mau menurunkan gadis dari atas pohon itu dan mengembalikannya ke tempat
semestinya. Tunggu di sini."
"Jangan bicara
macam orang tolol! Bagaimana kau bisa menduga akan kubiarkan kau mengambil
gadis itu?"
“Lho, ada hubungan
apa denganmu?"
"Ibu gadis itu
dulu istriku, dan aku takkan membiarkannya dibikin cedera. Kalau kau meletakkan
satu jari saja padanya, akan kurajang kau."
"Oh, menarik.
Engkau rupanya mengkhayalkan dirimu sebagai samurai. Terpaksa kukatakan di
sini, lama aku tak melihat samurai yang begini kurus. Tapi ada yang perlu
kauketahui. Galah Pengering di punggungku ini terus menangis dalam tidurnya,
karena sejak diturunkan sebagai pusaka belum sekali pun merasa puas minum
darah. Dan sudah sedikit karatan juga, jadi kupikir sekarang akan kugosok dia
sedikit dengan bangkaimu yang kurus itu. Dan jangan coba-coba lari!"
Matahachi tak punya
kemampuan menilai bahwa ini bukan gertak sambal, karenanya ia berkata mengejek,
"Cukup omongan besar itu! Kalau engkau mau berpikir sekali lagi, sekarang
ini waktunya. Pergi dari sini. selagi kau masih melihat jalan. Akan
kuselamatkan nyawamu."
"Sama juga
denganmu, hai manusia tampan. Kamu membanggakan diri bahwa namamu terlalu bagus
untuk disebutkan kepada orang-orang macam aku. Coba sebutkan, siapa namamu yang
indah itu? Menyebutkan nama itu bagian dari etiket dalam berkelahi. Atau kamu
tak tahu itu?"
"Aku tidak
keberatan menyebutnya, tapi jangan kaget kalau kamu mendengarnya."
"Aku akan
menguatkan diri untuk tidak terkejut. Tapi lebih dulu, apa gaya main
pedangmu?"
Matahachi
membayangkan bahwa orang yang mengoceh secara itu tak mungkin pemain pedang
berarti, maka taksirannya terhadap lawannya pun lebih turun lagi.
"Aku punya
sertifikat Gaya Chujo, cabang dari Gaya Toda Seigen," jelas Matahachi.
Kojiro kaget, tapi
mencoba menyembunyikannya.
Matahachi percaya
bahwa ia lebih unggul, karenanya ia berpendapat. tolol sekali kalau ia tidak
menekan terus. Menirukan orang yang bertanya kepadanya, katanya, "Sekarang
sebutkan, apa gayamu? Itu bagian etiket dalam perkelahian, Iho!"
"Nanti. Tapi
dari mana kamu belajar Gaya Chujo itu?"
"Dari Kanemaki
Jisai, tentu saja," jawab Matahachi fasih. "Dari siapa lagi?"
"Oh?" ucap
Kojiro yang sekarang benar-benar heran. "Dan apa kamu kenal Ito
Ittosai?"
"Tentu
saja." Menurut tafsiran Matahachi, pertanyaan-pertanyaan Kojiro itu
membuktikan bahwa cerita yang dikarangnya ada hasilnya, dan ia merasa yakin
bahwa orang muda itu akan segera mengajukan kompromi. Untuk lebih menekan
sedikit lagi, katanya, "Kukira tak ada alasan menyembunyikan hubunganku
dengan Ito Ittosai. Dia pendahuluku. Yang kumaksud, kami berdua belajar di
bawah pimpinan Kanemaki Jisai. Kenapa kamu tanyakan?"
Kojiro mengabaikan
saja pertanyaan itu. "Kalau begitu, boleh aku tanva lagi, siapa
kamu?"
"Aku Sasaki
Kojiro."
"Katakan
lagi!"
"Aku Sasaki Kojiro,"
ulang Matahachi dengan sopan sekali.
Setelah terdiam
sejenak karena tercengang, Kojiro pun memperdengarkan suara geram dan
memperlihatkan lesung pipitnya.
Matahachi menatapnya.
"Kenapa kamu pandang aku macam itu? Apa namaku mengejutkanmu?"
"Kukira
begitu."
'Baiklah... sekarang
pergi!" Matahachi memerintah dengan nada mengancam. dengan dagu
ditegakkan.
"Ha, ha, ha, ha!
Oh! Ha, ha, ha!" Kojiro memegang perutnya agar tidak roboh karena tawa.
Ketika akhirnya ia dapat mengendalikan diri kembali, katanva, "Sudah
banyak kutemui orang dalam perjalananku, tapi belum pernah aku mendengar hal
seperti ini. Nah, Sasaki Kojiro, sekarang sudilah kamu menyatakan padaku, siapa
aku ini?"
“Mana aku tahu?"
"Kamu mesti
tahu! Kuharap sikapku tidak terasa kasar, tapi untuk memastikan bahwa
pendengaranku benar, harap sebut namamu sekali lagi."
"Apa kamu tidak
bertelinga? Aku Sasaki Kojiro."
“Dan aku...?"
“Manusia lain,
kukira."
"Tentu saja,
tapi siapa namaku?"
"Bajingan kamu,
apa kamu mau mempermainkan aku?"
"Tentu saja
tidak. Aku sungguh-sungguh. Belum pernah aku lebih serius dari sekarang.
Katakan padaku, Kojiro, siapa namaku?"
"Kenapa bikin
susah diri sendiri? Jawab sendiri pertanyaan itu."
"Baik. Aku akan
bertanya pada diriku sendiri siapa namaku, dan kemudian, meskipun bisa kelihatan lancang, akan kusampaikan nama
itu padamu."
"Baik. "
"Jangan
terkejut!"
"Orang
goblok!"
"Aku Sasaki
Kojiro, dan dikenal juga sebagai Ganryu."
"A-apa?"
"Sejak zaman
nenek moyangku, keluargaku sudah tinggal di Iwakuni. Nama Kojiro itu kuterima
dari orangtuaku. Akulah orang yang di kalangan pemain pedang dikenal dengan
nama Ganryu. Nah, kapan dan bagaimana bisa menurutmu, di dunia ini terdapat dua
Sasaki Kojiro?"
"Kalau begitu
kamu... kamu...?
"Ya, sekalipun
banyak sekali orang mengadakan perjalanan di pedesaan, kamulah orang pertama
yang kutemui memakai namaku. Yang pertama sekali! Apa bukan suatu kebetulan
aneh bahwa kita bertemu?"
Matahachi berpikir cepat.
"Ada apa? Kamu
kelihatan gemetar." Matahachi jadi ngeri.
Kojiro mendekat,
menepuk bahunya, dan katanya, "Mari kita berteman." Dengan muka pucat
pasi Matahachi melepaskan diri dan mendengking. "Kalau kamu lari, kubunuh
kau!" Suara Kojiro itu menembus seperti lembing langsung ke wajah
Matahachi.
Galah Pengering
mendesis di atas bahu Kojiro bagai ular perak. Satu pukulan saja, tak lebih.
Dengan sekali lambungan Matahachi mental hampir tiga meter. Seperti serangga
yang diembuskan dari selembar daun, ia cerjungkir balik tiga kali dan jatuh
telentang tak sadarkan diri.
Kojiro malahan tak
melihat ke arah jatuhnya Matahachi. Pedang yang panjangnya tiga kaki dan masih
tak berdarah itu masuk kembali ke dalam sarungnya.
"Akemi!"
panggil Kojiro. "Turunlah! Takkan kulakukan hal itu lagi karena itu
kembalilah ke penginapan denganku. Oh, kurobohkan temanmu. tapi aku tidak
betul-betul melukainya. Turun sini, dan rawatlah."
Tak ada jawaban.
Karena tak melihat apa-apa di cabang-cabang gelap itu, Kojiro memanjat pohon,
tapi kemudian dilihatnya ia hanya sendirian. Akemi sudah lari lagi.
Angin bertiup lembut
lewat dedaunan pinus. Ia duduk diam di ala, dahan, bertanya-tanya pada diri
sendiri, ke mana terbangnya burung layang-layang yang kecil itu. Ia tak dapat
menduga, kenapa Akemi begitu takut kepadanya. Tidakkah ia mencurahkan cintanya
dengan cara terbaik yang dikenalnya? Memang mungkin caranya memperlihatkan
kasih sedikit kasar. tapi ia tak sadar bahwa cara itu berlainan dengan cara
orang lain dalam bercinta.
Jawaban atas soal itu
barangkali dapat ditemukan dalam sikapnya terhadap seni pedang. Selagi
kanak-kanak ia memasuki sekolah Kanemaki Jisai. Ia memperlihat-kan kemampuan
besar dan diperlakukan sebagai anak ajaib. Caranya mempergunakan pedang sungguh
luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah kegigihannya. Ia menolak
menyerah sama sekali. Kalau berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, semakin
ketat lagi ia berusaha.
Pada zaman ini, cara
yang dipergunakan seorang pesilat untuk menang jadi jauh kurang penting
dibandingkan dengan kemenangan itu sendiri. Tak seorang pun mempertanyakan
cara-cara itu dengan saksama, dan kecenderungan Kojiro untuk bertahan dengan
jalan apa pun sampai akhirnya menang tidak dianggap sebagai cara yang kotor.
Lawan-lawannya mengeluh karena ia masih terus saja menyerang mereka, padahal
kalau orang lain sudah mengaku kalah, tapi tak seorang pun menganggapnya tidak
jantan.
Pada suatu kali,
ketika ia masih kanak-kanak, sekelompok murid yang lebih besar dan
terang-terangan ia benci menghajarnya dengan pedang kayu sampai pingsan. Karena
kasihan kepadanya, salah seorang penyerangnya memberinya air dan menunggunya
sampai sadar kembali. Waktu itulah Kojiro merebut pedang kayu orang yang telah
menolongnya itu dan memukulnya sampai mati.
Kalau ia kalah dalam
pertarungan, tak pernah ia melupakannya. Ia akan mengintai terus sampai musuh
itu lengah-di tempat gelap, saat musuhnya berada di tempat tidur, atau bahkan
di kamar kecil dan diserangnya musuh itu dengan sehebat-hebatnya. Mengalahkan
Kojiro sama saja dengan menciptakan musuh kepala batu.
Setelah dewasa, ia
biasa bicara tentang dirinya sebagai seorang jenius. Memang ini bukan sekadar
bualan, dan baik Jisai maupun Ittosai membenarkannya. Ketika ia menyatakan
telah belajar menebas burung layang-layang yang sedang terbang dan menciptakan
gayanya sendiri, ia memang tidak mengada-ada. Itu pula yang menyebabkan orang
menganggapnya "tukang sihir", suatu pujian yang ia terima dengan
senang hati.
Tak seorang pun tahu,
apa wujud keinginannya yang keras itu, ketika Kojiro jatuh cinta kepada seorang
perempuan. Tapi tak mungkin ada keraguan bahwa di situ pun ia akan menempuh
jalannya yang biasa. Namun ia sendiri tak melihat ada hubungan apa pun antara
kemampuannya bermain pedang dengan caranya bercinta. Tak dapat ia memahami,
kenapa Akemi tidak menyukainya, padahal ia demikian cinta kepada gadis itu.
Ketika sedang
merenungkan masalah cintanya itu, ia lihat sesosok tubuh berjalan ke sana
kemari di bawah pohon, tanpa menyadari kehadiran Kojiro.
"Ada orang
menggeletak di sini," kata orang baru itu. Ia membungkuk untuk melihat
lebih jelas, kemudian serunya, "Oh, ini bangsat dari warung sake
itu!"
Orang itu biarawan
pengembara. Ia menurunkan bungkusan dari punggungnya, ucapnya,
"Kelihatannya tidak luka. Dan tubuhnya hangat." Ia meraba-rabanya dan
menemukan tali di bawah obi Matahachi. Tali dilepaskan dan diikatnya tangan
Matahachi ke punggung. Kemudian ia tekankan lututnya pada lekuk pinggang
Matahachi dan ia sentakkan bahu Matahachi ke belakang. Bersamaan dengan itu, ia
tekan keras saraf simpatisnya. Matahachi sadar kembali, merintih tak jelas.
Biarawan itu mengangkatnya seperti sekarung kentang ke sebatang pohon dan
menyandarkannya di situ.
"Berdiri!"
katanya tajam. Ditegaskannya perintahnya itu dengan tendangan. "Berdiri
kamu!"
Matahachi yang sudah
setengah jalan ke neraka itu memperoleh kembali kesadarannya, tapi belum dapat
memahami apa yang sedang terjadi. Masih dalam keadaan pusing, ia paksakan
dirinya berdiri.
"Bagus,"
kata si biarawan. "Berdiri saja begitu." Kemudian ia ikat kaki dan
dada Matahachi ke pohon.
Matahachi membuka
mata sedikit dan berteriak heran.
"Hei,
penipu," kata orang yang menangkapnya, "kau membuatku lari mengejar,
tapi semuanya sudah lewat sekarang." Pelan-pelan ia mulai menggarap
Matahachi. Ditamparnya dahinya beberapa kali hingga kepala Matahachi
membentur-bentur pohon. "Di mana kau mendapat kotak obat itu?"
tanyanya. "Katakan yang sebenarnya. Ayo!"
Matahachi tidak
menjawab.
"Kaupikir kau
bisa terus bertahan dengan tak tahu malu begitu, ya?" Dengan marah
biarawan itu menjepitkan jempol dan jari telunjuknya ke hidung Matahachi dan
mengguncangkan kepalanya ke depan ke belakang.
Matahachi
tersengal-sengal, dan ketika ia kelihatan mencoba berbican, biarawan itu
melepaskan hidunganya. "Aku akan bicara," kata Matahachi putus asa.
"Akan kuceritakan semuanya."
Air matanya meleleh.
"Peristiwa itu terjadi musim panas lalu...," mulainya, lalu
diceritakannya seluruh peristiwa itu, yang akhirnya dengan permintaan ampun.
"Saya tak dapat membayar uang itu sekarang juga, tapi saya berjanji, kalau
Bapak tidak membunuh saya, saya akan kerja keras dan mengembalikannya nanti.
Akan saya berikan janji tertulis, yang ditandatangani dan diberi meterai."
Mengakui kesalahan
seperti mengeluarkan nanah dari luka yang mesti disembunyikannya. Kini, setelah
tak ada lagi yang mesti disembunyikan, tak ada lagi yang mesti ditakutkan.
Paling tidak, itulah dugaan Matahachi.
"Benar
begitu?" tanya si biarawan.
"Benar."
Matahachi menundukkan kepala penuh sesal.
Sesudah beberapa
menit mereka diam, biarawan itu menarik pedang pendek dan menudingkannya ke
muka Matahachi.
Matahachi berteriak
sambil cepat menolehkan muka ke samping, "Bapak mau bunuh saya?"
"Ya, kau mesti
mati."
"Sudah saya
ceritakan semuanya pada Bapak dengan penuh kejujuran. Sudah saya kembalikan
kotak obat itu, dan akan saya serahkan kepada Bapak sertifikat itu. Tak lama
lagi akan saya bayar kembali uang itu. Saya bersumpah! Kenapa saya mesti
dibunuh?"
"Aku percaya
padamu, tapi kedudukanku sangat sulit. Aku tinggal di Shimonida, di Kozuke, dan
aku pembantu Kusanagi Tenki. Dia samurai yang tewas di Kuil Fushimi itu. Biar
aku berpakaian biarawan, aku ini samurai. Namaku Ichinomiya Gempachi."
Matahachi tidak
mendengarkan kata-kata itu. Ia mencoba melepaskan diri dan lari. "Saya
minta ampun," katanya hina dina. "Saya tahu sudah melakukan perbuatan
salah, tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Saya bermaksud menyampaikan semuanya
itu pada keluarganya, tapi kemudian, yah, kemudian saya kehabisan uang, dan
yah, saya tahu tak boleh saya melakukan itu, tapi saya sudah menggunakannya. Saya
mau minta ampun bagaimana saja menurut keinginan Bapak, tapi mohon jangan bunuh
saya."
"Rasanya lebih
baik kamu tidak minta ampun," kata Gempachi yang kelihatan sedang bergulat
dalam batinnya. Ia menggeleng-geleng sedih, lanjutnya, "Aku sudah pergi ke
Fushima menyelidiki ini. Semuanya cocok dengan yang kaukatakan. Tapi aku mesti
membawa pulang sesuatu untuk penghibur keluarga Tenki. Bukan uang. Aku cuma
butuh sesuatu buat menunjukkan bahwa pembalasan sudah dilaksana-kan. Tapi tak
ada satu penjahatnya, tak ada satu orang tertentu yang sudah membunuh Tenki.
Jadi, bagaimana aku dapat membawa kepala pembunuh itu buat mereka?"
"Tapi saya...
saya... saya tidak membunuh dia. Jangan Bapak salah."
"Aku tahu kau
tidak membunuh dia. Tapi keluarga dan teman-temannya tidak tahu dia dikeroyok
dan dibunuh pekerja. Dan lagi itu bukan cerita yang akan bikin dia terhormat.
Tak suka aku menceritakan pada mereka hal yang sebenarnya. Jadi, biarpun aku
kasihan padamu, kupikir kau mesti dijadikan orang yang bersalah itu. Akan lebih
baik keadaannya kalau kau setuju aku membunuhmu."
Sambil merenggangkan
tali-tali yang mengikatnya, Matahachi berteriak, "Lepaskan saya! Saya tak
mau mati!"
"Dengan
sendirinya. Tapi coba tinjau soal ini dari sudut lain. Kamu tak dapat membayar
sake yang kauminum. Itu berarti kau tidak cakap menghidupi dirimu sendiri.
Daripada kelaparan dan menjalani hidup memalukan di dunia yang kejam ini, apa
tidak lebih baik kau istirahat dengan damai di dunia lain? Kalau uang yang jadi
persoalanmu, aku punya sedikit. Dengan senang hati aku akan mengirimkan kepada
orangtuamu sebagai sumbangan penguburan. Dan kalau kau mau, aku dapat
mengirimkannya ke kuil leluhurmu sebagai sumbangan peringatan. Aku jamin, uang
akan disampaikan sebaik-baiknya."
"Gila. Aku tak
perlu uang; aku mau hidup! Tolong!"
"Aku sudah
menjelaskan semuanya baik-baik. Setuju atau tidak, kau terpaksa berperan selaku
pembunuh tuanku. Menyerahlah, kawan. Anggap saja ini nasib." Ia
mencengkeram pedangnya dan melangkah mundur, agar ada ruang baginya untuk
menebas.
"Gempachi,
tunggu!" seru Kojiro.
Gempachi menengadah
dan teriaknya, "Siapa di situ?"
"Sasaki
Kojiro."
Gempachi mengulang
nama itu pelan-pelan dengan curiga. Apakah ada Kojiro palsu lain lagi turun
dari langit? Namun suara itu mirip sekali dengan suara manusia, bukan suara
hantu. Ia melompat menghindari pohon dan mengangkat pedang tegak-tegak.
"Ini
keterlaluan," katanya sambil tertawa. "Rupanya tiap orang menyebut
dirinya Sasaki Kojiro sekarang ini. Di bawah sini ada satu, yang kelihatan
begitu sedih. Ah, ya! Sekarang aku mulai mengerti. Kau teman orang ini, ya?”
"Bukan, aku
Kojiro. Dengar, Gempachi, engkau sudah siap memotongku jadi dua kalau aku turun,
ya?"
"Ya. Bawa sini
berapa saja Kojiro palsu itu semaumu. Akan kuhadapi mereka semua."
"Cukup adil.
Kalau kau dapat memotongku, bolehlah kau yakin aku yang palsu, tapi kalau kau
yang mati, yakinlah bahwa aku Kojiro sejati. Aku turun sekarang, dan kuperingatkan
kamu, kalau kau tak dapat melukaiku di udara, Galah Pengering akan membelahmu
seperti sepotong bambu."
"Tunggu. Rasanya
aku ingat suaramu. Kalau pedangmu bernama Galah Pengering yang terkenal itu,
benar engkau Kojiro."
"Kau percaya
sekarang?"
"Ya, tapi apa
kerjamu di atas itu?"
"Kita bicarakan
nanti."
Kojiro melompat lewat
wajah Gempachi yang tengadah dan mendarat di belakangnya, disertai hujan daun
pinus. Perubahan sosok Kojiro itu mengagumkan Gempachi. Kojiro, menurut
ingatannya di sekolah Jisai itu. anak yang hitam kulitnya dan kikuk. Pekerjaan
satu-satunya waktu itu menimba air, dan sesuai dengan kecintaan Jisai akan
kesederhanaan, tidak pernah Kojiro menggunakan pakaian lain kecuali yang paling
sederhana.
Kojiro duduk di
pangkal pohon dan mengajak Gempachi berbuat demikian juga. Gempachi kemudian
bercerita bahwa Tenki dikira mata-mata dari Osaka dan dilempari batu sampai
mati, dan bahwa sertifikatnya jatuh ke tangan Matahachi.
Kojiro senang sekali
mengetahui ada orang yang memakai namanya, tapi ia mengatakan tak ada untungnya
membunuh orang yang demikian lemah. Ada cara lain untuk menghukum Matahachi.
Kalau Gempachi kuatir dengan keluarga Tenki atau reputasinya, Kojiro sendiri
akan pergi ke Kozuke dan mengatur segala sesuatunya agar majikan Gempachi
dianggap sebagai prajurit berani dan terhormat. Tak perlu membuat Matahachi
sebagai kambing hitam.
"Engkau setuju,
Gempachi?" tutup Kojiro.
"Kalau demikian,
kukira ya."
"Baiklah kalau
begitu. Aku mesti pergi sekarang, tapi kukira kau mesti pulang ke Kozuke."
"Memang aku mau
pulang. Aku akan langsung pulang."
"Terus terang,
aku agak buru-buru. Aku sedang mencari gadis yang tiba-tiba meninggalkanku.”
"Apa tak ada
yang kaulupakan?"
"Kukira
tidak."
"Bagaimana
dengan sertifikat itu?"
"Oh, itu."
Gempachi
menggerayangi Matahachi dan mengambil gulungan itu. Matahachi merasa ringan dan
lepas dari beban. Kini ia merasa hidupnya akan selamat, dan ia senang terlepas
dari dokumen itu.
"Hmm," kata
Gempachi. "Coba pikirkan, barangkali kejadian malam ini memang diatur roh
Jisai dan Tenki, hingga aku bisa mendapatkan kembali sertifikat ini dan
memberikannya padamu."
"Aku tak
mau," kata Kojiro.
"Kenapa?"
tanya Gempachi tak percaya.
"Aku tidak
memerlukannya."
"Aku tak
mengerti."
"Aku tak perlu
kertas macam itu."
"Apa yang
kaukatakan! Apa engkau tidak merasa berterima kasih kepada gurumu?
Bertahun-tahun Jisai mempersiapkan diri untuk memutuskan apakah dia akan
memberikan sertifikat ini padamu. Dan dia tidak juga mengambil keputusan,
sebelum akhirnya berada di ranjang kematian. Dia menugaskan Tenki untuk
menyerahkannya padamu, tapi lihatlah sendiri apa yang terjadi dengan Tenki.
Engkau mesti malu bersikap begitu."
"Apa yang
dilakukan Jisai itu urusannya sendiri. Aku punya ambisi sendiri."
"Bukan begitu
mestinya bicara."
"Jangan engkau
salah mengerti."
"Engkau menghina
orang yang sudah mengajarmu?"
"Sama sekali
tidak, tapi aku dilahirkan dengan bakat-bakat yang lebih besar daripada dia.
Aku bermaksud lebih maju daripada dia. Menjadi pemain pedang yang tak dikenal
di daerah pedesaan bukanlah tujuanku."
"Engkau
bersungguh-sungguh?"
"Tidak salah
lagi." Kojiro tidak menyesal mengungkapkan ambisi-ambisinya, sekalipun
menurut ukuran biasa tak patut. "Aku berterima kasih pada Jisai, tapi
sertifikat dari sekolah desa yang tidak begitu dikenal itu lebih merugikan
diriku daripada menguntungkan. Ito Ittosai menerima sertifikatnya, tapi dia
tidak meneruskan Gaya Chujo. Dia menciptakan gayanya yang baru. Aku bermaksud
berbuat demikian juga. Kepentinganku adalah menciptakan Gaya Ganryu. Tak lama
lagi nama Ganryu akan sangat terkenal. Engkau lihat, dokumen itu tak ada
artinya buatku. Bawa itu kembali ke Kozuke dan minta kuil di sana menyimpannya
bersama catatan kelahiran dan kematian." Tak ada sama sekali nada
kesederhanaan ataupun kerendahan hati dalam bicara Kojiro.
Gempachi memandangnya
benci.
"Tolong
sampaikan salamku untuk keluarga Kusanagi," kata Kojiro sopan.
"Beberapa lama lagi aku akan pergi ke timur dan mengunjungi mereka.
Yakinlah." Dan ia akhiri kata-kata perpisahan itu dengan senyum lebar.
Bagi Gempachi,
pameran kesopanan yang terakhir itu mengandung sikap menggurui. Ia berpikir
untuk menegur Kojiro atas sikapnya yang tak kenal terima kasih dan tidak hormat
kepada Jisai itu, tapi sesudah mempertimbangkannya lagi sejenak, ia menganggap
buang-buang waktu saja. Maka pergilah ia menghampiri bungkusannya, memasukkan
sertifikat ke dalamnya, dan mengucapkan selamat berpisah singkat dan pergi.
Sesudah ia pergi,
Kojiro tertawa senang sekali. "Aduh, aduh, dia marah rupanya. Ha, ha, ha,
ha!" Kemudian ia menoleh kepada Matahachi. "Nah, apa sekarang katamu
tentang dirimu sendiri, orang palsu tak berguna?"
Matahachi tentu saja
tak bisa bicara apa-apa.
"Jawab
pertanyaanku! Kamu mengaku mencoba memalsukan aku, kan?"
"Ya..”
"Aku tahu namamu
Matahachi, tapi siapa nama lengkapmu?"
"Hon'iden
Matahachi."
"Apa kamu
ronin?"
"Ya."
"Ambil pelajaran
dariku, keledai tak bertulang punggung! Kaulihat aku mengembalikan sertifikat
itu, kan? Kalau orang lelaki tak punya keberanian berbuat seperti itu, tak
bakal dia dapat melakukan apa-apa sendiri. Tapi! coba lihat dirimu itu! Kamu
pakai nama orang lain, mencuri sertifikatnya. dan ke sana kemari hidup dengan
reputasinya. Apa ada yang lebih keji daripada itu? Barangkali pengalaman malam
ini memberikan pelajaran kepadamu: kucing bisa saja mengenakan kulit macan,
tapi tetap saja dia kucing."
"Saya akan
berhati-hati sekali di masa depan."
"Aku menahan
diri tidak membunuhmu, tapi kukira lebih baik kamu membebaskan dirimu sendiri,
kalau kau bisa." Tapi tiba-tiba Kojiro mendapat pikiran baru. Ia hunus
belati dari sarungnya dan ia pun mengorek-ngorek kulit pohon di atas kepala
Matahachi. Serpihan kulit pohon berjatuhan ke leher Matahachi. "Aku butuh
alat tulis," gumam Kojiro.
"Ada kantong
kuas dan tempat tinta dalam obi saya," kata Matahachi ingin membantu.
"Bagus! Kupinjam
sebentar."
Kojiro membasahi kuas
itu dengan tinta dan menulis di atas petak batang pohon yang sudah ia korek
kulitnya. Kemudian ia mundur sedikil mengagumi hasil kerjanya. "Orang
ini," bunyinya, "adalah penipu lihai. Dengan menggunakan nama saya,
ia pergi ke sana kemari di pedesaan. melakukan perbuatan tidak terhormat. Saya
sudah menangkapnya, dan saya meninggalkannya di sini untuk diejek-ejek oleh
siapa saja. Nama saya, dan nama pedang saya yang menjadi milik saya seorang,
adalah Sasaki Kojiro, Ganryu."
"Cukup
begini," kata Kojiro puas.
Di hutan gelap itu
angin menderu seperti air pasang. Kojiro pergi sambil memikirkan ambisi masa
depannya dan kembali menempuh jalur aksinya waktu itu. Matanya menyala ketika
ia menerobos hutan, seperti seekor macan tutul.


0 komentar:
Posting Komentar