Belas Kasihan Kannon
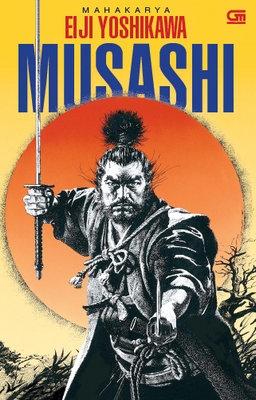
OTSU duduk
mendengarkan tetesan air yang turun dari atap yang bocor. Karena terpaan angin,
hujan itu melecut masuk dari bawah ujung atap, dan berkecipak mengenai tirai.
Tapi kini musim gugur, karenanya tak dapat diramalkan apakah pagi akan merekah
cerah dan jernih.
Kemudian Otsu
berpikir akan Osugi. "Apakah dia ada di luar, dalam badai ini, basah dan
kedinginan? Dia sudah tua. Mungkin dia takkan hidup sampai pagi. Biarpun tetap
hidup, bisa berhari-hari lagi sebelum akhirnya dia ditemukan orang. Dia bisa
mati kelaparan."
"Jotaro,"
panggilnya pelan. "Bangun." Ia kuatir Jotaro melakukan sesuatu yang
kejam. Ia mendengar sendiri Jotaro mengatakan kepada para kakitangan perempuan
tua itu, bahwa ia sedang menghukum perempuan itu, dan sambil lalu anak itu juga
menyatakan hal serupa dalam perjalanan ke penginapan.
"Hatinya
sebetulnya tidak begitu jahat," pikir Otsu. "Kalau aku mau terus
terang padanya, dia pasti dapat memahami diriku.... Aku mesti menemui
dia."
Ia buka daun pintu,
sambil pikirnya, "Kalau Jotaro marah, apa boleh buat." Hujan tampak
putih pada latar belakang langit yang hitam. Ia singsingkan kimononya, lalu
dari dinding ia ambil topi anyaman dari kulit bambu, dan ia ikatkan pada
kepalanya. Kemudian ia tutupkan mantel besar dari jerami ke bahunya, ia kenakan
sandal jerami, dan berangkat menerobos cucuran hujan yang turun dari atap.
Dekat kuil tempat ia
ditangkap Mambei, ia lihat tangga barn yang menuju kuil itu telah menjadi air
terjun bertingkat banyak. Di puncak tangga, angin jauh lebih kuat, melolong,
melintasi rumpun pohon kriptomeria, seperti kawanan anjing marah.
"Di mana dia
kira-kira?" pikirnya sambil mencoba menatap ke dalam tempat suci. Ia
berseru ke dalam ruang gelap di bawahnya, tapi tak ada jawaban. Ia menikung ke
belakang bangunan, dan berdiri di sana beberapa menit lamanya. Angin yang
melolong menerpanya seperti ombak di laut yang menggila. Berangsur-angsur
sadarlah ia akan adanya bunyi lain, yang hampir-hampir tak dapat dibedakan dari
bunyi badai. Bunyi itu berhenti, lalu mulai lagi.
"Oh-h-h!
Dengarkan aku...! Ada orang di situ?... Oh-h-h!"
"Nenek!"
seru Otsu. "Nek, di mana Nenek?" Karena boleh dikatakan ia hanya
berteriak ke dalam angin, suaranya tidak bisa terdengar jauh.
Tapi, entah
bagaimana, perasaan itu membentuk hubungan sendiri. "Oh! Ada orang di
sana. Ya, aku tahu... Tolong aku! Aku di sini! Tolong!"
Potongan-potongan
bunyi itu sampai ke telinga Otsu, dan ia mendengar nada putus asa di dalamnya.
"Nenek di
mana?" jeritnya parau. "Nenek, di mana Nenek?" Ia berlari
mengelilingi kuil, berhenti sebentar, kemudian berlari lagi keliling. Secara
kebetulan ia melihat semacam gua beruang, sekitar dua puluh langkah jauhnya,
dekat dasar jalan terjal yang menanjak ke tempat suci bagian dalam.
Ketika ia semakin
mendekat, ia tahu pasti bahwa suara perempuan tua itu datang dari dalam. Sampai
di pintu masuk. Ia berhenti dan menatap batu-batu besar yang menghalanginya.
"Siapa itu?
Siapa di situ? Jelmaan Kannon, ya? Kupuja dia tiap hari. Kasihanilah aku.
Selamatkan perempuan tua malang yang sudah diperangkap musuh!" Permohonan
Osugi bernada histeris. Setengah menangis setengah memohon, di celah gelap
antara hidup dan mati, ia membayangkan Kannon yang menaruh belas kasihan, dan
memanjatkan kepadanya doa berapi-api demi kelangsungan hidupnya.
"Oh,
bahagiaku!" teriaknya lupa daratan. "Kannon yang maha pengasih sudah
melihat kebaikan hatiku dan kasihan kepadaku. Dia datang menyelamatkan diriku!
Belas kasihan yang agung! Hiduplah Bodhisatwa Kannon, hiduplah Bodhisatwa
Kannon, hiduplah..."
Suara itu terhenti
seketika. Barangkali ia merasa sudah cukup, karena sudah sewajarnya bahwa pada
waktu ia sangat membutuhkan, Kannon akan datang dalam bentuk tertentu untuk
menolongnya. Ia kepala keluarga yang baik, ibu yang baik, dan ia merasa dirinya
adalah manusia lurus tanpa cacat. Karena itu, apa pun yang ia lakukan tentu
benar menurut akhlak.
Tapi kemudian, karena
merasa bahwa orang yang ada di luar gua bukan hantu, melainkan manusia yang
nyata dan hidup, ia pun tenang, dan ketika sudah tenang, ia pun pingsan.
Karena tak mengerti
kenapa tiba-tiba teriakan Osugi berhenti, Otsu jadi hilang kesabaran.
Bagaimanapun, pintu gua itu harus dibersihkan. Ia melipatgandakan usahanya,
hingga tali yang mengikat topi anyamannya lepas, dan topi serta jalinan
rambutnya yang hitam jadi berkibar-kibar ditiup angin.
Heran juga ia,
bagaimana Jotaro bisa meletakkan batu-batuan itu sendirian. Ia dorong dan ia
tarik batu-batuan itu dengan seluruh kekuatannya, namun tak satu pun bergerak.
Karena kehabisan tenaga, ia merasa jengkel pada Jotaro. Perasaan lega yang
semula meliputinya karena menemukan tempat Osugi, kini berubah menjadi rasa
gelisah yang pedih. "Tahan dulu, Nek! Sebentar lagi. Akan kukeluarkan
Nenek!" teriaknya. Biarpun sudah menekankan bibirnya ke dalam celah di
antara bebatuan itu, ia tak berhasil memperoleh balasan.
Segera kemudian ia
perdengarkan nyanyian lirih dan sayup:
"Pada waktu
berjumpa setan-setan pemakan manusia,
Naga berbisa atau
iblis,
Jika ia masih ingat
akan kekuasaan Kannon,
Maka tak suatu pun
berani mencederainya.
Jika pada waktu
dikepung binatang jahat,
Dengan taring tajam
dan cakar mengerikan,
ia masih ingat akan
kekuasaan Kannon..."
Sementara itu, Osugi
menyanyikan kitab Sutra tentang Kannon. Hanya suara bodhisatwa yang dapat
dipahaminya. Dengan tangan terkatup, kini ia berserah diri dengan air mata
menuruni pipi dan bibir bergetar, sementara kata-kata suci meluncur dari
mulutnya.
Tiba-tiba merasa
ganjil, Osugi berhenti menyanyi dan mengintip dari celah antara bebatuan.
"Siapa di sana?" teriaknya. "Aku tanya, siapa kamu?"
Angin sudah
menerbangkan mantel Otsu. Dalam keadaan bingung, kehabisan tenaga, dan berlumur
lumpur, ia membungkuk dan berseru, "Nenek baik-baik saja? Ini Otsu!"
"Siapa,
katamu?" terdengar pertanyaan curiga.
"Otsu!"
"Begitu."
Menyusul kediaman panjang, tapi akhirnya terdengar pertanyaan bernada tak
percaya. "Apa maksudmu, Otsu?"
Justru pada waktu
itulah gelombang guncangan pertama menimpa Osugi, dan dengan kasar
memorakporandakan pikiran-pikiran keagamaannya. "Kkenapa kau datang
kemari? Oh, aku tahu. Kau mencari si setan Jotaro itu!"
"Tidak, saya
datang buat menyelamatkan Nenek! Saya minta Nenek melupakan masa lalu. Saya
ingat, Nenek baik sekali pada saya, waktu saya masih gadis kecil. Tapi kemudian
Nenek memusuhi saya dan mencoba melukai saya. Saya tidak dendam pada Nenek.
Saya akui, saya memang keras kepala."
"Oh, jadi matamu
terbuka sekarang, dan kau bisa melihat buruknya perbuatan-perbuatanmu. Begitu,
ya? Maksudmu, apa kau mau kembali pada Keluarga Hon'iden, sebagai istri
Matahachi?"
"Oh, tidak,
bukan itu," kata Otsu cepat.
"Nah, kalau
begitu, kenapa kau di sini?"
"Saya kasihan
pada Nenek, dan saya tidak tahan."
"Dan sekarang
kau ingin aku berutang budi padamu. Itu yang kaucoba lakukan, ya?"
Otsu terlalu
terguncang untuk mengatakan sesuatu.
"Siapa yang
menyuruhmu datang menyelamatkan aku? Aku tak perlu bantuanmu sekarang. Kalau
kau menyangka dengan menolongku kau dapat membuatku tidak membencimu lagi, kau
keliru. Aku tak peduli betapa buruknya keadaanku, lebih baik aku mati daripada
kehilangan kebanggaan."
"Tapi, Nek,
bagaimana bisa Nenek menyuruhku meninggalkan orang seumur Nenek di tempat
mengerikan semacam ini?"
"Begitulah
bicaramu, enak dan manis. Kaukira aku tidak tahu, apa yang hendak dilakukan
olehmu dan Jotaro? Kalian berdua bersekongkol memasukkan aku ke dalam gua ini,
buat mempermainkan diriku. Kalau nanti aku keluar, aku mesti membalas dendam.
Kalian boleh yakin itu."
"Saya yakin
Nenek akan mengerti, bagaimana sesungguhnya perasaan saya. Biar bagaimana,
Nenek tak bisa tinggal di sini. Nenek akan sakit."
"Huh, aku bosan
dengan omong kosong ini!"
Otsu berdiri.
Tiba-tiba penghalang yang tak dapat digesernya dengan tenaga fisik itu bergerak
sendiri, seakan-akan digerakkan oleh air matanya. Sesudah batu teratas
berguling ke tanah, mengherankan bahwa ia tidak mengalami kesulitan lagi
menggulingkan batu di bawahnya ke samping.
Namun bukan air mata
Otsu sendiri yang membuka gua itu, karena Osugi mendorongnya juga dari dalam.
Ia pun menyeruduk ke luar, wajahnya merah manyala.
Otsu memperdengarkan
teriakan gembira, dan ia masih terhuyung-huyung karena mengerahkan tenaga, tapi
begitu Osugi berada di luar, ia langsung menangkap kerah Otsu. Dari ganasnya
serangan itu, seakan-akan tujuan Osugi bertahan hidup adalah untuk menyerang
penyelamatnya.
"Oh! Apa yang
Nenek lakukan? Ow!"
"Tutup
mulut!"
"Ken-napa!"
"Apa
maumu?" teriak Osugi sambil menjatuhkan Otsu ke tanah, dengan kemarahan
seorang perempuan liar. Otsu terkejut luar biasa.
"Ayo, sekarang
kita pergi!" dengus Osugi sambil menyeret gadis itu di tanah basah.
Sambil mengatupkan
tangan, kata Otsu, "Saya mohon, Nek. Hukumlah saya, kalau Nenek mau, tapi
jangan Nenek tinggal dalam hujan."
"Pandir! Tak
kenal malu, ya? Apa pikirmu kau bisa bikin aku kasihan padamu?"
"Saya takkan
lari. Tak akan... Oh! Sakit!"
"Tentu saja
sakit."
"Biarkan
saya...!" Tiba-tiba Otsu mengerahkan tenaga untuk meloloskan diri, dan
melompat berdiri.
"Tak
bakalan!" Seketika itu Osugi memperbarui serangannya dan mencengkeram
segenggam rambut Otsu . Wajah Otsu yang putih tertengadah ke langit, air hujan
membasahinya. Ia menutup mata.
"Perempuan sial!
Berapa banyak aku menderita bertahun-tahun ini karena kau!"
Setiap kali Otsu
membuka mulut untuk berbicara atau berusaha meloloskan diri, perempuan tua itu
menyentakkan rambutnya dengan kejam. Tanpa melepaskan rambut itu, ia banting
Otsu ke tanah, ia injak, dan ia tendang.
Kemudian, tiba-tiba
pada wajah Osugi muncul sebersit rasa terkejut, dan ia melepaskan rambut itu.
"Oh, apa yang
kulakukan?" gagapnya ketakutan. "Otsu?" panggilnya kuatir,
memandang sosok lemas yang tergeletak di kakinya.
"Otsu!"
Sambil membungkuk ia tatap baik-baik wajah yang basah oleh hujan dan sedingin
ikan mati itu. Gadis itu sepertinya sudah tidak bernapas.
"Dia... dia
mati!"
Osugi terperanjat.
Walaupun ia tak rela memaafkan Otsu, tak ada maksudnya membunuh gadis itu. Maka
ia meluruskan badan, merintih sambil mundur.
Berangsur-angsur baru
ia tenang, dan tak lama kemudian katanya, "Kukira tak ada yang bisa
dilakukan, kecuali pergi mencari pertolongan." Ia pun berangkat, tapi
kemudian ragu-ragu, menoleh, dan kembali. Ia gendong tubuh Otsu yang dingin itu
dan ia bawa masuk gua.
Pintu masuk gua itu
memang kecil, tapi bagian dalamnya luas. Di dekat dinding terdapat tempat yang
dulu dipakai para peziarah yang sedang mencari jalan untuk bersemadi
berlama-lama.
Ketika hujan reda, ia
pergi ke pintu dan mulai merangkak ke luar, tapi justru waktu itu hujan mulai
turun lagi. Air yang membanjiri mulut gua gemerecik hampir sampai ke bagian
terdalam gua.
"Tak lama lagi
pagi," pikirnya. Ia berjongkok acuh tak acuh, dan menanti badai reda
kembali.
Keadaan gelap gulita.
Tubuh Otsu pelan-pelan mulai mempengaruhi pikirannya. Ia merasa wajah yang
kelabu dingin itu menatap dirinya dengan nada menuduh. Mula-mula ia
menenteramkan dirinya dengan mengatakan, "Segalanya sudah ditakdirkan
untuk terjadi. Ambillah tempatmu di surga, sebagai Budha yang baru lahir.
Jangan simpan dendam terhadapku." Tapi, tak lama kemudian, rasa takut dan
tanggung jawab yang hebat mendorongnya untuk mencari perlindungan dalam
kesalehan. Sambil memejamkan mata, ia mulai menyanyikan sutra. Beberapa jam
berlalu.
Ketika akhirnya
bibirnya berhenti bergerak dan ia membuka mata, ia dengar burung-burung
mencicit. Udara tenang, hujan sudah berhenti. Lewat mulut gua, matahari
keemasan menjenguk kepadanya, mencurahkan cahayanya yang putih ke tanah kasar
di dalam.
"Apa pula
itu?" tanyanya keras, ketika la bangkit; matanya menatap sebuah prasasti
ukiran tangan tak dikenal pada dinding gua.
Ia berdiri di dekat
prasasti itu, dan membaca, "Pada tahun 1544, saya kirimkan anak saya yang
berumur enam belas tahun, bernama Mori Kinsaku, untuk ikut pertempuran Benteng
Tenjinzan di pihak Yang Dipertuan Uragami. Sejak itu saya tak pernah
melihatnya. Karena sedih, saya mengembara ke berbagai tempat suci bagi sang
Budha. Sekarang saya tempatkan di gua ini patung Bodhisatwa Kannon. Saya doakan
agar perbuatan ini, disertai air mata seorang ibu, akan melindungi hidupnya di
masa depan. Kalau di kemudian hari ada orang lewat tempat ini, saya mohon dia
menyerukan nama sang Budha. Inilah tahun kedua puluh satu, sejak kematian
Kinsaku. Penyumbang: Ibu Kinsaku, Kampung Aita."
Huruf-huruf yang
sudah mengalami pengikisan di beberapa tempat itu sukar dibaca. Hampir tujuh
puluh tahun sudah kampung-kampung yang berdekatan, seperti Sanumo, Aita, dan
Katsuta, diserang oleh Keluarga Amako, dan Yang Dipertuan Uragami diusir dari
bentengnya. Kenangan masa kecil yang takkan terhapus dari pikiran Osugi adalah
pembakaran benteng itu. Ia sempat melihat asap hitam melayang ke langit,
mayat-mayat manusia dan kuda menyeraki perladangan dan jalan-jalan kecil,
berhari-hari sesudahnya. Pertempuran itu hampir mencapai rumah-rumah petani.
Memikirkan ibu-anak
itu, termasuk kesedihannya, pengembaraannya, doanya, dan persembahannya, Osugi
merasa seperti ditikam. "Tentunya dia sedih sekali," katanya. Ia
berlutut dan mengatupkan tangannya.
"Hiduplah sang
Budha Amida. Hiduplah sang Budha Amida..."
Ia tersedu-sedu, air
mata jatuh ke tangannya, tapi belum lagi ia puas menangis, pikirannya sudah
tersadar kembali akan wajah Otsu yang dingin, tak peka terhadap sinar pagi, di
samping lututnya.
"Maafkan aku,
Otsu. Sungguh aku kejam! Aku mohon, maafkanlah aku!" Dengan wajah
mengungkapkan sesal yang sangat, ia angkat tubuh Otsu disertai pelukan lembut.
"Mengerikan... mengerikan. Buta oleh cinta ibu. Gara-gara bakti kepada
anak, aku menjadi setan buat perempuan lain. Kau punya ibu juga. Kalau ibu itu
mengenalku, pasti dia memandangku sebagai... iblis yang kotor...! Aku yakin
diriku benar, tapi buat orang lain aku monster yang jahat."
Kata-kata itu seperti
memenuhi gua, lalu meloncat kembali ke telinganya. Tak ada orang di situ, tak
ada mata mengawasi, tak ada telinga mendengar. Gelap malam telah berubah
menjadi sinar kebijaksanaan sang Budha.
"Kau sungguh
baik selama ini, Otsu. Bertahun-tahun lamanya kau disiksa orang tua bodoh yang
mengerikan ini, tapi tak pernah kau mengembalikan dendamku. Kau datang mencoba
menyelamatkan diriku, menantang segalanya... Aku menyadarinya sekarang. Semula
aku salah mengerti. Semua kebaikan hatimu kupandang jahat. Kebaikanmu kubalas
dengan dendam. Pikiranku kacau, menyeleweng. Oh, maafkan aku, Otsu."
Ia tekankan wajahnya
yang basah ke wajah Otsu. "Alangkah baiknya kalau anakku semanis dan
sebaik dirimu... Buka matamu, dan lihat aku memohon maaf padamu. Buka mulutmu,
caci diriku. Aku pantas diperlakukan begitu. Otsu... maafkan aku."
Sementara ia
memandang wajah itu sambil mencucurkan air mata kesedihan, di depan matanya
melintas gambaran dirinya sendiri. Gambaran itulah yang kelihatan pada
pertemuan-pertemuannya yang lalu dengan Otsu. Kesadaran akan betapa kejam
dirinya kini mencekam hatinya. Berkalikali ia berbisik, "Maafkan aku...
maafkan aku!" Bahkan terpikir olehnya, apakah tidak lebih baik ia duduk di
sana, sampai ia mati bersama gadis itu.
"Tidak!"
serunya mantap. "Tak perlu lagi menangis dan merintih! Barangkali...
barangkali dia tidak mati. Kalau kucoba, barangkali aku dapat berusaha supaya
dia kembali hidup. Dia masih muda. Hidupnya masih terbentang di depannya."
Pelan-pelan ia
letakkan kembali Otsu ke tanah, lalu ia merangkak keluar dari gua, ke tengah
sinar matahari yang menyilaukan. Ia tutup matanya, dan ia corongkan kedua
tangannya ke mulut. "Di mana orang-orang? Hei, orang-orang kampung! Sini!
Tolong!" Ia berlari ke depan beberapa langkah, sambil terus berseru-seru.
Terlihat gerakan di
tengah semak kriptomeria, kemudian terdengar teriakan, "Dia di sini!
Ternyata selamat!"
Sekitar sepuluh orang
anggota klan Hon'iden keluar dari semak. Mereka mendengar berita dari orang
yang masih selamat dan berlumuran darah akibat perkelahian dengan Jotaro malam
sebelumnya, lalu mereka menyusun kelompok pencari yang segera berangkat,
walaupun hujan turun membutakan mata. Mereka masih mengenakan mantel hujan, dan
tampak basah kuyup.
"Jadi, ibu
selamat!" seru orang pertama yang sampai pada Osugi, dengan gembira.
Mereka mengerumuni Osugi, wajah mereka mengungkapkan rasa lega luar biasa.
"Jangan
kuatirkan diriku," perintah Osugi. "Cepat lihat sana, apa gadis dalam
gua itu masih bisa ditolong. Sudah berjam-jam tak sadar. Kalau tidak kita
berikan obat sekarang juga... " Suaranya pekat.
Seperti hampir
kesurupan, ia menunjuk ke arah gua. Barangkali itu air mata kesedihan yang
pertama dicurahkannya sesudah kematian Paman Gon.
104. Pasang-Surut
Kehidupan
MUSIM gugur telah
lewat. Juga musim dingin.
Pagi-pagi, pada suatu
hari di bulan keempat tahun 1612, para penumpang menyiapkan diri di atas dek
kapal biasa yang berlayar dari Sakai di Provinsi Izumi ke Shimonoseki di
Nagato.
Sesudah mendapat
pemberitahuan bahwa kapal siap berangkat, Musashi bangkit dari bangku toko
Kobayashi Tarozaemon, dan membungkuk kepada orang-orang yang datang melepas
kepergiannya.
"Pertahankan
semangat," dorong mereka, sambil ikut bersamanya menuju dermaga.
Wajah Hon'ami Koetsu
terdapat di antara orang-orang yang hadir. Teman karibnya, Haiya Shoyu, tidak
bisa datang karena sakit, tapi ia diwakili anaknya, Shoeki. Bersama Shoeki ikut
juga istrinya, seorang wanita yang kecantikannya menyilaukan, hingga ke mana
saja ia pergi, kepala orang menoleh.
"Itu Yoshino,
kan?" seorang laki-laki berbisik sambil menarik lengan baju temannya.
"Dari
Yanagimachi?"
"Umm. Yoshino
Dayu dari Ogiya."
Shoeki memperkenalkan
wanita itu pada Musashi, tanpa menyebutkan namanya. Wajahnya tentu saja tak
dikenal Musashi, karena ia adalah Yoshino Dayu yang kedua. Tak seorang pun tahu
apa yang terjadi dengan Yoshino yang pertama, di mana tinggalnya sekarang, dan
apakah sudah menikah atau masih sendiri. Orang banyak sudah lama tak lagi
membicarakan kecantikannya yang luar biasa. Bunga berkembang, dan kemudian
gugur. Dan di dunia lokalisasi yang serba tak tetap itu, waktu berlalu dengan
cepat.
Yoshino Dayu. Nama
itu pasti membangkitkan kenangan tentang malammalam bersaiju, tentang api kayu
peoni, dan tentang kecapi yang rusak. "Sudah delapan tahun berlalu, sejak
kita pertama bertemu," kata Koetsu.
"Ya, delapan
tahun," sahut Musashi, yang juga heran, ke mana saja perginya tahun-tahun
itu. Ia merasa acara naik kapal hari ini menandai akhir satu tahap hidup
baginya.
Matahachi termasuk
salah seorang yang ikut mengantar, demikian juga beberapa samurai dari tempat
kediaman Hosokawa di Kyoto. Samurai-samurai lain menyampaikan ucapan selamat
dari Yang Dipertuan Karasumaru Mitsuhiro, dan ada pula satu rombongan, dua
sampai tiga puluh pemain pedang, yang karena pergaulan dengan Musashi di Kyoto,
menganggap diri mereka pengikut Musashi, sekalipun Musashi memprotes.
Musashi akan pergi ke
Kokura di Provinsi Buzen. Di sana ia akan berhadapan dengan Sasaki Kojiro,
untuk menguji keterampilan dan kematangannya. Atas usaha Nagaoka Sado,
konfrontasi yang menentukan dan lama prosesnya itu akhirnya akan berlangsung
juga. Perundingan-perundingannya panjang dan sukar, memerlukan pengiriman
banyak kurir dan surat. Bahkan sesudah Sado pada musim gugur lalu memastikan
bahwa Musashi ada di rumah Hon'ami Koetsu, penyempurnaan persiapan masih
membutuhkan waktu setengah tahun lagi.
Walaupun Musashi tahu
pertarungan akan terjadi, tak pernah terbayang olehnya ia akan berangkat
sebagai bintang yang dipuja-puja sejumlah besar pengikut dan pengagum. Besarnya
jumlah pengantarnya itu membuatnya malu, juga tidak memungkinkan ia berbicara
dengan orang-orang tertentu, seperti yang diinginkannya.
Yang paling memukau
dari acara pemberangkatan yang hebat ini adalah absurditasnya. Tak ada
keinginannya untuk menjadi idola siapa pun. Namun mereka datang untuk
mengungkapkan niat baik. Karena itu, tak kuasa ia menghentikan mereka.
Ia merasa sebagian
dari mereka dapat memahami dirinya. Ia berterima kasih atas ucapan selamat
mereka. Kekaguman mereka menyuntikkan ke dalam dirinya rasa takzim. Bersamaan
dengan itu, ia tersapu juga oleh gelombang sentimen dangkal yang namanya
popularitas. Reaksinya terhadap hal ini hampir-hampir berupa rasa takut,
kalau-kalau pujian berlebihan itu akan membuatnya lupa daratan. Bagaimanapun,
ia hanya manusia biasa.
Hal lain yang
mengesalkannya adalah proses pendahuluan yang berteletele itu. Dapat dikatakan
bahwa baik dirinya maupun Kojiro sudah tahu ke mana arah hubungan mereka, tapi
sementara itu dapat juga dikatakan bahwa orang banyak telah memaksa mereka
berdua untuk saling berhadapan, dan menetapkan bahwa mereka harus mengadakan penentuan
akhir, siapa yang lebih baik.
Dimulai dengan
omongan orang, "Saya dengar mereka merundingkan itu." Kemudian, kata
mereka, "Ya, mereka sudah pasti akan berhadapan." Dan kemudian lagi,
"Kapan pertarungan itu?"
Akhirnya, hari dan
jamnya sekalian disebarkan orang, sebelum mereka sendiri secara resmi
memutuskannya.
Musashi tak suka
menjadi pujaan khalayak. Dilihat dari perbuatan besarnya, memang tak dapat
dihindari lagi, ia akan dijadikan pahlawan. Tapi ia sendiri tidak mengejar hal
itu. Yang diinginkannya adalah kesempatan lebih banyak untuk bersemadi. Ia
perlu mengembangkan keselarasan, untuk menjamin agar gagasan-gagasannya tidak
melampaui kemampuannya bertindak. Melalui pengalamannya yang baru dengan Gudo,
ia telah maju selangkah lagi di jalan menuju pencerahan. Dan ia mulai merasakan
sukarnya mengikuti Jalan itu dengan lebih peka Jalan panjang dalam menempuh
hidup.
"Namun...,"
pikirnya. Di mana ia akan berada, kalau semua itu bukan demi kebaikan
orang-orang Zang mendukungnya? Apakah ia akan tetap hidup? Apakah ia akan
mengenakan pakaian? Kimono berlengan pendek hitam yang dikenakannya saat itu
khusus dijahit untuknya oleh ibu Koetsu. Sandal barunya, topi anyaman baru yang
dipegangnya, dan semua yang dibawanya sekarang, adalah pemberian orang yang
menaruh penghargaan kepadanya. Nasi yang ia makan ditanam orang lain. Ia hidup
dari karunia kerja orang lain. Bagaimana ia dapat membalas segala yang telah
mereka perbuat baginya?
Apabila pikirannya
menjurus ke arah ini, kebencian terhadap tuntutan para pendukungnya jadi
berkurang. Namun demikian, rasa kuatir akan mengecewakan mereka akan terus
terasa.
Tibalah waktunya
untuk berlayar. Terdengar doa-doa untuk keselamatan perjalanan, kata-kata
terakhir sebagai ucapan selamat jalan. Sementara itu, waktu yang tak kelihatan
mulai memisahkan lelaki dan perempuan yang ada di atas dermaga dengan pahlawan
mereka yang berangkat.
Tali penambat sudah
dilontarkan, kapal bergerak ke taut terbuka, dan layar besar mengembang seperti
sayap, berlatar belakang langit biru.
Seorang lelaki
berlari ke ujung dermaga, berhenti, dan mengentakkan kaki dengan jengkel.
"Terlambat!" geramnya. "Mestinya tadi aku tidak tidur siang.
Koetsu mendekatinya,
bertanya, "Apa Anda bukan Muso Gonnosuke?"
"Ya," jawab
yang ditanya sambil mengempit tongkatnya. "Saya pernah ketemu Anda di Kuil
Kongoji di Kawachi."
"Ya, tentu. Anda
Hon'ami Koetsu."
"Saya senang
sekali melihat Anda sehat walafiat. Dari apa yang saya dengar, sebetulnya saya
tak percaya Anda masih hidup."
"Dengar dari
siapa itu?"
"Musashi."
"Musashi?"
"Ya, dia tinggal
di rumah saya sampai kemarin. Dia menerima beberapa surat dari Kokura. Dalam
salah satu surat, Nagaoka Sado mengatakan Anda tertawan di Gunung Kudo. Menurut
dugaannya, Anda tentu terluka atau terbunuh."
"Semua itu
salah."
"Kami mendengar
juga bahwa Iori masih hidup di rumah Sado."
"Oh, jadi dia
selamat!" seru Gonnosuke, dan perasaan lega membanjiri wajahnya.
"Ya. Mari kita
duduk bercakap-cakap."
Ia ajak ahli tongkat
yang tegap itu ke sebuah warung. Sambil minum teh, Gonnosuke menyampaikan
ceritanya. Ia beruntung, karena sesudah melihat sendiri, Sanada Yukimura
berkesimpulan bahwa Gonnosuke bukan mata-mata. Ia pun dilepaskan, dan kedua
orang itu jadi bersahabat. Yukimura tidak hanya minta maaf atas kekeliruan para
anak buahnya, tapi juga mengirimkan sejumlah anak buahnya untuk mencari Iori.
Karena mereka tak
berhasil menemukan tubuh anak itu, Gonnosuke menyimpulkan anak itu masih hidup.
Sejak itu, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan pencarian di
provinsi-provinsi berdekatan. Ketika mendengar bahwa Musashi berada di Kyoto
dan pertarungan antara dia dan Kojiro akan berlangsung, Gonnosuke
melipatgandakan usahanya. Kemudian, sekembalinya ke Gunung Kudo kemarin, ia
mendengar dari Yukimura bahwa Musashi akan berlayar menuju Kokura hari ini. Ia
takut bertemu dengan Musashi tanpa Iori di sampingnya, atau tanpa berita apa
pun tentang anak itu. Tapi, karena ia tak tahu apakah akan pernah melihat
gurunya lagi dalam keadaan hidup, ia memberanikan diri datang. Ia minta maaf
pada Koetsu, seakan-akan Koetsu itu korban keteledorannya.
"Tak usah
kuatir," kata Koetsu. "Dalam beberapa hari akan ada kapal lain."
"Saya
betul-betul ingin melakukan perjalanan dengan Musashi." Ia berhenti di
situ, kemudian lanjutnya sungguh-sungguh, "Saya pikir perjalanan ini bisa
menjadi titik menentukan dalam hidup Musashi. Dia hidup sangat disiplin.
Kemungkinannya dia tak akan kalah dengan Kojiro. Namun dalam pertempuran macam
itu, siapa tahu? Di sini ada unsur supramanusia yang ikut terlibat. Semua
petarung harus menghadapinya; menang atau kalah, sebagian merupakan soal
keberuntungan."
"Saya pikir Anda
tak perlu kuatir. Ketenangan Musashi sungguh sempurna. Dia kelihatan
betul-betul yakin."
"Saya yakin
memang demikian, tapi Kojiro punya reputasi tinggi juga. Dan orang bilang,
sejak bertugas pada Yang Dipertuan Tadatoshi, dia berlatih dan tetap menjaga
kesiapan dirinya."
"Tapi ini akan
menjadi ujian kekuatan antara seorang jenius yang betul-betul angkuh, dengan
seorang biasa yang sudah menggosok bakat-bakatnya sebaik-baiknya, kan?"
"Saya sendiri
takkan menyebut Musashi orang biasa."
"Tapi dia memang
orang biasa. Itulah yang luar biasa padanya. Dia tak puas dengan hanya
mengandalkan diri pada pemberian alam. Karena tahu dirinya orang biasa, maka
dia selalu mencoba meningkatkan diri. Tak seorang pun menghargai usaha
mati-matian yang harus dia lakukan. Tapi sekarang, ketika latihannya yang
bertahun-tahun sudah memberikan hasil demikian hebat, tiap orang lalu bicara
bahwa dia memiliki 'bakat pemberian dewa'. Begitulah cara orang yang tidak
tekun berlatih menyenangkan diri."
"Terima kasih
atas ucapan itu," kata Gonnosuke. Ia merasa kata-kata Koetsu ini mungkin
ditujukan pada dirinya juga, selain Musashi. Sambil memandang tampang orang tua
yang lebar dan menyenangkan itu, pikirnya, "Dia pun begitu."
Koetsu waktu itu
tampak sebagaimana biasanya, sebagai orang yang suka bersenang-senang dan
dengan sengaja memisahkan dirinya dari bagian dunia lain. Pada waktu itu
matanya tidak memancarkan cahaya yang biasa diperlihatkannya apabila ia sedang
memusatkan diri pada cipta seni. Kim mata itu seperti lautan yang lembut,
tenang, dan tak terusik, di bawah langit yang jernih terang.
Seorang pemuda
menjenguk ke pintu dan berkata pada Koetsu, "Kita kembali sekarang?"
"Ah,
Matahachi!" jawab Koetsu bersahabat. Sambil menoleh pada Gonnosuke,
katanya, "Rasanya saya terpaksa meninggalkan Anda. Teman-teman saya
rupanya menanti."
"Apa Anda
kembali lewat Osaka?"
"Ya. Kalau kami
bisa sampai di sana pada waktunya, saya ingin naik kapal malam ke Kyoto."
"Oh, kalau
begitu saya berjalan bersama Anda saja sampai tempat itu." Demikianlah
Gonnosuke memutuskan melakukan perjalanan darat, bukannya menanti kapal
berikutnya.
Ketiga orang itu
berjalan berdampingan. Pembicaraan mereka jarang menyimpang dari Musashi,
tentang statusnya sekarang, dan perbuatan-perbuatan besarnya di masa lalu. Pada
suatu saat, Matahachi mengungkapkan keprihatinannya, katanya, "Saya
berharap Musashi menang, tapi Kojiro itu cerdik. Tekniknya bagus sekali."
Namun dalam suaranya tidak terasa kegairahan. Kenangannya tentang pertemuannya
dengan Kojiro begitu gamblang!
Senja hari mereka
sampai di jalan Osaka yang ramai. Secara bersamaan, Koetsu dan Gonnosuke tiba-tiba
sadar bahwa Matahachi tidak lagi bersama mereka.
"Ke mana
perginya dia?" tanya Koetsu.
Ketika mereka
menempuh kembali jalan itu, mereka lihat Matahachi sedang berdiri di ujung
jembatan, dengan asyik melihat ke arah tepi sungai. Di sana ibu-ibu dari
perkampungan gubuk-gubuk reyot yang atapnya hanva selembar itu sedang mencuci
alat-alat masak, gabah, dan sayuran.
"Aneh pancaran wajahnya,"
kata Gonnosuke. Ia dan Koetsu berdiri di tempat yang agak jauh, dan
memperhatikan.
"Dia!"
teriak Matahachi. "Akemi!"
Detik pertama
Matahachi mengenalinya, ia dikagetkan oleh nasib yang tak terduga-duga. Tapi,
beberapa saat kemudian, nasib malah mulai tampak sebaliknya. Takdir tidak
memperdayakan dirinya—melainkan sekadar menghadapkannya pada masa lalunya.
Akemi telah menjadi istrinya tanpa menikah. Karma mereka berdua memang
terjalin. Selama mendiami bumi yang sama, mereka ditakdirkan untuk bersatu
kembali, cepat atau lambat.
Tadi ia sukar
mengenali Akemi. Pesona dan kegenitannya dua tahun lalu sudah hilang. Wajahnya
kurus luar biasa, rambutnya tidak dicuci, dan hanya disanggul asal saja di
bawah tengkuk. Ia mengenakan kimono katun berlengan bentuk pipa, yang
panjangnya sedikit di bawah lutut, pakaian kerja istri kelas rendahan yang
tinggal di kota. Beda sekali dengan sutra warna-warni yang dikenakannya ketika
menjadi pelacur.
Ia berjongkok dalam
posisi yang biasa dilakukan para penjaja, dan ia memegang keranjang yang
tampaknya berat. Di dalam keranjang itu ia menjual remis besar, tiram laut, dan
lumut laut. Dagangannya masih banyak, menunjukkan bahwa jualannya tidak begitu
lancar.
Di punggungnya, ia
menggendong bayi berumur sekitar setahun dengan selembar kain kotor.
Yang paling membuat
jantung Matahachi berdentam lebih keras adalah anak itu. Ia hitung jumlah
bulan, sambil menekankan kedua telapak tangannya ke pipi. Kalau anak itu
umurnya jalan dua tahun, pasti terjadinya ketika mereka berdua tinggal di
Edo... dan Akemi sedang mengandung ketika mereka dicambuk di depan umum dulu.
Sinar matahari petang
yang terpantul dari sungai menari-nari di wajah Matahachi, hingga wajah itu
seperti bermandikan air mata. Ia sudah tuli terhadap kesibukan lalu lintas di
jalan. Akemi berjalan pelan sepanjang sungai. Matahachi menghampirinya sambil
melambai-lambaikan tangan dan berteriak-teriak. Koetsu dan Gonnosuke mengikuti.
"Matahachi, mau
ke mana?"
Matahachi sudah lupa
sama sekali akan dua orang itu. la berhenti, dan menanti mereka menyusulnya.
"Maaf," gumamnya. "Terus terang..." Terus terang? Bagaimana
mungkin ia menjelaskan pada mereka, apa yang akan dilakukannya sementara
dirinya pun tak dapat menjelaskannya pada diri sendiri? Pada waktu itu ia tidak
dapat memilah-milah perasaannya, namun akhirnya terlontar dari mulutnya,
"Saya sudah memutuskan untuk tidak menjadi pendeta... dan akan kembali
menjalani hidup biasa. Saya belum ditakdirkan untuk itu."
"Kembali kepada
hidup biasa?" seru Koetsu. "Begitu tiba-tiba? Hmm. Kau tampak aneh,
Matahachi."
"Saya tidak bisa
menjelaskan sekarang. Kalau saya jelaskan, barangkali akan kedengaran gila.
Baru saja saya lihat perempuan yang pernah hidup bersama saya. Dan dia
menggendong bayi. Saya pikir, itu pasti anak saya."
"Kau yakin
itu?"
"Ya,
yah...."
"Nah, tenangkan
hatimu, dan pikirkan. Apa itu betul-betul anakmu?"
"Ya! Saya sudah
jadi ayah... Maaf. Saya tidak tahu.... Saya malu. Tak dapat saya membiarkan dia
menempuh hidup semacam itu—menjual dagangan dengan keranjang, macam gelandangan
biasa. Saya mesti kerja dan menolong anak saya."
Koetsu dan Gonnosuke
saling pandang dengan cemas. Walau tidak yakin benar apakah Matahachi masih
lurus otaknya, kata Koetsu, "Kuharap kau sadar, apa yang sedang
kauperbuat."
Matahachi melepaskan
jubah pendeta yang menutup kimononya yang biasa, dan menyerahkannya kepada
Koetsu, bersama tasbihnya. "Saya minta maaf karena menyusahkan Bapak, tapi
apa boleh saya minta tolong menyampaikan ini kepada Gudo di Kuil Myoshinji?
Saya akan berterima kasih kalau Bapak sudi menyampaikan kepadanya bahwa saya
akan tinggal di Osaka ini, mencari pekerjaan dan menjadi ayah yang baik."
"Kau betul-betul
mau melakukan ini? Meninggalkan kependetaan begitu saj a?"
"Ya. Biar
bagaimana, Guru mengatakan pada saya, saya dapat kembali pada kehidupan biasa,
kapan saja saya mau."
"Hmm."
"Beliau
mengatakan kita tidak mesti berada dalam kuil untuk mempraktekkan ajaran
keagamaan. Itu lebih sukar, tapi beliau mengatakan, yang lebih terpuji adalah
mampu mengendalikan diri dan menjaga iman di tengah kebohongan, kemesuman, dan
pertentangan-segala yang buruk di dunia luar itu-daripada di lingkungan kuil
yang bersih dan murni."
"Saya yakin dia
benar."
"Sampai sekarang
ini, sudah setahun saya tinggal bersama beliau, tapi beliau belum memberikan
nama pendeta pada saya. Beliau selalu menyebut saya Matahachi. Barangkali ada
sesuatu yang bakal terjadi di masa depan, yang tidak saya mengerti. Waktu
itulah saya akan pergi menemuinya. Boleh saya minta tolong menyampaikan hal itu
kepada beliau?"
Dan dengan kata-kata
itu, Matahachi pergi.


0 komentar:
Posting Komentar