Bakti Seorang Anak
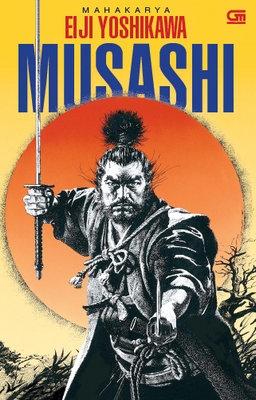
"SEDANG apa,
Nek, latihan nulis, ya?" Wajah Juro si Tikar Buluh itu menunjukkan
ekspresi kagum bercampur heran.
"Oh, kau,"
kata Osugi, sedikit kesal.
Sambil duduk di
sampingnya, Juro bergumam, "Menyalin kitab sutra Budha, ya?"
Pertanyaan itu tak dijawab. "Nenek kan sudah tua. Apa masih perlu berlatih
menulis? Atau Nenek bermaksud jadi guru kaligrafi di dunia sana?"
"Diam kau! Untuk
menyalin kitab suci, orang perlu suasana tenang. Kesunyian adalah yang terbaik.
Bagaimana kalau kau pergi saja?"
"Padahal aku
buru-buru pulang buat menceritakan apa yang kualami hari ini!"
"Soal itu bisa
menunggu."
"Kapan Nenek
akan selesai?"
"Mesti
kumasukkan semangat pencerahan sang Budha ke dalam setiap huruf yang kutulis
ini. Untuk membuat satu salinan, kubutuhkan tiga hari."
"Sabar sekali
Nenek, kalau begitu."
"Tiga hari apa
artinya? Musim panas ini akan kubuat beberapa lusin salinan. Aku bersumpah akan
membuat seribu salinan, sebelum mati. Akan kutinggalkan kepada orang-orang yang
tidak menaruh cinta yang wajar kepada orangtua mereka."
"Seribu salinan?
Banyak sekali."
"Itu sumpahku
yang suci."
"Ah, saya tidak
begitu bangga dengan itu, tapi saya kira, saya memang tidak begitu hormat pada
orangtua saya, seperti halnya semua orang yang ada di sini ini. Mereka sudah
lama melupakan orangtua mereka. Satu-satunya yang masih ingat ibu dan bapaknya
adalah majikan kita itu."
"Sungguh
menyedihkan dunia tempat hidup kita ini."
"Ha, ha. Nenek
benar. Tentunya Nenek punya anak yang tidak berbakti juga."
"Menyesal harus
kukatakan bahwa anakku itu memang sudah banyak menimbulkan kesedihan padaku.
Itu sebabnya aku bersumpah. Ini kitab Sutra tentang Cinta Agung Orangtua. Semua
orang yang tidak memperlakukan ibu dan ayah mereka dengan benar, mesti dipaksa
membacanya."
"Nenek
betul-betul akan memberikan salinan... apa namanya itu... pada seribu
orang?"
"Orang bilang,
dengan menanam satu benih pencerahan, kita dapat memenangkan seratus orang, dan
kalau satu tunas pencerahan dapat menyediakan tempat untuk seratus hati,
berarti sepuluh juta jiwa akan dapat diselamatkan." Osugi meletakkan
kuasnya, mengambil satu salinan yang sudah selesai, dan menyerahkannya kepada
Juro. "Nah, kau boleh ambil ini. Coba kaubaca, kalau ada waktu."
Osugi tampak begitu
saleh, hingga tawa Juro hampir pecah, tapi ia dapat mengendalikan diri.
Ditahannya dirinya untuk tidak menjejalkan saja kertas itu ke dalam kimononya,
seperti kertas lap yang lain; sebaliknya diangkatnya kertas itu dengan penuh
hormat ke dahinya, lalu diletakkannya di pangkuan.
"Jadi, Nenek
benar-benar tak ingin tahu tentang apa yang terjadi hari ini? Barangkali
kepercayaan Nenek kepada sang Budha itu ada hasilnya. Saya sudah bertemu dengan
orang yang agak khusus hari ini."
"Siapa pula
itu?"
"Miyamoto
Musashi. Saya lihat dia di Sungai Sumida, sedang turun dari perahu
tambang."
"Kau melihat
Musashi? Kenapa tidak kaukatakan dari tadi?" Didorongnya meja tulis itu
sambil bersungut-sungut. "Apa betul itu? Di mana dia sekarang?"
"Nah, nah,
tenang dulu, Nek. Juro tua ini tidak biasa melakukan sesuatu setengah-setengah.
Sesudah saya ketahui siapa dia, saya ikuti dia tanpa sepengetahuannya. Dia
pergi ke sebuah penginapan di Bakurocho."
"Oh, dia tinggal
dekat sini?"
"Ya, tidak dekat
sekali."
"Mungkin buatmu
tidak dekat, tapi buatku, ya. Aku sudah pergi ke mana-mana di negeri ini,
mencari dia." Osugi serentak berdiri, pergi ke lemari pakaian, dan
mengeluarkan pedang pendek yang sudah beberapa angkatan disimpan keluarganya.
"Bawa aku ke
sana," perintahnya.
"Sekarang?"
"Tentu saja
sekarang."
"Tadinya saya
kira Nenek ini punya banyak kesabaran tapi... kenapa Nenek mesti pergi
sekarang?"
"Aku selalu siap
menjumpai Musashi, kalau perlu seketika itu juga. Kalau aku terbunuh, kau dapat
mengirimkan tubuhku pada keluargaku di Mimasaka."
"Apa Nenek tak
bisa menunggu sampai majikan pulang? Kalau kita pergi macam ini, saya bisa
didamprat gara-gara menemukan Musashi."
"Tapi kita tidak
tahu, kapan Musashi akan pergi ke tempat lain lagi."
"Nenek jangan
kuatir. Saya sudah mengirimkan orang buat mengamatamati tempat itu."
"Kau bisa jamin
Musashi takkan pergi?"
"Ha? Saya sudah
menolong Nenek, tapi Nenek mau mengikat saya dengan kewajiban? Tapi baiklah,
saya jamin betul-betul. Nah, sekarang ini Nenek mesti tenang, duduklah menyalin
kitab sutra atau kegiatan semacamnya."
"Di mana
Yajibei?"
"Dia dalam
perjalanan ke Chichibu, dengan kelompok agamanya. Saya tak tahu pasti, kapan
dia kembali."
"Tak bisa aku
menunggu."
"Kalau begitu,
bagaimana kalau kita undang Sasaki Kojiro? Nenek bisa membicarakan soal itu
dengannya."
Pagi harinya, sesudah
menghubungi mata-matanya, Juro memberitahu Osugi bahwa Musashi sudah pindah
dari penginapan, ke rumah seorang penggosok pedang.
"Nah, apa
kataku!" ujar Osugi. "Tak bisa kita mengharapkan dia tinggal diam
selamanya di satu tempat. Tahu-tahu nanti dia sudah pergi lagi." Osugi
duduk menghadap meja tulis, tapi sepanjang pagi itu ia tidak menulis satu patah
kata pun.
"Tapi Musashi tak
bersayap," Juro menandaskan. "Tenanglah. Koroku akan menjumpai Kojiro
hari ini."
"Hari ini?
Bukannya tadi malam kau mengirim orang ke sana? Coba katakan sekarang, di mana
Kojiro tinggal. Aku akan pergi sendiri."
Ia bersiap-siap
pergi, tapi tiba-tiba Juro sudah menghilang, hingga Osugi terpaksa minta
petunjuk pada sejumlah anak buah lain. Karena jarang meninggalkan rumah selama
lebih dari dua tahun di Edo itu, Osugi tidak kenal betul dengan kota tersebut.
"Kojiro tinggal
dengan Iwama Kakubei," kata orang kepadanya.
"Kokubei adalah
pengikut Keluarga Hosokawa, tapi rumahnya sendiri ada di jalan raya
Takanawa."
"Jaraknya
sekitar setengah perjalanan mendaki Bukit Isarago. Semua orang bisa menunjukkan
tempat itu."
"Kalau Nenek ada
kesulitan, tanyakan Tsukinomisaki. Itu nama lain untuk Bukit Isarago."
"Rumah itu mudah
dikenal, karena gerbangnya bercat merah terang. Itu satu-satunya tempat yang
pakai gerbang merah di sana."
"Baiklah, aku
mengerti," kata Osugi tak sabar, dengan perasaan benci karena secara tak
langsung orang menganggapnya pikun atau bodoh.
"Rasanya tidak
begitu sukar, karena itu lebih baik aku jalan. Jaga semuanya selagi aku pergi.
Hati-hati dengan api. Kita tak ingin tempat ini terbakar, selagi Yajibei
pergi." Ia mengenakan zori, memeriksa apakah benar pedang pendeknya sudah
di pinggangnya, lalu memegang erat tongkatnya dan berangkat.
Beberapa menit
kemudian, Juro kembali dan bertanya di mana Osugi. "Dia tanya kami,
bagaimana pergi ke rumah Kakubei, lalu pergi sendiri."
"Yah, apa yang
bisa kita lakukan dengan perempuan tua yang keras kepala?" Kemudian Juro
berteriak ke arah kamar orang-orang lelaki,
"Koroku!"
Koroku meninggalkan
judinya dan seketika menjawab panggilan itu. "Kau mau ketemu Kojiro tadi
malam, tapi kau undurkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Perempuan tua itu
sudah pergi sendiri."
"Betul?"
"Kalau nanti
majikan datang, perempuan itu pasti buka mulut."
"Betul. Dan
dengan lidahnya yang brengsek itu, kita bisa celaka dibuatnya."
"Yah. Kalau
jalannya sama dengan bicaranya, itu baik saja, tapi badan sekurus belalang
begitu! Kalau dia ditubruk kuda, matilah dia. Aku tak suka menyuruhmu, tapi
lebih baik susullah dia, dan jaga supaya dia sampai di sana dalam keadaan
utuh."
Koroku pun lari. Juro
merenungkan brengseknya keadaan itu, dan duduk di sudut kamar para pemuda.
Kamar itu besar, barangkali sepuluh kali tiga belas meter luasnya. Lantainya
tertutup tikar tipis dari anyaman halus. Berbagai macam pedang dan senjata lain
bertebaran di mana-mana. Pada beberapa paku tergantung sapu tangan, kimono,
pakaian dalam, topi kebakaran, dan barang-barang lain yang biasa diperlukan
gerombolan bandit. Dan ada dua barang yang tak pantas ada di sana. Yang pertama,
kimono perempuan berwarna terang dengan pelipit sutra merah. Yang lain, gagang
cermin bersepuh emas, tempat menggantungkan kimono itu. Kedua barang itu
diletakkan di sana atas perintah Kojiro. Diterangkan oleh Kojiro kepada Yajibei
secara agak misterius, bahwa kalau sekelompok lelaki hidup bersama di satu
kamar, tanpa ada sesuatu yang sifatnya perempuan, orangorang itu akan cenderung
tak terkendalikan dan saling berkelahi, bukan sebaliknya, menyimpan tenaga
untuk pertempuran yang bermakna.
"Curang kau,
bangsat!"
"Siapa yang
curang? Gila kau!"
Juro melontarkan
pandangan menghina kepada para penjudi itu, dan berbaring menyilangkan kaki
seenaknya. Karena adanya keributan itu, tak mungkin ia tidur, tapi ia tak hendak
merendahkan diri dengan ikut salah satu permainan kartu atau dadu itu. Tak ada
saingan, seperti dilihatnya.
Ketika la memejamkan
mata, terdengar satu suara kesal mengatakan, "Sial hari ini-sama sekali
tak ada untung!" Orang yang kalah itu menjatuhkan bantal ke lantai, dengan
mata sedih orang yang kalah besar, dan membaringkan diri di samping Juro.
Sesudah itu disusul orang lain, lalu yang lain-lain juga.
"Apa ini?"
tanya seorang dari mereka, sambil mengulurkan tangan untuk memegang kertas yang
jatuh dari kimono Juro. "Aku akan... Iho, ini dari kitab sutra! Apa pula
gunanya orang hina macam kau membawa-bawa kitab sutra?"
Juro membuka sebelah
matanya yang mengantuk, dan katanya malas, "Oh, itu ya? Perempuan itu yang
menyalin. Dia bilang, dia sudah bersumpah akan membuat seribu lembar."
"Coba
kulihat," kata yang lain, dan merebut kertas itu. "Tahu apa sih kau ini! Oh, tulisan ini
manis dan jelas. Tiap orang bisa membacanya."
"Maksudmu, kau
bisa membacanya?"
"Tentu. Ini
permainan anak-anak."
"Baiklah, mari
kita dengar sebagian. Coba nyanyikan yang baik. Nyanyimu macam pendeta."
"Kau bercanda,
ya? Ini bukan lagu pop."
"Aah, apa
bedanya? Dulu orang biasa menyanyikan kitab sutra. Begitulah mulanya lagu
pujaan Budha itu. Kita kenal lagu pujaan, karena kita mendengarnya, kan?"
"Tak bisa kita
menyanyikan kata-kata ini dengan lagu pujaan." "Kalau begitu, pakai
lagu apa saja yang kau suka."
"Nyanyikan,
Juro."
"Karena
terdorong oleh semangat orang-orang lain itu, sambil terus menelentang Juro
membuka kitab sutra di atas wajahnya, dan memulai,
"Sutra tentang
Cinta Agung Orangtua.
Demikianlah yang
pernah kudengar. Sekali, ketika sang Budha berada Di Puncak Burung Nasar yang
Suci Di Kota penuh Istana Kerajaan,
Dan berkhotbah kepada
para bodhisatwa dan murid, Berkumpullah massa biarawan, Biarawati dan orang
awam, lelaki dan perempuan, Seluruh rakyat dari sekalian langit, Dewa-dewa naga
dan jin,
Mendengarkan Hukum
yang Suci.
Mereka berkumpul
sekitar takhta bertatah permata Dan menatap dengan mata nyalang Ke arah wajah
yang suci... "
"Apa maksudnya
semua itu?"
"Kalau di situ
dikatakan 'biarawati', apa itu maksudnya gadis-gadis yang kita namakan
biarawati itu? Soalnya, kudengar biarawati-biarawati Yoshiwara sudah mulai
membedaki mukanya sampai putih, dan mau memberikannya pada kita dengan bayaran
lebih murah daripada di rumah pelacuran..."
"Diam kau!"
"Pada waktu itu
sang Budha Mengkhotbahkan Hukum sebagai berikut: 'Hai, kalian lelaki dan wanita
yang baik, Akuilah utangmu atas belas kasih ayahmu, Akuilah utangmu atas
kemampuan ibumu. Demi kehidupan manusia di dunia ini, Milikilah karma sebagai
asas pokok, Dan milikilah orangtua sebagai sumber terdekat nasabmu."
"Ah, isinya cuma
bagaimana bersikap baik kepada ibu dan bapak. Kita sudah sejuta kali
mendengarnya."
"Ssst!"
"Ayo nyanyikan
lagi. Kami akan diam."
"Tanpa ayah,
anak takkan lahir. Tanpa ibu, anak takkan diberi makan. Semangat berasal dari
benih ayah; Tubuh tumbuh di dalam rahim ibu'"
Juro berhenti untuk
mempersiapkan diri kembali dan mengorek hidungnya, kemudian mulai lagi.
"Karena hubungan
ini,
Maka perhatian
seorang ibu kepada anaknya Sungguh tiada bandingannya di dunia ini..., "
Melihat orang-orang
lain diam, Juro bertanya, "Kalian mendengarkan, tidak?"
"Ya.
Teruskan."
"Semenjak ia
menerima anak di dalam rahimnya,
Maka sembilan bulan
lamanya,
Selagi pergi, datang,
duduk, dan tidur, Ia selalu dikunjungi penderitaan,
Ia tak lagi mencintai
makanan, minuman, atau pakaian seperti biasa,
Dan hanya
memprihatinkan keselamatan kelahiran. "
"Capek
aku," keluh Juro. "Sudah cukup, kan?"
"Belum. Ayo
terus nyanyi. Kami mendengarkan."
"Bulannya pun
penuh, dan harinya mencukupi.
Pada saat kelahiran,
angin karma mendorong, Tulang sang ibu diamuk rasa nyeri. Sang ayah menggigil
takut.
Sanak keluarga dan
pembantu kuatir dan merana. Dan ketika anak lahir dan jatuh ke atas rumput,
Kegembiraan sang ayah dan ibu tak terbatas, Bandingannya perempuan pelit Yang
menemukan permata ajaib mahakuasa. Ketika sang anak memperdengarkan bunyi-bunyi
pertama,
Sang ibu merasa ia
sendiri lahir kembali. Dadanya menjadi tempat istirahat sang anak, Pangkuannya
menjadi tempat mainnya,
Dan buah dadanya
menjadi sumber makanannya Cinta sang ibu, itulah hidupnya.
Tanpa sang ibu, sang
anak tak dapat mengenakan atau menanggalkan pakaian. Walaupun sang ibu lapar.
Ia ambil makanan dari
mulutnya sendiri dan ia berikan kepada anaknya.
Tanpa sang ibu, sang
anak tak dapat makan.... "
"Ada apa? Kenapa
berhenti?"
"Tunggu dulu
sebentar!"
"Hei, coba lihat
itu. Dia nangis seperti bayi."
"Diam kau!"
Semua tadi dimulai
secara iseng untuk melewatkan waktu, hampir-hampir sebagai kelakar, tapi makna
kata-kata sutra itu ternyata berhasil mengendap. Tiga-empat orang, di luar si
pembaca, memperlihatkan wajah tanpa senyum, dengan mata menerawang jauh.
"Sang ibu pergi
ke kampung yang bertetangga untuk bekerja. Ia menimba air, membuat api, Menumbuk
beras, membuat tepung. Malam hari, ketika ia kembali, Sebelum ia sampai rumah,
ia dengar bayinya menangis, Dan hatinya penuh cinta.
Dadanya naik-turun,
hatinya memekik, Air susu memancar, tak dapat ia menahan.
Ia lari ke rumab.
Melihat ibunya mendekat dari jauh. Sang bayi menggerakkan otak, menggoyangkan
kepala, Dan melolong memanggil ibunya. Ibunya membungkuk, Mengangkat kedua
tangan anak itu, Meletakkan bibirnya ke bibir anaknya. Tak ada cinta yang lebih
besar dari ini. Bila anak itu berumur dua tahun, la meninggalkan dada ibunya.
Tapi tanpa ayahnya,
tak mungkin ia tahu api dapat membakar. Tanpa ibunya, tak mungkin ia tahu pisau
dapat mengiris jari. Bila ia berumur tiga tahun, ia disapih dan belajar makan.
Tanpa ayahnya, tak mungkin ia tahu racun dapat membunuh. Tanpa ibunya, tak
mungkin ia tahu obat dapat menyembuhkan.
Apabila orangtua
pergi ke rumah-rumah lain Dan mendapat makanan lezat, Mereka tidak memakannya,
tapi memasukkannya ke kantung Dan membawanya pulang untuk anak itu, agar ia
girang.... "
"Kau mewek lagi,
ya?"
"Tak tahan aku.
Teringat sesuatu."
"Hentikan. Kau
bisa bikin aku nangis juga."
Sifat sentimental
dalam hubungan dengan orangtua adalah tabu keras bagi para warga masyarakat
tersingkir ini, karena menyatakan rasa cinta sebagai anak akan mengundang
tuduhan lemah, keperempuan-perempuanan, atau lebih buruk lagi dari itu. Tapi
hati Osugi yang sudah tua itu pasti akan senang sekali bila melihat mereka
sekarang. Pembacaan kitab sutra itu telah mencapai inti hidup mereka,
kemungkinan karena kesederhanaan bahasanya.
"Sudah habis,
ya? Tak ada lagi?"
"Oh, masih
banyak lagi."
"Nah?"
"Tunggu sebentar
dong!" Juro berdiri, membuang ingus keras-keras, lalu duduk untuk
melagukan sisanya.
"Anak itu
semakin besar.
Sang ayah membawa
pakaian untuk dikenakannya. Sang ibu menyisir ikal rambutnya. Mereka berdua
memberikan segala yang indah dari milik mereka, Sedang untuk mereka sendiri
hanya yang sudah tua dan usang. Akhirnya anak itu mengambil istri Dan membawa
orang asing itu masuk rumah. Orangtua itu menjadi lebih jauh. Suami-istri yang
baru itu akrab satu dengan yang lain.
Mereka diam di kamar
mereka sendiri, dan mengobrol bahagia berdua. "
"Memang begitu
itu," sela satu suara.
"Orangtua
menjadi tua.
Semangat mereka
melemah, kekuatan mereka menghilang. Hanya anak tumpuan mereka, Hanya istrinya
bekerja untuk mereka.
Tetapi sang anak
tidak lagi mendatangi mereka. Malam hari maupun siang hari. Kamar mereka
dingin.
Tiada lagi
pembicaraan menyenangkan. Mereka seperti tamu yang kesepian di sebuah
penginapan.
Datang saat gawat,
dan mereka memanggil anaknya. Sembilan dari sepuluh, sang anak tidak datang,
Tidak juga ia melayani mereka. Ia jadi marab dan mencerca mereka, katanya,
lebih baik mati daripada hidup terus tanpa guna di dunia ini. Orangtua
mendengarkan, dan hatinya penub keberangan. Sambil menangis, kata mereka, ketika
kau kecil,
Tanpa kami, tak akan
kau lahir. Tanpa kami, tak akan kau tumbuh. Ah! Betapa kami..."
Juro mendadak
berhenti dan melemparkan teks itu. "Oh, aku... aku tak bisa. Yang lain
saja yang baca."
Tapi tak seorang pun
menggantikan tempatnya. Mereka semua menangis seperti anak hilang. Ada yang
berbaring menelentang, ada yang tengkurap, ada yang duduk bersilang kaki,
dengan kepala menunduk di antara kedua lututnya. Mereka berurai air mata,
seperti anak-anak yang tersesat.
Ke tengah suasana
yang hampir tak mungkin terjadi ini masuklah Sasaki Kojiro.


0 komentar:
Posting Komentar