Setan-Setan Gunung
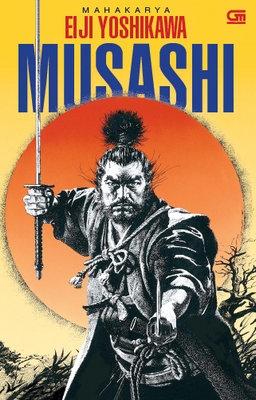
"BAIKLAH, saya
sampaikan dengan terus terang. Saya tak ingin merepotkan Anda. Keramahtamahan
Anda sangat saya hargai, dan itu cukup."
"Baik, Pak.
Bapak sungguh baik budi," jawab pendeta itu.
"Saya cuma ingin
beristirahat. Itu saja." "Oh, silakan, silakan."
"Nah, sekarang
saya harap Anda mau memaafkan kekasaran saya," kata samurai itu sambil
seenaknya berbaring miring, dan mengganjal kepalanya yang sudah ubanan dengan
lengannya.
Tamu yang baru datang
di Kuil Tokuganji itu adalah Nagaoka Sado, tangan kanan Yang Dipertuan Hosokawa
Tadaoki dari Buzen. Ia bukan orang yang punya banyak waktu untuk urusan
pribadi, tapi pada kesempatan-kesempatan seperti peringatan tahunan
meninggalnya ayahnya, ia selalu datang, dan biasanya ia bermalam, karena kuil
itu sekitar dua puluh mil jauhnya dari Edo. Untuk ukuran orang berpangkat
seperti dirinya, perjalanannya itu ia lakukan dengan sederhana saja, kali ini
hanya diiringi dua samurai dan seorang pelayan pribadi yang masih muda. Untuk
dapat sebentar saja meninggalkan bangunan Hosokawa itu, ia mesti membuat-buat
alasan. Jarang ia mendapat kesempatan melakukan sesuatu yang ia senangi, maka
ketika ia dapat melakukannya, seperti sekarang ini, ia dengan sungguh-sungguh
menikmati sake buatan setempat, sambil mendengarkan kodok-kodok berbunyi.
Sebentar saja ia sudah dapat melupakan segalanya-masalah-masalah pemerintahan
dan kebutuhan yang tak henti-hentinya untuk menyesuaikan diri dengan nuansa
peristiwa sehari-hari.
Sesudah makam malam,
si pendeta lekas-lekas membereskan pinggan mangkuk, dan pergi. Sado mengobrol
iseng dengan para pelayannya yang duduk di dekat dinding. Hanya wajah mereka
yang tampak dalam cahaya lampu.
"Mau rasanya
berbaring terus di sini, dan masuk Nirwana, seperti sang Budha," kata Sado
malas.
"Tapi hati-hati,
jangan sampai Bapak pilek. Udara malam lembap."
"Ah, sudahlah.
Beberapa pertempuran sudah dialami badan ini dengan selamat. Dia akan sanggup
menghadapi sendiri satu-dua bersin. Tapi coba cium bau kembang masak itu! Harum
sekali, ya?"
"Saya tak
mencium apa-apa."
"Tidak? Kalau
indra penciummu begitu lemah... apa kau yakin kau sendiri tidak pilek?"
Sementara mereka
sibuk dengan kelakar yang kelihatannya ringan ini, tiba-tiba kodok-kodok
berhenti berbunyi, dan seseorang berteriak keras, "Setan kau! Apa kerjamu
di sini, mengawas-awasi kamar tamu?"
Seketika pengawal
Sado berdiri.
"Ada apa?"
"Siapa di
sana?"
Sementara mata tajam
mereka menyelidiki halaman, detap kaki-kaki kecil kedengaran menjauh ke arah
dapur.
Seorang pendeta masuk
dari beranda, membungkuk, dan katanya, "Maaf atas gangguan ini. Cuma
seorang dari anak-anak sini. Tak perlu kuatir."
"Anda
yakin?"
"Tentu. Dia
tinggal beberapa mil dari sini. Ayahnya dulu kerja sebagai tukang kuda, sampai
meninggalnya baru-baru ini. Kakeknya kabarnya seorang samurai. Tiap kali anak
itu melihat samurai, dia berhenti untuk melihat, dan menggigit jari."
Sado duduk.
"Anda jangan terlalu keras dengan dia. Kalau dia ingin menjadi samurai,
bawa dia masuk. Kita keluarkan gula-gula, dan kita bicarakan soal itu."
Waktu itu Iori sudah
sampai dapur. "Hei, Nek," teriaknya. "Saya kehabisan jewawut.
Isi dong ini." Karung yang disodorkannya pada perempuan tua yang sudah
keriput dan kerja di dapur itu barangkali bisa muat setengah gantang.
Perempuan itu
membalas dengan teriakan. "Jaga lidahmu, pengemis! Bicaramu seakan kami
berutang padamu."
"Dan lagi
berani-berani amat kau ini!" kata seorang pendeta yang sedang mencuci
piring. "Pendeta kepala kasihan padamu, karena itu kami beri kau makanan,
tapi jangan kurang ajar. Kalau kau minta bantuan, mesti sopan."
"Saya tidak
mengemis. Saya berikan pada pendeta kantung peninggalan ayah saya. Dalam
kantung itu ada uang, dan banyak jumlahnva."
"Kau kira berapa
banyak dapat ditinggalkan seorang tukang kuda yang hidup di desa itu?"
"Mau kasih
jewawut sama saya atau tidak?"
"Nah, begitu
lagi. Coba lihat dirimu itu. Kau memang sinting, mau saja menerima
perintah-perintah ronin tolol itu. Dari mana pula asal orang itu? Siapa dia?
Kenapa dia mesti makan makananmu?"
"Sama sekali
bukan urusanmu."
"Huh. Mencangkul
terus di tanah tandus, di mana takkan mungkin timbul ladang atau kebun atau apa
pun! Seluruh desa menertawakan kalian."
"Siapa yang
minta nasihatmu?"
"Apa pun
penyakit yang ada dalam kepala ronin itu, pasti menular. Apa yang kalian
temukan di sana itu-satu kuali emas, macam dalam dongeng. Kau ini masih plonco,
tapi sudah menggali kuburanmu sendiri."
"Tutup mulutmu,
dan beri aku jewawut. Jewawut! Sekarang!"
Pendeta masih
menggoda Iori beberapa menit lagi, dan tiba-tiba suatu benda dingin berlumpur
mengenai wajahnya. Mata si pendeta melotot, kemudian tahulah ia benda apa
itu—seekor kodok berkutil. Ia menjerit dan menyerbu ke arah anak itu, tapi
ketika ia berhasil mencengkeram leher baju si anak, pendeta lain datang
menyatakan bahwa anak itu diminta masuk ruangan samurai.
Pendeta kepala sudah
mendengar juga keributan itu, dan bergegas ke dapur. "Apa dia sudah bikin
apa-apa yang mengganggu tamu kita?" tanyanya cemas.
"Tidak. Sado
baru saja mengatakan ingin bicara dengannya, dan mau memberinya
gula-gula."
Pendeta kepala buru-buru
menggandeng tangan Iori dan membawanya langsung ke ruangan Sado.
Iori dengan malu-malu
duduk di samping sang pendeta, dan Sado bertanya, "Berapa umurmu?"
"Tiga
belas."
"Kau ingin
menjadi samurai, ya?"
"Betul,"
jawab Iori sambil mengangguk-angguk bersemangat.
"Ya, ya.
Bagaimana kalau kau pindah tinggal di rumahku? Mula-mula kau mesti membantu
melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi nanti akan kubikin kau magang
samurai."
Iori menggelengkan
kepala, tanpa kata-kata. Sado mengira sikap demikian itu disebabkan rasa malu,
dan ia meyakinkan anak itu bahwa tawarannya sungguh-sungguh.
Iori melontarkan
pandangan marah, katanya, "Saya dengar Bapak mau memberi saya gula-gula.
Mana gula-gula itu?"
Dengan wajah pucat,
pendeta kepala menampar pergelangan tangannva.
"Jangan marahi
dia," kata Sado dengan nada memarahi. Ia memang suka pada anak-anak, dan
cenderung untuk selalu menuruti kemauan mereka. "Dia benar. Seorang lelaki
mesti memenuhi janjinya. Ambilkan gula-gula itu."
Ketika gula-gula itu
dibawa masuk, Iori mulai menjejalkannya ke dalam kimononya.
Sado heran juga,
tanyanya, "Kau tidak memakannya di sini?"
"Tidak. Guru
saya menanti saya di rumah."
"Oh? Kau punya
guru?"
Iori tak mau
susah-susah menjawab. Ia meloncat dari ruangan dan merighilang ke kebun.
Sado merasa tingkah
laku Iori itu menarik sekali. Tapi tidak demikian halnya dengan pendeta kepala.
Ia membungkuk ke lantai dua-tiga kali sebelum pergi ke dapur, mengejar Iori.
"Di mana anak
kurang ajar itu?"
"Dia ambil
karung jewawut itu, dan pergi."
Mereka mendengarkan
sebentar, tapi yang mereka dengar tak lain dari bunyi lengkingan yang tidak
selaras. Iori sudah memetik daun sebuah pohon, dan mencoba memainkan satu lagu.
Tapi rupanya di antara beberapa lagu yang dikenalnya, tak ada yang dapat
dimainkan dengan baik. Lagu kerja tukang-tukang kuda terlalu lambat, sedangkan
lagu-lagu pesta Bon terlalu rumit. Akhirnya ia memainkan saja lagu yang mirip
dengan musik tari suci di tempat suci setempat. Ini cocok sekali untuknya,
karena ia menyukai tari-tarian itu. Kadang-kadang dulu ayahnya membawanya
melihat tari-tarian itu.
Sekitar setengah jam
ke Hotengahara, di tempat bertemunya dua aliran air menjadi sebuah sungai,
tiba-tiba ia terkejut. Daun itu terloncat dari mulutnya, disertai semprotan
ludah, dan ia melompat ke rumpun bambu di samping jalan.
Di atas sebuah
jembatan sederhana, berdiri tiga atau empat orang, sedang terlibat dalam
percakapan rahasia. "Mereka!" seru Iori lirih.
Ancaman yang pernah
didengarnya mendering lagi dalam telinganya yang ketakutan. Apabila para ibu di
daerah ini memarahi anak-anaknya, mereka terbiasa mengatakan, "Kalau kau
nakal, setan-setan gunung akan turun mengambilmu." Terakhir kali
setan-setan gunung itu benar-benar datang adalah pada musim gugur dua tahun
yang lalu.
Sekitar tiga puluh
kilometer dari situ, di Pegunungan Hitachi, ada sebuah tempat suci yang
dipersembahkan kepada dewa gunung. Berabad-abad sebelumnya, penduduk begitu
takut pada dewa itu, hingga desa-desa bergiliran memberikan sesaji tahunan
berupa padi dan perempuan kepadanya. Apabila tiba giliran sebuah desa, maka
penduduk desa itu mengumpulkan persembahan dan berarak-arak membawa obor ke
tempat suci itu. Kemudian, setelah ketahuan bahwa dewa itu hanya seorang
manusia, mereka menjadi lalai memberikan persembahan.
Selama berlangsungnya
perang saudara, apa yang dinamakan dewa gunung itu mulai mengumpulkan
persembahan dengan paksa. Tiap dua atau tiga tahun, gerombolan perampok
bersenjatakan tombak-kapak, tombak berburu, kapak-apa saja yang dapat
menimbulkan rasa takut dalam hati penduduk yang damai-turun mula-mula ke satu
desa, kemudian ke desa lain, membawa pergi segala yang memenuhi selera mereka,
termasuk istri-istri orang dan anak-anak gadis. Kalau korban memberikan
perlawanan, penjarahan pun disertai pembantaian.
Karena serbuan
terakhir mereka masih tergambar jelas dalam kenangannya, Iori menyembunyikan
diri di semak-semak. Kelompok yang terdiri atas lima bayangan datang berlari
melintas ladang ke jembatan. Kemudian, di tengah kabut malam itu, datang
kelompok lain yang lebih kecil, menyusul kelompok lain lagi, sampai jumlah
bandit itu mencapai antara empat puluh dan lima puluh orang.
Iori menahan napas
dan memperhatikan baik-baik, sementara mereka bersoal jawab tentang tindakan
yang akan mereka ambil. Segera kemudian mereka mencapai kesepakatan. Pemimpin
mereka mengeluarkan perintah dan menuding ke arah desa. Orang-orang itu
menyerbu ke sana, seperti kawanan belalang.
Tak lama kemudian,
kabut malam penuh oleh suara ingar-bingarburung, binatang ternak, kuda,
lolongan manusia, tua maupun muda.
Iori cepat mengambil
keputusan untuk meminta bantuan dari samurai yang ada di Kuil Tokuganji, tapi
begitu ia meninggalkan persembunyian bambu itu, terdengar teriakan dari
jembatan, "Siapa di sana?" Ia tak melihat bahwa dua orang
ditinggalkan untuk berjaga di jembatan. Dengan napas terengah-engah ia berlari
sekencang-kencangnya, tapi kedua kakinya yang pendek itu bukan tandingan untuk
dua orang dewasa.
"Ke mana kau
pergi?" teriak orang yang pertama menangkapnya.
"Siapa
kau?"
Iori bukannya
menangis seperti bayi yang akan membuat orang-orang itu lengah, tapi sebaliknya
mencakar-cakar memberontak, melawan tangan-tangan kuat yang memenjarakannya.
"Dia melihat
kita semua. Dia akan melapor."
"Kita pukuli
saja sampai babak belur, lalu kita buang ke sawah."
"Aku ada pikiran
yang lebih baik."
Mereka membawa Iori
ke sungai, mereka lemparkan ke bawah, kemudian mereka sendiri menyusul
melompat, dan mereka ikatkan Iori ke salah satu tiang jembatan.
"Nah, di situ
dia akan aman." Kedua bajingan itu naik kembali ke pos mereka di jembatan.
Lonceng kuil
berdentang-dentang di kejauhan. Iori ketakutan melihat nyala api yang membubung
di atas desa itu membuat sungai menjadi merah darah. Suara bayi menangis dan
perempuan-perempuan melolong terdengar makin lama makin dekat. Kemudian
terdengar roda-roda berkeracak naik jembatan. Setengah lusin bandit menggiring
kereta-kereta sapi dar kuda-kuda yang bermuatan barang rampasan.
"Sampah
kotor!" teriak satu suara lelaki.
"Kembalikan
istriku!"
Perkelahian di atas
jembatan itu singkat, tapi ganas. Orang-orang memekik dan logam berdentangan,
jeritan melangit, dan sesosok mayat berlumuran darah mendarat di kaki Iori.
Tubuh lain tercebur ke sungai, memerciki wajahnya dengan darah dan air. Satu
demi satu para petani jatuh dari jembatan, enam orang semuanya. Tubuh-tubuh itu
naik ke permukaan dan mengapung turun menghilir, tapi satu orang yang belum
mati benar mencengkeram buluh dan mencakar tanah, hingga ia dapat mengangkat
setengah badannya dari air.
"Hei!"
teriak Iori. "Lepaskan tali ini. Saya akan minta tolong. Akan saya
usahakan supaya Bapak bisa balas dendam." Kemudian suaranya berubah jadi
teriakan. "Ayo! Lepaskan saya. Saya mesti selamatkan desa itu." Tapi
orang itu tak bergerak.
Iori mendesak
ikatannya dengan seluruh tenaganya, dan akhirnya ia berhasil mengendurkannya
sedikit, hingga dapat memerosotkan badan dan menendang bahu orang itu.
Wajah yang menoleh
kepadanya itu bernoda lumpur dan darah kental. Matanya pudar, tak paham.
Orang itu merangkak
dengan penuh kesakitan, mendekat. Dengan sisa tenaganya la lepaskan simpul
tali. Ketika tali terlepas, ia rebah dan mati.
Iori memandang
hati-hati ke jembatan, dan menggigit bibir. Di atas sana terdapat lebih banyak
tubuh orang. Tapi ia beruntung. Sebuah roda gerobak terperosok ke dalam papan
yang sudah lapuk. Para perampok menariknya keluar dalam keadaan tergesa-gesa,
dan tidak melihat Iori meloloskan diri.
Karena sadar tidak
akan bisa sampai ke kuil, Iori berjingkat menyusur bayangan pepohonan, sampai
akhirnya tiba di tempat yang cukup dangkal untuk diseberangi. Ketika sampai di
seberang sana, ia sudah berada di ujung Hotengahara. Ia tempuh jarak satu
kilometer lagi ke pondoknya, seakan-akan kilat sedang menyambar-nyambar
tumitnya.
Ketika sudah
menghampiri bukit tempat berdirinya pondok, ia lihat Musashi berdiri di luar,
memandang langit. "Cepat ikut!" teriak Iori.
"Ada apa?"
"Kita mesti
pergi ke desa."
"Apa api itu di
sana?"
"Ya, setan-setan
gunung itu datang lagi."
"Setan?...
Bandit, ya?"
"Ya, paling
tidak empat puluh orang jumlahnya. Kita mesti menyelamatkan orang desa."
Musashi masuk ke
dalam pondok, dan keluar lagi membawa kedua pedangnya.
Sementara ia
mengikatkan sandalnya, Iori berkata, "Ikuti saya. Akan saya tunjukkan
jalannya."
"Jangan. Kau
tinggal di sini."
Iori tak dapat
mempercayai telinganya.
"Terlalu
berbahaya."
"Tapi saya tidak
takut."
"Kau bisa
menghalangi."
"Tapi Bapak
tidak tahu jalan terdekat ke sana!"
"Api itu bisa
jadi penunjukku. Sekarang jadilah anak baik, dan tinggal saja di sini."
"Baik,
Pak." Iori mengangguk patuh, tapi dengan perasaan sangat was-was. Ia
menolehkan kepala ke arah desa, dan memandang muram ketika Musashi melejit ke
arah nyala merah itu.
Bandit-bandit
mengikat para tawanan perempuan yang merintih dan menjerit dalam satu barisan,
dan menarik mereka tanpa kenal ampun ke jembatan.
"Jangan lagi
berkaok-kaok!" teriak seorang bandit. "Seperti tak bisa jalan saja.
Ayo jalan!"
Ketika perempuan-perempuan
itu bertahan, bajingan-bajingan itu mendera mereka dengan cambuk. Seorang
perempuan jatuh, menyeret jatuh yang lain-lain. Seseorang menangkap tali itu
dan memaksa mereka berdiri kembali. Bentaknya, "Anjing-anjing kepala batu!
Apa yang kalian rintihkan? Mau saja kalian tinggal di sini, kerja macam budak
sepanjang hidup, cuma demi secuwil jewawut? Coba lihat diri kalian itu, cuma
kulit pembalut tulang. Kalian bisa jauh lebih makmur, kalau mau
bersenang-senang dengan kami.
Mereka pilih salah satu
binatang yang tampaknya lebih sehat dan penuh bermuatan barang rampasan, mereka
ikatkan tali itu padanya, lalu mereka cambuk pantat binatang itu keras-keras.
Tali pun mengencang dengan tibatiba, dan jeritan-jeritan membelah udara ketika
perempuan-perempuan itu disentakkan lagi ke depan. Yang terjatuh terseret
terus, wajah mereka menggaruk-garuk tanah.
"Berhenti!"
jerit seorang. "Tanganku bisa lepas!"
Gelombang tawa parau
melanda kawanan perampok itu.
Tapi pada saat itu,
kuda dan perempuan-perempuan itu mendadak berhenti.
"Ada apa?... Oh,
ada orang di depan!"
Semua mata ditajamkan
untuk melihat.
"Siapa di
sana?" raung seorang bandit.
Bayangan tenang yang
berjalan ke arah mereka itu membawa pedang. Bandit-bandit yang sudah tajam
mencium bau, dengan seketika dapat mengenali bau yang mereka cium—darah yang
menetes-netes dari pedang.
Orang-orang yang ada
di depan mundur dengan kikuk, dan Musashi menaksir kekuatan musuhnya. Dua belas
orang, semuanya berotot keras dan tampak kasar. Sesudah sadar kembali dari
guncangan awal, mereka menyiapkan senjata dan mengambil jurus bertahan. Satu orang
berlari ke depan, membawa kapak. Seorang lagi, yang membawa tombak berburu.
mendekat dari arah diagonal sambil merunduk rendah, mengancam rusuk Musashi.
Orang yang memegang kapak maju pertama.
"A-w-w-k!"
Kedengaran seperti menggigit lidah sendiri sampai putus. orang itu menggeliat
hebat, kemudian roboh.
"Kalian tak
kenal aku?" suara Musashi mendering tajam. "Aku pelindung rakyat,
utusan dewa yang mengawasi desa ini." Detik itu juga ia menangkap tombak
yang diarahkan kepadanya, menyentakkannya dari tangan pemiliknya, dan
membantingnya keras ke tanah. Dengan cepat ia menyerbu ke tengah gerombolan
bajingan itu, sibuk menangkis tusukan-tusukan yang datang dari segala penjuru.
Tapi, sesudah serangan pertama yang dilancarkan selagi mereka masih berkelahi
dengan penuh keyakinan, tahulah Musashi apa yang bakal terjadi. Persoalannya
bukan jumlah, tapi kekompakan dan kontrol diri lawan.
Melihat bahwa satu
demi satu rekan mereka berubah menjadi peluru yang menyemburkan darah,
bandit-bandit itu segera mengundurkan diri, makin lama makin jauh, akhirnya
panik dan kehilangan segala kemampuan untuk menyusun diri.
Selagi berkelahi pun
Musashi dapat menarik pelajaran, memanfaatkan pengalaman yang kelak menuntunnya
kepada metode khusus untuk dipergunakan pihak lemah terhadap pihak kuat. Ini
adalah pelajaran berharga, yang tidak dapat diperoleh dalam perkelahian dengan
musuh tunggal.
Kedua pedangnya masih
berada dalam sarungnya. Bertahun-tahun ia berlatih menguasai seni menangkap
senjata lawan dan membalikkannya untuk menyerang. Sekarang ia melaksanakan
teori itu dalam praktek, merebut pedang dari orang pertama yang dihadapinya.
Alasannya bukan karena pedangnya, yang ia anggap sebagai jiwanya sendiri itu,
terlampau bersih untuk dinodai darah perampok biasa. Ia hanya bertindak
praktis: untuk melawan persenjataan yang beraneka ragam itu, pedang bisa
rompal, bahkan bisa patah.
Ketika lima atau enam
orang yang masih selamat melarikan diri ke arah desa, Musashi mengambil waktu
semenit-dua menit untuk beristirahat dan mengatur napas, dengan perkiraan
mereka akan datang kembali membawa bala bantuan. Kemudian ia bebaskan
perempuan-perempuan itu, dan ia perintahkan mereka yang masih bisa berdiri
untuk membantu yang lain.
Sesudah mengucapkan
beberapa patah kata untuk menghibur dan menyemangati mereka, ia mengatakan
bahwa tergantung pada mereka sendiri untuk menyelamatkan orang tua, anak-anak,
dan suami mereka.
"Kalian akan
merana kalau kalian tetap hidup, sedangkan mereka tewas, kan?" tanyanya.
Terdengar bisik-bisik
setuju.
"Kalian
sebetulnya punya kekuatan untuk melindungi diri dan menyelamatkan yang
lain-lain. Tapi kalian tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan itu. Karena
itulah kalian menjadi korban bandit-bandit itu. Kita mesti mengubah keadaan
ini. Akan kubantu kalian menggunakan kekuatan yang kalian miliki. Yang
pertama-tama mesti dilakukan, persenjatai diri kalian."
Ia suruh mereka
mengumpulkan senjata yang bertebaran itu, dan membagikannya satu-satu pada
semua perempuan.
"Sekarang ikut
aku, dan lakukan seperti kuperintahkan. Kalian tak perlu takut. Coba yakinkan
diri kalian, bahwa dewa daerah ini ada di pihak kalian."
Ketika ia pimpin
perempuan-perempuan itu menuju desa yang terbakar, orang-orang lain yang juga
menjadi korban, muncul dari balik bayangan pepohonan dan menggabungkan diri
dengan mereka. Sebentar kemudian, kelompok itu sudah berkembang menjadi pasukan
kecil yang jumlahnya hampir seratus orang. Para perempuan mendekap orang-orang
yang mereka cintai sambil berurai air mata. Anak-anak perempuan dipersatukan kembali
dengan orangtuanya, istri-istri dengan suaminya, ibu-ibu dengan anak-anaknya.
Semula, ketika
perempuan-perempuan menceritakan bagaimana Musashi menghadapi bandit-bandit
itu, orang-orang lelaki hanya mendengarkan dengan wajah bengong, tak percaya
bahwa itulah ronin goblok dari Hotengahara itu. Ketika mereka mempercayainya,
rasa terima kasih mereka tak disembunyikan lagi, sekalipun ada kesulitan dalam
hal dialek.
Sambil menoleh kepada
kaum pria, Musashi minta mereka mencari senjata. "Apa pun bisa digunakan,
bahkan tongkat yang cukup berat dan baik, atau sebatang bambu yang masih baru."
Tak seorang pun
membantah atau bertanya tentang perintah-perintahnya.
Musashi bertanya,
"Berapa orang bandit semuanya?"
"Sekitar lima
puluh."
"Berapa rumah di
desa itu?"
"Tujuh
puluh."
Musashi
memperhitungkan, barangkali seluruhnya ada tujuh atau delapan ratus orang.
Biarpun orang tua dan anak-anak tidak dimasukkan, perampok masih kalah jauh
jumlahnya, sepuluh lawan satu.
Ia tersenyum geram,
karena penduduk desa yang damai itu tadinya percaya tak ada jalan lain kecuali
mengangkat tangan dengan putus asa. Ia tahu bahwa jika tidak dilakukan suatu
tindakan, kekejian itu akan berulang. Malam itu ia ingin melaksanakan dua hal:
menunjukkan pada orang-orang desa, bagaimana melindungi diri sendiri, dan
mengusahakan agar para perampok itu pergi untuk selamanya.
"Pak,"
teriak seorang lelaki yang baru saja datang dari desa. "Mereka sedang
jalan ke sini."
Walaupun sekarang
orang-orang desa sudah bersenjata, berita itu membuat mereka gelisah. Terlihat
tanda-tanda mereka ragu dan akan lari.
Untuk mengembalikan keyakinan
mereka, Musashi berkata keras, "Tak ada yang perlu dikuatirkan. Aku sudah
menduga. Kuminta kalian bersembunyi di kedua sisi jalan, tapi pertama-tama
dengarkan perintahku." Ia berbicara cepat tapi tenang, dan dengan singkat
mengulangi beberapa hal yang mesti ditekankan. "Kalau mereka sampai di
sini, akan kubiarkan mereka menyerangku. Kemudian aku akan pura-pura lari.
Mereka akan mengejarku. Kalian-kalian semua-tinggal di tempat kalian. Aku tak
butuh bantuan apa-apa.
"Tapi sebentar
kemudian mereka akan kembali. Nah, waktu mereka kembali, serang! Bikin suara
ribut, bikin mereka terkejut. Pukul lambung mereka, kaki dan dada meraka-mana
saja yang tak terlindung. Habis melayani rombongan pertama itu, kalian sembunyi
lagi, dan tunggu yang berikutnya. Lakukan terus begitu, sampai mereka semua
mati."
Belum lagi ia selesai
mengucapkan kata-kata itu dan para petani menyebar, kaum perusak itu muncul.
Dari pakaian dan tiadanya kerja sama pada mereka, Musashi menduga kekuatan
tempur mereka itu masih primitif, seperti pada zaman dahulu, ketika orang masih
berburu dan menangkap ikan untuk hidup. Nama Tokugawa tak ada artinya bagi
mereka, begitu pula nama Toyotomi. Pegununganlah tempat kediaman suku mereka.
Orang-orang desa itu bertugas menyediakan makanan dan perbekalan bagi mereka.
"Berhenti!"
perintah satu orang yang ada di depan kawanan. Jumlah mereka sekitar dua puluh
orang, sebagian memegang pedang kasar, sebagian lagi lembing, satu membawa
kapak perang, yang lain tombak berkarat. Dengan latar belakang nyala api, tubuh
mereka tampak seperti bayang-bayang setan sehitam jelaga.
"Apa ini
orangnya?"
"Ya, itu dia
orangnya."
Musashi berdiri
menghadang, sekitar dua puluh meter di hadapan mereka. Mereka bingung, dan
mulai meragukan kekuatan sendiri. Untuk sesaat tak seorang pun dari mereka
bergerak.
Tapi itu hanya
berlangsung sebentar. Mata Musashi yang menyala-nyala mulai menyeret mereka ke
arahnya, tanpa dapat ditawar lagi.
"Kau bajingan
mau mencoba menghalangi jalan kami?"
"Betul!"
raung Musashi sambil menangkap pedang dan menyerbu ke tengah mereka. Maka
berkumandanglah suara seru, diikuti keributan angin pusaran. Tak mungkin lagi
melihat gerakan masing-masing orang. Suasana jadi seperti kerumunan semut yang
berputar-putar.
Sawah di satu sisi
jalan dan tanggul yang dibarisi pepohonan dan semak belukar di sisi yang lain
itu baik sekali untuk Musashi, karena memberikan semacam perlindungan, tapi
sesudah bertempur sebentar, ia melakukan pengunduran diri secara strategis.
"Lihat."
"Bangsat itu
lari!"
"Kejar
dia!"
Mereka mengejarnya
sampai sudut terjauh ladang terdekat, dan di situ ia membalik dan menghadapi
mereka kembali. Karena tak ada apa pun di belakangnya, kedudukannya kelihatan
lebih buruk, tapi ia terus memaksa lawan-lawannya bertahan dengan bergerak
cepat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, bila ada yang membuat gerakan keliru,
Musashi segera menghantamnya.
Sosok tubuhnya yang
hitam seakan melenting dan tempat yang satu ke tempat lain, sementara darah
menyembur di depannya, tiap kali ia berhenti. Bandit-bandit yang tidak terbunuh
jadi terlalu bingung untuk berkelahi, sedangkan Musashi sendiri semakin dahsyat
pukulannya. Pertempuran ini lain dengan pertempuran di Ichijoji. Ia tidak
merasa berdiri di perbatasan antara hidup dan mati. Ia sudah mencapai tingkat
di luar dirinya, sementara tubuh dan pedangnya terus bekerja, tanpa mesti
berpikir secara sadar. Para penyerang melarikan diri tunggang-langgang.
Bisikan berantai
terdengar di antara orang-orang desa. "Mereka datang." Kemudian
sekelompok dari mereka melompat keluar dari persembunyian dan menyerang
dua-tiga bandit pertama, dan membunuh mereka hampir tanpa kesukaran. Para
petani masuk kembali ke dalam kegelapan, dan proses itu berulang lagi, sampai
semua bandit berhasil dihadang dan dibunuh. Ketika jumlah mayat dihitung,
keyakinan orang desa meningkat.
"Ternyata mereka
tidak begitu kuat," satu orang berkata megah.
"Tunggu! Ini
datang satu lagi."
"Hajar
dia!"
"Hai, jangan
serang. Ronin itu!"
Dengan sedikit saja
kekacauan, mereka membariskan diri sepanjang jalan, seperti serdadu yang sedang
diperiksa oleh jenderalnya. Semua mata tertuju kepada pakaian Musashi yang
basah oleh darah, dan pedangnya yang juga mengucurkan darah. Pedang itu rompal di
selusin tempat. la buang pedang itu, dan ia pungut sebatang lembing.
"Kerja kita
belum selesai," katanya. "Cari senjata buat kalian sendiri, dan mari
ikut aku. Dengan menyatukan kekuatan, kalian dapat mengusir kaum perusak itu
dari desa dan menyelamatkan keluarga kalian."
Tak seorang pun
ragu-ragu. Perempuan dan anak-anak pun mendapat senjata dan ikut serta.
Kerusakan yang
menimpa desa tidak seluas yang mereka takutkan, karena kediaman mereka terpisah
satu sama lain. Tetapi ternak yang ketakutan menimbulkan keributan baru, dan
ada seorang bayi yang menangis keras. Letusan-letusan keras terdengar dari tepi
jalan. Di situ api menjalar ke sebuah rumpun bambu yang masih hijau.
Bandit-bandit tidak
kelihatan di mana pun.
"Di mana
mereka?" tanya Musashi. "Rasanya aku mencium bau sake. Di mana ada
banyak sake terkumpul?"
Orang desa demikian
sibuk melihat api, hingga tak seorang pun mencium bau itu, tapi seorang dari
mereka berkata, "Tentunya di rumah kepala Dia punya bertong-tong
sake."
"Kalau begitu,
kita cari mereka di sana," kata Musashi.
Sementara mereka
maju, lebih banyak lagi orang keluar dari persembunyian dan menyatukan diri
dengan barisan mereka. Musashi puas melihat berkembangnya semangat kesatuan.
"Nah, di
sana," kata satu orang sambil menuding sebuah rumah besar yang dikelilingi
tembok tanah.
Sementara para petani
menyusun diri, Musashi memanjat tembok dan memasuki benteng bandit-bandit itu.
Pemimpinnya dan wakil-wakil terpentingnya menyembunyikan diri dalam kamar
berlantai tanah. Mereka sedang meneguk sake dan memperhatikan gadis-gadis muda yang
mereka tawan.
"Jangan
bingung!" teriak sang pemimpin marah, dengan dialek gunung yang kasar.
"Dia cuma satu orang. Tak perlu aku sendiri yang turun tangan. Kalian
semua hadapi dia." Ia sedang memarahi seorang bawahan yang berlari masuk
membawa berita kekalahan di luar desa itu.
Ketika pemimpin
mereka terdiam, yang lain-lain mulai mendengar ributnya suara marah di luar
tembok, dan mulailah mereka bergerak gelisah. Sambil menjatuhkan daging ayam
yang baru setengah dimakan dan mangkuk-mangkuk sake, mereka bangkit berdiri dan
secara naluriah menjangkau senjata. Kemudian mereka berdiri, menatap pintu
masuk ke kamar itu.
Musashi menggunakan
lembingnya sebagai galah, melompat lewat jendela samping yang tinggi, dan
mendarat langsung di belakang si pemimpin. Orang itu memutar badan, tapi
seketika itu juga ia sudah tertembus lembing. Dengan memperdengarkan bunyi
"A-w-r-g" mengerikan, ia mencekal lembing yang bersarang di dadanya
dengan kedua tangan. Dengan tenang Musashi melepaskan lembing itu, dan rebahlah
orang itu ke tanah, sementara mata lembing dan gagangnya mencuat dari
punggungnya.
Orang kedua yang
menyerang Musashi terampas pedangnya. Musashi membelah tubuhnya, kemudian
menebaskan pedang itu ke kepala orang ketiga, dan menusukkannya ke dada orang
keempat. Yang lain-lain lari tunggang-langgang ke pintu. Musashi melemparkan
pedang itu ke arah mereka, dan sebagai kelanjutan gerak itu, ia mencabut
lembing dari tubuh si pemimpin.
"Jangan
bergerak!" teriaknya. Ia menyerang dengan lembing yang dipegang mendatar,
dan memisahkan para bandit itu menjadi dua, seperti air ditempa galah. Ini
memberikan kepadanya cukup ruang untuk secara efektif menggunakan senjata
panjang itu. Sekarang lembing diayunkannya dengan penuh kecekatan, untuk
mencoba daya lenting gagangnya yang terbuat dari kayu ek hitam itu. Ia memukul
ke samping, menebas ke bawah, dan menusuk tanpa kenal ampun ke depan.
Bandit-bandit yang
mencoba keluar dari gerbang terhalang jalannya oleh orang-orang desa yang
bersenjata. Beberapa orang memanjat dinding. Waktu mereka turun ke tanah,
kebanyakan langsung dibunuh di tempat. Dari beberapa orang yang selamat
meloloskan diri, hampir seluruhnya mendapat luka yang membikin cacat.
Untuk sesaat udara
penuh pekik kemenangan orang-orang muda maupun tua, lelaki maupun perempuan.
Ketika gejolak kemenangan yang pertama itu mereda, suami-istri, orang tua, dan
anak-anak pun saling mendekap dan mengucurkan air mata kegembiraan.
Di tengah adegan
gembira luar biasa, seseorang bertanya, "Bagaimana kalau mereka datang
lagi?"
Tiba-tiba suasana
jadi diam penuh pertanyaan.
"Mereka takkan
kembali," kata Musashi tegas. "Takkan kembali ke desa ini. Tapi
jangan terlampau yakin. Urusan kalian menggunakan bajak, bukan pedang. Kalau
kalian terlalu bangga dengan kemampuan tempur kalian, hukuman yang akan
dijatuhkan dari langit kepada kalian akan lebih buruk daripada gempuran
setan-setan gunung mana pun."
"Sudah kalian
ketahui apa yang terjadi?" tanya Nagaoka Sado pada kedua samurai itu,
ketika mereka kembali ke Kuil Tokuganji. Di kejauhan, di sebelah sana ladang
dan paya, ia dapat melihat cahaya api di desa itu semakin surut.
"Semuanya sudah
tenang sekarang."
"Apa kalian usir
bandit-bandit itu? Berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan pada desa?"
"Orang-orang
desa sudah membunuh semuanya, kecuali beberapa orang sebelum kami sampai di
sana. Yang lain-lain lari."
"Aneh." Ia
tampak tekejut, karena jika hal itu benar, ada gagasan yang hendak
dilaksanakannya mengenai cara memerintah di daerah tuannya sendiri.
Sewaktu meninggalkan
kuil hari berikutnya, ia mengarahkan kudanya ke desa itu. Katanya,
"Sebetulnya ini di luar jalur, tapi mari kita lihat."
Seorang pendeta ikut
serta untuk menunjukkan jalan. Selagi berjalan. Sado berkata, "Tubuh-tubuh
sepanjang tepi jalan itu kelihatannya seperti bukan para petani yang
memotong," dan ia minta lebih banyak perincian kepada samurainya.
Penduduk desa tidak
jadi tidur, melainkan kerja keras mengubur mayat dan membersihkan reruntuhan
kebakaran besar itu. Tapi ketika melihat Sado dan kedua samurai itu, mereka
lari ke dalam rumah dan menyembunyikan diri.
"Bawa seorang
dari orang-orang desa itu kemari, dan mari kita coba mengetahui apa yang
terjadi," katanya kepada si pendeta.
Orang yang datang
bersama si pendeta memberikan uraian cukup terperinci tentang peristiwa yang
terjadi malam itu.
"Sekarang mulai
dapat diterima akal," kata Sado mengangguk. "Siapa nama ronin
itu?"
Petani yang tak
pernah mendengar nama Musashi itu menelengkan kepala. Ketika Sado mendesak
bertanya, si pendeta berkeliling beberapa waktu lamanya, dan kembali dengan
membawa keterangan yang dibutuhkan.
"Miyamoto
Musashi?" tanya Sado sambil merenung. "Apa dia yang dikatakan guru
oleh anak lelaki itu?"
"Betul. Dari
caranya mencoba menggarap petak tanah gurun di Hotengahara, penduduk desa
menduga dia agak sinting."
"Aku ingin
ketemu dia," kata Sado, tapi kemudian teringat olehnya pekerjaan yang
menantinya di Edo. "Tapi tak apalah, lain kali saja aku bicara dengannya,
kalau aku kemari lagi." Ia memutar kudanya dan meninggalkan petani itu
berdiri di tepi jalan.
Beberapa menit
kemudian, ia berhenti di depan gerbang kepala desa. Di situ tergantung sebuah
papan yang masih baru, dengan tulisan tinta mengilap, Peringatan untuk Penduduk
Desa: Bajakmu adalah Pedangmu. Pedangmu adalah Bajakmu. Selagi kerja di ladang,
jangan lupa serbuan luar. Selagi memikirkan serbuan luar, jangan lupa ladangmu.
Segala hal mesti berimbang dan terpadu. Yang paling penting, jangan melawan
Jalan Pergantian Generasi.
"Hmm. Siapa yang
menulis ini?"
Kepala desa akhirnya
keluar, dan kini membungkuk ke tanah di depan Sado. "Musashi,"
jawabnya.
Sambil menoleh pada
si pendeta, kata Sado, "Terima kasih Anda sudah membawa kami kemari.
Sayang sekali saya tak dapat menjumpai Musashi, tapi sekarang memang tak ada
waktu. Saya akan kembali tak lama lagi."


0 komentar:
Posting Komentar