Hujan Musim Semi yang
Merah
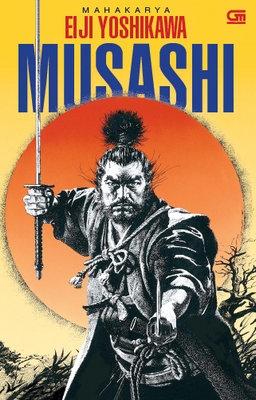
"Yajibei tak ada
di sini?" tanya Kojiro keras.
Para penjudi begitu
tenggelam dalam permainan, dan orang-orang yang menangis sedang tenggelam dalam
kenangan tentang masa kecil mereka, hingga tak seorang pun menjawab.
Ia pergi mendapatkan
Juro yang sedang menelentang dengan mata tertutup tangan, katanya, "Boleh
aku tanya, apa yang terjadi di sini?"
"Oh, saya tidak
tahu Anda yang datang tadi." Di sana-sini, orang-orang buru-buru menghapus
mata dan membuang ingus, ketika Juro dan lainlainnya bangkit berdiri dan
membungkuk malu-malu kepada guru pedang mereka.
"Kau
menangis?" tanya Kojiro.
"Ya, ya. Maksud
saya... tidak."
"Aneh sekali kau
ini."
Yang lain-lain pergi
menjauh, dan Juro bercerita tentang peristiwa yang dialaminya, bertemu dengan
Musashi. Ia merasa senang ada pokok soal yang dapat mengalihkan perhatian
Kojiro dari keadaan di kamar para pemuda itu. "Karena majikan pergi,"
katanya, "kami tidak tahu apa yang mesti dilakukan, dan Osugi memutuskan
pergi sendiri untuk bicara dengan Anda."
Mata Kojiro
menyala-nyala. "Musashi menginap di penginapan Bakurocho?"
"Betul, tapi
sekarang dia tinggal di rumah Zushino Kosuke."
"Oh, ini
peristiwa kebetulan yang menarik."
"Apa betul
begitu?"
"Kebetulan aku
mengirimkan Galah Pengeringku pada Zushino buat digarap. Sebetulnya sekarang
ini harus selesai. Aku datang kemari hari ini buat mengambilnya."
"Anda sudah
pergi ke sana?"
"Belum. Kupikir,
aku singgah beberapa menit dulu ke sini."
"Untung sekali.
Kalau mendadak memperlihatkan diri, Musashi bisa menyerang Anda."
"Aku tidak takut
padanya. Tapi bagaimana mungkin aku bicara dengan wanita tua itu, kalau dia tak
ada di sini?"
"Saya kira dia
belum sampai Isarago. Akan saya kirim pelari yang baik, buat mem-bawanya
kembali."
Dalam sidang perang
yang diadakan malam itu, Kojiro mengemukakan pendapat bahwa tak ada alasan
untuk menanti kembalinya Yajibei. Ia sendiri akan bertindak selaku pembantu
Osugi, hingga Osugi akhirnya dapat melakukan balas dendam. Juro dan Koroku
minta ikut, tapi lebih banyak untuk gengsi daripada untuk membantu. Sekalipun
sadar akan reputasi Musashi sebagai petarung, tak pernah mereka membayangkan
bahwa ia sebanding dengan guru mereka yang gemilang itu.
Namun mereka tak bisa
berbuat apa-apa malam itu. Osugi memang bersemangat sekali, tapi ia sangat
lelah dan mengeluh sakit punggung. Maka mereka memutuskan melaksanakan rencana
mereka itu malam berikutnya.
Sore keesokan
harinya, Osugi mandi air dingin, menghitamkan gigi, dan mencat rambutnya. Senja
hari itu, ia melakukan persiapan menghadapi pertempuran, mula-mula mengenakan
jubah dalam putih yang dibelinya untuk pakaian mati dan sudah dibawa ke
mana-mana bertahun-tahun lamanya itu. Ia sudah mencapkan jubah itu, demi nasib
baik, di setiap tempat suci dan kuil yang ia kunjungi-Sumiyoshi di Osaka, Oyama
Hachiman dan Kiyomizudera di Kyoto, Kuil Kannon di Asakusa, dan berlusin-lusin
bangunan keagamaan yang kurang menonjol di berbagai bagian negeri ini. Cap-cap
suci yang tertera di jubah itu sudah membuatnya menyerupai kimono celup ikat.
Osugi merasa lebih aman dengan jubah itu daripada, misalnya, dengan baju besi.
Dengan hati-hati ia
sisipkan surat kepada Matahachi ke dalam sabuk di bawah obi-nya, bersama satu
salinan Sutra tentang Cinta Agung Orangtua. Juga sepucuk surat lain yang selalu
disimpannya dalam kantung uang kecil. Surat itu berbunyi, Walaupun aku sudah
tua, sudah menjadi nasibku mengembara di seluruh negeri ini, dalam usaha
melaksanakan satu harapan besar. Tak mungkin aku mengetahui kesudahannya, tapi
aku mungkin terbunuh oleh musuh bebuyutanku, atau mati karena penyakit di
pinggir jalan. Sekiranya ini nasib yang menimpa, kuminta para pejabat dan
orang-orang yang berkemauan baik menggunakan uang dalam kantung ini untuk mengirim
tubuhku pulang. Osugi, janda Hon'iden, Kampung Yoshino, Provinsi Mimasaka.
Sesudah pedang
terletak pada tempatnya, tulang kering sudah terbungkus kain pembalut kaki
warna putih, tangan sudah mengenakan sarung tangan tanpa jari, dan obi yang
berjahit kasar sudah erat mengikat kimononya yang tak berlengan itu, maka
persiapan yang dilakukannya hampir sempurna. Sebuah mangkuk berisi air
diletakkannya di meja tulis, lalu ia berlutut di depannya, dan katanya,
"Aku pergi sekarang." Kemudian ia memejamkan mata dan duduk tak
bergerak-gerak, menujukan seluruh pikirannya kepada Paman Gon.
Juro membuka shoji
sedikit dan mengintip. "Sudah siap, Nek?" tanyanya. "Sudah
waktunya kita berangkat. Kojiro menunggu."
"Aku siap."
Ia menggabungkan diri
dengan yang lain-lain, memasuki tempat kehormatan yang mereka sediakan di depan
ceruk kamar. Koroku mengambil mangkuk dari meja, meletakkannya ke tangan Osugi,
dan dengan hati-hati mengisinya dengan sake. Kemudian dituangkannya juga untuk
Kojiro dan Juro. Ketika keempat orang itu sudah minum, lampu mereka padamkan,
dan mereka berangkat.
Beberapa orang
Hangawara minta dibawa serta, tapi Kojiro menolak, karena rombongan besar tidak
hanya akan menarik perhatian, tapi juga membebani mereka nanti dalam
pertempuran.
Ketika mereka sedang
keluar dari pintu gerbang, seorang anak muda berseru kepada mereka untuk
menunggu. Ia kemudian menyalakan api dengan batu api, sebagai tanda nasib baik.
Di luar itu, di bawah langit yang kelam oleh awan mendung, burung-burung bulbul
menyanyi.
Selagi mereka
menempuh jalan-jalan gelap dan sunyi, anjing-anjing mulai menyalak, kemudian
menyingkir, barangkali karena secara naluriah mereka merasa keempat manusia itu
sedang melaksanakan misi yang menakutkan.
"Apa itu?"
tanya Koroku sambil menatap ke belakang, ke arah jalan sempit.
"Apa kau melihat
sesuatu?"
"Ada orang
mengikuti kita."
"Barangkali
salah seorang dari rumah kita," kata Kojiro. "Mereka semua begitu
ingin ikut kita."
"Mereka lebih
suka cekcok daripada makan."
Mereka mengikuti
belokan jalan, dan Kojiro berhenti di bawah tepian atap sebuah rumah, katanya,
"Toko Kosuke di sekitar sini, kan?" Suara mereka beralih menjadi
bisikan.
"Di jalan ini,
di pinggir sana."
"Apa yang mesti
kita lakukan sekarang?" kata Koroku.
"Terus seperti
rencana. Kalian bertiga sembunyi dalam bayangan. Aku masuk toko."
"Bagaimana kalau
Musashi menyelinap keluar dari pintu belakang?"
"Jangan kuatir.
Kurang kemungkinannya dia lari dariku, seperti aku juga dari dia. Kalau dia
lari, habislah riwayatnya sebagai pemain pedang."
"Tapi barangkali
kita mesti menempatkan diri di kedua sisi yang berhadapan sekitar rumah itu,
buat berjaga-jaga."
"Baik. Nah,
seperti kita setujui, akan kubawa Musashi ke luar, dan aku akan berjalan
bersamanya. Kalau nanti kami sampai dekat Osugi, aku akan mencabut pedang dan
mengejutkannya. Itulah saatnya Osugi keluar dan menyerang."
Osugi sampai lupa
diri karena bersyukur. "Terima kasih, Kojiro. Kau begitu baik terhadapku.
Kau tentunya inkarnasi Hachiman yang Agung." Ia menangkupkan kedua
tangannya dan membungkuk, seakan-akan ia berhadapan dengan dewa perang sendiri.
Dalam hati, Kojiro
sepenuhnya yakin bahwa apa yang ia lakukan itu benar. Rasanya manusia biasa
takkan bisa membayangkan betapa besar perasaan benar diri yang dimiliki Kojiro
saat ia naik menuju pintu Kosuke itu.
Semula, ketika
Musashi dan Kojiro masih muda belia, penuh semangat, dan berhasrat memperlihatkan
keunggulan, sebetulnya tidak ada alasan yang dalam untuk terjadinya permusuhan
di antara mereka. Memang benar ada persaingan, tapi hanya pergesekan yang biasa
muncul antara dua petarung yang kuat perkasa dan hampir sebanding. Tetapi, yang
kemudian menyayat hati Kojiro, adalah karena Musashi lambat laun memperoleh
kemasyhuran sebagai pemain pedang. Dari pihak Musashi sendiri, ia menghormati
keterampilan Kojiro yang luar biasa itu, terkecuali wataknya, dan ia selalu
menghadapi Kojiro dengan cukup hati-hati. Namun tahun-tahun berlalu, dan mereka
mendapati diri mereka saling berselisih mengenai berbagai soal Keluarga
Yoshioka, nasib Akemi, peristiwa janda Hon'iden. Sekarang sudah tak mungkin
lagi untuk berdamai.
Dan kini, ketika
Kojiro memutuskan untuk menjadi pelindung Osugi, jalannya peristiwa sudah
menjadi nasib yang tak terelakkan lagi.
"Kosuke!"
Kojiro mengetuk-ngetuk pintu dengan pelan. "Apa kau masih jaga?"
Cahaya lampu menerobos sebuah celah, tapi tak ada tanda kehidupan lain di dalam
rumah.
Beberapa saat
kemudian, terdengar pertanyaan. "Siapa?"
"Iwama Kakubei
menggosokkan pedangku padamu. Aku datang mengambilnya."
"Pedang yang
besar panjang itu?"
"Buka dulu, biar
aku masuk."
"Tunggu
sebentar."
Pintu terbuka, dan
kedua orang itu saling pandang. Kosuke menghalangi jalan, katanya singkat,
"Pedang itu belum selesai."
"Oh,
begitu." Kojiro mendesak melewati Kosuke, dan duduk di anak tangga yang
menuju toko. "Kapan selesainya?"
"Nah, coba
ya...." Kosuke menggosok dagunya dan menarik sudut-sudut matanya ke bawah,
membuat wajahnya jadi tampak lebih sedih lagi.
Kojiro merasa dirinya
dipermainkan. "Apa menurutmu tidak terlalu lama kau menggarap
pedangku?"
"Sudah saya
katakan dengan terang sekali pada Kakubei, saya tak bisa menjanjikan kapan
selesainya."
"Aku tak bisa
lagi tanpa pedang itu."
"Kalau begitu,
Anda ambillah kembali."
"Apa pula
ini?" Kojiro tercengang. Tukang tidak biasa bicara demikian kepada
samurai. Tapi Kojiro tidak mencoba mencari ketegasan mengenai apa yang
melatarbelakangi sikap orang itu, melainkan langsung mengambil kesimpulan bahwa
kunjungannya itu sudah diketahui terlebih dulu. Karena menurut pendapatnya ia
mesti bertindak cepat, maka katanya, "Omong-omong, kudengar Miyamoto
Musashi dari Mimasaka tinggal di sini denganmu."
"Dari mana Anda
dengar itu?" kata Kosuke, tampak waspada. "Kebetulan dia memang
tinggal dengan kami."
"Bisa tolong
panggilkan dia? Sudah lama aku tidak ketemu dia, sejak kami di Kyoto."
"Siapa nama
Anda?"
"Sasaki Kojiro.
Dia tahu siapa aku."
"Akan saya
sampaikan bahwa Anda di sini, tapi saya tak tahu apakah dia mau menjumpai
Anda."
"Tunggu
sebentar."
"Ya?"
"Barangkali
lebih baik kujelaskan. Kebetulan aku mendengar di rumah Yang Dipertuan Hosokawa
bahwa orang yang wajahnya seperti Musashi tinggal di sini. Aku datang dengan
maksud mengundang Musashi ke luar, untuk minum dan bicara sedikit."
"Saya
mengerti." Kosuke membalikkan tubuh dan pergi ke belakang rumah.
Kojiro
menimbang-nimbang, apa yang akan dilakukannya kalau Musashi menaruh kecurigaan
dan menolak menjumpainya. Dua-tiga muslihat terpikir olehnya, tapi sebelum
sempat mengambil keputusan, ia sudah dikejutkan oleh jeritan panjang
menghebohkan.
Ia melompat seperti
orang yang baru ditendang dengan kasar. Ia salah perhitungan. Strateginya telah
diketahui—tidak hanya diketahui, melainkan telah berbalik menge-nainya. Musashi
tentu telah menyelinap dari pintu belakang, menikung ke depan, dan menyerang.
Tapi siapa yang menjerit tadi? Osugi? Juro? Koroku?
"Kalau begini
jadinya...," pikir Kojiro muram ketika ia berlari ke luar. Otot-ototnya
menegang, darahnya berpacu, dan dalam sekejap ia sudah siap menghadapi
segalanya. "Biar bagaimana, cepat atau lambat aku mesti bertempur
dengannya," pikirnya. Ia tahu itu, semenjak terjadinya peristiwa di celah
Gunung Hiei. Sekarang tibalah waktunya! Kalau Osugi sudah dirobohkan, Kojiro
bersumpah, darah Musashi akan menjadi persembahan bagi kedamaian abadi jiwa
orang tua itu.
Baru saja melewati
jarak sekitar sepuluh langkah, ia mendengar namanya dipanggil dari sisi jalan.
Suara yang terdengar kesakitan itu seolah menghentikan larinya.
"Koroku,
ya?"
"S-saya
ke-kena!"
"Juro! Di mana
Juro?"
"D-dia
juga!"
"Di mana
dia?" Sebelum datang balasan, Kojiro sudah melihat sosok Juro yang basah
kuyup oleh darah, sekitar dua puluh meter jauhnya. Seluruh tubuhnya lalu siap
siaga menjaga keselamatan dirinya. Tuturnya, "Koroku! Ke mana perginya
Musashi?"
"Bukan...
bukan... Musashi!" Koroku menggelengkan kepalanya ke kirike kanan, karena
tak mampu mengangkatnya.
"Apa katamu?
Kaubilang bukan Musashi yang menyerangmu?"
"Bukan...
bukan... Musa..."
"Siapa itu
tadi?"
Pertanyaan itu tidak
terjawab oleh Koroku.
Dengan pikiran kacau,
Kojiro berlari mendekati Juro dan menariknya berdiri pada kerah kimononya yang
merah lengket. "Juro, coba katakan, siapa itu tadi? Ke mana
perginya?"
Tetapi Juro bukannya
menjawab, melainkan meratap dengan napas terakhir yang berurai air mata,
"Ibu... maafkan... mestinya tak..."
"Apa yang kau
omongkan itu?" dengus Kojiro sambil melepaskan pakaian yang basah oleh
darah itu.
"Kojiro! Kojiro!
Kau itu, ya?"
Kojiro berlari ke
arah suara Osugi, dan di situ dilihatnya perempuan tua itu tergeletak tanpa
daya di selokan, wajah dan rambutnya penuh dengan jerami dan kupasan sayuran.
"Keluarkan aku dari sini," mohonnya.
"Apa kerja Ibu
di air kotor itu?"
Suara Kojiro lebih
terdengar marah daripada bersimpati. Direnggutkannya Osugi dengan serta-merta
ke jalan, dan di situ Osugi roboh seperti gombal. "Ke mana perginya orang
itu?" tanya Osugi, mendahului kata-kata yang akan diucapkan Kojiro.
"Orang yang
mana? Siapa yang menyerang Ibu tadi?"
"Aku tidak tahu
betul kejadiannya, tapi aku yakin orang yang mengikuti kita tadi itu."
"Apa dia
menyerang tiba-tiba?"
"Ya! Entah dari
mana, macam tiupan angin. Tak sempat lagi bicara. Dia melompat dari tempat
gelap, dan menyerang Juro dulu. Begitu Koroku menarik pedang, dia sudah luka
juga."
"Ke mana dia pergi?'
"Dia dorong aku
ke samping, jadi aku tak melihatnya, tapi langkah kakinya ter-dengar ke
sana." Osugi menuding ke sungai.
Kojiro berlari
melintasi lapangan kosong, tempat orang biasa menyelenggarakan pasar kuda, dan
sampai di tanggul Yanagihara. Di situ ia berhenti dan menoleh ke sekitar. Tak
jauh dari situ, ia melihat beberapa tumpukan kayu, lampu, dan orang. Ketika
sudah dekat, ia lihat orang-orang itu adalah pemikul joli. "Dua teman saya
dipukul orang di jalan cabang, tak jauh dari sini," katanya. "Tolong
ambil mereka dan bawa ke rumah Hangawara Yajibei di daerah tukang kayu. Bersama
mereka ada seorang perempuan tua. Bawa dia juga."
"Apa mereka
diserang penyamun?"
"Apa di sekitar
sini ada penyamun?"
"Banyak sekali.
Kami sendiri mesti hati-hati."
"Mestinya tadi
ada orang lari dari sudut sana. Apa kalian tak melihatnya?"
"Maksud Tuan,
baru saja?"
"Ya."
"Saya berangkat sekarang,"
kata pemikul joli itu. la dan teman-temannya mengangkat tiga joli dan bersiap
berangkat. "Bagaimana bayarannya?" tanya seorang. "Minta saja
kalau sudah sampai sana."
Kojiro cepat
memeriksa tepi sungai dan sekitar tumpukan kayu. Sambil memeriksa, ia
memutuskan untuk kembali ke rumah Yajibei. Tak banyak gunanya bertemu dengan
Musashi tanpa Osugi. Dan lagi kurang bijaksana menghadapi orang itu dalam
keadaan pikiran seperti sekarang.
Ia kembali dan sampai
di sebuah tempat terbuka yang sempit. Salah satu sisi tempat terbuka itu
ditumbuhi sebaris pohon paulownia. Ia memandangnya sebentar, kemudian, ketika
membalik, ia melihat kilas pedang di antara pepohonan itu. Sebelum ia
menyadarinya, setengah lusin daun sudah runtuh. Pedang itu diarahkan ke kepalanya.
"Pengecut tak
punya hati!" teriaknya.
"Bukan!"
terdengar balasannya, ketika pedang untuk kedua kalinya menebas dari kegelapan.
Kojiro berpusing dan
melompat balik sejauh tiga meter penuh. "Kalau kau Musashi, kenapa tidak
pakai cara..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pedang itu sudah
menyerang lagi. "Siapa kau!" teriaknya. "Apa kau tidak salah
sasaran?"
Tebasan ketiga dapat
ia elakkan dengan baik. Si penyerang terengah-engah. Sebelum mencoba menebas
untuk keempat kalinya, sadarlah ia bahwa usaha yang dilakukannya sia-sia saja.
Ia mengubah taktik dan mulai mendesak ke depan, sambil menyorongkan pedang.
Matanya memancarkan api. "Diam kau!" teriaknya. "Tak ada yang
salah sama sekali! Tapi akan menyegarkan ingatanmu kalau kau tahu namaku. Aku Hojo
Shinzo."
"Oh, jadi kau
salah seorang murid Obata?"
"Kau sudah
menghina guruku dan membunuh beberapa kawanku."
"Tapi, menurut
sopan santun prajurit, kau bebas menantangku terang-terangan, kapan saja.
Sasaki Kojiro tak biasa main petak umpet."
"Kubunuh
kau."
"Silakan, coba
saja."
Sambil memperhatikan
orang itu makin mendekat-empat meter, diam-diam Kojiro pun melonggarkan bagian
atas kimononya dan melekatkan tangan kanannya ke pedang. "Ayo!"
teriaknya.
Tantangan itu
ternyata menimbulkan keraguan pada Shinzo, kesangsian sesaat. Tubuh Kojiro
membungkuk ke depan, lengannya mendetak seperti busur, dan terdengar dering
logam. Detik berikutnya pedangnya sudah mendetak tajam, masuk kembali ke
sarungnya. Yang tampak tadi hanya sebaris kilasan cahaya.
Shinzo masih berdiri,
kakinya terbuka lebar. Tidak ada darah yang keluar, tapi jelas ia sudah
terluka. Walaupun pedangnya masih terulur setinggi mata, tangan kirinya dengan
refleks sudah memegang leher.
"Oh!"
Terdengar suara tergagap dari depan dan belakang Shinzo—dari Kojiro dan dari
orang yang berlari mendekat dari arah belakang Shinzo. Bunyi langkah kaki dan
suara itu menyebabkan Kojiro lari ke dalam gelap.
"Apa yang
terjadi?" teriak Kosuke. la menggapai untuk membantu Shinzo, tapi tubuh
orang itu roboh dengan seluruh bobotnya ke tangannya.
"Oh, gawat
ini!" teriak Kosuke, "Tolong! Hei! Tolong!"
Sekeping daging yang
tak lebih besar dari kerang remis jatuh dari leher Shinzo. Darah menyembur,
semula membasahi lengan Shinzo, kemudian tepi kimononya, dan terus ke kakinya.
Potongan Kayu
BLUK. Satu lagi buah
prem yang masih hijau jatuh dari pohon di kebun gelap di luar. Musashi tidak
menghiraukannya, itu pun kalau ia mendengarnya. Dalam cahaya lampu yang terang
namun bergoyang-goyang itu. rambutnya yang kusut tampak berat dan tegak,
kelihatan kering dan kemerahan.
"Bukan main
sukarnya anak ini!" demikian ibunya dulu sering mengeluh. Watak keras
kepala yang demikian sering menyebabkan si ibu mencucurkan air mata itu masih
melekat padanya, sama teguhnya dengan bekas luka di kepalanya. Sisa sebuah
bisul besar selagi ia kecil dulu.
Kenangan tentang
ibunya kini mengapung di dalam angannya. Sekali-sekali, wajah yang sedang
diukirnya mirip sekali dengan wajah ibunya.
Beberapa menit
sebelum itu, Kosuke datang ke pintunya. Setelah ragu-ragu sebentar, ia berseru,
"Anda masih kerja? Ada orang datang. Namanya Sasaki Kojiro. Katanya ingin
ketemu. Dia menunggu di bawah. Anda mau bicara dengannya, atau saya katakan
saja Anda sudah tidur?"
Musashi hanya
samar-samar menyadari bahwa Kosuke sudah mengulang-ulang pesan itu, tapi ia
sendiri tak yakin apakah sudah menjawab.
Meja kecil, lutut
Musashi, dan lantai di sekitar itu sudah penuh serpihan kayu. Ia sedang
berusaha menyelesaikan patung Kannon yang ia janjikan pada Kosuke sebagai ganti
pedang itu. Tugas itu lebih menantang lagi. karena merupakan pesanan khusus
dari Kosuke, orang yang jelas sekali sikap suka atau tidak sukanya.
Ketika pertama kali
Kosuke mengeluarkan potongan kayu sepanjang duapuluh lima sentimeter dari
sebuah lemari, dan pelan-pelan menyerahkan kepadanya, Musashi melihat bahwa
kayu itu mestinya sudah enam atau tujuh ratus tahun umurnya. Kosuke
memperlakukan kayu itu seperti pusaka, karena kayu itu berasal dari sebuah kuil
abad delapan di kubur Pangeran Shotoku di Shinaga.
"Waktu itu saya
melakukan perjalanan ke sana," Kosuke menjelaskan, "ketika mereka
sedang membetulkan bangunan-bangunan tua itu. Beberapa biarawan dan tukang kayu
bodoh mengampaki balok-balok tua itu untuk kayu api. Saya tak tahan melihat
kayu itu disia-siakan demikian, karena itu saya minta mereka memotongkan kayu
ini buat saya."
Urat kayu itu baik,
begitu juga sentuhan kayu itu pada pisau, tapi karena Kosuke demikian tinggi
menilai hartanya itu, Musashi jadi gugup. Kalau ia membuat kesalahan sedikit
saja, pasti ia merusak bahan yang tak tergantikan lagi itu.
Ia mendengar debam
keras yang kedengarannya seperti angin mengempaskan gerbang sampai terbuka di
pagar halaman. Ia menengadah dari pekerjaannya, barangkali untuk pertama
kalinya semenjak ia mulai mengukir, dan pikirnya, "Apa mungkin Iori?"
Ia menelengkan kepala, menanti.
"Kenapa berdiri
menganga saja?" teriak Kosuke pada istrinya. "Apa kau tidak lihat,
orang ini luka parah? Tak ada bedanya kamar yang mana!"
Di belakang Kosuke,
orang-orang yang mengangkut Shinzo sibuk menawarkan pertolongan.
"Ada minuman
keras buat membasuh luka? Kalau tak ada, saya akan pulang mengambil."
"Saya akan
memanggil dokter."
Sesudah keributan itu
mereda sedikit, kata Kosuke, "Saya ucapkan terima kasih kepada Anda
sekalian. Saya pikir kita sudah menyelamatkan hidupnya. Tak perlu kuatir
lagi." Ia membungkuk rendah kepada masing-masing orang itu, ketika mereka
meninggalkan rumah.
Akhirnya mulai
sadarlah Musashi bahwa ada sesuatu yang telah terjadi, dan Kosuke terlibat
dalam kejadian itu. Ia mengibaskan serpihan kayu dari pangkuannya, menuruni tangga
yang tersusun dari peti-peti penyimpanan yang bertingkat-tingkat, dan pergi ke
kamar tempat Kosuke dan istrinya sedang berdiri menekuri orang yang terluka
itu.
"Oh, Anda masih
jaga?" tanya si penggosok pedang, sambil menyingkir memberikan tempat pada
Musashi.
Musashi duduk dekat
bantal orang itu, memperhatikan wajahnya baikbaik, dan tanyanya. "Siapa
dia?"
"Saya sendiri
terkejut bukan main. Saya tidak mengenalinya, sampai kami sudah membawanya
kemari. Ini Hojo Shinzo, anak Yang Dipertuan Hojo dari Awa. Dia pemuda yang
sangat berbakti, yang beberapa tahun lamanya belajar di bawah pimpinan Obata
Kagenori."
Hati-hati Musashi
mengangkat ujung pembalut putih di sekitar leher Shinzo, memeriksa luka yang
sudah dibakar, dan kemudian dicuci dengan alkohol. Gumpal daging sebesar kerang
remis itu teriris rapi sekali, hingga kelihatan nadi lehernya yang
berdetik-detik. Maut sudah demikian dekat.
"Siapa?"
Musashi bertanya-tanya dalam hati. Melihat bentuk lukanya, ada kemungkinan
pedangnya sedang mengayun ke atas dalam pukulan layang-layang terbang. Pukulan
layang-layang terbang? Ini ciri khas Kojiro.
"Anda tahu
kejadiannya?" tanya Musashi.
"Belum."
"Saya juga tidak
tahu, tentu saja, tapi saya dapat mengatakan ini." Ia mengangguk-kan
kepala, penuh keyakinan. "Ini ulah Sasaki Kojiro."
Sampai di kamarnya
sendiri, Musashi berbaring di atas tatami, berbantalkan tangan, tanpa
menghiraukan barang-barang yang berantakan di sekitarnya. Kasurnya telah
dihamparkan, tapi tak dihiraukannya, sekalipun ia sudah lelah.
Hampir empat puluh
delapan jam berturut-turut ia bekerja membuat patung itu. Karena ia bukan
pematung, maka ia tak punya keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk
memecahkan masalah-masalah sulit, dan ia juga tidak dapat membuat
goresan-goresan cekatan untuk mengoreksi kesalahan. Tak ada yang menjadi
pegangannya, kecuali gambaran Kannon yang disimpannya dalam hati. Satu-satunya
teknik baginya adalah bagaimana menjernihkan otaknya dari pikiran-pikiran
sampingan, dan berusaha keras untuk secara tulus memindahkan gambaran itu ke
dalam kayunya.
Sejenak ia mengira
patung itu sudah berbentuk, tapi ternyata bentuk itu salah. Gambaran dalam
pikirannya salah dituangkan oleh kerja belati di tangannya. Kali lain ia merasa
mendapat kemajuan lagi, tapi kembali ukiran itu meleset. Sesudah berkali-kali
membuat kesalahan, potongan kayu kuno itu pun surut, tinggal sepanjang sepuluh
senti.
Ia mendengar burung
bulbul berbunyi dua kali, dan ia tertidur selama sekitar satu jam. Ketika
terbangun, tubuhnya yang kuat kembali menggelembung penuh kekuatan, dan
pikirannya jernih sejernih-jernihnya. Ia bangkit, dan pikirnya, "Kali ini
pasti berhasil." Ia pergi ke sumur di belakang rumah, membasuh wajah, dan
meneguk air banyak-banyak. Dengan badan segar kembali, ia duduk di samping lampu
lagi dan mulai bekerja dengan tenaga baru.
Pisau itu sekarang
terasa lain. Melalui urat kayu, ia rasakan sejarah berabad-abad termuat dalam
potongan kayu itu. Ia tahu bahwa kalau kali ini ukirannya salah lagi, takkan
ada yang tertinggal kecuali timbunan serpihan kayu yang tak berguna. Beberapa
jam berikutnya, ia memusatkan perhatian dengan saksama. Tidak sekali pun
punggungnya ditegakkan, dan ia juga tidak berhenti untuk minum air. Langit
menjadi terang, burung-burung mulai menyanyi, dan semua pintu rumah itu dibuka
agar rumah dapat dibersihkan, tapi pintu Musashi sendiri tetap tertutup.
Perhatiannya terus terpusat pada ujung pisaunya.
"Musashi, Anda
tak apa-apa?" tanya tuan rumah dengan nada kuatir, ketika ia membuka shoji
dan masuk kamar.
"Tidak bagus,"
keluh Musashi. Ia menegakkan badan dan melemparkan belati ke samping. Potongan
kayu itu tinggal seukuran ibu jari manusia. Kayu di sekitar kakinya bertebaran
seperti saiju.
"Tidak
bagus?"
"Tidak
bagus."
"Bagaimana
kayunya?"
"Habis.... Tak
dapat saya menampilkan bentuk bodhisatwa itu." Ia meletakkan tangan di
belakang kepala, dan baru merasa dirinya kembali ke bumi, sesudah
tergantung-gantung di antara khayal dan pencerahan dalam jangka waktu tak
menentu. "Betul-betul tidak bagus. Sudah waktunya melupakan dan
bersemedi."
Ia berbaring
menelentang, memejamkan mata, dan gangguan-gangguan terasa menyingkir,
digantikan oleh kabut yang membutakan. Lambat laun pikirannya terisi oleh
gagasan tunggal tentang kehampaan tak terbatas.
Kebanyakan tamu yang
meninggalkan penginapan pagi itu adalah pedagang kuda. Mereka pulang sesudah
berakhirnya pasar empat hari pada hari sebelumnya. Selama beberapa minggu
mendatang, penginapan tidak akan mendapat banyak pengunjung.
Melihat Iori menaiki
tangga, pemilik penginapan memanggilnya dari kantor.
"Ada apa?"
tanya Iori. Dan tempat yang menguntungkan itu, ia dapat melihat bagian botak
yang disamarkan dengan baik di kepala perempuan itu.
"Mau ke mana
kau?"
"Ke atas, ke
tempat guru saya. Apa ada yang salah?"
"Lebih dari
itu," jawab perempuan itu dengan pandangan jengkel. "Kapan kau
meninggalkan tempat ini?"
Iori menghitung
dengan jari, dan menjawab, "Hari sebelum kemarin dulu, saya pikir."
"Jadi, tiga hari
yang lalu?"
"Betul."
"Kau
berlambat-lambat, ya? Apa yang terjadi? Apa ada rubah menenungmu?"
"Bagaimana kau
bisa tahu? Kau sendiri mestinya rubah." Ion pun mengikik mendengar
kata-kata tangkisannya sendiri, kemudian mulai naik lagi.
"Gurumu tak ada
di situ lagi."
"Aku tak
percaya." la lari mendaki tangga, tapi segera berbalik dengan pandangan
cemas. "Apa dia ganti kamar?"
"Ada apa
denganmu ini? Sudah kukatakan, dia sudah pergi."
"Betul-betul
pergi?" Dalam suara Iori terdengar nada panik. "Kalau kau tak
percaya, lihat saja dulu rekeningnya. Lihat, tidak?"
"Tapi kenapa?
Kenapa dia pergi sebelum aku pulang?"
"Karena kau
pergi terlalu lama."
"Tapi...
tapi..." Iori menangis. "Ke mana dia pergi? Ayolah, kasih tahu."
"Dia tidak
bilang ke mana perginya. Kurasa dia meninggalkanmu karena kau begitu tak
berguna."
Wajah Iori berubah
warha, dan ia menyerbu ke jalan. la melihat ke timur, ke barat, kemudian ke
langit. Air matanya bercucuran.
Sambil menggaruk
kepalanya yang botak dengan sisir, pecahlah tawa garau perempuan itu.
"Jangan nangis lagi," serunya. "Aku cuma membohongimu. Gurumu
tinggal di rumah penggosok pedang di sana itu." Baru saja ia selesai
bicara, sebuah ladam jerami melayang masuk kantor itu.
Dengan takut-takut,
Iori duduk bersila di dekat Musashi, dan dengan suara ditekan melaporkan,
"Saya sudah kembali."
Ia melihat suasana
murung menyelimuti rumah. Serpihan kayu belum dibersihkan, dan lampu yang sudah
padam masih terletak di tempatnya semalam.
"Saya sudah
kembali," ulang Iori, tapi tidak lagi keras seperti tadi. "Siapa
ini?" gumam Musashi, sambil pelan-pelan membuka mata. "Iori."
Musashi cepat duduk.
Ia merasa lega melihat anak itu kembali dengan selamat, tapi satu-satunya yang
diucapkannya adalah, "Oh, kau, ya?"
"Minta maaf,
begitu lama saya pergi." Kata-kata itu tak terbalas. "Maafkan
saya." Permintaan maaf maupun bungkukan sopan tidak mendatangkan balasan.
Musashi mengetatkan
obi-nya, katanya, "Buka jendela-jendela, dan bersihkan kamar."
Ia keluar kamar, dan
baru Iori sempat berkata, "Baik, Pak." Musashi pergi ke kamar bawah
di belakang, dan bertanya pada Kosuke, bagaimana keadaan si sakit pagi itu.
"Kelihatannya
sudah bisa beristirahat lebih baik."
"Anda mestinya
lelah. Apa saya mesti kembali sesudah makan pagi. supaya Anda dapat
beristirahat?"
Kosuke menjawab tak
ada perlunya. "Ada satu hal yang perlu dilakukan." tambahnya.
"Saya pikir, kita mesti kasih tahu Perguruan Obata tentang ini. tapi tak
ada orang yang bisa saya suruh."
Musashi menawarkan
pergi sendiri atau menyuruh Iori, kemudian ia kembali ke kamarnya sendiri, yang
kini sudah rapi. Ia duduk, dan katanya. "Iori, apa ada balasan
suratku?"
Karena lega tidak
dimarahi, anak itu tersenyum. "Ya, saya membawa balasan. Ada di sini."
Dengan wajah penuh kemenangan, ia mengambil surat dari dalam kimononya.
"Bawa
sini."
Iori maju berlutut
dan meletakkan kertas lipatan itu ke tangan Mushasi yang diulurkan.
Dengan permintaan
maaf, terpaksa saya sampaikan, tulis Sukekuro, bahwa Yang Dipertuan Munenori
sebagai guru shogun tidak dapat melakukan pertarungan dengan Anda, sebagaimana
Anda kehendaki. Namun kalau Anda datang berkunjung dengan tujuan lain, ada
kemungkinan Yang Dipertuan menyambut Anda di dojo. Kalau Anda masih merasa ingin
sekali mencoba tangan Anda melawan Gaya Yagyu, saya pikir yang terbaik adalah
Anda menghadapi Yagyu Hyogo. Namun dengan menyesal perlu saya sampaikan bahwa
ia berangkat ke Yamato kemarin, untuk mendampingi Yang Dipertuan Sekishusai
yang sakit keras. Karena demikian keadaannya, terpaksa saya mohon Anda
mengundurkan kunjungan Anda sampai lain hari. Pada waktu lain, saya senang
dapat mengatur segala sesuatunya.
Sambil pelan-pelan
menggulung kembali gulungan panjang itu, Musashi tersenyum. Karena merasa lebih
aman, Iori melunjurkan kakinya dengan enak, katanya, "Rumah itu bukan di
Kobikicho, tapi di tempat yang namanya Higakubo. Rumah itu besar sekali, bagus
sekali, dan Kimura Sukekuro memberi saya banyak makanan yang enak-enak."
Dengan alis
melengkung, yang menyatakan tak setuju dengan sikap akrab itu, Musashi berkata
muram, "Iori."
Kaki anak itu cepat
bergerak kembali pada kedudukan yang wajar, yaitu bersimpuh di bawahnya,
"Ya, Pak."
"Biarpun kau
tersesat, apa tiga hari itu tidak terlalu lama menurutmu? Apa yang
terjadi?"
"Saya kena
tenung rubah."
"Rubah?"
"Ya, Pak,
rubah."
"Bagaimana
mungkin anak macam kau, yang lahir dan dibesarkan di desa, kena tenung
rubah?"
"Saya tidak
tahu, tapi setelah itu saya tak ingat, di mana tadinya saya berada selama
setengah hari setengah malam."
"Hmm. Aneh
sekali."
"Ya, Pak. Tap
pikir saya sendiri begini. Barangkali rubah di Edo lebih dendam kepada orang
banyak daripada yang ada di kampung."
"Kukira benar
begitu." Melihat sikap sungguh-sungguh anak itu, Musashi tak sampai hati
memakinya, tapi ia merasa perlu mengejar maksudnya. "Tapi kukira,"
sambungnya, "kau waktu itu akan melakukan sesuatu yang tak semestinya."
"Tapi rubah itu
mengikuti saya, dan supaya dia tidak menenung saya, saya lukai dia dengan
pedang saya. Dan akibatnya dia menghukum saya."
"Ah, tak
mungkin."
"Tak mungkin,
ya?"
"Tidak. Bukan
rubah yang menghukummu. Itu hati nuranimu sendiri yang tidak kelihatan. Sekarang
duduklah di situ, dan pikirkan hal itu sebentar. Kalau nanti aku kembali,
ceritakan padaku, apa arti semua itu menurutmu."
"Baik, Pak. Apa
Bapak mau pergi sekarang?"
"Ya, ke suatu
tempat dekat Tempat Suci Hirakawa, di Kojimachi."
"Bapak kembali
petang hari, kan?"
"Ha, ha.
Tentunya, kecuali kalau rubah menangkapku."
Musashi berangkat,
meninggalkan Iori untuk merenungkan hati nuraninya. Di luar, langit digelapkan
oleh awan suram, awan musim hujan di tengah musim panas.


0 komentar:
Posting Komentar