Peringatan Ibu
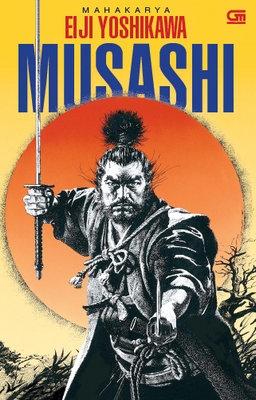
"Bu," kata
Gonnosuke, "Ibu ini sudah keterlaluan. Apa Ibu tak lihat aku sendiri juga
jengkel?" Waktu itu ia menangis, dan kata-kata itu keluar
tersendat-sendat.
"Ssst! Nanti dia
bangun." Suara ibunya pelan, tapi tegas. Nadanya seperti mengomeli anak
umur tiga tahun. "Kalau kau memang merasa kecewa, satu-satunya yang mesti
kaulakukan adalah kendalikan dirimu dan ikuti Jalan itu dengan segenap hatimu.
Menangis tak banyak gunanya. Dan lagi tak pantas. Hapus mukamu itu."
"Pertama-tama,
Ibu berjanji memaafkan aku atas kegagalan kemarin."
"Memang tak
mungkin Ibu tidak mengomelimu, tapi Ibu kira bagaimanapun soal ini soal
keterampilan. Orang bilang, makin lama orang tidak menghadapi tantangan, makin
lemah dia. Sudah sewajarnya kalau kau kalah."
"Mendengar
pendapat Ibu, membuat soal ini lebih berat lagi. Ibu sudah memberikan dorongan
padaku, tapi aku kalah. Aku tahu sekarang, tak ada bakat atau semangatku
menjadi petarung sejati. Terpaksa aku meninggalkan seni perang, dan puas
menjadi petani saja. Lebih banyak aku dapat berbuat untuk Ibu dengan cangkul
daripada dengan tongkat."
Musashi sudah
terjaga. Ia duduk tegak, dan kagum mengetahui bahwa pemuda dan ibunya
menanggapi perkelahian itu demikian sungguh-sungguh. Ia sendiri sudah
melupakan-nya, menganggapnya sebagai kesalahan dirinva dan Gonnosuke.
"Tinggi sekali rasa kehormatan mereka," gumamnya. Diam-diam ia
merangkak ke kamar sebelah. Ia pergi ke ujung kamar dan mengintip dari celah
papan shoji.
Dalam cahaya samar
matahari terbit, tampak ibu Gonnosuke duduk membelakangi altar Budha. Gonnosuke
berlutut dengan patuh di depannya, matanya memandang ke bawah dan wajahnya
basah oleh air mata.
Sambil mencengkeram
bagian belakang kerah anaknya, kata ibu berapi-api, "Apa katamu tadi? Apa
pula itu, mau hidup sebagai petani' " Sambil menarik anaknya ke dekatnya,
hingga kepala Gonnosuke terletak di lututnya, ia melanjutkan dengan nada sakit
hati, "Cuma satu pegangan Ibu menempuh tahun-tahun ini, yaitu agar dapat
menjadikanmu seorang samurai untuk memulihkan nama baik keluarga kita. Karena
itu kuminta kau membaca semua buku itu dan mempelajari seni perang. Dan itu
sebabnya Ibu bisa hidup bertahun-tahun ini dalam serba kekurangan. Tapi
sekarang... sekarang kaubilang akan membuang semua itu?"
Si ibu sendiri mulai
menangis. "Semenjak kau membiarkan dia mengunggulimu, di situ kau mesti
sudah ada niat memperbaiki namamu. Dia masih di sini. Kalau nanti dia bangun,
tantang dia mengadakan pertarungan lagi. Itulah satu-satunya jalan untuk
mendapatkan kembali kepercayaan dirimu."
Sambil mengangkat
muka, kata Gonnosuke sedih, "Sekiranya aku dapat melakukannya, Bu, tak
akan aku merasa seperti sekarang ini."
"Apa yang
terjadi denganmu? Tak wajar sikapmu ini. Di mana semangatmu?"
"Tadi malam,
ketika aku pergi dengannya ke empang, kubuka selalu mataku lebar-lebar, mencari
kesempatan menyerangnya, tapi aku tak dapat melakukannya. Meskipun pada diri
sendiri terus kubisikkan dia cuma seorang ronin tak bernama, tapi saat
kuperhatikan dia baik-baik, tanganku menolak bergerak."
"Itu karena kau
berpikir seperti pengecut."
"Terserah. Aku
tahu dalam diriku mengalir darah samurai Kiso. Dan aku belum lupa bagaimana aku
berdoa di depan Dewa Ontake dua puluh satu hari lamanya."
"Kau sudah
bersumpah di depan Dewa Ontake akan menggunakan tongkatmu untuk menciptakan
perguruan sendiri, kan?"
"Ya, tapi kukira
aku terlalu puas diri. Tak pernah aku memikirkan bahwa orang lain pun tahu cara
bertarung. Kalau aku sementah seperti kutunjukkan kemarin, bagaimana mungkin
aku mendirikan perguruan sendiri? Daripada aku hidup dalam kemiskinan dan
menyaksikan Ibu kelaparan, lebih baik kupatahkan tongkatku dan kulupakan
dia."
"Belum pernah
sebelum ini kau kalah, dan kau sudah mengalami sejumlah pertandingan.
Barangkali Dewa Ontake bermaksud memberikan pelajaran kepadamu dengan kekalahan
kemarin itu. Barangkali kau dihukum karena merasa terlalu yakin. Meninggalkan
tongkat untuk lebih mencurahkan perhatian pada Ibu bukan cara untuk membuat Ibu
bahagia. Kalau ronin itu bangun, tantang dia. Kalau kau kalah lagi, baru boleh
kau mematahkan tongkat dan melupakan ambisimu."
Musashi kembali ke
kamarnya untuk memikirkan persoalan itu. Kalau Gonnosuke menantangnya, terpaksa
ia berkelahi. Dan kalau ia berkelahi, ia pasti menang. Gonnosuke akan hancur,
dan ibunya akan patah hati.
"Tak ada jalan
lain kecuali menghindarinya," simpulnya. Tanpa menimbulkan bunyi,
dibukanya pintu ke beranda, dan ia keluar.
Matahari pagi
menumpahkan cahaya keputihan lewat pepohonan. Di sudut pekarangan, di dekat
gudang, lembu itu berdiri, bersyukur atas datangnya hari baru dan atas rumput
yang tumbuh di kakinya. Setelah diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada
binatang itu, Musashi pergi melintasi pohon-pohon penahan angin dan menempuh
jalan setapak yang berkelokkelok melintasi perladangan.
Gunung Koma hari itu
tampak dari puncak sampai ke kakinya. Gumpalar awan tak terhitung jumlahnya,
kecil-kecil seperti kapas, masing-masing berlainan bentuknya, dan semua bermain
dengan bebasnya di tengah angin.
"Jotaro masih
muda, dan Otsu lemah," kata Musashi pada diri sendiri.
"Tapi ada saja
orang yang memiliki kebaikan hati untuk membela orang yang masih muda dan
lemah. Kekuatan di alam semesta ini yang akan menentukan, apakah aku akan
menemukan mereka atau tidak." Semangatnya yang kacau semenjak pengalaman
di air terjun itu rupanya sudah terancam bahaya kehilangan jalan. Namun
sekarang semangat itu kembali menapaki jalan yang mesti ditempuhnya. Pada pagi
seperti ini, berpikir semata-mata tentang Otsu dan Jotaro rasanya seperti katak
di bawah tempurung. Biarpun mereka itu penting baginya, ia mesti tetap
mencurahkan perhatian ke Jalan yang menurut sumpahnya akan diikutinya sepanjang
hidup ini dan hidup berikutnya.
Narai, yang
dicapainya sebentar selepas tengah hari itu, adalah masyarakat yang sedang
berkembang. Satu toko memperagakan aneka warna kulit bulu di depan pintunya.
Yang lain khusus menjual sisir Kiso.
Dengan maksud
menanyakan jalan, Musashi melongokkan kepala ke sebuah toko yang menjual obat
dari empedu beruang. Ada papan nama yang bunyinya "Beruang Besar",
dan di dekat pintu masuk terdapat seekor beruang besar dalam kandang.
Sambil membalikkan
badan, pemilik toji yang baru selesai menuangka,n teh ke cangkirnya mengatakan,
"Cari apa, Pak?"
"Apa Anda tahu
toko milik orang yang namanya Daizo?"
"Daizo? Turun
sana, di persimpangan satu lagi." Orang itu keluar toko sambil memegang
cangkir tehnya, dan menuding jalan itu. Tapi ketika dilihatnya magangnya pulang
dari melakukan suruhan, ia pun memanggilnnya "Sini kamu! Bapak ini mau ke
tempat Daizo. Barangkali dia tidak mengenali toko itu, karena itu lebih baik
kauantar ke sana."
Magang itu gundul,
tapi berkuncung di depan dan belakang. Ia jalan bergegas, diikuti Musashi.
Musashi merasa bersyukur atas kebaikan itu. Ia membayangkan bahwa Daizo
tentunya sangat dihormati orang-orang sekotanya.
"Di sana,"
kata anak itu. Ia menuding bangunan di sebelah kiri, dan segera pergi.
Musashi heran, karena
sebelumnya ia menyangka akan melihat cokel seperti yang biasa menjual
barang-barang perbekalan musafir. Jendela etalasenya yang berjeruji panjangnya
enam meter, dan di belakang toko itu terdapat dua gudang. Rumahnya besar dan
tampak memanjang ke belakang. Tembok tinggi mengelilingi pekarangan, berpintu
masuk mengesankan. Pintu itu tertutup.
Dengan sikap
ragu-ragu, Musashi membuka pintu dan berseru, "Selamat siang!" Bagian
dalam rumah yang luas dan remang-remang itu mengingatkannya pada bagian dalam
tempat pembuatan sake. Karena lantainya terbuat dari tanah, udaranya sejuk
menyenangkan.
Seorang lelaki
berdiri di depan meja pemegang buku di dalam kantor. Kantor itu berupa ruangan
yang lantainya ditinggikan dan tertutup tatami.
Sesudah menutup pintu
di belakangnya, Musashi menjelaskan maksudnya. Belum lagi ia selesai bicara,
kerani itu sudah mengangguk, katanya, "Ya, ya, jadi Anda datang menjemput
anak itu." Ia membungkuk dan menawarkan bantalan pada Musashi. "Maaf
kalau saya katakan Anda terlambat. Dia muncul di sini tengah malam, ketika kami
sedang mempersiapkan keberangkatan majikan kami. Rupanya perempuan teman
jalannya diculik orang, dan dia ingin majikan kami membantu menemukannya.
Majikan mengatakan dengan senang hati akan mencoba, tapi beliau tak dapat
memberikan jaminan apa-apa. Kalau perempuan itu diambil bromocorah atau bandit
dari sekitar tempat ini, takkan ada masalah. Tapi rupanya yang mengambil itu
musafir lain, dan orang itu pasti menghindari jalan-jalan utama. Tadi pagi
Majikan mengirim orang-orang untuk melihat, tapi mereka tidak menemukan
petunjuk. Anak itu menangis mendengarnya, karena itu Majikan menasihatkan
supaya dia ikut saja. Dengan begitu, mereka dapat mencari perempuan itu di
jalan, atau bahkan berjumpa dengan Anda. Anak itu kelihatan ingin sekali pergi,
dan tak lama sesudah itu, mereka berangkat. Saya kira sudah sekitar empat jam
sampai sekarang. Sayang sekali Anda terlambat!"
Musashi merasa
kecewa, walau ia tahu tak mungkin ia tiba pada waktunya, biarpun misalnya Ia
berangkat lebih dini dan berjalan lebih cepat. Tinggallah ia menghibur diri,
dengan pendapat bahwa masih ada hari esok.
"Ke mana Daizo
pergi?" tanyanya.
"Sukar saya
mengatakan. Kami tidak buka toko dalam arti biasa. Ramuan ini disiapkan di
pegunungan dan dibawa kemari. Dua kali setahun, musim semi dan musim gugur,
para pedagang menimbunnya di sini dan pergi meninggalkannya. Karena tak banyak
yang mesti dilakukan, Majikan sering melakukan perjalanan, kadang-kadang ke
kuil-kuil atau tempat-tempat suci, kadang-kadang juga ke tempat-tempat yang
terkenal pemandangannya. Sekarang ini saya kira dia pergi ke Zenkoji,
mengelilingi Echigo, kemudian ke Edo. Tapi itu cuma dugaan. Tak pernah dia
menyebutkan ke mana akan pergi.... Apa Anda suka teh?"
Sementara teh segar
diambil dari dapur, Musashi menanti dengan tak sabar dan gelisah di tengah
lingkungan yang demikian rupa itu. Ketika teh datang, ia menanyakan penampilan
Daizo.
"Oh, kalau melihatnya,
Anda akan segera mengenalinya. Umurnya lima puluh dua tahun, sangat tegap juga
tampak kuat, mukanya agak persegi, merah sehat, sedikit bopeng. Pelipis
kanannya agak botak."
"Berapa
tingginya?"
"Rata-rata, saya
kira.”
"Bagaimana
pakaiannya?"
"Kebetulan Anda
bertanya. Saya kira itulah jalan terbaik untuk mengenalinya. Dia memakai kimono
katun Cina bergaris-garis yang dipesannya dari Sakai, khusus untuk perjalanan
ini. Kain itu sangat tidak biasa. Saya sangsi ada orang lain yang memakainya."
Musashi mendapat
kesan tersendiri tentang watak dan penampilan orang itu. Karena alasan
kesopanan, ia berlama-lama tinggal di situ, menghabiskan tehnya. Ia tidak dapat
menyusul mereka sebelum matahari terbenam, tapi menurut perhitungannya, kalau
ia berjalan malam, pada waktu fajar ia akan sampai di Celah Shiojiri dan dapat
menanti mereka di sana.
Waktu ia sampai di
kaki celah itu, matahari sudah menghilang dan kabut petang turun dengan
lembutnya ke jalan raya. Waktu itu musim semi, lampu rumah-rumah sepanjang
jalan menegaskan sepinya pegunungan. Tempat itu masih lima mil jauhnya dari
puncak celah. Musashi mendaki terus tanpa berhenti, sampai tiba di Inojigahara,
suatu tempat tinggi dan rata dekat celah. Di sini ia berbaring di antara
bintang-bintang, membiarkan pikirannya mengelana. Tak lama kemudian, ia
tertidur lelap.
Kuil kecil Sengen
menandai puncak bukit karang yang berdiri menjulang seperti bisul di atas
dataran tinggi. Itulah titik tertinggi wilayah Shiojiri.
Tidur Musashi
terganggu suara-suara orang. "Naik sini," teriak seseorang.
"Dari sini kita dapat melihat Gunung Fuji." Musashi duduk dan
memandang ke sekitar, tapi tak melihat seorang pun.
Cahaya pagi itu
memesona. Dan di sana kelihatan segi tiga merah Gunung Fuji yang mengapung di
lautan awan, masih mengenakan mantel salju musim dinginnya. Pemandangan itu
melantunkan pekik kegembiraan kekanak-kanakan dari bibir Musashi. Ia telah
menyaksikan banyak lukisan tentang gunung yang terkenal ini dan memiliki
gambaran tersendiri tentangnya, tapi baru pertama kali inilah ia benar-benar
menyaksikannya. Gunung itu hampir seratus lima puluh kilometer jauhnya, tapi
seperti terletak pada dataran yang sama dengan dataran tempatnya berdiri.
"Indah
sekali!" desahnya, dan dibiarkannya air mata mengambang pada matanya yang
tidak berkedip.
Ia tertegun oleh
kekecilannya sendiri, dan sedih memikirkan betapa tak berarti dirinya di tengah
keluasan alam semesta. Semenjak kemenangannya di pohon pinus lebar itu,
diam-diam ia sudah berani berpikir bahwa hanya ada beberapa orang, itu pun
kalau benar-benar ada, yang seperti dirinya, memenuhi syarat untuk disebut
pemain pedang besar. Hidupnya di bumi ini pendek, terbatas, tetapi keindahan
dan kemegahan Gunung Fuji itu abadi. Jengkel dan murung, ia bertanya pada diri
sendiri, bagaimana ia dapat memberikan arti kepada prestasi-prestasi dengan
pedangnya itu.
Ada hal yang tak
terhindarkan dalam cara alam itu menjulang dengan anggun dan garang di atas
dirinya. Wajarlah bahwa ia ditakdirkan tetap berada di bawahnya. Maka ia
berlutut di hadapan gunung itu, berharap agar kecongkakannya diampuni, lalu ia
menangkupkan tangan untuk berdoa demi ketenangan abadi ibunya dan demi
keselamatan Otsu dan Jotaro. Ia menyatakan terima kasih kepada negerinya dan
mohon diizinkan menjadi besar, sekalipun misalnya ia tidak dapat ambil bagian
dalam kebesaran alam.
Tetapi selagi
berlutut, berbagai pikiran datang berlomba dalam otaknya. Apakah yang
menyebabkan ia berpikir bahwa manusia itu sendiri kecil? Tidakkah alam itu
sendiri besar hanya apabila dicerminkan oleh mata manusia? Tidakkah dewa-dewa
sendiri ada hanya apabila mereka mengadakan hubungan dengan hati makhluk hidup?
Manusia adalah jiwa-jiwa hidup, bukannya batu karang mati yang melaksanakan
perbuatan-perbuatan terbesar.
"Sebagai
manusia," katanya pada dirinya, "aku tidak begitu jauh dari dewa-dewa
dan alam semesta. Aku dapat menyentuh mereka dengan pedang semeter yang kubawa
ini. Tapi itu tak akan terjadi seandainya aku masih merasakan perbedaan yang
begitu besar antara alam dan manusia. Dan seandainya aku tetap jauh dari dunia
empu sejati, manusia yang berkembang penuh."
Renungannya terganggu
oleh ocehan beberapa saudagar yang sudah naik ke tempat yang tak jauh darinya,
dan sedang memandang puncak gunung itu. "Mereka benar. Kita dapat
melihatnya."
"Tapi tak sering
kita dapat membungkuk di hadapan gunung suci itu dari tempat ini."
Para musafir masuk
seperti barisan semut dari dua jurusan, sambil memikul beraneka warna muatan.
Cepat atau lambat, Daizo dan Jotaro akan sampai di atas bukit ini. Sekiranya ia
kebetulan gagal menemukan mereka di antara para musafir itu, pasti mereka
melihat papan pernyataan yang ditinggalkannya di kaki batu karang: Kepada Daizo
dari Narai. Saya ingin sekali bertemu dengan Anda apabila lewat tempat ini.
Saya nantikan Anda di kuil atas. Musashi, guru Jotaro.
Matahari sudah tinggi
sekarang. Selama itu, Musashi terus mengawasi jalan, seperti seekor burung
elang, tapi tak ada tanda-tanda Daizo. Di sisi lain celah itu, jalan terbagi
menjadi tiga. Satu langsung menuju Edo, lewat Koshu. Jalan kedua, yang
merupakan jalan utama, melewati Celah Usui dan memasuki Edo dari utara. Jalan
ketiga membelok ke provinsi-provinsi utara. Apakah Daizo menuju utara ke
Zenkoji atau menuju timur ke Edo, ia tetap mesti menggunakan celah ini. Namun,
seperti disadari Musashi, orang tidak selamanya bepergian dengan cara yang
diharapkan. Pedagang besar itu bisa saja pergi ke suatu tempat yang jauh dari
jalan yang biasa ditempuh orang, atau dapat juga ia menginap satu malam lagi di
kaki gunung. Musashi memutuskan tidak ada jeleknya kembali ke sana untuk
bertanya tentang Daizo.
Baru saja ia menuruni
pintasan yang menuju karang terjal, didengarnya suara serak yang dikenalnya,
"Itu dia di atas!" Seketika itu juga teringat olehnya tongkat yang
sudah menyerempet tubuhnya dua malam sebelum itu.
"Turun dari
sana!" teriak Gonnosuke. Ia menatap Musashi dengan tongkat di tangan.
"Kau lari! Kau sudah menduga aku akan menantangmu dan kau lari ke luar!
Turun sini, dan ayo lawan aku sekali lagi!"
Musashi berhenti di
antara dua batu, bersandar pada salah satu darinya dan menatap Gonnosuke tanpa
mengucapkan sepatah kata pun.
Gonnosuke
menyimpulkan bahwa Musashi takkan datang, karena itu katanya pada ibunya,
"Ibu tunggu di sini. Aku akan naik dan melemparkannya ke bawah. Lihat
saja!"
"Tunggu!"
cela ibunya yang waktu itu naik lembu. "Itulah kesalahanmu. Kau tidak
sabaran. Kau mesti belajar membaca pikiran musuhmu sebelum masuk dalam
pertempuran. Sekiranya dia melemparkan batu besar padamu. apa yang akan
terjadi?"
Musashi mendengar
suara mereka, tapi kata-katanya tak jelas. Tentang dirinya, ia merasa sudah
menang. Ia sudah mengerti bagaimana Gonnosuke menggunakan tongkatnya. Yang
terasa mengganggu adalah kebencian mereka dan keinginan mereka untuk membalas
dendam. Kalau Gonnosuke kalah lagi, mereka akan jauh lebih dendam lagi. Dari
pengalamannya dengan Keluarga Yoshioka, ia kenal jeleknya pertarungan yang
mengakibatkan permusuhan lebih besar lagi. Lebih gawat dari itu adalah ibu
orang itu yang menurut penglihatan Musashi adalah Osugi kedua, seorang
perempuan yang mencintai anak lelakinya secara membuta dan akan menaruh dendam
abadi pada siapa saja yang merugikan anaknya.
Ia membalikkan badan
dan mulai mendaki.
"Tunggu!"
Tertahan oleh daya
suara perempuan tua itu, Musashi berhenti dan membalikkan badan.
Perempuan itu turun
dari lembu dan berjalan ke kaki batu. Ketika merasa yakin bahwa Musashi
memperhatikan, ia berlutut meletakkan kedua tangannya ke tanah dan membungkuk
rendah.
Musashi belum pernah
melakukan apa pun yang menyebabkan perempuan itu menghinakan diri di
hadapannya, namun ia balas membungkuk sebaik-baiknya di jalan setapak berbatu
itu. Tangannya dikedepankan, seakan hendak menolong perempuan itu berdiri.
"Samurai yang
baik!" seru perempuan itu. "Saya malu muncul di hadapan Anda seperti
ini. Saya yakin Anda tidak menyimpan perasaan lain terhadap saya, selain
perasaan mencemoohkan karena sifat keras kepala saya. Tapi saya bertindak
seperti ini bukan karena benci, dengki, atau niat jahat. Saya harap Anda
menaruh kasihan pada anak saya. Sepuluh tahun lamanya dia berlatih sendirian
tanpa guru, tanpa teman, tanpa lawan yang benar-benar bernilai. Saya mohon Anda
memberikan kepadanya pelajaran sekali lagi dalam seni pertarungan."
Musashi mendengarkan
tanpa berkata-kata.
"Saya gusar
melihat Anda meninggalkan kami seperti ini," sambung perempuan itu dengan
penuh perasaan. "Prestasi anak saya dua hari lalu itu jelek sekali. Kalau
dia tidak melakukan sesuatu untuk membuktikan kemampuannya, baik dia maupun
saya takkan dapat menghadapi nenek moyang kami. Sekarang ini, dia tak lebih
dari seorang petani yang kalah berkelahi. Karena dia sudah mendapat peruntungan
baik berjumpa dengan petarung setaraf Anda, sungguh sayang kalau dia tidak
mengambil keuntungan dari pengalaman itu. Itu sebabnya saya bawa dia kemari.
Saya mohon Anda memperhatikan permintaan saya ini dan menerima
tantangannya."
Selesai berbicara, ia
membungkuk lagi, hampir seperti sedang memuja di kaki Musashi.
Musashi turun bukit,
memegang tangannya dan membantunya kembali naik lembu. "Gonnosuke,"
katanya, "ambil tali ini. Mari kita bicara sambil jalan. Akan
kupertimbangkan aku berkelahi denganmu atau tidak."
Musashi berjalan agak
di depan mereka. Tak sepatah kata pun diucapkannya, sekalipun ia menyarankan
bicara tentang soal itu. Gonnosuke terus memandang punggung Musashi dengan
sikap curiga, sekali-sekali dengan iseng menjentikkan cambuk pada kaki lembu.
Ibunya tampak gelisah dan kuatir.
Ketika mereka telah
berjalan sekitar satu kilometer, Musashi menggerutu dan menoleh ke belakang.
"Baik, aku akan berkelahi!" katanya.
Sambil melepaskan
tali, Gonnosuke berkata, "Kau siap sekarang?" Ia menoleh ke sekitar
untuk memeriksa posisinya, seakan-akan ia hendak menyelesaikan perkara itu
seketika itu juga.
Musashi mengabaikan
saja pemuda itu, dan sebaliknya menyapa ibunya, "Apa Ibu siap menghadapi
yang terburuk? Pertarungan macam ini sama saja dengan perkelahian sampai mati,
sekalipun senjatanya tidak sama."
Untuk pertama kalinya
perempuan tua itu tertawa. "Tak perlu berkata begitu. Kalau dia kalah dari
orang yang lebih muda seperti Anda, dia dapat meninggalkan seni perang sama
sekali. Dan kalau dia memang meninggalkannya, tak ada lagi gunanya hidup. Kalau
itu yang terjadi, saya takkan dendam pada Anda."
"Kalau memang
begitu pikir Ibu, baik." Musashi mengambil tali yang tadi dijatuhkan
Gonnosuke. "Kalau kita tetap di jalan, orang banyak akan datang. Mari kita
ikatkan lembu ini, dan saya akan berkelahi sampai kapan pun."
Sebatang pohon besar
tumbuh di tengah tanah datar tempat mereka berdiri. Musashi menudingnya dan
mengajak mereka ke sana.
"Siapkan dirimu,
Gonnosuke," katanya tenang.
Gonnosuke tidak
memerlukan dorongan lagi. Seketika itu ia sudah berdiri di hadapan Musashi,
dengan tongkat dihadapkan ke tanah.
Musashi berdiri
dengan tangan kosong, lengan dan bahunya kendur. "Kau tidak bersiap?"
tanya Gonnosuke.
"Buat
apa?"
Kemarahan Gonnosuke
menggejolak. "Ambil senjata untuk berkelahi. Apa saja."
"Aku siap."
"Tanpa
senjata?"
"Senjataku di
sini," jawab Musashi, meletakkan tangan kirinya ke gagang pedang.
"Kau berkelahi
dengan pedang?"
Jawaban Musashi hanya
senyuman kecil miring pada sudut mulutnya. Mereka sampai pada tahap yang tak
memungkinkan penghamburan percakapan kecil.
Ibu Gonnosuke duduk
di bawah pohon, sambil memperhatikan seperti Budha dari batu. "Jangan
berkelahi dulu. Tunggu!" katanya.
Tapi keduanya tidak
mendengar kata-kata itu. Mereka saling menatap, tanpa membuat gerakan sekecil
apa pun. Tongkat Gonnosuke ada di bawah lengannya, menanti kesempatan memukul.
Tongkat itu seakan-akan telah menghirup seluruh udara dataran tinggi itu, dan
siap mengembuskannya dalam suatu pukulan besar bercampur jeritan. Tangan
Musashi menempel ke bagian bawah gagang pedangnya, matanya seakan menembus
tubuh Gonnosuke. Secara mental pertempuran sudah dimulai, karena mata dapat
mendatangkan kerusakan lebih hebat kepada manusia daripada pedang atau tongkat.
Sesudah sayatan pembukaan dilakukan dengan mata, barulah pedang atau tongkat
menyelinap masuk dengan mudah.
"Tunggu!"
seru si ibu lagi.
"Ada apa?"
tanya Musashi sambil melompat mundur dua-tiga meter ke tempat aman.
"Anda berkelahi
dengan pedang sungguhan?"
"Cara saya tidak
membedakan pedang kayu atau pedang sungguhan."
"Saya bukannya
mau menghentikan Anda."
"Saya minta Ibu
mengerti. Dari kayu atau baja, pedang itu mutlak. Dalam pertarungan yang
betul-betul, tidak ada ukuran setengah jalan. Satu-satunya cara untuk
menghindari bahaya adalah lari."
"Anda benar
sekali, tapi menurut saya dalam pertandingan sepenting ini Anda mesti
menyatakan diri secara resmi. Masing-masing dari kalian menghadapi lawan yang
jarang kalian temui. Pada waktu perkelahian selesai semuanya sudah
terlambat."
"Benar."
"Gonnosuke,
sebutkan dulu namamu."
Gonnosuke membungkuk
resmi kepada Musashi. "Moyang jauh kami kabarnya Kakumyo yang pernah
berjuang di bawah panji-panji prajurit besar dari Kiso, Minamoto no Yoshinaka.
Sesudah kematian Yoshinaka, Kakumyo menjadi pengikut Honen yang kudus. Ada
kemungkinan, kami berasal dari keluarga yang sama dengan dia. Berabad-abad
nenek moyang kami hidup di wilayah ini, tapi pada angkatan ayahku kami
menderita bencana yang takkan kusebutkan di sini. Dalam kekecewaanku, aku pergi
dengan ibuku ke Kuil Ontake dan bersumpah secara tertulis bahwa aku akan
memulihkan nama baik kami dengan mengikuti Jalan Samurai. Di hadapan dewa Kuil
Ontake, aku memperoleh teknik penggunaan tongkat. Aku sebut itu Gaya Muso,
artinya Gaya Wahyu, karena aku memperolehnya di kuil itu. Orang menyebutku Muso
Gonnosuke."
Musashi balas
membungkuk. "Keluargaku diturunkan oleh Hirata Shogen. Keluargaku cabang
dari Keluarga Akamatsu dari Harima. Aku anak tunggal Shimmen Munisai yang
tinggal di desa Miyamoto, di Mimasaka. Aku mendapat nama Miyamoto Musashi. Aku
tak punya keluarga dekat, dan aku membaktikan hidupku pada Jalan Pedang. Kalau
aku gugur oleh tongkat, tak perlu kau susah payah mengurus mayatku."
Ia kembali pada jurus
awalnya. Teriaknya, "Siap!"
"Siap!"
Perempuan tua itu
kelihatan hampir tak bernapas. Bukannya membiarkan bahaya datang pada dirinya
dan anaknya, ia justru pergi mencari-cari bahaya itu, dan dengan sengaja
menempatkan anaknya di hadapan pedang Musashi yang berkilau. Jalan yang
ditempuhnya itu sungguh tak terpikirkan untuk seorang ibu biasa, tapi ia
percaya sepenuhnya bahwa yang diperbuatnya itu benar. Sekarang ia duduk dalam
sikap resmi, bahunya sedikit dikedepankan dan tangannya disusun di pangkuan
dengan santun. Tubuhnya seperti mengecil dan mengisut. Sukar dipercaya bahwa ia
telah melahirkan beberapa anak. Semuanya meninggal kecuali seorang, tapi ia
bertekad menempuh berapa pun kesulitan yang ada untuk menjadikan anaknya yang
masih hidup itu seorang petarung.
Mata perempuan itu
memperlihatkan kilas cahaya, seakan-akan semua dewa dan bodhisatwa di alam
semesta berkumpul dalam dirinya untuk menyaksikan pertempuran itu.
Begitu Musashi
mencabut pedangnya, bulu roma Gonnosuke meremang. Secara naluriah ia merasa
bahwa berhadapan dengan pedang Musashi, nasibnya sudah ditentukan. Yang ia
lihat di hadapannya ini adalah orang yang belum pernah ia saksikan. Dua hari
sebelumnya, ia perhatikan Musashi dalam sikap santai dan luwes, bagaikan
garis-garis lembut mengalir pada tulisan kaligrafi.
Ia tak siap menghadapi
orang yang kini ia hadapi. Orang yang bisa menjadi contoh dalam soal
kecermatan, seperti huruf yang ditulis persegi dan rapi sekali, di mana garis
dan titik terletak pada tempat yang tepat.
Karena sadar telah
salah menilai lawan, ia merasa tak dapat mengayunkan serangan hebat seperti
yang ia lakukan sebelumnya. Tongkatnya tetap dalam kedudukan seimbang, tapi
tidak berdaya di atas kepalanya.
Selagi kedua orang
itu berhadapan dalam diam, kabut pagi terakhir telah menghilang. Seekor burung
terbang malas di antara mereka dan pegunungan tampak kabur di kejauhan.
Sekonyong-konyong sebuah jeritan membelah udara, seakan-akan burung itu
terjungkal ke bumi. Sukar sekali dikatakan bunyi itu berasal dari pedang atau
dari tongkat. Bunyi itu seperti tak nyata, seperti tepukan sebelah tangan,
menurut istilah para pemeluk Zen.
Serentak dengan itu,
dua tubuh yang bergerak seirama senjata masing-masing, mengubah posisi.
Perubahan itu terjadi lebih cepat daripada beralihnya gambaran dari mata ke
otak. Pukulan Gonnosuke tidak mengenai sasaran. Secara defensif, Musashi
memutar lengan bawahnya dan menyapukannya ke atas dari sisi Gonnosuke, ke suatu
titik di atas kepalanya, hingga hampir saja mengenai bahu kanan dan pelipisnya.
Sesudah itu Musashi melepaskan pukulan balik yang hebat, suatu pukulan yang
sebelumnya telah menyebabkan semua lawannya kerepotan. Tetapi Gonnosuke menahan
pedang itu di atas kepala dengan tongkat yang dipegang dekat kedua ujungnya.
Sekiranya pedang itu
tidak miring saat mengenai kayu, senjata Gonnosuke pasti terbelah dua. Seraya
beranjak, Gonnosuke menusukkan siku kiri ke depan dan mengangkat siku kanan,
dengan maksud memukul jaringan saraf simpatis Musashi. Tetapi pada saat yang
seharusnya mendatangkan dampak menentukan itu, ujung tongkat ternyata masih
kurang satu inci dari tubuh Musashi.
Karena pedang dan
tongkat bersilang di atas kepala Gonnosuke, maka mereka sama-sama tak dapat
maju atau mundur. Keduanya tahu bahwa gerakan keliru berarti maut mendadak.
Sekalipun posisi waktu itu serupa jalan buntu: perisai-pedang, lawan,
perisai-pedang, namun Musashi sadar akan perbedaan penting antara pedang dan
tongkat. Tongkat jelas tak punya perisai, tak punya lempengan, tak punya
gagang, tak punya ujung, tetapi di tangan seorang ahli seperti Gonnosuke, bagian
mana pun dari senjata sepanjang empat kaki itu dapat menjadi lempengan, ujung,
atau gagang. Dengan demikian, tongkat itu jauh lebih serbaguna daripada pedang,
dan bahkan dapat dipergunakan sebagai lembing pendek.
Karena tak dapat
meramalkan reaksi Gonnosuke, Musashi tak dapat menarik senjatanya. Gonnosuke,
sebaliknya, berada pada posisi lebih berbahaya: senjatanya hanya memainkan
peranan pasif untuk menahan lempengan pedang Musashi. Jika ia membiarkan
semangatnya guncang sesaat saja, pedang akan membelah kepalanya.
Wajah Gonnosuke
pucat. Ia menggigit bibir bawahnya, dan keringat berkilau di sekitar
sudut-sudut matanya yang menengadah. Kedua senjata yang bersilang itu mulai
berguncang, dan napas Gonnosuke menjadi berat.
"Gonnosuke!"
teriak ibunya. Wajahnya lebih pucat lagi. Ia mengangkat tubuhnya dan menampar
pahanya sendiri. "Pahamu terlalu tinggi!" teriaknya. Kemudian ia
menjatuhkan diri ke depan. Kesadaran seakan-akan meninggalkan dirinya.
Terdengar suara seolah ia muntah darah.
Tampak seolah pedang
dan tongkat akan tetap berpaut sampai kedua petarung itu berubah menjadi batu.
Mendengar teriakan perempuan tua itu, kedua petarung berpisah dengan kekuatan
lebih mengerikan daripada ketika mereka berpaut.
Sambil mengentakkan
tumit ke tanah, Musashi melompat mundur tiga meter jauhnya. Jarak itu dalam
sekejap ditutup Gonnosuke beserta panjang tongkatnya. Hampir Musashi tak
berhasil melompat ke samping.
Karena serangan maut
mi, Gonnosuke terhuyung ke depan dan kehilangan keseimbangan, hingga
punggungnya terbuka untuk serangan. Musashi bergerak dengan kecepatan elang
pemburu, dan kilat cahaya kecil pun mengenai otot-otot punggung musuhnya; musuh
terhuyung dan jatuh tengkurap, diiringi embik anak sapi ketakutan. Musashi
duduk bergedebuk di rumput, sambil menangkupkan tangan di perut.
"Aku
menyerah," teriaknya.
Tidak terdengar suara
apa pun dari pihak Gonnosuke. Ibunya hanya menatap kosong ke sosok yang tak
berdaya itu. Ia terlalu takjub, hingga tak dapat berbicara.
"Cuma punggung
pedang yang saya pakai tadi," kata Musashi kepadanya. Tapi karena
kelihatannya ibu itu tidak memahaminya, katanya lagi, "Bawakan dia air.
Lukanya tidak begitu parah."
"Apa?" teriak
perempuan itu tak percaya. Melihat bahwa pada tubuh anaknya tak ada darah, ia
berjalan tertatih-tatih ke sisinya dan memeluknya. Ia sebut nama anaknya, ia
bawakan air, dan kemudian ia guncang-guncangkan sampai Gonnosuke sadar kembali.
Gonnosuke memandang
kosong pada Musashi beberapa menit lamanya, kemudian datang mendekat dan
membungkukkan kepala sampai ke tanah. "Maaf," katanya pendek.
"Anda terlalu baik buat saya."
Musashi, yang seperti
baru tersadar dari keadaan kesurupan, meraih tangannya, katanya, "Kenapa
begitu? Kau tidak kalah, akulah yang kalah." Ia buka bagian depan
kimononya. "Lihat ini!" Ia tuding noda merah bekas pukulan tongkat.
"Sedikit saja lagi, aku terbunuh." Dalam suaranya terasa getar
guncangan, karena sesungguhnya ia belum dapat membayangkan kapan dan bagaimana
ia mendapat luka itu.
Gonnosuke dan ibunya
menatap tanda merah itu, tapi tidak mengatakan apa-apa.
Musashi menutup
kembali kimononya, dan bertanya kepada perempuan tua itu, kenapa ia
memperingatkan ada yang keliru atau berbahaya dalam jurus anaknya?
"Saya bukan ahli
dalam soal-soal ini, tapi ketika saya perhatikan dia mengerahkan seluruh
kekuatannya untuk menahan pedang Anda, terasa oleh saya dia kehilangan
kesempatan. Dia tak dapat maju, tak dapat mundur, padahal dia terlampau
bergairah waktu itu. Tapi saya melihat sekiranya dia mau menurunkan pahanya
saja, sedangkan letak tangan tetap dipertahankan, ujung tongkat dengan
sendirinya dapat memukul dada Anda. Semua itu terjadi cuma sesaat. Waktu itu
saya sendiri tak sadar akan apa yang saya katakan."
Musashi mengangguk.
Ia menganggap dirinya beruntung, menerima pelajaran bermanfaat tanpa mesti
membayar dengan hidupnya. Gonnosuke pun mendengarkan dengan takzim. Ia juga
memperoleh wawasan baru. Apa yang baru saja dialaminya itu bukannya wahyu,
melainkan perjalanan ke perbatasan hidup dan mati. Ibunya, yang mengerti bahwa
ia berada di ambang bencana, telah memberikan pelajaran bagaimana bertahan
hidup.
Bertahun-tahun
kemudian, sesudah Gonnosuke memantapkan gayanya sendiri dan menjadi terkenal di
mana-mana, ia mencatat teknik yang ditemukan ibunya saat itu. Walaupun ia
menulis cukup panjang tentang kesetiaan ibunya dan pertandingannya dengan
Musashi, ia tetap menahan diri dan tidak mengatakan ia menang. Sebaliknya,
untuk selanjutnya kepada orang banyak ia mengatakan kalah, walaupun kekalahan
itu merupakan pelajaran yang tidak ternilai baginya.
Sesudah menyampaikan
harapannya akan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak, Musashi melanjutkan
perjalanan dari Inojigahara ke Kamisuwa. Ia tidak tahu bahwa ia terus diikuti
oleh samurai yang di sepanjang jalan itu terus menanyai tukang kuda di pos kuda
dan semua musafir lain. apakah mereka melihat Musashi.


0 komentar:
Posting Komentar