Biji Rami
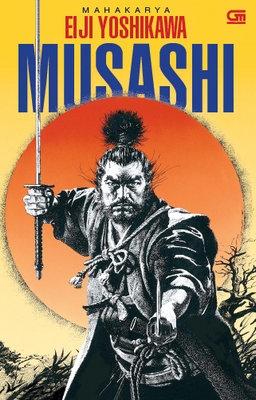
HYOGO semakin cemas.
Sesudah masuk ke kamarOtsu, dengan membawa surat dari Takuan, ia mencari gadis
itu di seluruh pekarangan benteng, dan makin lama kekuatirannya semakin
memuncak.
Surat dari bulan
sepuluh tahun lalu, yang tak jelas sebab keterlambatannya itu, bercerita
tentang akan diangkatnya Musashi sebagai instruktur shogun. Takuan minta Otsu
secepat mungkin datang ke ibu kota, karena Musashi akan segera membutuhkan
rumah dan "orang untuk mengurusnya". Hyogo tak sabar lagi ingin
melihat wajah Otsu menjadi cerah.
Karena tidak menemukan
gadis itu, akhirnya ia bertanya pada penjaga pintu gerbang, dan mendapat
jawaban bahwa orang-orang sedang pergi mencari Otsu. Hyogo menarik napas
panjang. Pikirnya, sungguh bukan kebiasaan Otsu membuat orang lain kuatir, dan
bukan kebiasaannya pula tidak meninggalkan pesan. Jarang ia bertindak
menurutkan kata hati, sekalipun dalam hal sekecil-kecilnya.
Namun, sebelum ia
sempat membayangkan hal yang terburuk, datang berita bahwa mereka sudah
kembali, Otsu dengan Sukekuro; dan Ushinosuke dengan orang-orang yang dikirim
ke Tsukigase. Anak itu minta maaf pada semua orang-entah untuk apa—tak seorang
pun tahu, lalu ia tergesa-gesa pulang.
"Mau ke mana kau
ini?" tanya salah seorang abdi.
"Saya mesti
kembali ke Araki. Ibu saya pasti kuatir, kalau saya tidak pulang."
"Kalau kau
mencoba pulang sekarang," kata Sukekuro, "ronin-ronin akan
menangkapmu, dan kecil kemungkinannya mereka akan membiarkanmu hidup. Kau bisa
tinggal di sini malam ini, dan pulang besok pagi."
Ushinosuke menggumam
tak jelas, menyatakan setuju, lalu ia disuruh ke gudang kayu di daerah
lingkaran luar, tempat para magang samurai tidur.
Hyogo memanggil Otsu
dengan isyarat, kemudian membawanya ke sisi, dan menyampaikan apa yang telah
ditulis Takuan. Dan ia tidak kaget ketika Otsu mengatakan, "Saya akan
pergi besok pagi." Wajahnya yang merah padam mengungkapkan perasaannya.
Kemudian Hyogo
mengingatkan Otsu tentang akan datangnya Munenori, dan menyarankan pada Otsu
untuk kembali ke Edo bersamanya, sekalipun ia tahu benar jawaban apa yang akan
didengarnya dari Otsu. Otsu tak punya selera untuk menunggu dua hari lagi,
apalagi dua bulan. Hyogo berusaha sekali lagi, dengan mengatakan bahwa kalau
Otsu mau menanti sampai sesudah upacara penguburan, Otsu akan dapat mengadakan
perjalanan dengannya ke Nagoya, karena ia telah mendapat panggilan untuk
menjadi pengikut Yang Dipertuan Tokugawa dari Owari. Dan ketika Otsu sekali
lagi menyatakan keberatan, ia mengatakan pada Otsu bahwa ia kurang senang
melihat Otsu akan mengadakan perjalanan jauh sendirian. Di setiap kota dan
penginapan sepanjang jalan itu, Otsu akan menjumpai gangguan, bahkan bahaya.
Otsu tersenyum.
"Anda rupanya lupa. Saya sudah terbiasa dengan perjalanan. Tak ada yang
perlu Anda kuatirkan."
Malam itu, dalam
pesta perpisahan sederhana, tiap orang memperlihatkan rasa sayangnya pada Otsu,
dan pada pagi berikutnya yang terang dan jernih, seluruh keluarga dan para
pembantu berkumpul di gerbang depan, melepas kepergian Otsu.
Sukekuro mengirim
orang untuk memanggil Ushinosuke, karena menurut perkiraannya Otsu dapat
menunggang sapinya sampai Uji. Dan ketika orang itu kembali dengan laporan
bahwa anak itu sudah pulang malam sebelumnya, Sukekuro memerintahkan supaya
diambilkan kuda.
Otsu merasa statusnya
terlampau rendah untuk mendapatkan perlakuan seperti itu, dan ia menolak
tawaran tersebut, namun Hyogo bersikeras. Kuda kelabu berbintik-bintik itu
dituntun oleh seorang samurai magang, menuruni lereng landai yang menuju
gerbang luar.
Hyogo berjalan
sebentar, kemudian berhenti. Ia tak dapat menyangkal, kadang-kadang ia merasa
iri pada Musashi, sebagaimana ia iri pada siapa pun yang dicintai Otsu.
Walaupun hati Otsu menjadi milik orang lain, rasa sayangnya pada Otsu tidak
berkurang. Otsu telah menjadi teman perjalanan yang menyenangkan dalam
perjalanan dari Edo, dan berminggu-minggu dan berbulan-bulan sesudahnya ia
mengagumi pengabdian yang diberikan gadis itu dalam merawat kakeknya. Walaupun
cintanya lebih dalam daripada sebelumnya, cinta itu tidaklah mementingkan diri
sendiri. Sekishusai memerintahkan ia membawa gadis itu dengan selamat kepada
Musashi, dan Hyogo bermaksud melakukannya. Bukanlah sifatnya untuk mendambakan
peruntungan orang lain, ataupun merampas peruntungan itu dari orang yang
bersangkutan. Tak dapat ia membayangkan tindakan yang terpisah dari Jalan
Samurai. Melaksanakan keinginan kakeknya itu sendiri merupakan pernyataan
cintanya.
Ia sedang tenggelam
dalam angan-angan itu, ketika Otsu menoleh dan membungkuk menyatakan terima
kasih pada orang-orang yang telah menunjukkan jasa baik kepadanya. Ia
berangkat, dan menyentuh beberapa kembang prem. Melihat secara tak sengaja daun
bunga yang berguguran itu, hampir-hampir Hyogo dapat mencium semerbak baunya.
Ia merasa itulah terakhir kali ia melihat Otsu, dan ia senang dapat berdoa
diam-diam demi kebaikan masa depan Otsu. Ia tetap berdiri dan memandang,
sementara Otsu menghilang dari pandangan.
"Pak."
Hyogo menoleh dan
senyuman tersungging pada wajahnya. "Ushinosuke. Ya, ya. Kudengar kau
pulang juga semalam, biarpun kularang."
"Ya, Pak, ibu
saya..." Ushinosuke memang masih terlalu muda, hingga menyebut berpisah
dengan ibunya saja bisa membuat ia menangis.
"Baiklah. Bagus
kalau seorang anak lelaki memperhatikan ibunya. Tapi bagaimana kau bisa
menyelamatkan diri dan ronin-ronin di Tsukigase itu?"
"Oh, mudah,
Pak."
"Betul
mudah?"
Anak itu tersenyum.
"Mereka tak ada di sana. Mereka mendengar Otsu datang dari benteng, karena
itu mereka takut akan diserang. Saya kira mereka tentunya pindah ke seberang
gunung itu."
"Ha, ha. Kalau
begitu, kita tak perlu lagi kuatir dengan mereka, kan? Kau sudah sarapan
belum?"
"Belum,"
jawab Ushinosuke sedikit malu. "Saya tadi bangun pagi, supaya dapat
menggali kentang liar buat Pak Kimura. Kalau Bapak suka, nanti saya
bawakan."
"Terima
kasih."
"Apa Bapak tahu
di mana Otsu sekarang?"
"Dia baru saja berangkat
ke Edo."
"Ke
Edo?..." Dan dengan ragu-ragu, katanya, "Saya ingin tahu, apakah dia
sudah menyampaikan pada Bapak atau Pak Kimura tentang keinginan saya."
"Dan apa
keinginanmu?"
"Selama mi, saya
ingin Bapak menjadikan saya pembantu samurai."
"Kau masih
terlalu muda buat pekerjaan itu. Barangkali nanti, kalau kau sudah lebih
besar." '
"Tapi saya ingin
belajar main pedang. Pak, bantulah saya. Saya mesti belajar selagi ibu saya
masih hidup."
"Apa kau belajar
pada orang lain?"
"Tidak, tapi
saya sudah latihan menggunakan pedang kayu, dengan pohon dan binatang."
"Oh, itu bagus
juga buat permulaan. Kalau nanti kau sudah sedikit lebih besar, kau bisa ikut
aku ke Nagoya. Sebentar lagi aku akan tinggal di sana."
"Tempat itu di
Owari, kan? Tak bisa saya pergi sejauh itu, selagi ibu saya masih hidup."
Hyogo jadi tergerak
hatinya, katanya, "Sini ikut aku!" Ushinosuke ikut tanpa
berkata-kata. "Kita pergi ke dojo. Akan kulihat, apa kau punya bakat jadi
pemain pedang."
"Ke dojo?"
Ushinosuke pun bertanya pada diri sendiri, apakah ia sedang bermimpi. Sejak
kecil ia sudah menganggap dojo Yagyu yang kuno itu sebagai lambang segala yang
paling diinginkannya di dunia ini. Sukekuro memang pernah mengatakan ia boleh
masuk, hanya saja itu belum pernah dilakukannya. Tapi sekarang ia diundang
masuk oleh salah seorang anggota keluarga!
"Cuci
kakimu."
"Baik,
Pak." Ushinosuke pergi ke kolam kecil di dekat pintu masuk, dan dengan
hati-hati sekali mencuci kakinya. Dengan cermat dibersihkannya kotoran yang ada
di sela-sela kukunya.
Begitu berada di
dalam, ia merasa kecil dan tidak berarti. Kayu-kayu blandar dan kaso itu tua
dan pejal, dan lantai dipoles sampai mengilap, hingga ia dapat berkaca di sana.
Suara Hyogo terdengar lain ketika mengatakan, "Ambil pedang."
Ushinosuke memilih
sebilah pedang kayu ek hitam dari antara senjatasenjata yang tergantung di
dinding. Hyogo mengambil juga sebilah, dan dengan ujung pedang diarahkan ke
lantai, ia berjalan ke tengah ruangan.
"Siap?"
tanyanya dingin.
"Ya," jawab
Ushinosuke sambil mengangkat senjatanya setinggi dada.
Hyogo membuka jurus,
sedikit menyudut. Ushinosuke menggembungkan badan seperti landak. Alisnya
terangkat, wajahnya mengerut ganas, dan darahnya menderas. Ketika Hyogo
memberikan isyarat dengan mata bahwa ia akan menyerang, Ushinosuke menggeram
keras. Sambil mengentakkan kaki ke lantai, Hyogo maju cepat ke depan, dan
melancarkan serangan menyamping ke pinggang Ushinosuke.
"Belum!"
teriak anak itu. Dengan sikap seakan menendang lantai dan dirinya, ia melompat
tinggi-tinggi, sampai melewati bahu Hyogo. Hyogo menjulurkan tangan kirinya dan
mendorong sedikit kaki anak itu ke atas. Ushinosuke berjungkir-balik dan
mendarat di belakang Hyogo. Dalam sekejap ia tegak kembali dan berlari untuk
memegang kembali pedangnya.
"Cukup,"
kata Hyogo.
"Ah, sekali
lagi!"
Ushinosuke mencekal
pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dengan kedua belah
tangan, dan menyerbu ke arah Hyogo seperti burung elang. Tapi senjata Hyogo
yang diarahkan langsung kepadanya menghentikan gerakan itu. Ia melihat
pandangan mata Hyogo, dan air matanya berlinang.
"Anak ini punya
semangat," pikir Hyogo, namun ia berpura-pura marah. "Kau
curang!" teriaknya. "Kau lompat di atas bahuku." Ushinosuke tak
dapat menjawab.
"Kau tidak tahu
kedudukanmu; dan lancang terhadap atasan! Duduk di sana!" Anak itu
berlutut dengan tangan ke depan, dan membungkuk meminta maaf. Hyogo
mendekatinya, menjatuhkan pedang kayu itu, dan menarik pedangnya sendiri.
"Kubunuh kau sekarang! Jangan menjerit."
"B-b-bunuh
saya?"
"Julurkan
lehermu! Buat seorang samurai, tak ada yang lebih penting daripada patuh kepada
aturan sopan santun. Biarpun kau cuma anak tani, perbuatanmu itu tak dapat
diampuni."
"Bapak mau bunuh
saya cuma karena perbuatan kasar?"
"Betul."
Ushinosuke menengadah
sebentar kepada samurai itu dengan mata pasrah, kemudian mengangkat kedua
tangan ke arah kampungnya, katanya, "Ibu, aku akan jadi bagian dari tanah
di benteng ini. Aku tahu, Ibu akan sedih. Maafkan aku karena tidak menjadi anak
yang baik." Kemudian dengan patuh ia menjulurkan lehernya.
Hyogo tertawa dan
memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Sambil menepuk-nepuk punggung
Ushinosuke, katanya, "Kau tidak betul-betul berpikir aku akan membunuh
anak macam kau, kan?"
"Jadi, Bapak
tidak sungguh-sungguh?"
"Tidak."
"Bapak bilang,
sopan santun itu penting. Jadi, apa bisa dibenarkan kalau seorang samurai
bercanda macam itu?"
"Ini bukan
lelucon. Kalau kau mau berlatih jadi samurai, aku mesti tahu orang macam apa
kau itu."
"Tadi saya pikir
Bapak sungguh-sungguh," kata Ushinosuke. Napasnya kembali normal.
"Kaubilang belum
pernah dapat pelajaran," kata Hyogo. "Tapi waktu kudesak kau ke tepi
ruangan, kau lompat ke atas bahuku. Tidak banyak murid dapat berbuat begitu,
biarpun sudah dapat latihan tiga-empat tahun."
"Tapi saya
memang belum pernah belajar pada orang lain."
"Tak perlu
dirahasiakan. Kau pasti punya guru yang baik. Siapa dia?"
Anak itu berpikir
sebentar, kemudian katanya, "Oh, ya, sekarang saya ingat, bagaimana saya
belajar lompat."
"Siapa yang
mengajar?"
"Bukan manusia
yang mengajar."
"Peri air
barangkali?"
"Bukan, biji
rami."
"Apa?"
"Biji
rami."
"Mana mungkin
kau belajar dari biji rami?"
"Begini, di
pegunungan itu ada beberapa petarung-orang-orang yang dapat menghilang dari
depan mata kita. Saya melihat latihan mereka beberapa kali."
"Maksudmu ninja,
ya? Tentunya kelompok Iga yang kaulihat itu. Tapi apa hubungannya dengan biji
rami?"
"Begini. Sesudah
rami itu ditanam pada musim semi, tak lama kemudian tumbuh kecambahnya."
"Lalu?"
"Saya lompati
pokok itu. Tiap hari saya latihan melompat ke sana kemari. Kalau udara lebih
panas, kecambah itu tumbuh cepat—bukan main cepatnya—jadi, dari hari ke hari
saya lompat lebih tinggi lagi."
"Oh,
begitu."
"Saya lakukan
itu tahun lalu dan tahun sebelumnya. Dari musim semi sampai musim gugur."
Pada waktu itu
Sukekuro masuk dojo, katanya, "Hyogo, ini ada surat lagi dari Edo."
Hyogo membacanya,
lalu katanya, "Otsu belum jauh, kan?"
"Tak lebih dari
delapan kilometer, barangkali. Apa yang terjadi?"
"Ya. Takuan
bilang, pengangkatan Musashi dibatalkan. Mereka rupanya sangsi akan wataknya.
Kupikir, kita tak boleh membiarkan Otsu terus pergi ke Edo tanpa memberitahu
dia."
"Saya akan
pergi!"
"Tidak, biar aku
yang pergi."
Sambil mengangguk
pada Ushinosuke, Hyogo meninggalkan dojo dan langsung pergi ke kandang.
Setengah perjalanan
menuju Uji, ia mulai berpikir. Biarpun Musashi tak jadi diangkat, buat Otsu
akan sama saja; yang diminati Otsu orangnya, bukan statusnya. Sekalipun Hyogo
misalnya berhasil meyakinkannya untuk tinggal sedikit lebih lama di Koyagyu,
Otsu pasti akan pergi terus ke Edo. Jadi, buat apa menghalangi perjalanannya
dengan menyampaikan berita buruk itu?
Hyogo kembali ke
Koyagyu dan melambatkan jalan kudanya. Dilihat dari luar, ia tampak tenang,
namun di hatinya berkecamuk perjuangan hebat. Oh, kalau sekiranya ia dapat
melihat Otsu sekali lagi! Ia mesti mengakui pada diri sendiri, bahwa itulah
alasan sebenarnya ia menyusul Otsu, namun ia tak akan mengakuinya pada orang
lain.
Hyogo mencoba
mengendalikan perasaannya. Seperti semua orang lain, prajurit terkadang
mengalami saat-saat lemah, saat-saat gila. Namun kewajibannya sebagai seorang
samurai sudah jelas: berkeras hati, sampai ia mencapai keseimbangan yang
tenang. Sekali ia berhasil menyeberangi rintangan khayal, jiwanya akan ringan
dan bebas, dan matanya akan terbuka melihat pohon-pohon dedalu hijau di
sekitarnya, dan setiap lembar rumput yang ada. Cinta bukanlah satu-satunya
emosi yang dapat mengusik hati seorang samurai. Hatinya adalah dunia yang sama
sekali berbeda. Pada masa ini, dunia sedang sangat membutuhkan orang-orang muda
berbakat, jadi bukan waktunya tergiur oleh sekuntum bunga yang ada di tepi
jalan.
Menurut Hyogo, yang
penting adalah bagaimana berdiri di tempat yang benar, agar ia dapat
menunggangi ombak zaman. "Ramai juga, ya?" ujar Hyogo dengan hati
riang.
"Ya, Nara jarang
begini baik keadaannya," jawab Sukekuro. "Macam pesiar saja."
Beberapa langkah di
belakang mereka, ikut juga Ushinosuke. Hyogo mulai menyukai anak itu. Anak itu
sekarang lebih sering datang ke benteng, dan dalam masa peralihan untuk menjadi
abdi biasa. Waktu itu ia memanggul makan siang kedua orang itu. Ia membawa
sepasang sandal cadangan untuk Hyogo, yang ia ikatkan ke obi-nya.
Mereka berada di
sebuah lapangan terbuka di tengah kota. Di satu sisi menjulang pagoda Kofukuji
yang bertingkat lima, di atas hutan yang mengitarinya. Di seberang lapangan
tampak rumah-rumah para pendeta Budha dan Shinto. Walaupun hari itu tenang dan
udara seperti pada musim semi, namun di daerah-daerah rendah tempat berdiamnya
penduduk kota, mengambang kabut tipis. Kerumunan orang yang berjumlah antara
empat sampai lima ratus itu tidak tampak terlalu besar, karena luasnya
lapangan. Sebagian dari rusa yang memasyhurkan nama Nara itu berjalanjalan di
antara para penonton, di sana-sini mengendus-endus potonganpotongan makanan
yang lezat.
"Mereka belum
selesai juga, ya?" tanya Hyogo.
"Belum,"
kata Sukekuro. "Rupanya sedang istirahat makan siang."
"Jadi, pendeta
pun mesti makan!"
Sukekuro tertawa.
Waktu itu berlangsung
semacam pertunjukan. Kota-kota besar biasanya memiliki teater, tapi di Nara dan
kota-kota yang lebih kecil, pertunjukan itu diadakan di udara terbuka. Para
tukang sulap, penari, tukang boneka, demikian juga para pemanah dan pemain
pedang, semuanya melakukan pertunjukan di luar. Tapi atraksi hari ini lebih
dari sekadar hiburan. Tiap tahun para pendeta pemain lembing Hozoin mengadakan
pertandingan. Dengan itu mereka menetapkan susunan kedudukan mereka di kuil.
Karena pertunjukan dilaksanakan di depan umum, para pemain harus berjuang keras
dan pertarungan sering berlangsung hebat dan menakjubkan. Di depan Kuil
Kofukuji dipasang papan pengumuman yang dengan jelas menyatakan bahwa
pertandingan itu terbuka untuk semua orang yang mengabdikan diri kepada seni
bela diri, namun orang luar yang berani menghadapi pendeta pemain lembing itu
sedikit sekali.
"Bagaimana kalau
kita cari tempat duduk untuk makan siang?" tanya Hyogo. "Rasanya kita
masih punya banyak waktu."
"Di mana tempat
yang baik?" tanya Sukekuro, memandang ke sekitar.
"Di sini,"
seru Ushinosuke. "Bapak-bapak bisa duduk di atas sini." Ia menunjuk
selembar tikar buluh yang telah diambilnya entah dari mana, dan ditebarkannya
di atas bukit kecil yang menyenangkan. Hyogo kagum akan kecekatan anak itu, dan
secara keseluruhan ia pun senang kebutuhan-kebutuhannya diperhatikan, walaupun
menurut anggapannya sifat penuh perhatian itu bukan watak yang ideal untuk
seorang calon samurai.
Sesudah mereka
mengambil tempat duduk sebaik-baiknya, Ushinosuke menyuguhkan hidangan:
gumpalan nasi kasar, acar prem asam, dan pasta buncis manis, semuanya
terbungkus daun bambu kering untuk memudahkan membawanya.
"Ushinosuke,"
kata Sukekuro, "lari sana kepada para pendeta itu, dan ambil sedikit teh.
Tapi jangan katakan untuk siapa."
"Akan mengganggu
sekali, kalau sampai mereka ke sini menyatakan hormat," tambah Hyogo, yang
waktu itu menenggelamkan muka ke bawah topi anyamannya. Wajah Sukekuro pun
lebih dari setengahnya tertutup bandana, seperti yang biasa dipakai para
pendeta.
Ketika Ushinosuke
berdiri, seorang anak lelaki lain yang jaraknya sekitar lima belas meter dari
sana mengatakan, "Sungguh saya tak mengerti. Tadi tikar itu di sini."
"Lupakan,
Iori," kata Gonnosuke. "Tikar itu tidak penting."
"Tentunya ada
yang mencuri. Siapa kira-kira yang melakukannya?"
"Tak usah
repot-repot." Gonnosuke duduk di rumput, mengeluarkan kuas dan tinta, dan
mulai mencatat pengeluarannya dalam buku catatan kecil, suatu kebiasaan yang
baru-baru ini didapatnya dari Ion.
Dalam beberapa hal,
sikap Iori memang terlampau serius untuk anak semuda dirinya. Ia memperhatikan
benar keuangan pribadinya, tidak pernah memboroskan sesuatu. Ia rapi bukan
main, dan ia merasa berterima kasih atas setiap mangkuk nasi yang diterimanya
dan setiap hari cerah yang dihadapinya. Singkat kata, ia orang yang ingin
serbalurus, dan memandang rendah orang yang tidak bersifat seperti dirinya.
Terhadap orang yang
mencuri milik orang lain, walaupun hanya selembar tikar murah, ia merasa muak.
"Oh, itu
dia," teriaknya. "Orang-orang di sana yang mengambilnya. Hei!"
la berlari ke arah mereka, tapi sekitar sepuluh langkah sebelum sampai,
tiba-tiba ia berhenti untuk menimbang-nimbang apa yang akan dikatakannya, dan
tahu-tahu ia sudah berhadapan dengan Ushinosuke.
"Apa
maumu?" geram Ushinosuke.
"Apa maksudmu,
apa mauku?" bentak Ion.
Sambil memandangnya
dengan sikap dingin, seperti sikap orang kampung terhadap orang luar, kata
Ushinosuke, "Kau yang tadi meneriaki kami."
"Siapa membawa
pergi barang orang lain, dia itu pencuri!"
"Pencuri? Kau
ini kurang ajar!"
"Tikar itu punya
kami!"
"Tikar? Aku tadi
menemukan tikar itu di tanah. Apa itu yang bikin kau gusar?"
"Tapi tikar itu
penting buat orang yang sedang melakukan perjalanan," kata Iori agak
muluk. "Karena dapat melindungi dari hujan, menjadi alas tidur. Banyak
lagi hal lain. Kembalikan tikar itu!"
"Boleh kau
mengambilnya, tapi tarik dulu kata-katamu bahwa aku pencuri!"
"Aku tak perlu
minta maaf buat mengambil kembali milik kami sendiri. Kalau tidak
kaukembalikan, akan kuambil kembali!"
"Boleh coba. Aku
Ushinosuke dari Araki. Tak mau aku kalah dengan orang kerdil macam kau. Aku ini
murid seorang samurai."
"Aku berani
bertaruh, memang kau murid samurai," kata Iori sambil berdiri sedikit
lebih lurus. "Kau berani omong besar karena ada orang banyak di sekitar
sini, tapi kau takkan berani berkelahi, kalau kita cuma berdua."
"Aku takkan lupa
kata-kata itu."
"Datang ke sana
nanti."
"Ke mana?"
"Dekat pagoda.
Kau datang sendiri."
Mereka berpisah.
Ushinosuke pergi mengambil teh, dan ketika ia kembali membawa poci teh dari
tembikar, pertandingan sudah mulai lagi. Ketika berdiri dalam lingkaran besar
bersama para penonton lain, Ushinosuke menancapkan matanya pada Iori,
menantangnya dengan mata itu. Iori membalas. Keduanya yakin menang.
Orang banyak yang
ribut itu terdorong ke sana-sini, hingga debu kuning naik ke udara. Di tengah
lingkaran, berdiri seorang pendeta, memegang lembing sepanjang tongkat unggas.
Satu demi satu lawan-lawan maju ke depan, menantangnya. Satu demi satu pula
mereka diruntuhkan ke bumi, atau diterbangkan ke udara.
"Ayo maju!"
teriaknya, tapi akhirnya tak ada lagi orang yang datang. "Kalau tak ada
lagi, saya pergi. Ada yang keberatan untuk menyatakan diri saya, Nankobo,
sebagai pemenang?" Setelah belajar di bawah pimpinan In'ei, ia menciptakan
gayanya sendiri, dan kini menjadi saingan utama Inshun. Inshun sendiri hari ini
tidak hadir, dengan alasan sakit. Tak seorang pun tahu, apakah ia takut pada
Nankobo, atau lebih suka menghindari konflik.
Ketika tak seorang
pun maju ke depan, pendeta bertubuh besar dan tegap itu menurunkan lembingnya,
memegangnya mendatar, dan menyatakan, "Tak ada lagi penantang."
"Tunggu!"
seru seorang pendeta, sambil berlari ke depan Nankobo. "Saya Daun, murid
Inshun. Saya menantang Anda."
"Siapkan
dirimu."
Sesudah saling
membungkuk, kedua orang itu melompat menjauh. Kedua lembing mereka begitu lama
saling tatap, seperti makhluk hidup, hingga orang banyak menjadi bosan dan
mulai berteriak-teriak menghendaki aksi.
Kemudian
sekonyong-konyong teriakan mereda. Lembing Nankobo menghunjam ke kepala Daun,
dan seperti pengejut burung yang digulingkan angin, tubuhnya pelan-pelan
menyandar ke samping, kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah. Tiga-empat pemain
lembing berlari maju, bukan untuk membalas dendam, tapi hanya untuk menyeret
tubuh itu ke luar.
Nankobo dengan
sombong membidangkan dadanya dan mengamati orang banyak. "Rupanya tak
banyak lagi orang yang berani. Kalau memang masih ada, silakan maju."
Seorang pendeta
gunung maju ke depan, dari belakang sebuah tenda. Ia menurunkan pen perjalanan
dari punggungnya, dan tanyanya, "Apa pertandingan ini hanya terbuka buat
pemain lembing Hozoin?'
"Tidak,"
jawab pendeta-pendeta Hozoin serentak.
Pendeta itu
membungkuk. "Kalau begitu, saya ingin mencoba. Ada yang bisa meminjamkan
pedang kayu pada saya?"
Hyogo memandang
Sukekuro, katanya, "Oh, ini mulai menarik."
"Barangkali
juga."
"Tak sangsi lagi
bagaimana jadinya."
"Bukan itu
maksudku. Kupikir Nankobo takkan mau berkelahi. Kalau dia mau, dia akan
kalah."
Sukekuro tampak
bertanya-tanya, tapi ia tidak minta penjelasan.
Satu orang
menyerahkan pedang kayu kepada pendeta pengembara itu. Ia berjalan mendekati
Nankobo, membungkuk, dan menyampaikan tantangannya. Umurnya sekitar empat puluh
tahun, tapi tubuhnya yang seperti baja pegas itu mengisyaratkan bahwa ia
terlatih bukan dalam cara pendeta gunung, melainkan di medan laga. Ia tentunya
orang yang sudah banyak kali berhadapan dengan maut, dan siap menghadapi maut
dengan tenang. Gaya bicaranya lembut, dan matanya tenang.
Nankobo memang
angkuh, tapi la bukan orang bodoh. "Anda orang luar?" tanyanya asal
saja.
"Ya," jawab
si penantang, membungkuk sekali lagi.
"Tunggu
sebentar." Nankobo melihat dua hal dengan jelas: tekniknya kemungkinan
memang lebih baik daripada teknik pendeta itu, tapi pada akhirnya ia takkan
dapat menang. Sejumlah prajurit terkemuka yang kalah dalam Pertempuran
Sekigahara diketahui masih menyamar sebagai pendeta pengembara. Hanya Tuhan
yang tahu, siapa orang itu.
"Saya tak bisa
menghadapi orang luar," kata Nankobo sambil menggeleng.
"Saya sudah
tanya peraturannya tadi, dan jawabannya bisa."
"Dengan yang
lain bisa-bisa saja, tapi saya memilih untuk tidak bertarung dengan orang luar.
Saya berkelahi bukan dengan tujuan mengalahkan lawan. Ini kegiatan keagamaan.
Di sini saya mendisiplinkan jiwa saya lewat lembing."
"Oh,
begitu," kata si pendeta disertai tawa kecil. Ia agaknya masih hendak
mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Ia menimbang-nimbang sebentar, kemudian
mengundurkan diri dari medan, mengembalikan pedang kayu itu, dan menghilang.
Nankobo memakai
kesempatan itu untuk keluar, tanpa memedulikan bisik-bisik orang bahwa
mengundurkan diri itu baginya berarti pengecut. Diikuti dua-tiga muridnya, ia
berjalan dengan megahnya, seperti jenderal penakluk.
"Nah, apa
kataku?" kata Hyogo.
"Anda betul
sekali."
"Orang itu pasti
salah satu dari orang-orang yang bersembunyi di Gunung Kudo. Gantikan jubah
putih dan dandanannya itu dengan ketopong dan baju zirah, dan dia akan menjadi
salah seorang pemain pedang besar beberapa tahun lalu."
Orang-orang sudah
menjarang, dan Sukekuro mulai mencari Ushinosuke, tapi anak itu tidak kelihatan
olehnya. Mendapat isyarat dari Iori tadi, ia pergi ke pagoda, dan kini mereka
berdua berdiri saling tatap dengan ganasnya.
"Jangan salahkan
aku, kalau kau terbunuh," kata Iori.
"Omong besar
kau!" kata Ushinosuke, mengambil tongkat untuk senjata.
Iori menyerbu dengan
pedang diangkat tinggi-tinggi. Ushinosuke melompat mundur. Karena menurut
pendapatnya Ushinosuke takut, Iori berlari langsung ke arahnya, tapi Ushinosuke
melompat sambil menendang sisi kepalanya. Tangan Iori memegang kepalanya, dan
ia rebah ke tanah. Tapi ia cepat pulih kembali, dan dalam sekejap sudah berdiri
lagi. Kedua anak itu ber-hadapan-hadapan dengan senjata terangkat.
Lupa akan ajaran
Musashi dan Gonnosuke, Iori menyerang dengan mata tertutup. Ushinosuke
menyamping sedikit dan memukul dengan tongkat.
"Ha! Aku
menang!" teriak Ushinosuke. Tapi ketika dilihatnya Iori tak bergerak sama
sekali, ia jadi ketakutan dan lari.
"Siapa
bilang!" bentak Gonnosuke. Tongkatnya yang empat kaki panjangnya itu
menghantam pinggul Ushinosuke.
Ushinosuke jatuh
sambil menjerit kesakitan, tapi sesudah melihat Gonnosuke sekilas, ia bangkit
dan lari lagi seperti kelinci, hingga kepalanya membentur Sukekuro.
"Ushinosuke! Apa
yang terjadi di sini?"
Ushinosuke cepat
menyembunyikan diri di belakang Sukekuro, sehingga samurai itu berhadap-hadapan
dengan Gonnosuke. Untuk sesaat seakanakan benturan tak dapat dihindari lagi.
Tangan Sukekuro menyambar pedang, sedangkan Gonnosuke mengetatkan pegangan
tongkatnya.
"Boleh saya
bertanya?" tanya Sukekuro. "Kenapa Anda mengejar anak ini, seperti
mau membunuhnya?"
"Sebelum
menjawab, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa Anda lihat tadi dia
merobohkan anak itu?"
"Apa anak itu
teman Anda?"
"Ya. Apa ini
salah seorang pembantu Anda?"
"Secara resmi
tidak." Sambil menatap Ushinosuke, tanyanya garang, "Kenapa kaupukul
anak itu, lalu lari? Katakan yang sebenarnya sekarang."
Belum lagi Ushinosuke
membuka mulut, Iori sudah mengangkat kepala dan berteriak, "Itu tadi
pertarungan!" Sambil duduk kesakitan, katanya, "Kami berdua
bertarung, dan saya kalah."
"Apa kalian
berdua sudah saling tantang sesuai aturan, dan sepakat bertempur?" tanya
Gonnosuke. Ia memandang kedua anak itu bergantian, dan tampak nada kagum dalam
matanya.
Dengan sikap sangat
malu, Ushinosuke berkata, "Saya tidak tahu itu tadi tikarnya."
Kedua pria itu saling
menyeringai. Sadarlah mereka bahwa kalau tadi mereka tidak mengendalikan diri,
kejadian sepele yang kekanak-kanakan itu dapat berakhir dengan pertumpahan
darah.
"Saya
menyesalkan kejadian ini," kata Sukekuro. "Begitupun saya. Saya harap
Anda memaafkan saya."
"Tidak apa-apa.
Guru saya menanti kami, karena itu lebih baik kami pergi sekarang."
Mereka keluar pintu
gerbang sambil tertawa, Gonnosuke dan Iori ke kiri, Sukekuro dan Ushinosuke ke
kanan.
Kemudian Gonnosuke
menoleh, katanya, "Boleh saya bertanya? Kalau kami terus mengikuti jalan
ini, apa kami akan sampai Benteng Koyagyu?"
Sukekuro mendekati
Gonnosuke, dan beberapa menit kemudian, ketika Hyogo bergabung dengan mereka,
ia menyampaikan pada Hyogo siapa orang-orang itu, dan kenapa mereka ada di
sana.
Hyogo menarik napas
panjang dengan sikap simpatik. "Sayang sekali. Coba kalau Anda datang tiga
minggu lalu, sebelum Otsu pergi menggabungkan diri dengan Musashi di Edo."
"Tapi dia tak
ada di Edo," kata Gonnosuke. "Tak ada yang tahu di mana dia berada,
termasuk teman-temannya."
Iori berusaha menahan
air matanya, namun sesungguhnya ia ingin sekali pergi sendiri ke suatu tempat,
untuk melampiaskan perasaannya. Dalam perjalanan turun, tidak henti-hentinya ia
bicara tentang pertemuan dengan Otsu, atau setidaknya demikianlah kesan
Gonnosuke. Dan ketika percakapan orang-orang dewasa itu beralih pada
peristiwa-peristiwa di Edo, ia pun lama-lama merasa asing. Kepada Gonnosuke,
Hyogo minta lebih banyak informasi tentang Musashi, minta kabar tentang
pamannya, dan minta perincian tentang hilangnya Ono Tadaaki. Kelihatannya
pertanyaannya takkan ada habisnya, demikian juga jawaban yang diberikan
Gonnosuke.
"Ke mana kau
pergi?" tanya Ushinosuke pada Iori, sambil menyusulnya dari belakang dan
meletakkan tangan dengan simpati ke bahu Iori. "Kau menangis, ya?"
"Tentu saja tidak!"
Tapi ketika menggeleng, air matanya terlontar jatuh.
"Hmm... Kau bisa
menggali kentang liar, tidak?"
"Tentu."
"Ada kentang di
sana. Mau tahu siapa yang bisa menggali paling cepat?"
Iori menerima
tantangan itu, dan mereka mulai menggali.
Hari sudah menjelang
senja, dan karena masih banyak yang dibicarakan, Hyogo mendesak Gonnosuke untuk
tinggal beberapa hari di benteng. Namun Gonnosuke mengatakan lebih suka
melanjutkan perjalanan.
Selagi mengucapkan
kata-kata perpisahan, mereka menyadari bahwa kedua anak itu hilang lagi. Tapi
sejenak kemudian Sukekuro menunjuk, dan katanya, "Itu mereka di sana.
Rupanya mereka sedang menggali."
Iori dan Ushinosuke
sedang tenggelam dalam kegiatan masing-masing. Karena rapuhnya akar kentang,
mereka mesti menggali dengan hati-hati sampai dalam. Ketiga lelaki itu senang
melihat ketekunan mereka, dan diam-diam mendekati mereka dari belakang, serta
memperhatikan mereka beberapa menit lamanya. Akhirnya Ushinosuke menengadah
melihat mereka. la tergagap sedikit, sedangkan Iori menoleh sambil menyeringai.
Lalu mereka kembali bekerja keras.
"Aku
menang!" teriak Ushinosuke sambil mencabut kentang panjang dan
meletakkannya di tanah.
Melihat lengan Iori
masih terbenam sampai bahu dalam lubang, Gonnosuke berkata tak sabar,
"Kalau kau tidak lekas menyelesaikannya, aku pergi sendiri!"
Sambil meletakkan
satu tangan ke paha, seperti seorang petani tua, Iori memaksa dirinya berdiri,
dan katanya, "Oh, tak sanggup aku. Sampai malam takkan selesai."
Dengan wajah menyerah, dikibaskannya tanah dari kimononya.
"Tak bisa kau
mengeluarkan kentang itu, padahal sudah menggali begitu dalam?" tanya
Ushinosuke. "Mari aku tarikkan."
"Tidak,"
kata Iori sambil mencegah tangan Ushinosuke. "Nanti patah." Dengan
hati-hati dikembalikannya tanah itu ke dalam lubang, dan dipadatkannya.
"Selamat
tinggal," kata Ushinosuke. Dengan bangga ia memanggul kentangnya, dan
secara kebetulan kelihatan ujungnya yang patah.
Melihat itu, Hyogo
berkata, "Kau kalah. Boleh saja kau menang dalam perkelahian, tapi kau
tidak lulus dalam pertandingan menggali kentang."


0 komentar:
Posting Komentar