Kecapi Rusak
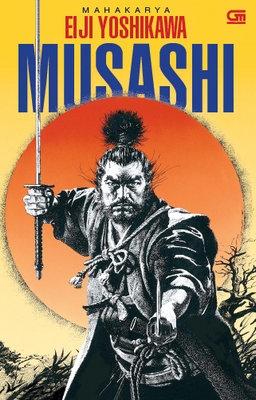
EMPAT-lima batang
kayu di perapian menyala lembut, menyebarkan aroma menyegarkan Dan menerangi
kamar kecil itu seakan tengah hari. Asap lembut itu tidak menyebabkan mata
sakit. Asapnya seperti daun-daur, peoni terbawa angin, sekali-sekali dinodai
bunga-bunga api warna emas lembayung dan merah tua. Manakali api menunjukkan
tanda-tanda akar. mati, Yoshino menambahkan potongan-potongan ranting api
sepanjang tiga puluh sentimeter yang diambil dari bak.
Orang-orang itu
terlampau terpikat oleh keindahan nyala api, hingga tidak bertanya tentang kayu
api, tapi akhirnya Mitsuhiro mengatakan "Kayu apa yang kaupergunakan itu?
Itu bukan kayu pinus."
"Bukan,"
jawab Yoshino. "Ini kayu peoni."
Mereka agak heran,
karena peoni dengan ranting-rantingnya yang pipih dan rimbun itu rasanya tidak
begitu cocok untuk kayu api. Yoshino mengambil bilah yang baru sedikit hangus
dan menyerahkannya pada Mitsuhiro.
Ia mengatakan
tunggul-tunggul peoni di kebun itu sudah ditanam lebildari seratus tahun yang
lalu. Pada awal musim dingin, tukang-tukang kebun memangkasnya rendah-rendah
dan membuang bagian atasnya yang dimakan cacing. Hasil pangkasan itu disimpan
untuk kayu api. Jumlahnva kecil, tapi cukup untuk Yoshino.
Menurut Yoshino,
bunga peoni adalah raja bunga. Barangkali masuk akal bahwa cabang-cabangnya
yang layu memiliki mutu yang tak ditemukan pada kayu biasa, tepat seperti
orang-orang tertentu memiliki nilai yang tidak dipunyai orang lain. "Tak
banyak orang yang jasanya dapat diberitahu sesudah kembangnya layu dan
mati," demikian renungnya. Dan dengan senyum sendu ia menjawab
pertanyaannya sendiri. "Kita manusia ini berkembang hanya selama kita
muda, kemudian menjadi kering, menjadi kerangka tak berbau, malahan bisa juga
sebelum kita mati."
Sebentar kemudian
Yoshino berkata, "Saya minta maaf karena tak ada lagi yang dapat saya
suguhkan kecuali sake dan api, tapi setidaknya ini cukup untuk sampai matahari
terbit."
"Engkau tak
perlu minta maaf. Ini hidangan yang cocok untuk seorang pangeran." Shoyu
memang tulus dalam memuji, sekalipun ia terbiasa dengan kemewahan.
"Ada satu hal
lagi yang saya inginkan dari Bapak-bapak," kata Yoshino. "Sudikah
Bapak-bapak menulis kenangan tentang malam ini?"
Ia menggosok batu tinta,
dan gadis-gadis menghamparkan babut wol di kamar sebelah, serta meletakkan
beberapa carik kertas tulis Cina. Kertas itu ulet dan menyerap, karena terbuat
dari bambu dan kayu arbei bahan kertas, tepat sekali untuk tulisan kaligrafi.
Mitsuhiro mengambil
alih peranan tuan rumah, dan menoleh kepada Takuan, katanya, "Pak pendeta
yang baik, karena Nyonya memintanya, silakan Bapak menulis sesuatu yang cocok.
Atau barangkali kita mesti bertanya dulu pada Koetsu?"
Koetsu beringsut
dengan lututnya. Ia mengambil kuas, berpikir sejenak, lalu menggambar kembang
peoni.
Di atas kembang itu
Takuan menulis:
Kenapakah aku
bergayut
Pada hidup yang
begini jauh Dari kecantikan dan nafsu? Peoni yang cantik pun
Membuang daun
bunganya dan mati.
Sajak Takuan itu bergaya
Jepang. Mitsuhiro memilih menulis dalam gaya Cina dan menurunkan baris-baris
sajak Tsai Wen:
Apabila aku sibuk,
gunung memandangku Apabila aku senggang, aku memandang gunung Walau
kelihatannya sama, tapi tak sama
Karena kesibukan
lebih rendah dari kesenggangan.
Di bawah sajak
Takuan, Yoshino menulis:
Sekalipun kala
berkembang
Napas kesedihan
mengapung Di atas bunga-bungaan
Apakah bunga
memikirkan masa depannya Ketika daun bunganya hilang?
Shoyu dan Musashi
memperhatikan tanpa mengatakan sesuatu. Musashi lega karena tak seorang pun
memaksanya menuliskan sesuatu.
Mereka kembali ke
perapian dan mengobrol beberapa waktu lamanya, sampai akhirnya Shoyu melihat
sebuah biwa, sejenis kecapi, di samping ceruk dalam kamar, dan minta kepada
Yoshino untuk bermain bagi mereka. Yang lain-lain mendukung saran itu.
Tanpa sikap malu-malu
Yoshino mengambil alat musik itu dan duduk di tengah kamar dalam yang
remang-remang cahayanya. Ia menunjukkan sikap seorang empu yang bangga akan
keterampilannya, tapi ia pun tidak berusaha menunjukkan sikap terlalu rendah
hati. Semua orang membersihkan diri dari pikiran-pikiran sampingan agar dapat
mencurahkan perhatian kepada usaha Yoshino membawakan petikan dari Dongeng
tentang Heike. Nada-nada lembut dan halus digantikan dengan nada-nada
menggelora, kemudian oleh paduan nada patah-patah. Api mati, dan kamar menjadi
gelap. Karena terpesona oleh musik, tak seorang pun bergerak, sampai akhirnya
letusan kecil bunga api membawa mereka kembali ke bumi.
Ketika musik
berhenti, Yoshino berkata disertai senyum selintas, "Saya takut permainan
saya tidak begitu bagus." Ia simpan kembali kecapinya dan kembali ke dekat
api. Ketika orang-orang berdiri untuk pulang, Musashilah yang pertama menuju pintu
dengan senangnya, karena selamat dari kebosanan lebih lanjut. Yoshino
mengucapkan selamat jalan kepada yang lain-lain satu per satu, tapi tidak
mengatakan sesuatu pun kepadanya. Baru ketika ia hendak meninggalkan tempat
itu, Yoshino diam-diam mencekal lengan kimononya.
"Menginaplah di
sini, Musashi. Aku... takkan membiarkan engkau pulang." Wajah seorang
perawan yang sedang diganggu pun tidak mungkin lebih merah daripada wajah
Musashi waktu itu. Musashi mencoba menutupinya dengan berpura-pura tidak
mendengar, tapi semua yang lain tahu bahwa Musashi terlampau bingung untuk
berbicara.
Sambil menoleh pada
Shoyu, Yoshino berkata, "Tak apa-apa kalau dia saya tahan di sini,
kan?"
Musashi melepaskan
tangan Yoshino dari lengan kimononya. "Tidak, saya pergi dengan
Koetsu."
Tapi ketika Musashi
bergegas menuju pintu, Koetsu menghentikannya. "Jangan seperti itu,
Musashi. Apa salahnya engkau menginap di sini malam ini? Kau bisa pulang ke
rumahku besok. Biar bagaimana, Nyonya sudah berbaik hati menunjukkan
perhatiannya padamu." Dan secara mencolok ia pun pergi meng-gabungkan diri
dengan kedua orang lainnya.
Sikap hati-hati
Musashi mengingatkannya bahwa orang-orang itu dengan sengaja mencoba
memperdayakannya agar mau tinggal, tapi kemudian mereka akan menertawakannya.
Namun sikap sungguh-sungguh yang ia baca pada wajah Yoshino dan Koetsu
menyatakan bahwa ajakan itu tidak sekadar lelucon.
Shoyu dan Mitsuhiro
senang sekali melihat kikuknya Musashi dan terus menggodanya. Seorang dari
mereka berkata, "Kau orang yang paling beruntung di negeri ini," dan
yang lain menyatakan bersedia menggantikannya.
Kelakar berhenti
dengan datangnya seorang lelaki yang oleh Yoshino telah disuruh mengawasi
sekitar tempat kediamannya. Orang itu datang dengan napas terengah-engah,
giginya gemeletuk karena ngeri.
"Bapak-bapak
dapat meninggalkan tempat ini," katanya, "tapi Musashi barangkali tak
mungkin. Cuma gerbang utama yang sekarang terbuka. Kedua sisi gerbang, sekitar
Warung Teh Amigasa dan sepanjang jalan, penuh samurai bersenjata lengkap,
berkeliaran dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka dari Perguruan Yoshioka.
Pedagang-pedagang kuatir akan terjadi sesuatu yang mengerikan, karena itu
mereka semua menutup pintu lebih awal. Sebelah sana, arah ke lapangan berkuda,
kata orang paling tidak ada seratus orang."
Orang-orang itu kagum
bukan main, tidak hanya oleh laporan itu, melainkan juga oleh tindakan
berjaga-jaga yang telah diambil Yoshino. Hanya Koetsu yang mendapat firasat
bahwa sesuatu telah terjadi.
Yoshino telah menduga
ada sesuatu yang telah terjadi ketika ia melihat noda darah pada lengan kimono
Musashi.
"Musashi,"
kata Yoshino, "kau sudah mendengar sendiri bagaimana keadaan di luar.
Sekarang mungkin kau bisa lebih mantap lagi untuk pergi dari sini, cuma untuk
membuktikan dirimu tidak takut. Tapi kuminta kau tidak melakukan sesuatu yang
gegabah. Kalau musuh-musuhmu menganggapmu pengecut, kau bisa membuktikan pada
mereka besok bahwa kau bukan pengecut. Malam ini di sini saja kau bersantai.
Menyenangkan diri sepuas-puasnya adalah tanda seorang lelaki sejati.
Orang-orang Yoshioka mau membunuhmu. Pasti bukan hat memalukan kalau kau
menghindarinya. Tapi banyak orang akan mengutukmu kalau penilaianmu tidak
tepat, yaitu jika kau berkeras masuk dalam perangkap mereka.
"Tentu saja
persoalan utama di sini adalah kehormatan pribadimu, tapi kuminta kau
mempertimbangkan kesulitan yang akan menimpa orang-orang di tempat ini, akibat
timbulnya perkelahian. Hidup teman-temanmu akan berada dalam bahaya juga. Dalam
keadaan seperti ini, satu-satunya yang paling bijaksana bagimu adalah tinggal
di sini."
Tanpa menanti jawaban
Musashi, Yoshino menoleh kepada orang-orang lain, dan katanya, "Saya kira
Bapak-bapak bisa pergi sekarang, asal saja berhati-hati di perjalanan."
Beberapa jam
kemudian, lonceng berbunyi empat kali. Bunyi musik dan nyanyian di kejauhan
sudah lenyap. Musashi duduk di ambang kamar perapian, bagai tawanan yang sedang
kesepian menantikan fajar. Yoshino tinggal di dekat api.
"Kau tidak
kedinginan di situ?" tanyanya. "Datanglah kemari, di sini
hangat."
"Jangan pikirkan
aku. Pergilah tidur. Kalau matahari terbit nanti, aku akan mencoba
keluar."
Kata-kata itu sudah
berkali-kali diucapkan, tapi tak ada hasilnya sama sekali.
Biarpun Musashi tidak
pandai berbasa-basi, Yoshino merasa tertarik kepadanya. Orang mengatakan
perempuan yang dapat menilai lelaki sebagai lelaki, dan bukan sebagai sumber
pendapatan, tidak mungkin mencari keria di daerah pelesiran. Ucapan ini cuma
klise yang diulang-ulang oleh pars pengunjung rumah-rumah pelacuran, yaitu
orang-orang yang hanya mengenal pelacur biasa dan tak ada hubungannya dengan
pelacur-pelacur besar. Perempuan-perempuan dengan tingkat pendidikan dan
latihan sepeni Yoshino, mampu sekali merasa jatuh cinta. Umur Yoshino hanya
setahun atau dua tahun lebih tua dari Musashi, tapi alangkah berlainan
pengalaman mereka dalam cinta. Melihat Musashi duduk kaku, mengendalikan
perasaannya, dan menghindari wajahnya, seakan-akan memandang dirinya itu akan
membuatnya buta, Yoshino sekali lagi merasa seperti perawan yang masih polos
dan sedang dirundung cinta pertama.
Para pelayan, yang
tidak memahami adanya ketegangan psikologis itu. menghamparkan kasur yang cocok
untuk anak lelaki atau anak perempuan daimyo di kamar sebelah. Lonceng-lonceng
kecil keemasan berkilau lembut di sudut-sudut bantal satin.
Bunyi salju yang
meluncur dari atap bukan tidak mirip dengan bunyi orang meloncat dari pagan ke
halaman. Setiap kali mendengarnya, rambut Musashi tegak seperti landak.
Sarafnya seakan mencapai ujung-ujung rambut itu.
Yoshino bergidik di
sekujur tubuhnya. Itulah waktu terdingin pada malam hari, yaitu tepat sebelum
fajar merekah. Namun perasaan tak enak yang diderita Yoshino bukanlah akibat
dingin. Perasaan itu diakibatkan karena melihat lelaki ganas itu, dan perasaan
itu berbenturan menjadi suatu irama yang ruwet dengan rasa tertariknya yang
wajar kepada Musashi.
Ketel di atas api
mulai bersiul dan bunyi riang itu menenangkannya. Diam-diam dituangkannya teh.
"Sebentar lagi
pagi. Minumlah secangkir teh dan hangatkan dirimu dekat api."
"Terima
kasih," kata Musashi tanpa bergerak.
"Sudah siap
sekarang," kata Yoshino lagi, kemudian berhenti mencoba. Ia tak ingin
Musashi merasa jengkel terhadap dirinya. Namun ia sedikit tersinggung juga
melihat teh itu terbuang sia-sia. Sesudah teh terlalu dingin untuk diminum,
dituangkannya ke dalam ember kecil yang memang tersedia untuk itu. Apa gunanya
menawarkan teh pada orang kasar macam ini, yang tak dapat menilai sama sekali
keelokan minum teh? demikian pikirnya.
Sekalipun Musashi
membelakanginya, Yoshino dapat melihat bahwa tubuh Musashi sekencang ketopong
baja. Dan mata Yoshino jadi tampak bersimpati.
"Musashi."
"Apa?"
"Kau ini berjaga
terhadap siapa?"
"Tidak terhadap
siapa-siapa. Aku mencoba untuk tidak terlalu bersantai."
"Justru karena
musuh-musuhmu?"
"Tentu
saja."
"Dalam keadaan
sekarang, kalau engkau tiba-tiba diserang dengan keras, kau akan segera
terbunuh. Aku yakin, dan itu membuatku sedih." Musashi tidak menjawab.
"Seorang
perempuan macam diriku tidak tahu apa-apa tentang Seni Perang, tapi dari
mengamatimu malam ini, aku mendapat perasaan yang mengerikan, seolah aku sedang
melihat orang yang akan dirobohkan pedang. Terasa ada bayangan maut pada
dirimu. Apakah seorang prajurit betul-betul dapat merasa aman, kalau setiap
saat dia menghadapi berlusin-lusin pedang? Dapatkah orang seperti itu
mengharapkan kemenangan?"
Pertanyaan itu
terdengar simpatik, tapi justru mengganggu ketenangan Musashi. Dengan cepat ia
memutar badan, beranjak ke perapian, dan duduk menghadapi Yoshino.
"Jadi, menurut
pendapatmu, aku belum matang?"
"Oh, aku sudah
membuatmu marah, ya?"
"Tak pernah aku
bisa marah oleh kata-kata perempuan. Tapi aku ingin tahu, kenapa menurutmu
kelakuanku seperti orang yang akan terbunuh?"
Dengan perasaan tak
senang ia menyadari bahwa oleh orang-orang Yoshioka ia telah dijerat dengan
jaringan pedang, strategi, dan kutukan. Ia sudah tahu sebelumnya bahwa ia akan
menghadapi usaha balas dendam, dan di halaman Rengeoin pun ia sudah bermaksud
pergi menyembunyikan diri. Tapi perbuatan demikian akan terasa kasar oleh
Koetsu dan akan berarti menyalahi janji kepada Rin'ya. Namun yang lebih
menentukan persoalan adalah keinginan untuk tidak dituduh lari karena takut.
Sesudah kembali ke
Ogiya, menurutnya ia sudah memperlihatkan kesabaran yang mengagumkan. Tapi
sekarang Yoshino menertawakan ketidakmatangannya. Ia sebetulnya takkan
terganggu sekiranya Yoshino mengolok-oloknya dengan cara pelacur, tapi Yoshino
kelihatannya serius sekali.
Ia menyatakan tidak
marah, tapi kenyataannya matanya setajam ujung pedang, dan ia langsung menatap
wajah Yoshino yang putih. "Jelaskan kata-katamu itu." Dan ketika
Yoshino tidak segera menjawab, katanya, "Atau barangkali kau cuma
berkelakar?"
Lesung pipit Yoshino
yang sejenak tadi hilang kini muncul lagi. "Bagaimana mungkin kau
mengatakan begitu?" Ia tertawa sambil menggoyangkan kepala. "Apa
menurutmu aku akan berkelakar tentang soal yang begitu serius untuk seorang
prajurit?"
"Nah, lalu apa
maksudmu? Coba ceritakan!"
"Baik. Karena
kau kelihatannya ingin sekali tahu, akan kucoba menjcukan. Apa kau mendengarkan
waktu aku main kecapi?"
"Ada hubungan
apa dengan kecapi?"
"Barangkali
sinting juga aku menanyakan itu. Tapi karena sedang tegar. telingamu tentunya
tak mungkin menangkap nada-nada musik yang halus dan indah."
"Tidak benar.
Aku tadi mendengarkan."
"Dan apa sempat
engkau bertanya di dalam hati, bagaimana mungkin gabungan nada-nada lunak dan
keras, dan kalimat-kalimat lemah dan kuat yang demikian rumit itu dapat
dihasilkan oleh empat senar?"
"Aku
mendengarkan ceritanya. Apa lagi yang mesti didengarkan?"
"Banyak orang
memang begitu sikapnya, tapi aku ingin membuat perbandingan antara kecapi dan
manusia sebagai makhluk. Aku takkan membicarakan teknik bermain, tapi akan
kubacakan sekarang sajak Po Chu-i, di mana ia melukiskan bunyi-bunyi kecapi.
Aku yakin engkau kenal sajak itu."
Yoshino mengerutkan
dahinya sedikit ketika membawakan sajak itu dengan suara rendah dan dengan gaya
antara menyanyi dan berbicara.
Dawai-dawai besar
mendengung seperti hujan, Dawai-dawai kecil berbisik seperti rahasia,
Mendengung, berbisik... dan kemudian berbaur Seperti mencurahkan mutiara
besar-kecil ke dalam piring baru jadi. Kita mendengar kepodang yang berkilauan,
walau tersembunyi dalam bunga. Kita mendengar kali tersedu sedih di sepanjang
tepian pasir... Kalau dihentikan sentuhan dinginnya, dawai itu bagai putus
Seakan tidak terus,
tapi nada-nada yang menghilang ke dasar kesedihan dan persembunyian ratapan
Lebih dapat ia
bercerita dalam diam daripada dalam bunyi...
Sebuah jambangan
tiba-tiba pecah dan airnya tumpah, Dan kuda-kuda berketopong melompat dan
senjata-senjata membentur dan menghantam Dan sebelum ia menjatuhkan beliungnya,
ia akhiri permainan dengan satu pukulan,
Dan keempat dawai pun
memperdengarkan satu bunyi, seperti kain sutra yang koyak.
"Ya begitulah,
sebuah kecapi sederhana dapat menghasilkan aneka nada yang tak terbatas
jumlahnya. Semenjak aku menjadi magang, hal itu sudah mengherankan diriku.
Akhirnya kupecahkan kecapi untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian
kucoba membuat sendiri. Dan sesudah mencoba macam-macam hal, akhirnya aku
mengerti bahwa rahasia alat itu terletak di hatinya."
Ia berhenti dan pergi
mencari kecapi dari kamar sebelah. Kembali ke tempat semula, ia pegang alat
musik itu pada lehernya dan ia dirikan di depan Musashi.
"Kalau
kauperiksa hati di dalamnya, engkau dapat melihat kenapa berbagai variasi nada
itu mungkin dihasilkan." Ia ambil sebuah pisau yang bagus dan tajam dengan
tangannya yang luwes, kemudian ia torehkan pisau itu cepat dan tajam ke bagian
belakang kecapi yang berbentuk buah pir itu. Dengan tiga-empat torehan cekatan,
pekerjaan itu selesai, demikian cepat dan menentukan, hingga Musashi
hampir-hampir mengharap melihat darah menyembur dari alat musik itu. Ia bahkan
merasakan denyut nyeri, seolah-olah mata pisau itu menoreh dagingnya sendiri.
Sambil menyembunyikan pisau di belakang dirinya, Yoshino mengangkat kecapi itu
agar Musashi dapat melihat susunannya.
Musashi memandang
wajah Yoshino, kemudian memandang kecapi yang sudah rusak itu, dan bertanya
dalam hati apakah Yoshino sebenarnya memiliki juga sifat keras seperti
dinyatakan dengan cara memainkan pisau itu. Rasa nyeri akibat jerit torehan itu
membekas.
"Seperti
kaulihat," kata Yoshino. "Bagian dalam kecapi ini hampir seluruhnya
bolong. Segala variasi datangnya dari benda melintang di bagian tengah ini.
Potongan kayu inilah tulang-belulang alat musik ini, alat vitalnya, hatinya.
Kalau bentuknya lurus betul dan kaku, bunyinya monoton, tapi kenyataannya
barang itu dibentuk melengkung. Tapi itu saja tak cukup untuk menciptakan
variasi nada yang tanpa batas itu. Variasi itu dapat diciptakan dengan
membiarkan benda melintang itu mendapat kebebasan bergetar ke sana kemari.
Dengan kata lain, kekayaan nada itu ada karena adanya kebebasan gerak tertentu,
dan karena ada kelenturan tertentu pada ujung-ujung intinya.
"Ini sama saja
dengan manusia. Dalam kehidupan ini kita mesti memiliki keluwesan. Semangat
kita harus dapat bergerak bebas. Terlampau kaku dan keras berarti rapuh dan tak
memiliki daya tanggap."
Mata Musashi tak
bergerak menatap kecapi, dan bibirnya tidak terbuka.
"Soal ini
seharusnya jelas bagi semua orang," lanjut Yoshino, "tapi
keistimewaan manusia adalah menjadi kaku, kan? Dengan satu sentilan alat
pemetik aku dapat membuat keempat dawai kecapi ini terdengar seperti kmbing,
seperti pedang, atau seperti koyakan kain, karena adanya keseimbangan yang baik
antara kemantapan dan keluwesan dalam inti kayu. Malam ini, ketika pertama kali
aku melihatmu, aku dapat merasakan tidak adanva keluwesan padamu, yang ada cuma
kekerasan kaku dan pantang menyerah. Kalau benda melintang itu sama tegang dan
kakunya dengan engkau, satu sentilan alat pemetik saja akan memutuskan dawai,
barangkali termasuk juga papan suaranya sendiri. Mungkin kelihatannya congkak bahwa
aku mengatakan semua ini, tapi aku menguatirkanmu. Aku tidak berkelakar atau
menertawakanmu. Mengerti?"
Ayam jantan berkokok
di kejauhan. Sinar matahari yang dipantulkan salju menembus celah-celah tirai
hujan. Musashi duduk menatap kecapi yang telah cacat itu dan remah-remah kayu
di lantai. Kokok ayam jantan tidak terdengar olehnya. Ia tak melihat sinar
matahari.
"Oh," kata
Yoshino, "sudah pagi." Ia kelihatan merasa sayang bahwa malam telah
lewat. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil lagi kayu api, tapi ternyata kayu
api telah habis.
Bunyi-bunyi pagi
hari-pintu yang berderak membuka dan kicau burungburung-masuk ke dalam kamar,
tapi Yoshino tak juga bergerak membuka tirai hujan. Walaupun api sudah dingin,
darah mengalir hangat di dalam nadinya.
Gadis-gadis muda yang
meladeninya cukup paham dan tidak membuka pintu rumah kecilnya sebelum mereka
dipanggil.


0 komentar:
Posting Komentar