Mata
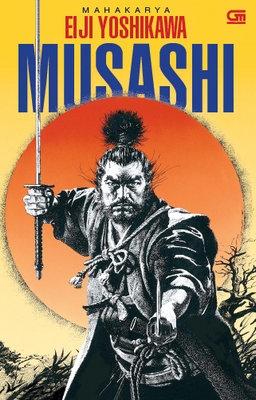
"SENSEI!"
panggil Iori, yang belum cukup tinggi untuk melihat lewat atas rumput tinggi
itu. Mereka berada di Dataran Musashino, yang kata orang meliputi sepuluh
kabupaten.
"Aku di
sini," jawab Musashi. "Kenapa kau begitu lama?"
"Saya pikir ada
jalan, tapi saya tersesat terus. Berapa jauh lagi kita mesti jalan?"
"Sampai kita
menemukan tempat yang baik untuk tinggal."
"Tinggal? Kita
akan tinggal di sekitar sini?"
"Kenapa
tidak?"
Iori menatap langit.
Ia memikirkan keluasan dan kekosongan tanah di sekitarnya itu, dan katanya,
"Heran."
"Tapi coba
bayangkan keadaannya waktu musim gugur. Langit jernih indah, embun segar di
rumput. Apa memikirkannya saja tidak membuatmu merasa lebih jernih?"
"Barangkali
juga, tapi saya tidak antihidup di kota seperti Bapak."
"Sebetulnya aku
tidak anti.. Dalam hat tertentu, sungguh senang hidup di antara orang banyak,
tapi biarpun dengan kulit tebal, tidak tahan aku tinggal di sana, kalau papan-papan
itu dipasang. Kaulihat sendiri apa yang mereka katakan."
Ion menyeringai.
"Memikirkannya saja saya jadi gila."
"Tapi kenapa
pula kau marah?"
"Saya tidak
tahan. Ke mana pun saya pergi, tak ada yang bicara baik tentang Bapak."
"Tak ada yang
dapat kuperbuat dalam hat itu."
"Bapak dapat
merobohkan orang-orang yang menyebarkan desas-desus
itu. Bapak dapat
memasang papan-papan sendiri buat menantang mereka."
"Tak ada gunanya
memulai perkelahian yang tak dapat kita menangkan."
"Bapak takkan
kalah dari sampah masyarakat itu. Tak mungkin."
"Tidak, kau
keliru. Aku akan kalah."
"Bagaimana
mungkin?"
"Karena jumlah.
Kalau kupukul sepuluh, akan datang seratus lagi. Kalau kukalahkan seratus, akan
datang seribu. Tak ada kemungkinan menang dalam keadaan macam itu."
"Berarti Bapak
akan terus ditertawakan orang selama hidup?"
"Tentu saja
tidak. Seperti semua orang lain, aku bertekad memiliki nama harum. Aku berutang
budi pada nenek moyangku. Dan aku bermaksud menjadi orang yang tak pernah
ditertawakan. Itulah yang mau kupelajari di stnt.
"Kita bisa saja
berjalan terus, tapi saya kira kita takkan menemukan rumah. Bagaimana kalau
kita mencoba mencari kuil buat tinggal lagi?"
"Itu bukan
gagasan jelek, tapi sebenarnya yang kuinginkan adalah menemukan tempat yang
banyak pohonnya, dan membangun rumah kita sendiri."
"Macam
Hotengahara lagi, ya?"
"Tidak. Kali ini
kita takkan bertani. Kupikir, barangkali aku akan melakukan semadi Zen tiap
hari. Kau bisa membaca buku-buku, dan aku memberikan pelajaran main pedang
padamu."
Mereka memasuki
dataran itu dari desa Kashiwagi, pintu masuk Koshu menuju Edo. Mereka menuruni
lereng panjang itu dari Junisho Gongen, kemudian menelusuri jalan sempit yang
berkali-kali seakan menghilang di antara rumput musim panas yang mengombak.
Ketika akhirnya mereka sampai di bukit kecil yang ditumbuhi pinus, Musashi
melakukan pengamatan cepat atas dataran itu, dan katanya, "Ini cocok
sekali." Baginya, tempat mana pun bisa menjadi rumahnya-bahkan lebih dari
itu: di mana pun ia berada, itulah alam semesta.
Mereka meminjam
peralatan dan menggaji seorang buruh dari rumah pertanian terdekat. Cara
Musashi membangun rumah sama sekali tidak canggih: sesungguhnya la masih dapat
belajar cukup banyak dengan mengamati burung-burung yang sedang membuat sarang.
Hasilnya, yang selesai beberapa hari kemudian, tampak aneh. Rumah itu kurang
kokoh dibandingkan rumah pertapa di gunung, tapi tidak sekasar gubuk.
Tiang-tiangnya dari balok yang masih berkulit, sedangkan sisanya dari gabungan
kasar papan, kulit kayu, bambu, dan miskantus.
Musashi mundur untuk
memperhatikan rumah itu balk-balk, kemudian ujarnya sambil berpikir,
"Rumah ini tentunya mirip rumah yang didiami orang banyak pada zaman
dewa-dewa." Satu-satunya yang mengimbangi keprimitifan rumah itu adalah
lembar-lembar kertas yang ditata sedemikian rupa dengan penuh cinta, menjadi
shoji kecil.
Hari-hari berikutnya,
suara Iori sudah mengalun dari belakang kerai buluh. la mengulang-ulang
pelajarannya, suaranya menggema mengatasi bunyi jangkrik. Latihan yang
ditempuhnya dalam segala hal sangat keras.
Kepada Jotaro,
Musashi tidak menekankan disiplin, karena menurut pendapatnya waktu itu, yang
terbaik adalah membiarkan anak-anak yang sedang tumbuh itu berkembang secara
alamiah. Tapi, sejalan dengan berlalunya waktu, ia melihat bahwa sifat-sifat
jelek cenderung berkembang dan sifat-sifat balk tertekan. Dan ia melihat bahwa
pohon dan tanaman yang hendak ditanaminya tak mau tumbuh, sementara rumput liar
dan semaksemak tumbuh pesat, tak peduli berapa sering ia menebasnya.
Selama beberapa ratus
tahun sesudah Perang Onin, bangsa ini seperti massa tanaman rami yang tumbuh
liar dan kacau. Kemudian Nobunaga menebasi semuanya itu, Hideyoshi mengikatnya,
dan Ieyasu telah membuka serta melembutkan tanahnya untuk membangun dunia baru.
Musashi melihat bahwa kaum prajurit yang hanya menjunjung tinggi praktekpraktek
perang, kini tidak lagi merupakan unsur dominan dalam masyarakat. Ciri mereka
yang paling menonjol adalah ambisi yang tak terbatas. Tapi Sekigahara sudah
mengakhiri semua itu.
Musashi sudah
mendapat keyakinan, biarpun bangsa ini tetap berada di tangan Keluarga
Tokugawa, atau kembali kepada Keluarga Toyotomi, tapi rakyat pada umumnya sudah
tahu, ke arah mana mereka ingin bergerak: dari kemelut menuju ketertiban, dan
dari kehancuran menuju pembangunan.
Kadang-kadang ia
merasa dirinya terlalu terlambat dilahirkan. Begitu kebesaran Hideyoshi masuk
ke daerah-daerah pedesaan terpencil dan menggugah hati anak-anak lelaki seperti
Musashi, maka kemungkinan untuk mengikuti langkah-langkah Hideyoshi sudah
menguap.
Jadi, pengalaman
sendirilah yang menuntun Musashi mengambil keputusan untuk menekankan disiplin
dalam pendidikan Iori. Kalau ia hendak menciptakan seorang samurai, ia mesti
menciptakannya untuk masa mendatang. Bukan untuk masa lalu.
"Iori."
"Ya, Pak."
Anak itu langsung saja berlutut di depan Musashi, sebelum kata-kata itu selesai
diucapkan.
"Sudah hampir
senja. Waktunya belajar. Ambil pedang-pedang itu."
"Baik,
Pak." Ketika pedang-pedang sudah diletakkannya di hadapan Musashi, ia
berlutut dan secara resmi memohon pelajaran.
Pedang Musashi
panjang, sedangkan pedang Iori pendek, tapi keduanya pedang latihan dari kayu.
Guru dan murid saling berhadapan, diam kaku, pedang dipegang setinggi mata.
Seberkas sisa sinar matahari mengambang di kaki langit. Rumpun pohon
kriptomeria di belakang pondok sudah terbenam dalam kegelapan, tapi kalau orang
melihat ke arah bunyi jangkrik, akan tampak sepotong bulan lewat rerantingan.
"Mata,"
kata Musashi.
Iori membuka matanya
lebar-lebar. "Mataku. Lihat mataku."
Iori berusaha
sebaik-baiknya, tapi pandangan matanya rupanya selalu mental sama sekali dari
mata Musashi. Bukannya menatap, tapi langsung kalah oleh mata lawannya. Ketika
mencoba lagi, ia bahkan merasa pusing.
Mulai terasa olehnya,
kepala itu seakan-akan bukan lagi kepalanya sendiri. Tangannya, kakinya,
seluruh tubuhnya terasa goyah.
"Lihat
mataku!" perintah Musashi dengan garang, segarang-garangnya. Tapi
pandangan mata Iori mengembara lagi. Kemudian, ketika ia dapat memusatkan
perhatian ke mata gurunya, ia lupa akan pedang di tangannya. Kayu melengkung
yang pendek itu terasa seberat batangan baja.
"Mata,
mata!" kata Musashi sambil maju sedikit.
Iori berusaha untuk
tidak rebah ke belakang. Untuk itu, sampai berlusin-lusin kali ia dicerca.
Begitu ia berusaha mengikuti gerak lawannya dan bergerak maju, kakinya seperti
terpaku ke bumi. Tak dapat ia maju atau mundur, dan terasa olehnya suhu
badannya naik. "Apa yang terjadi dengan diriku?" Pikiran itu meledak
seperti bunga api di dalam dirinya.
Merasakan terjadinya
ledakan kekuatan mental ini, Musashi memekik, "Serang!" Pada saat itu
juga, ia merendahkan bahunya, mundur, dan mengelak dengan kecekatan seekor
ikan.
Sambil terengah, Iori
meloncat ke depan, memutar badan, tapi Musashi sudah berdiri di tempat tadi ia
berdiri. Konfrontasi pun dimulai, tepat seperti tadi, guru dan murid diam tanpa
suara.
Tak lama kemudian,
rumput basah oleh embun, dan alis bulan bergantung di atas pepohonan
kriptomeria. Setiap kali angin bertiup, serangga-serangga seketika berhenti
bernyanyi. Musim gugur tiba, sekalipun tidak menakjubkan di siang hari,
bunga-bunga liar kini berayun-ayun dengan anggunnya, seperti jubah bulu dewa
yang sedang menari.
"Cukup,"
kata Musashi sambil menurunkan pedang.
Ia serahkan pedang
itu kepada Iori, tapi waktu itu juga terdengar oleh mereka suara dari arah
rumpun pohon. "Siapa pula itu?" kata Musashi.
"Barangkali
musafir tersesat yang ingin bermalam."
"Lari sana,
lihat."
Iori berlari ke sisi
rumah, dan Musashi mendudukkan diri di beranda bambu, memandang ke arah
dataran. Pohon-pohon elalia sudah tinggi, puncaknya berkembang halus. Rumput
bermandikan cahaya, menampilkan kemilau musim gugur yang khas.
Ketika Iori kembali,
Musashi bertanya, "Musafir, ya?"
"Bukan,
tamu."
"Tamu? Di
sini?"
"Hojo Shinzo.
Dia sudah menambatkan kudanya, dan sekarang menunggu Bapak di belakang."
"Rumah ini tak
ada depan atau belakangnya, tapi kupikir lebih baik kuterima dia di sini."
Iori berlari memutar
lewat sisi pondok, dan teriaknya, "Silakan jalan lewat sini."
"Oh,
menyenangkan sekali," kata Musashi. Matanya menyatakan kegembiraan ketika
melihat Shinzo sudah sembuh sama sekali.
"Maaf, begitu
lama saya tidak menghubungi. Saya kira Anda tinggal di sini supaya jauh dari
orang banyak? Saya harap Anda memaafkan saya, karena saya singgah tanpa
diduga-duga macam ini."
Mereka bertukar
salam, kemudian Musashi mengajak Shinzo ikut dengannya ke beranda.
"Bagaimana Anda
bisa menemukan tempat saya? Tak seorang pun saya beritahu bahwa saya ada di
sini."
"Zushino Kosuke.
Dia bilang, Anda menyelesaikan Kannon yang Anda janjikan kepadanya, dan
menyuruh Iori mengirimkannya."
"Ha, ha. Kalau
begitu, Iori yang membongkar rahasia itu. Tidak apalah. Saya belum cukup tua
untuk meninggalkan dunia ini dan mengundurkan diri. Tapi saya pikir, kalau saya
menghilang beberapa bulan lamanya, desasdesus jahat itu akan mereda. Dan akan
berkurang bahaya pembalasan terhadap Kosuke dan teman-teman saya yang
lain."
Shinzo menundukkan
kepala. "Saya mesti minta maaf pada Anda. Semua kesulitan ini, sayalah
penyebabnya."
"Tidak
sepenuhnya begitu. Itu soal kecil. Akar sesungguhnya dari persoalan ini ada
kaitannya dengan urusan antara Kojiro dan saya."
"Apa Anda tahu
dia sudah membunuh Obata Yogoro?"
"Tidak."
"Ketika
mendengar tentang diri saya, Yogoro memutuskan membalas dendam sendiri. Dia
bukan tandingan Kojiro."
"Saya sudah
memperingatkan dia...." Bayangan Yogoro yang berdiri di pintu masuk rumah
ayahnya masih jelas dalam pikiran Musashi. "Sayang sekali," pikirnya.
"Saya bisa
mengerti perasaannya," sambung Shinzo. "Semua murid sudah pergi, dan
ayahnya sudah meninggal. Dia tentunya berpikir, dialah satu-satunya yang dapat
melakukan pembalasan. Paling tidak, rupanya dia sudah pergi ke rumah Kojiro.
Tapi tak seorang pun melihat mereka bersama-sama, tak ada bukti yang
nyata."
"Mm. Barangkali
peringatan itu berakibat sebaliknya dari yang saya maksud-justru menggugah rasa
harga dirinya, hingga dia merasa mesti berkelahi. Sayang!"
"Memang. Yogoro
satu-satunya orang sedarah dengan Sensei. Dengan kematiannya, Keluarga Obata
tak ada lagi. Namun ayah saya sudah membicarakan persoalan ini dengan Yang
Dipertuan Munenori, yang kemudian berhasil menempuh prosedur pemungutan anak.
Saya akan menjadi ahli waris dan pengganti Kagenori, dan menggunakan nama
Obata.... Memang saya belum yakin bahwa saya sudah cukup matang. Saya pun
kuatir akan mengakhiri semua ini dengan mendatangkan aib lebih lanjut kepada
beliau. Bagaimanapun, beliau penganjur terbesar tradisi militer Koshu."
"Ayah Anda
adalah Yang Dipertuan dari Awa. Apakah tradisi militer Hojo tidak dianggap sama
dengan Perguruan Koshu? Dan ayah Anda guru yang sama besarnya dengan
Kagenori?"
"Itu kata orang.
Nenek moyang kami berasal dari Provinsi Totomi. Kakek saya mengabdi pada Hojo
Ujitsuna dan Ujiyasu dari Odawara, dan ayah saya dipilih oleh Ieyasu sendiri
untuk menggantikan mereka sebagai kepala keluarga."
"Sebagai orang
yang berasal dari keluarga militer terkenal, apakah tidak luar biasa bahwa Anda
menjadi murid Kagenori?"
"Ayah saya
mempunyai murid sendiri, dan dia memberikan kuliah pada shogun tentang ilmu
pengetahuan militer. Tapi dia bukannya mengajarkan sesuatu pada saya,
sebaliknya dia suruh saya pergi dan belajar dari orang lain. Carl jalan yang
keras! Itulah ayah saya."
Musashi merasakan
kesopanan, dan bahkan keagungan yang wajar, pada sikap Shinzo itu. Dan itu
barangkali memang sudah sewajarnya, pikirnya, karena ayah Shinzo, Ujikatsu,
adalah seorang jenderal terkemuka, dan ibunya, putri Hojo Ujiyasu.
"Saya takut sudah
terlalu banyak bicara," kata Shinzo. "Sesungguhnya, ayah saya yang
menyuruh saya kemari. Tentu saja wajar sekali kalau beliau yang datang
menyatakan terima kasih pada Anda, tapi sekarang beliau sedang menerima tamu
yang ingin sekali bertemu dengan Anda. Ayah minta saya pulang bersama Anda.
Maukah Anda datang?" Dan ia memandang wajah Musashi penuh tanya.
"Tamu ayah Anda
ingin bertemu dengan saya?"
"Betul."
"Siapa dia? Saya
hampir tak kenal siapa pun di Edo."
"Orang yang Anda
kenal sejak kecil."
Musashi tak dapat
membayangkan, siapa orangnya. Matahachi barangkali? Samurai dari Benteng
Takeyama? Seorang teman ayahnya?
Barangkali bahkan
Otsu.... Tapi Shinzo menolak membuka rahasianya. "Saya dilarang
mengatakannya. Dan tamu itu mengatakan lebih baik memberikan kejutan pada Anda.
Maukah Anda datang?"
Rasa ingin tahu
Musashi pun bangkit. Ia mengatakan pada diri sendiri, tak mungkin itu Otsu,
tapi dalam hati ia berharap demikian.
"Mari,"
katanya sambil berdiri. "Iori, jangan tunggu aku."
Shinzo senang misinya
berhasil, dan ia pergi ke belakang rumah, membawa kudanya. Pelana dan
sanggurdinya meneteskan air embun. Sambil memegang kekang, ia menawarkannya
kepada Musashi, yang tanpa banyak bicara langsung menaikinya.
Ketika mereka
berangkat, kata Musashi pada Iori, "Jaga dirimu, aku mungkin tidak kembali
sampai besok." Tak lama kemudian, sosoknya sudah lenyap ditelan kabut
malam.
Iori duduk tenang di
beranda, tenggelam dalam lamunan.
"Mata,"
pikirnya. "Mata." Tak terhitung sudah berapa kali ia diperintahkan
menatap ke mata lawan, namun ia belum dapat memahami maksud perintah itu,
maupun menghilangkannya dari pikiran. la menatap kosong ke Sungai Surga.
Apa yang salah
dengannya? Kenapa kalau Musashi menatapnya, ia tak dapat balas menatap? Ia
lebih jengkel akan kegagalannya itu daripada orang dewasa, dan ketika sedang
berusaha keras menemukan penjelasan tentang soal itu, tiba-tiba dilihatnya
sepasang mata. Mata itu tertuju kepadanya dari antara ranting-ranting tanaman
anggur yang membelit sebuah pohon di depan pondok.
"Apa itu?"
pikirnya.
Mata yang bersinar
cemerlang itu mengingatkannya pada mata Musashi selagi berlangsung pelajaran
praktek.
"Tentunya seekor
kuskus." Sudah beberapa kali ia melihat binatang itu sedang makan anggur
liar. Mata itu seperti barn akik, mata hantu ganas.
"Binatang!"
teriak Iori. "Kaupikir aku tak punya keberanian? Kaupikir dapat
menundukkan aku dengan pandangan mata? Akan kutunjukkan padamu! Tak bakal aku
kalah darimu."
Dengan tekad teguh ia
ketatkan alisnya, dan ia menatap balik. Kuskus itu tak bergerak untuk melarikan
diri, mungkin karena keras kepala, mungkin juga karena rasa ingin tahu. Matanya
begitu cemerlang.
Iori begitu serius
dengan usahanya itu, hingga ia lupa bernapas. la bersumpah untuk tidak kalah.
la tak mau kalah oleh binatang hina itu. Setelah beberapa waktu yang terasa
seperti beberapa jam, ia tiba-tiba sadar bahwa ia menang. Daun-daun anggur itu
bergoyang, dan kuskus pun lenyap.
"Nah, tahu rasa
kau!" kata Iori girang. Badannya basah oleh keringat, tapi la merasa lega
dan segar kembali. Ia berharap dapat mengulangi perbuatannya itu, kalau nanti
berhadapan lagi dengan Musashi.
Ia turunkan kerai
buluh di jendela dan ia matikan lampu, kemudian ia pergi tidur. Cahaya putih
kebiruan memantul dari rumput di luar. Ia tertidur, tapi di dalam kepalanya la
seolah melihat satu titik kecil yang bersinar seperti permata. Pada waktunya,
titik itu tumbuh menjadi bentuk samar wajah kuskus itu.
Dalam tidurnya ia
berguling ke sana kemari dan mengeluh, dan tiba-tiba ia merasa yakin bahwa di
kaki kasurnya terdapat sepasang mata yang memandanginya. Dengan susah payah ia
bangun. "Bajingan!" teriaknya sambil menjangkau pedangnya. la ayunkan
pedang itu sehebat-hebatnya, tapi akibatnya la jadi jungkir-balik. Bayangan
kuskus itu menjadi titik yang bergerak di kerai. Ia tebas binatang itu dengan
kejam, kemudian ia berlari ke luar, dan ia tetak tanaman anggur dengan ganas.
Matanya menengadah ke langit, mencari mata kuskus.
Dan pelan-pelan,
tampak jelas olehnya dua bintang besar kebiruan.


0 komentar:
Posting Komentar