Lingkaran
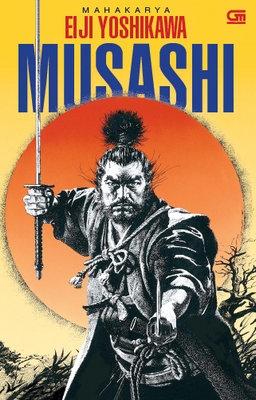
RENCANA perjalanan
guru Zen itu eksentrik tak keruan. Suatu kali, di waktu hujan turun sepanjang
hari, ia tinggal di penginapan dan minta Matahachi memberikan kepadanya
pengobatan moxa. Di Provinsi Mino ia tinggal selama tujuh hari di Daisenji,
kemudian singgah beberapa hari di kuil Zen di Hikone. Jadi, perjalanan keKyoto
itu ditempuh lambat sekali.
Musashi tidur di
tempat apa saja yang dapat ditemukannya. Kalau Gudo tinggal di penginapan, ia
bermalam di luar, atau di penginapan lain. Kalau pendeta itu dan Matahachi
menginap di kuil, ia berteduh di bawah gerbang. Kemelaratan bukan apa-apa
baginya dibandingkan kebutuhannya akan perkataan Gudo.
Pada suatu malam, di
luar sebuah kuil di tepi Danau Biwa, tiba-tiba ia tersadar akan datangnya musim
gugur. Ia pandangi dirinya, dan dilihatnya dirinya sudah mirip peminta-minta.
Rambutnya sudah seperti sarang tikus, karena ia memang sudah berketetapan untuk
tidak bersisir sebelum pendeta itu melunak sikapnya. Berminggu-minggu ia tidak
mandi dan bercukur. Pakaiannya dengan cepat berubah menjadi rombengan, dan
terasa seperti kulit pohon pinus di kulitnya.
Bintang-bintang
seperti akan jatuh dari langit. Ia pandangi tikar buluhnya, dan pikirnya,
"Sungguh bodoh aku!" Seketika sadarlah ia, betapa sinting sikapnya
selama itu. Ia tertawa pahit. Selama itu, dengan teguh dan diam ia berpegang
pada tujuannya, tapi apa yang ia harapkan dari guru Zen itu? Apa tak mungkin ia
menjalani hidup tanpa mesti menyiksa diri sedemikian rupa? Ia bahkan merasa
kasihan pada kutu-kutu yang hidup di tubuhnya.
Gudo dengan tegas
mengatakan bahwa ia tak punya "apa pun" untuk diberikan. Sungguh
tidak beralasan mendesaknya memberikan sesuatu yang tak dimilikinya. Salahkah
membencinya, sekalipun ia kurang menunjukkan perhatian dibanding perhatian yang
diberikannya pada seekor anjing sesat di jalan?
Musashi memandang ke
langit, lewat rambut yang meneduhi matanya. Tak sangsi lagi-itulah bulan musim
gugur. Tapi nyamuk-nyamuk itu... Kulitnya yang sudah penuh bilur-bilur merah
tidak lagi peka terhadap gigitannya.
Ia sudah siap untuk
mengaku pada dirinya sendiri, bahwa ada hal yang tidak ia mengerti, tapi apakah
itu? Kalau sekiranya ia dapat memahami apa gerangan hal itu, pedangnya akan
terbebas dari ikatannya, dan segala yang lain pun akan terpecahkan dalam
sesaat. Namun, begitu ia merasa akan dapat meraihnya, selalu saja hal itu
lolos.
Kalau usahanya
menempuh Jalan itu berakhir di sini, ia lebih suka mati, sebab untuk apa
lagi hidup ini? Selagi berbaring di
bawah atap gerbang, dan kantuk tidak juga datang, ia bertanya apa gerangan yang
belum dipahaminya selama ini. Teknik pedangkah? Tidak, lebih dari itu.
Pemecahan masalah Otsu? Tidak, tak seorang lelaki pun dapat begini sengsara
hanya karena cinta kepada seorang perempuan. Jawaban yang dicarinya pasti
meliputi segalanya, namun dengan segala kebesarannya, jawaban itu bisa saja
hanya sesuatu yang kecil, yang tak lebih dari biji madat.
Ia terbungkus dalam
tikar, seperti ulat. Terpikir olehnya, apakah Matahachi tidur enak.
Membandingkan dirinya dengan temannya, ia merasa iri. Masalah-masalah Matahachi
agaknya tidak melumpuhkan. Musashi kelihatan selalu mencari masalah-masalah
baru, dan dengan itu la menyiksa dirinya.
Matanya kini tertumpu
pada sebuah piagam yang tergantung di tiang gerbang. Ia bangkit dan
mendekatinya, agar dapat melihat lebih dekat. Dalam cahaya bulan ia membaca:
Saya mohon, cobalah
temukan sumber asasi.
Pai yun tergerak oleh
jasa Pai-ch'ang,
Hu-ch'iu kecewa atas
ajaran peninggalan Pai yun.
Seperti para
pendahulu kita yang agung, janganlah hanya memetiki dedaunan,
Atau menyibukkan diri
dengan rerantingan.
Agaknya tulisan itu
cuplikan dari Wasiat Daito Kokushi, pendiri Daitokuji.
Musashi membaca
kembali dua baris terakhir. Dedaunan dan rerantingan.... Berapa banyak orang
terlontar dari jalur hidupnya oleh hal-hal yang tak ada kaitannya? Apakah ia
sendiri bukan contoh hal itu? Pikiran itu serasa meringankan bebannya, namun
keraguannya tak juga hilang. Kenapa pedangnya tidak tunduk kepadanya? Kenapa
matanya berpaling dari tujuannya? Apakah yang mencegahnya mencapai
ketenteraman?
Bagaimanapun, semua
ini terasa demikian sia-sia. Ia tahu apabila orang telah menempuh Jalan itu
sejauh-jauhnya, maka ia mulai terombangambing dan terserang keresahan-dedaunan
dan rerantingan. Bagaimana mungkin orang membebaskan diri dari lingkaran itu?
Bagaimana orang dapat sampai kepada intinya dan menghancurkannya?
Kutertawakan ziarahku
yang sepuluh tahun ini
Jubah yang lusuh,
topi yang rombeng, ketukan di pintu Zen.
Sesungguhnya Hukum
Budha itu sederhana:
Makan nasimu, minum
tehmu, kenakan pakaianmu.
Musashi terkenang
kembali akan sajak tulisan Gudo ini, yang dipakainya untuk mengejek diri
sendiri. Gudo kira-kira sebaya Musashi ketika mengarang sajak itu.
Pada kunjungan
Musashi yang pertama ke Kuil Myoshinji, pendeta itu hampir menendangnya dari
pintu. "Jalan pikiran aneh apa pula yang mendorongmu datang ke
rumahku?" begitu teriaknya. Tapi Musashi bersikeras, dan kemudian, sesudah
ia memperoleh izin masuk, Gudo menyuguhinya sajak ironis itu. Dan ia
menertawakan Musashi, seraya mengucapkan katakata yang telah diucapkannya
beberapa minggu lalu, "Kau selalu bicara... Itu sia-sia!"
Dalam keadaan benar-benar
putus asa, Musashi membuang sama sekali keinginan untuk tidur, dan la berjalan
mengitari pintu gerbang. Justru pada waktu itu ia melihat dua orang muncul dari
kuil.
Gudo dan Matahachi
berjalan dengan langkah cepat luar biasa. Barangkali panggilan mendesak telah
datang dari Kuil Myoshinji, kuil kepala sekte Gudo. Apa pun halnya, ia melewati
begitu saja para biarawan yang telah berkumpul untuk mengucapkan selamat jalan
kepadanya, dan langsung menuju Jembatan Kara di Seta.
Musashi mengikutinya
melewati kota Sakamoto yang tertidur, melintasi toko-toko cetak kayu, toko-toko
sayur dan buah, bahkan juga penginapanpenginapan ramai yang semuanya sudah
terkunci rapat. Satu-satunya yang hadir adalah bulan yang pucat.
Mereka meninggalkan
kota itu, mendekati Gunung Hiei, melewati Miidera dan Sekiji yang terselimut
tirai kabut. Mereka hampir tak menjumpai siapa pun. Ketika mereka sampai di
celah, Gudo berhenti dan mengatakan sesuatu pada Matahachi. Di bawah mereka
terletak Kyoto, di arah lain keluasan Danau Biwa yang tenang. DI luar bulan,
segala sesuatu tampak seperti mika, lautan kabut lunak keperakan.
Ketika beberapa waktu
kemudian mereka sampai di celah itu, terkejutlah Musashi bahwa dirinya hanya
beberapa kaki jaraknya dan sang guru. Dalam beberapa minggu ini, itulah pertama
kali mereka bertemu pandang. Gudo tak mengatakan apa pun. Musashi pun tak
mengatakan sesuatu.
"Sekarang...
inilah waktunya!" pikir Musashi. Kalau pendeta itu nanti sampai sejauh
Myoshinji, ia terpaksa menanti beberapa minggu sebelum sempat bertemu lagi
dengannya.
"Saya mohon,
Pak," katanya. Dadanya menggembung dan lehernya melipat. Suaranya seperti
suara seorang anak yang dengan ketakutan mencoba menyampaikan sesuatu yang tak
hendak dikatakannya. Ia beringsut maju dengan takut-takut.
Pendeta itu tidak
berkenan menanyakan apa yang dikehendakinya. Wajahnya mirip wajah patung
berpernis kering. Hanya matanya yang menonjol putih, menatap marah pada
Musashi.
"Saya mohon,
Pak," katanya. Tanpa menghiraukan apa pun, kecuali hasrat menyala-nyala
yang mendesaknya maju, Musashi menjatuhkan diri berlutut dan menundukkan
kepala. "Sepatah kata kebijaksanaan! Satu patah kata saja...!"
Ia merasa seperti
sudah berjam-jam menanti. Ketika akhirnya ia tak dapat lagi mengendalikan diri,
ia memperbarui permohonannya.
"Aku sudah
dengar semuanya itu!" sela Gudo. "Matahachi bicara tentangmu tiap
malam. Aku sudah tahu semua yang perlu kuketahui, bahkan juga tentang perempuan
itu."
Kata-kata itu seperti
kerat es. Andaikata pun Musashi ingin mengangkat kepalanya, ia tak dapat
berbuat demikian.
"Matahachi,
tongkat!"
Musashi menutup mata,
menguatkan diri menanti pukulan. Namun Gudo bukannya memukul, melainkan
menggambar lingkaran di sekitar dirinya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, ia
lontarkan tongkat itu, dan katanya, "Ayo pergi, Matahachi!" Dan
mereka pergi cepat-cepat.
Musashi jadi naik
pitam. Sesudah berminggu-minggu menderita aib yang kejam, dalam usaha yang
tulus untuk menerima ajaran, penolakan Gudo jauh lebih buruk daripada sekadar
tiadanya rasa iba. Penolakan itu kejam, brutal! Pendeta itu mempermainkan
manusia!
"Pendeta
babi!"
Musashi menatap
garang ke arah dua orang yang melangkah pergi itu. Bibirnya mengatup erat,
membentuk berengut marah.
"Tak ada
apa-apa." Mengenang kata-kata Gudo itu, ia menyimpulkan bahwa kata-kata
itu hanya dusta, seolah-olah hendak menyatakan bahwa orang itu punya sesuatu
yang bisa ditawarkan, padahal kenyataannya "tak ada apa-apa" dalam
kepalanya yang tolol itu.
"Awas!"
pikir Musashi. "Aku tidak butuh kau!" la takkan mengandalkan diri
pada siapa pun. Analisis terakhirnya menyatakan tak seorang pun dapat
diandalkan, kecuali diri sendiri. Ia seorang lelaki, seperti halnya Gudo dan
guru-guru sebelumnya.
Ia berdiri,
setengahnya digerakkan oleh kemarahan sendiri. Beberapa menit lamanya ia
menatap bulan, tapi ketika kemarahannya mendingin, terpandang olehnya lingkaran
itu. la masih berdiri di dalamnya, dan ia menoleh ke sekitar. Baru berbuat
demikian, teringat olehnya tongkat yang tidak jadi memukulnya.
"Lingkaran? Apa
pula artinya?" Dan ia biarkan pikirannya berkembang. Satu garis penuh,
tanpa awal, tanpa akhir, tanpa penyimpangan. Kalau lingkaran itu diluaskan
tanpa batas, akan menjadi alam semesta. Kalau dikerutkan, akan sama dengan
titik kecil tempat jiwanya bersemayam. Jiwa itu bulat. Alam semesta ini bulat.
Bukan dua. Satu! Satu ujud-dirinya dan alam semesta.
Dengan bunyi berdetak
ia cabut pedangnya, dan ia acungkan dengan arah diagonal. Bayangan dirinya
menyerupai lambang huruf "o". Lingkaran alam semesta ini tetap sama.
Dengan tanda yang sama itu, ia sendiri tidak berubah. Hanya bayangannya yang
berubah.
"Hanya
bayangan," pikirnya. "Bayangan itu bukan diriku yang
sebenarnya." Dinding tempat ia membenturkan kepalanya selama ini hanyalah
bayangan, bayangan pikiran yang kacau.
Ia mengangkat
kepalanya, dan pekik ganas pun meledak dari bibirnya.
Dengan tangan kiri ia
acungkan pedang pendeknya. Bayangan itu berubah lagi, tapi citra alam semesta
secuil pun tidak. Kedua pedang itu hanyalah satu pedang. Dan keduanya adalah
bagian dari lingkaran itu.
Ia mengeluh dalam,
matanya terbuka. Ketika ia memandang bulan lagi, terlihat olehnya lingkaran
besar yang dapat dianggap serupa dengan pedang, atau dengan jiwa orang yang
menginjak bumi.
"Sensei!"
pekiknya sambil berlari mengejar Gudo. Memang tak ada lagi yang diharapkannya
dari pendeta itu, tapi ia harus minta maaf karena telah demikian hebat
membencinya.
Selusin langkah
kemudian, ia berhenti. "Cuma dedaunan dan rerantingan," pikirnya.


0 komentar:
Posting Komentar